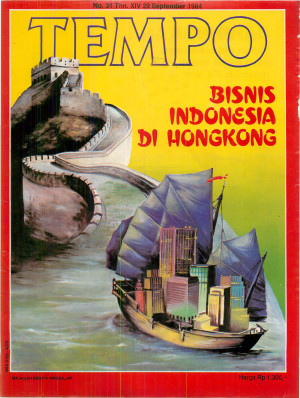ADA seorang termasyhur yang menentang demokrasi. Namanya Socrates. Pemikir Yunani kuno itu dihukum mati pada tahun 399 Sebelum Masehi. Alasannya, kata seorang penulis: ia tak berada di pihak demokrasi yang menang. Musuh besar orang-orang demokrat, Critias, memang murid Socrates. Dalam perang saudara yang mengoyak-ngoyak Athena antara pendukung oligarki dan demokrasi, Critias akhirnya kalah. Demokrasi pun dipulihkan. Memang, suatu pengampunan besar-besaran dimaklumkan - tapi tidak untuk Socrates. Kita tak tahu jelas, kenapa demikian. Tapi ini memang bukan cerita tentang satu bagian sejarah Yunani. Socrates adalah sekadar contoh bagaimana seorang pemikir, yang begitu setia kepada kemerdekaan berpikir dan menyatakan pendapat, justru hendak menunjukkan bahwa"demokrasi" tak dengan sendinnya berhubungan dengan kemerdekaan itu. Demokrasi adalah nonsens, kata Socrates. Suara rakyat sering kali suara gombal. Kebajikan (arete) yang terutama adalah pengetahuan. Memilih para pengelola pemenntahan dengan cara pungutan suara itu tak masuk di akal. Bukankah seorang nakoda juga tak dipilih dengan pemungutan suara? Socrates barangkali melucu, dengan sedikit sarkasme. Tapi para muridnya, terutama Plato, kemudian membuktikan betapa benarnya sang guru. Di sckitar tahun 400 SM, kaum demokrat yang menang menganggap perlu bahwa warga yang miskin harus hadir di ekklesia. Majelis permusyawaratan rakyat memang hendak dihindarkan dari kekuasaan para orang kaya. Maka, tiap warga yang hadir pun memperoleh imbalan uang, kurang lebih memadai sebagai pengganti pendapatan satu han. Tak ayal, majelis itu pun dengan segera dikuasai rakyat yang miskin. Yang kaya lebih baik tinggal di rumah. Kehadiran si melarat yang dibayar itu akhirnya yang dipersalahkan sebagai sebab merosotnya mutu majelis. Keputusan salah sering terjadi. Seorang filsuf bahkan pernah mengatakan, jangan-jangan majelis itu dibayar oleh musuh Athena untuk bersidang saking banyaknya kesalahan yang mereka buat. Demokrasi di Yunani kuno akhirnya berakhir, setelah sekitar satu abad turun naik. Di hari-hari menielang runtuhnya sistem itu Athena pun berkembang jadi sejenis "republik para advokat". Yang didengar khalayak adalah para orator. Sejumlah juru pidato yang pandai, penuh api, dan penuh aksi muncul. Mereka beradu pendapat, membakar rasa, dan gairah. Yang termasyhur di antaranya, Demosthenes, bahkan sanggup berbulan-bulan mengucilkan diri di gua, berlatih melontarkan kata-kata yang paling hebat dan gaya yang paling memikat, termasuk bila ia harus berdusta. Tak heran bila Plato - dan ia bukan pendukung pemerintahan oleh demos alias warga kebanyakan - mengernyitkan alis di hadapan kebisingan itu. Para orator, baginya, hanyalah pemberi racun yang akhirnya membunuh demokrasi sendiri. Sebab, sering yang diumbar adalah kebanggaan massa ataupun prasangka-prasangka mereka, bukan pikiran tenang yang bijaksana. Tapi Plato, seperti Socrates, hidup beratus-ratus tahun yang silam. Di abad ini kita bicara tentang "rakyat" (kadang disebut sebagai "massa") dengan lebih hormat. Yang menarik ialah, ditutupi atau tidak, orang sebenarnya tetap cemas dalam memandang "rakyat" yang terhormat itu. Baik di Uni Soviet maupun di Cina, para pemimpin "demokrasi rakyat" toh merasa bahwa "rakyat" itu tak bisa dibiarkan tanpa kediktatoran pucuk pimpinan partai. Di Iran yang Islam, baik Ayatullah Kho meini maupun Ali Shanati sama-sama menggarisbawahi "kepemimpinan", dengan asumsi bahwa para demos itu sering kali mirip anak-anak yang butuh bimbingan. Kerakyatan atau semangat populis tetap semangat yang memikat di abad ke-20, tapi rupanya orang memang harus berhati-hati dengan vox populi. Adolf Hitler dan Mussolini (kedua-duanya orator yang pandai) membuktikan bahwa suatu gerakan yang sangat merusak - bahkan ganas - dapat terjadi karena kepedihan, purbasangka, kecurigaan, dan cemburu rakyat banyak, yang telah dapat dikibarkan sebagai panji. Tapi salahkah para demos Salahkah kepedihan dan cemburu dan purbasangka mereka? Di abad ke-4 Sebelum Masehi, Athena mencicipi getah pahit dari pertumbuhannya sendiri. Industri berkembang pesat. Kekayaan dari tanah telah diganti oleh kekayaan dari perdagangan, dalam bentuk uang yang berjalan dari bank ke bank. Tragisnya, kelas menengah nyaris habis oleh perang-perang saudara. Maka, Plato pun bicara tentang "dua kota" yang bersengketa, yang satu milik si kaya dan yang lain si miskin. Yang tampak hanyalah dua ekstrem. Dalam situasi seperti itu, sang filsuf, yang menyerukan sikap moderat, yang sadar bahwa sebaik-baiknya perkara adalah di tengah-tengah, tak ada guna. Ia, dalam kata-kata Plato, ibarat "seorang manusia yang jatuh di antara hewan yang liar". Tak didengar, meskipun luka di hati yang dalam. Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini