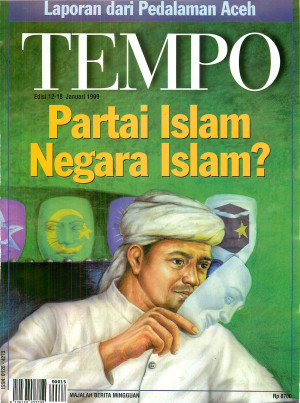ACEH adalah problem yang tumbuh dari sejarah kesalahpahaman. Kesalahpahaman pokok adalah tentang Indonesia itu sendiri. Indonesia, yang dinyanyikan dengan khidmat oleh jutaan anak-anak, sebenarnya bukanlah sebuah wujud yang datang sejak penciptaan alam semesta. Indonesia adalah sebuah proyek baru yang belum bisa dianggap selesai.
Dalam sejarah, Aceh dikenal sebagai wilayah yang—paling tidak menurut para pemimpin yang ada di sana tahun 1940-an itu—memilih jadi bagian republik baru yang berdiri tahun 1945 itu, Indonesia. Kata kunci di situ adalah "memilih". Dengan kata lain, dengan kemauan. Dari sini tampak bahwa Indonesia adalah sesuatu yang dibangun karena kemauan orang banyak, di antaranya orang Aceh. Proyek ini dimulai tahun 1928. Ia diberi bentuk yang lebih kukuh sejak 1945.
Tapi kemauan yang mendorong proyek itu bukanlah sesuatu yang abstrak. Kemauan itu milik sebuah kalangan, sebuah generasi, yang terikat waktu, yang mungkin terpaut dengan latar belakang sosial atau kepentingan sendiri. Karena datang dari manusia yang konkret, kemauan itu bisa berubah. Mereka yang punya mau jadi "Indonesia" tahun 1945 mungkin saja tak selamanya berada dalam posisi yang sama. Bisa jadi generasi lama hilang dan generasi baru tak sepaham. Sangat mungkin pula bahwa para pelaku yang dulu bersama-sama orang Aceh dan lain-lain membangun proyek "Indonesia" itu kemudian berganti memilih variasi kesepakatan.
Bahwa Aceh kemudian memunculkan gerakan perlawanan terhadap "Pusat", di antaranya gerakan separatisme Aceh Merdeka, hal itu menunjukkan bahwa ada yang kemudian telantar dalam proyek bersama itu. Ada tendensi untuk menganggap bahwa "Indonesia" sesuatu yang sudah beres hanya karena sebagai ide ia sudah final. Memang ada pelbagai adaptasi yang sudah dilakukan. Tahun 1959, misalnya, Aceh jadi daerah istimewa. Tapi hampir tak ada usaha untuk merundingkan kembali, setiap kali, arrangement yang sudah terbentuk. Sedikit sekali kemauan untuk menengok kembali sejauh mana "proyek menjadi-Indonesia" itu bisa tetap atau harus direvisi, terutama di Aceh.
Simbol "Jawa" dan Soeharto
Ini terutama terasa di bawah Orde Baru. Memang tak adil untuk menaruh semua kesalahan di kantong Soeharto. Gerakan "separatisme" bersenjata di Aceh sudah meletup sejak sebelum 1966. Tetapi yang membuat keadaan tambah parah adalah sifat birokratik-otoriter dari sistem yang dibangun setelah itu.
Sistem itu melihat negara kesatuan yang ada ibarat sebuah rumah yang denahnya pasti dan tinggal pakai. Orde Baru tak punya ideolog atau juru bicara yang menggugah—seperti Bung Karno—untuk membuat bangunan yang belum rampung itu menjadi suatu cita-cita yang bergelora. Sebagai gantinya, Orde Baru punya mesin pemerintahan yang bisa menjangkau ke mana-mana.
Salah satu prestasi pemerintahan Soeharto adalah perbaikan transpor dan telekomunikasi antardaerah. Tak kurang dari itu, kemampuannya untuk menampilkan birokrasi sebagai kekuatan yang tangguh -- lebih sebagai kekuatan politik yang mengendalikan masyarakat, bukan sebagai aparat publik. Ada penyeragaman desa sebagai satuan administrasi di tingkat bawah, ada keharusan setia Golkar. Intervensi Pusat atas pemilihan gubernur jadi lazim, juga pengiriman pasukan ABRI ke wilayah yang terpencil.
Namun pembentukan "Indonesia" tak cukup hanya dengan itu. Persatuan Indonesia juga tak hanya dijaga dengan menghukum siapa saja yang mencoba mengutik-utik ide negara kesatuan. Persatuan Indonesia juga perlu simbol yang tak dipaksakan dari atas. Maka, ketika simbol yang dibawakan Soeharto hampir sepenuhnya simbol "Jawa" (tentu saja "Jawa" sebagaimana ia rumuskan), mereka yang bukan-Jawa mendapatkan diri mereka dalam suasana asing. Dan ini berjalan terus terutama dengan kian terpusatnya kekuasaan negara dalam person Soeharto. Apalagi suara lain dari bawah tidak terdengar.
Refleks militer
Dalam keadaan bisu itu, pekik protes yang sedikit nyaring pun sudah dianggap ancaman gawat. Semua tahu, Aceh dirundung perasaan tertinggal secara ekonomi, juga setelah sejak 1971 Mobil OIl menemukan lapangan gas alam di Arun. Tatkala pers dan media lain ditekan, dan DPRD hanya alat pemerintah daerah, soal ini tertutup. Ketika akhirnya bulan Mei 1989 frustrasi meledak—antara lain 8.000 orang melabrak sebuah pertunjukan sirkus di Lhokseumawe—Pusat pun terkejut. Dan yang digunakan adalah refleks militer, bukan kebijakan politik: Mei tahun 1989 itu, daerah operasi militer (DOM) pun berlaku.
DOM memang bisa menaikkan uang operasi dan ketergantungan Mobil Oil, misalnya, pada proteksi ABRI. Tapi juga represi. Di banyak tempat rakyat Aceh melihat keangkuhan dan kekejaman prajurit ABRI, dan tak ada cara mengoreksi hal itu. Tentara praktis tak kenal hukum lagi. Tak ada organisasi politik di desa, tak ada sarana untuk menyatakan pendapat dan mengoreksi keadaan. Baru setelah Soeharto jatuh dan suara bebas terdengar, DOM dicabut—dan kisah kebrutalan selama inilah yang terbongkar.
Kini tinggal dilihat, terlambat atau belumkah keadaan. Kebencian sudah menjalar, dengan atau tanpa hasutan kaum "separatis". Presiden dan Panglima ABRI memang sudah minta maaf. Tapi itu tak dianggap cukup lagi, apalagi tindak-lanjutnya tak ada.. Jakarta belum mengurus keluarga korban yang sekitar 2.000 itu, menghukum sejumlah pelaku kekejaman, dan meneguhkan hak otonomi Aceh. Mungkin bahkan suatu pengaturan baru harus dilakukan. Mungkin namanya bukan federasi, tetapi yang pasti bukan seperti sistem yang sekarang dikeramatkan: negara kesatuan.Singkatnya, memberi isyarat perbaikan yang meyakinkan. Kalau tidak, proyek "Indonesia" harus ditinjau kembali.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini