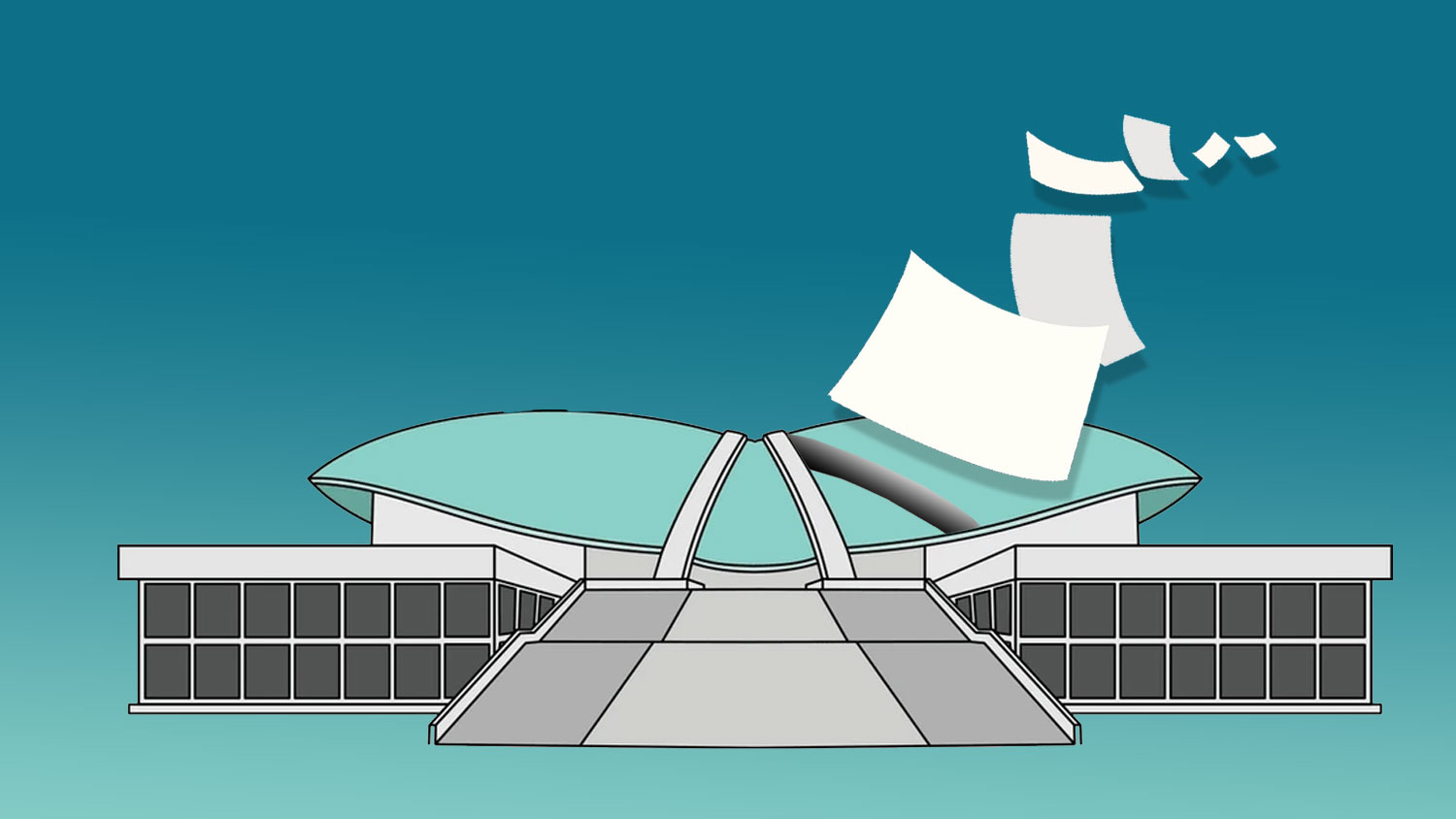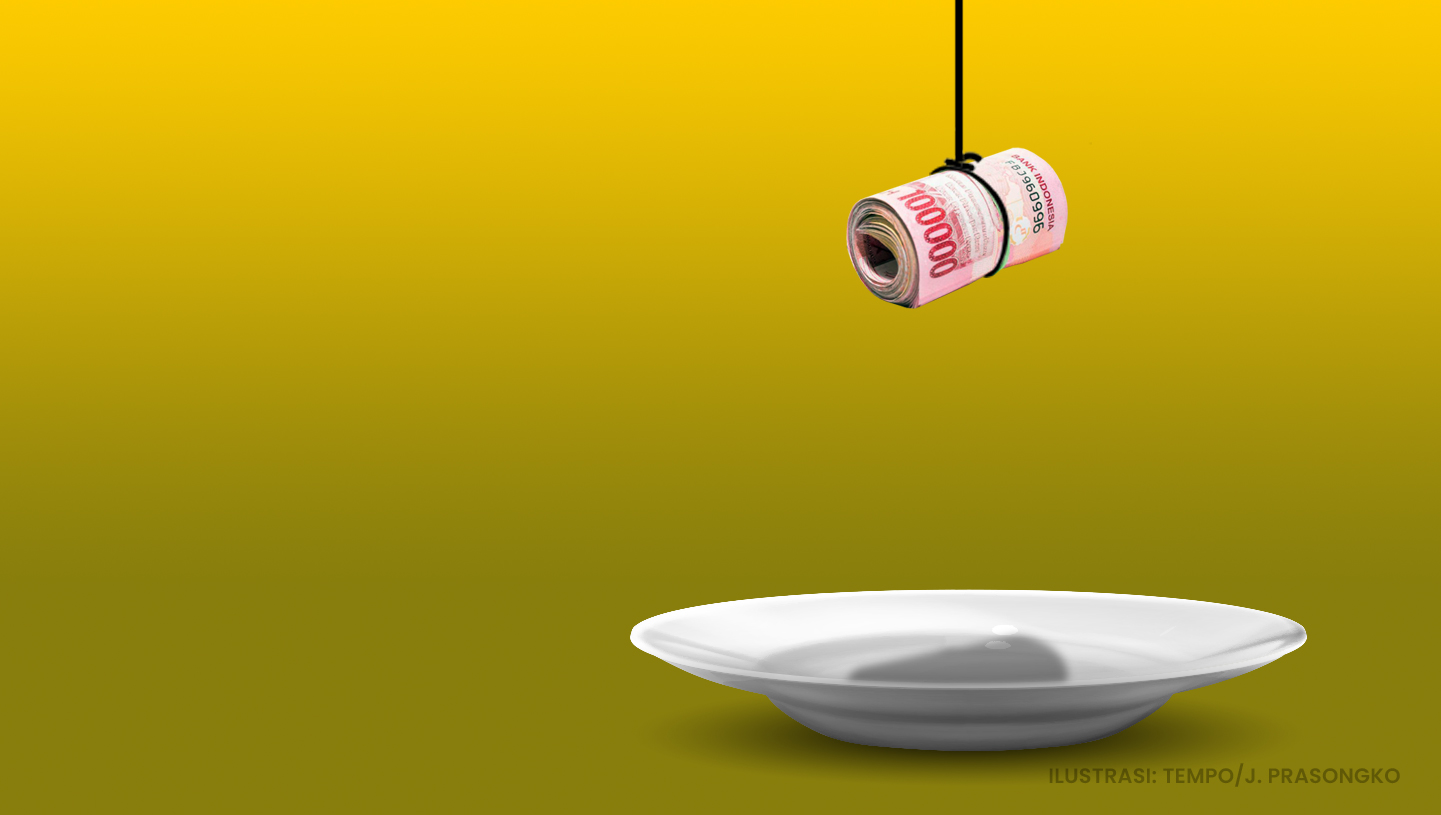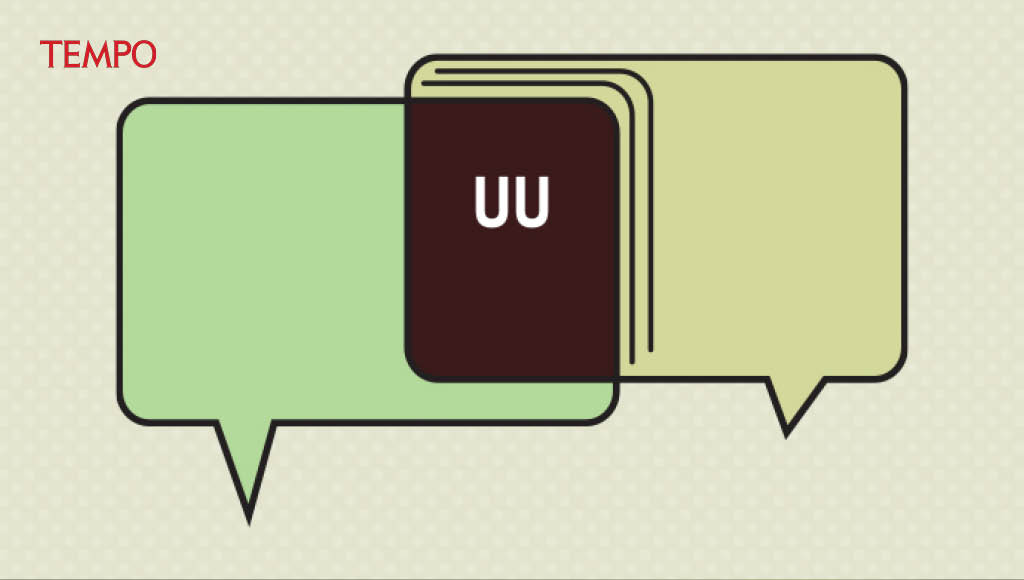Ahmad Syafii Maarif
Ketua Umum PP Muhamaddiyah
Sampai hari ini, kita baru punya tiga presiden. Ketiganya sama-sama dihadapkan kepada dilema politik dan ekonomi yang serba ruwet. Dua presiden pertama lahir dari rahim subkultur semifeodal, yang ketiga dari subkultur yang relatif demokratis dan egaliter.
Dalam wacana pergerakan nasional sejak permulaan abad ini, sebenarnya, secara teoretis masalah demokrasi sebagai sistem politik sudah selesai. Yang menjadi persoalan adalah pelaksanaannya yang tersendat-sendat dan sering benar dihadapkan kepada tembok-tembok otoriter. Bahkan yang lebih tragis lagi adalah dikeluarkannya Dekrit 5 Juli 1959 dengan membubarkan Majlis Konstituante hasil Pemilu 1955—yang dalam kenyataannya telah membunuh demokrasi atas nama Demokrasi Terpimpin. Karena sistem ini juga gagal, dikenalkan pulalah makhluk demokrasi lain dengan nama Demokrasi Pancasila. Seperti pendahulunya, sistem ini pun adalah sistem otoriter yang gagal, sekalipun berlindung di bawah payung Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Kita tengok presiden pertama. Bung Karno punya otak cemerlang dan penampilan fisik yang anggun. Dalam karir politiknya, Bung Karno memang diakui sebagai salah seorang yang sangat berhasil memporakporandakan rantai kolonialisme. Tetapi, karena partai-partai pada 1950-an selalu terlibat dalam sengketa politik yang tak kunjung usai, Bung Karno menjadi tidak sabar. Insting otoriternya, yang telah lama dibentuk oleh subkultur feodal, dari bawah sadarnya memunculkan gagasan penguburan partai-partai dan sekaligus ingin menampilkan diri sebagai penyelamat bangsa dengan menduduki posisi sentral secara nasional.
Undang-Undang Dasar Sementara 1950 hanya memposisikannya sebagai presiden simbol tanpa kekuasaan riil. Selanjutnya, atas saran A.H. Nasution, ide kembali kepada UUD 1945 diikutinya dengan agendanya sendiri pula. Apalagi, Majlis Konstituante gagal menetapkan UUD yang permanen. Dilema politik itu diatasinya dengan Dekrit 5 Juli 1959.
Ajaibnya move ini juga didukung oleh sebagian besar partai politik dalam parlemen, kecuali Masyumi pimpinan Prawoto dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) pimpinan Sutan Sjahrir. Seperti sudah dapat diperkirakan sebelumnya, nasib kedua partai ini sudah di ujung tanduk: diperintahkan bubar pada Agustus 1960. Dengan bubarnya kedua kekuatan demokrasi itu, Indonesia, tak disangsikan lagi, sedang meluncur ke jurang otoritarianisme yang didukung oleh partai-partai yang lemah karakter dan tidak punya visi yang jauh ke depan.
Dilema terberat yang dihadapi Bung Karno adalah menyikapi pemberontakan Gerakan 30 September/PKI pada 1965 dan epilognya. Masyarakat menuntut pembubaran partai kiri itu, tetapi Bung Karno menolaknya karena gagasannya Nasionalisme-Agama-Komunisme (Nasakom) pasti menjadi berantakan. Sejauh mana keterkaitan Bung Karno dengan gerakan ini belum ada kejelasan sampai hari ini. Filsafat mendhem jero mikul dhuwur (menutupi yang buruk, mengangkat yang baik) Soeharto adalah penyebab utama dari semua ketidakjelasan ini.
Kemudian diperkenalkan sistem Demokrasi Pancasila untuk menggantikan sistem lama dengan figur sentralnya Jenderal Soeharto (11 Maret 1966-21 Mei 1998). Dibandingkan dengan Soekarno yang insinyur, Soeharto lebih banyak dibentuk dalam lingkungan kemiliteran pada masa penjajahan Jepang dan sesudahnya. Sedangkan pendidikan formalnya, seperti yang dituturkan dalam otobiografinya, hanyalah sampai tingkat sekolah schakel Muhammadiyah di Yogyakarta dan tamat pada 1939.
Filsafat mendhem jero mikul dhuwur adalah cara Soeharto mengatasi dilema hubungannya dengan Bung Karno, tetapi itu tidak menyelesaikan apa-apa secara hukum dan konstitusional. Sekiranya Bung Karno diperiksa dan diadili secara santun dalam keterkaitan atau tidak keterkaitannya dengan G-30-S/PKI, sesungguhnya bangsa ini akan mendapat kejelasan historis yang diperlukan. Dan kabarnya Bung Karno memang ingin diadili secara terbuka.
Pada masa Demokrasi Terpimpin, politik adalah panglima, sedangkan pada masa Demokrasi Pancasila, ekonomi yang dijadikan panglima. Semuanya harus ditundukkan kepada ideologi ini, termasuk moral dan agama. Jadi, karena moral dan agama telah dipisahkan dari proses pembangunan, yang mengemuka pada akhirnya adalah watak serakah sentralistis yang menular ke mana-mana. Ibarat kanker, akarnya menjalar ke segala penjuru tidak bisa dibendung, telah membeliti seluruh batang tubuh bangsa. Karena itu, sejak pertengahan 1997, pada saat terjadi krisis moneter, sampai sekarang, bangsa ini menjadi tertatih-tatih.
Sebagaimana Bung Karno, Pak Harto juga tidak merasa berbuat salah apa-apa selama kepemimpinannya. Dengan demikian yang salah adalah kekuatan yang meruntuhkan rezimnya. Tentang sikap Pak Harto ini saya juga mendapat informasi dari Laksamana (Purn.) Sudomo baru-baru ini, setelah yang bersangkutan menemui Pak Harto sekitar dua minggu sebelumnya. Kata Sudomo, "Pak Harto tidak merasa bersalah apa-apa."
Bukankah fenomena ini sebuah drama, pemimpin yang lupa daratan dan lupa lautan? Bagaimana halnya dengan B.J. Habibie yang menempati urutan ketiga dari estafet kepresidenan Indonesia?
Presiden B.J. Habibie (21 Mei 1998-sekarang) muncul dalam situasi ketidakpastian sejarah dan hukum. Namanya yang agung dalam ilmu dirgantara dunia tampaknya tidak mampu menolongnya mengurus politik bangsa pada masa transisi yang kritis ini.
Sebenarnya, jika saja presiden ketiga ini mau dan berani secara tegas menyikapi rezim Orde Baru yang korup, Habibie akan dicatat sebagai presiden pahlawan. Mementum sejarah yang sedang berjalan sekarang memberi peluang emas kepadanya untuk menampilkan diri sebagai reformis sejati, sekalipun kita tahu tidak mudah baginya untuk memutuskan hubungan psikologis dengan presiden kedua yang lebih dari dua dasawarsa menjadi atasannya.
Janganlah filsafat mendhem jero mikul dhuwur dipegang secara tidak tepat sehingga hukum dan pengadilan tidak pernah difungsikan secara tegas dan tegar. Kekayaan yang menggunung yang terkumpul di tangan satu keluarga dan kroninya, secara kasat mata, harus diserahkan sebagian besar kepada negara. Beranikah Habibie menempuh jalan terjal tetapi mulia ini? Tampaknya ujian sejarah ini akan dan sedang dilalui Habibie dalam minggu-minggu mendatang yang serba menegangkan ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini