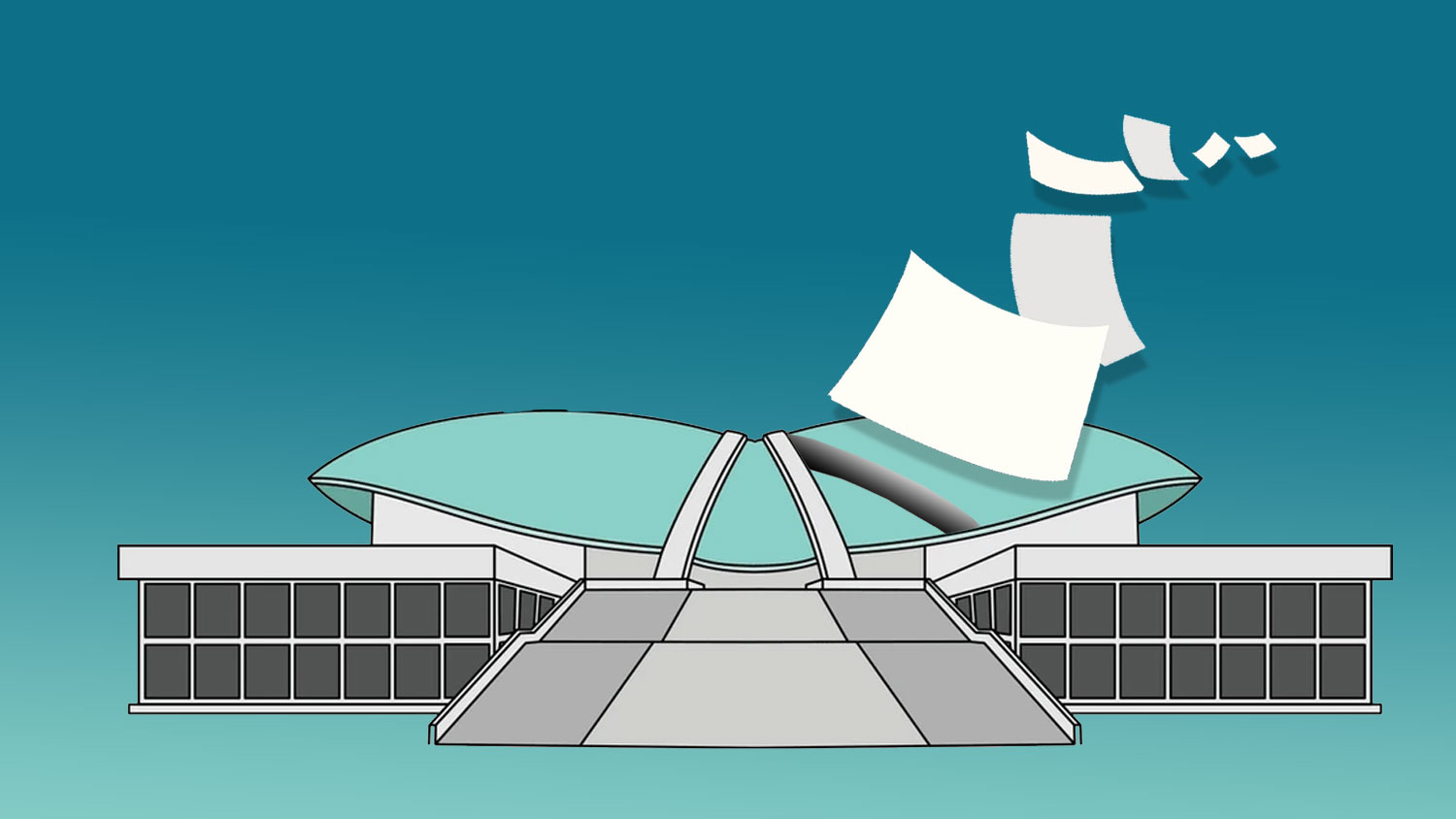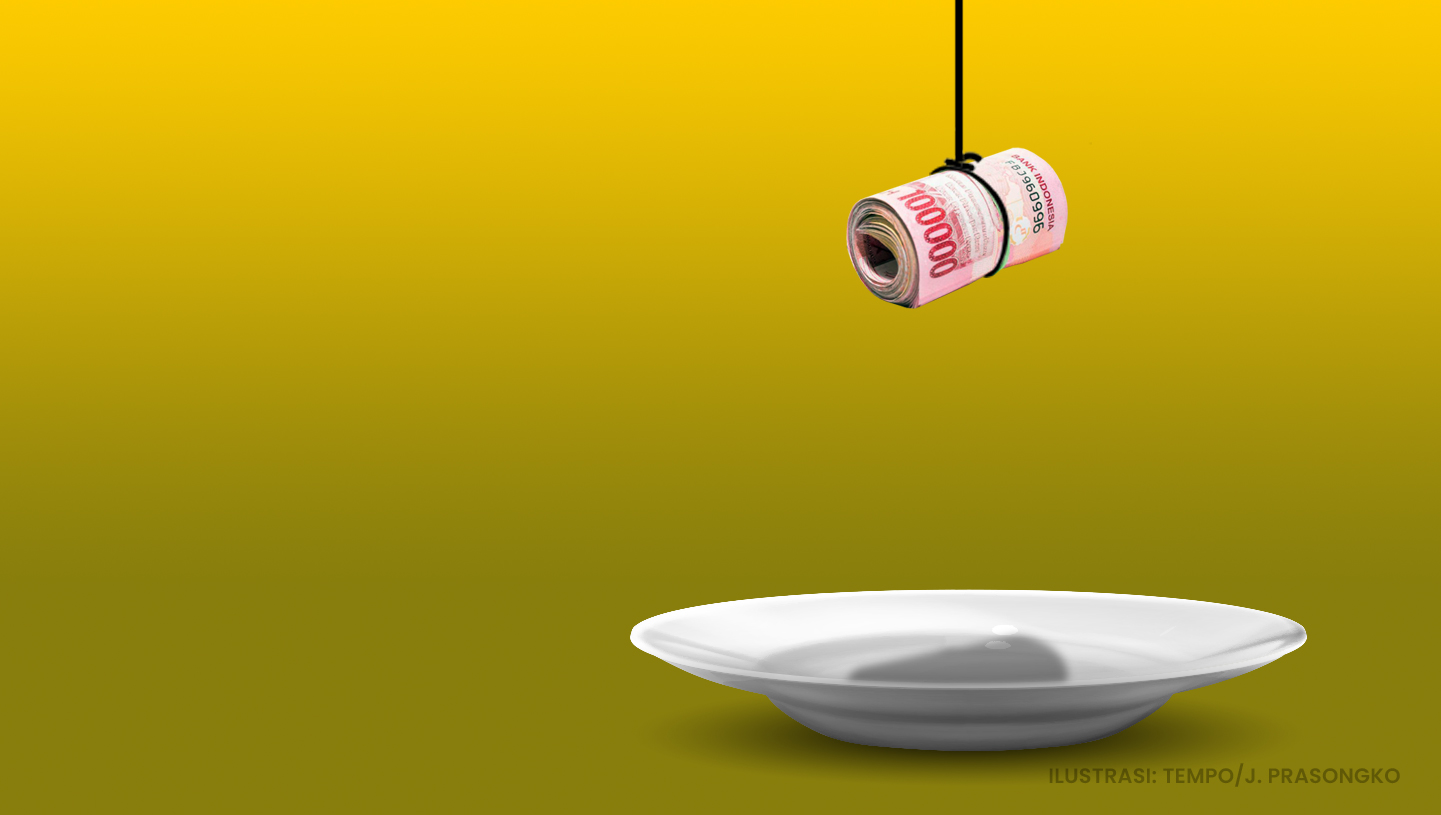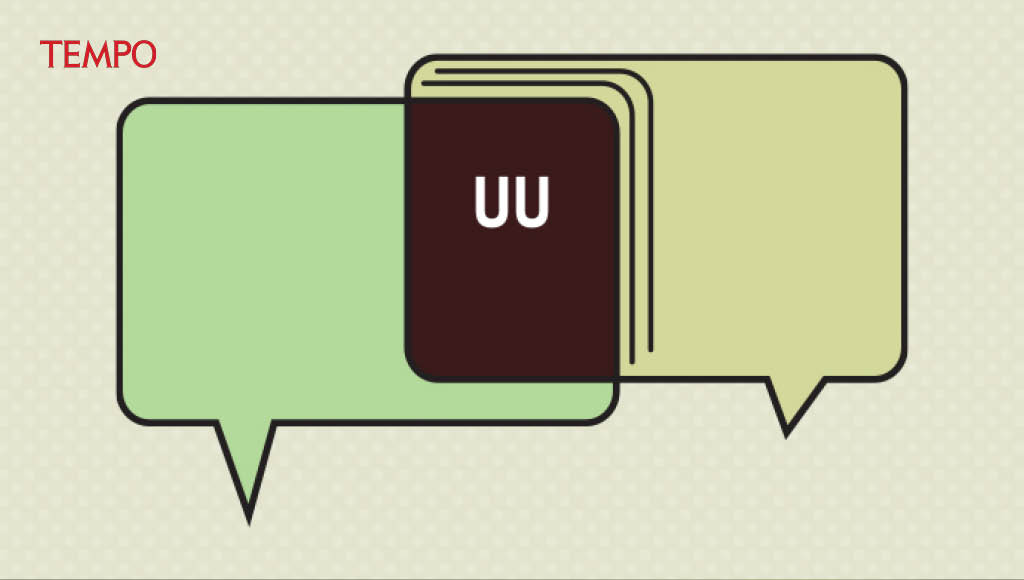Imam B. Prasodjo
Staf Pengajar Sosiologi, FISIP-UI
Haruskah penutup abad ke-20 ini disambut dengan gembira ataukah duka? Entahlah. Yang jelas, pada peralihan waktu ini, rakyat Indonesia seperti harus bersiap menyambut datangnya pemimpin-pemimpin baru, baik di tingkat lokal maupun nasional. Angin reformasi telah membawa harapan (yang tak jarang berlebihan) hadirnya pemimpin autentik, yang aspiratif terhadap rakyat. Rasa jenuh dan hambar terhadap pemimpin birokratis yang bertebaran selama ini sering memunculkan kerinduan pada pola kepemimpinan yang lebih ber-"hati." Tiba-tiba, banyak dari kita terbayang pada figur pemimpin seperti Tjokroaminoto, Hatta, Agus Salim, Natsir, atau Sjahrir. Mereka orang-orang yang tidak gemerlap, tetapi terasa begitu dekat.
Namun, apakah angin perubahan yang kini tengah terjadi akan memberi jawaban terhadap rasa kerinduan ini? Dobrakan reformasi yang melahirkan pemilu "instant" ini kiranya akan sulit begitu saja melahirkan pemimpin-pemimpin pilihan. Selama Orde Baru, sistem kekuasaan sentralistis dan dominasi birokrasi telah menghancurkan basis-basis sistem pengaderan pemimpin "bottom-up". Politik massa mengambang yang memarginalkan peran partai dan ormas telah memandulkan mesin pelatihan kepemimpinan. Akibatnya, pada masa peralihan ini, saat tokoh-tokoh status quo dituntut turun karena korup, sulit dijumpai wajah-wajah segar pemimpin terlatih dan dekat dengan rakyatnya yang tumbuh karena proses seleksi alamiah. Keadaan lebih buruk terjadi manakala perubahan sosial-politik kali ini telah menuntut pergantian kepemimpinan yang terburu-buru dan, tak jarang, asal tunjuk.
Yang dikhawatirkan adalah, pada penutup abad ini, panggung politik kita justru akan didominasi oleh munculnya tokoh dadakan, tipe pemimpin cangkokan (jadi-jadian), yang lahir bukan melalui proses seleksi ketat, tetapi muncul secara insidental dari suatu kerumunan massa. Reformasi yang kini tengah terjadi telah melahirkan begitu banyak kerumunan yang penuh amarah (angry crowds) yang menjadi tempat subur bagi munculnya "pemimpin kerumunan". Ini semua terjadi akibat kepanikan di tengah krisis ekonomi ataupun kejenuhan atas kekuasaan yang represif.
Apa jadinya bila tipe pemimpin dominan yang kita jumpai pada awal abad ke-21 ini adalah tipe crowd leadership? Sigmund Freud (Group Psychology and the Analysis of the Ego, 1921) berteori tentang model kepemimpinan "hipnotis" yang lahir akibat kerumunan (the hypnotic model of crowd leadership). Pola kepemimpinan ini, menurut Freud, berciri pada adanya pola kepatuhan mekanistis para pengikut terhadap pimpinan. Juga pada saat yang sama, kepatuhan itu dengan mudah ditularkan (suggestible) kepada sesama anggota, sehingga menjadi satu ikatan kepatuhan kolektif. Dengan demikian, setiap orang, baik pemimpin maupun pengikutnya, seperti menjelma menjadi "hypnotizer" antarsesamanya. Dapat dibayangkan, dalam pola hubungan ini, sikap rasional yang kritis antara yang dipimpin dan yang memimpin akan sulit terjadi.
Dalam kaitan ini, kita pun teringat pada Max Weber, yang memperkenalkan tipe pemimpin karismatis. Pola kepemimpinan karismatis, dalam batas tertentu, seperti mirip dengan model kepemimpinan "hipnotis" Sigmund Freud, dalam arti sama-sama melihat adanya hubungan kekuasaan yang sangat asimetris antara pemimpin dan yang dipimpin. Namun, pemimpin kharismatis terlihat lebih menempati posisi sentral dalam komunitas karena kedudukannya yang lebih sakral.
Dapat dibayangkan, tipe kepemimpinan semacam ini tentu bukan tipe yang cocok untuk masa depan demokrasi kita, yang justru sangat menuntut terciptanya pola hubungan egaliter antara yang memimpin dan yang dipimpin. Demikian pula, prinsip-prinsip egaliterian (kesamaan) justru baru tumbuh dengan baik bila tidak terjadi proses "sakralisasi" pemimpin—suatu proses yang menempatkan pemimpin sebagai "orang luar biasa" ataupun "orang suci" yang mendapatkan kedudukan khusus karena "pilihan Tuhan" atau "kekuatan gaib" lainnya. Dalam bentuk yang lebih sekuler, sakralisasi pemimpin bisa terjadi bila pemimpin mendapat berbagai perlakuan khusus yang didasarkan pada status keturunannya (ascribed status), termasuk memberi pandangan berlebih karena "kehebatan pinjaman" (borrowing status) yang diperoleh dari kedudukan sosial anggota keluarga, seperti status suami, ayah, ibu, atau nenek moyang.
Berbagai strategi dapat dilakukan untuk menghidari proses sakralisasi pemimpin. Pertama, adalah perlunya sikap masyarakat umum untuk mencoba berdisiplin tidak mengaitkan ascribed status, yang berakibat pada munculnya mitos atau penghormatan berlebihan terhadap seorang pemimpin. Evaluasi terhadap kedudukan pemimpin hanya didasarkan semata-mata pada etika, prestasi (achievement), dan kemampuan (capability) yang dimiliki. Kedua, harus dicegah terjadinya eksklusivisme pemimpin akibat proses pengambilan jarak (social distancing) yang mengakibatkan terisolasinya rakyat dari pemimpinnya. Ketiga, pemimpin harus sering terlibat dalam berbagai dialog publik sehingga publik dapat memahami pikirannya, dan sekaligus memberi ruang selebarnya untuk saling koreksi.
Kiranya, hanya dengan "membumi", seorang pemimpin dapat menghindarkan diri dari proses sakralisasi dalam dirinya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini