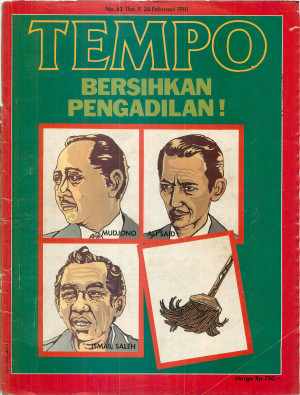PAGI itu datanglah giliranku didatangi wakil Slagorde
Purnapahlawan 45 dengan surat resmi
nomor-trek-huruf-trek-nomor-huruf-lagi-trek-tahun. Peri hal:
menjual sendok garpu piring baki dari aluminium, pisau,
gambar-gambar sablon. Mohon (sukarela wajib) menolong para
purna yang entah mengapa tidak mendapat jatah pemerataan
kekayaan rekan-rekan bekas gerilyawan lain. Tanda tangan, cap
formal? komplit dengan buku-tulis daftar nama-nama penyumbang
(hampir semua orang-orang desa sederhana) yang membeli (sukarela
wajib) barang-barang aluminium tadi dengan harga-harga bagaikan
granat mortir palagan Ambarawa.
Kupandang orang muda yang membawa komersialisasi kepahlawanan
serba aluminium itu.
"Lho, kok saudara masih begitu muda? Dulu ikut batalyon mana?"
tanyaku menguji.
Tetapi segera aku menyesal, mengapa masih bertanya begitu.
Kasihan aku terkenang pada seorang paman polisi berpangkat
sangat bawah, yang jujur, dan pernah mengeluh lunglai. Ia begitu
malu disuruh oleh kompolnya mengadakan momen surat-surat
kendaraan, tetapi sekaligus harus menjual karcis pacuan kuda
yang diproyek oleh Polri lokal.
Mungkin orang muda di mukaku itu, yang necis, yang sopan,
dengan sepatu mengkilat rambut mengkilau (benar-benar tipe
proletariat kerah putih yang memilukan) hanya di suruh ayahnya
saja. Mungkin dia malu juga mengemis begitu, tetapi apa boleh
buat.
Maka aku pun apa boleh buat, terserah dia jujur atau penipu
belaka dengan surat-surat penugasan palsu, kuikuti kawan-kawan
sedesa membeli (sukarela wajib). Sebilah pisau besi lunak,
tumpul kasar model zaman gerilya seharga Rp 400 walaupun aku
tahu, di pasar harganya cuma Rp 150 dan boleh ditawar.
Dengan menghibur diri menurut ilmu-untung Kiai Mataram dari
Beringin Salatiga: "Masih untung dia cuma menggerilya Rp 400.
Daripada yang menggerilya Rp 400 juta."
Dan pagi itu juga, para pembaca, toh terbukti Kiai Mataram
dengan ilmu Begjo-nya (yang terus terang saja tidak sepenuhnya
kuamini) mengutus pelipur lara. Seperti proletar kerah-putih
tadi, masuklah tanpa kulo-nuwun seorang koboi pribumi jelata.
Dadanya telanjang, bersandal jepit terjepit di sabuk. Ia masuk
ke dalam halaman rumah kami membawa bambu runcing kecil tetapi
panjang.
Gerilyawan juga? Ya, betul! Tetapi gerilyawan semut rangrang.
Dia datang untuk mencari itu serangga sosial besar semerah
rambut Belanda yang sengit sekali bila menggigit. Di pucuk bambu
teramat runcing itu terpasung bekas basket nasi, persis moncong
pesawat pemburu MIG yang aerodinamis.
Dengan MIG pribuminya itu sang tamu berkelana dari desa ke desa.
Pandangnya menengadah, matanya yang jeli setajam pilot Israel
menembus dedaunan. Dari jauh ia sudah mensinyalir sarang-sarang
semut Belanda yang sedang asyik bersalin. Dan rupa-rupanya pilot
MIG kita ini berhasil, sebab dalam bakul kedua yang ia bawa
kulihat seonggok besar telur-telur semut, seperti nasi belaka.
Memang akhir-akhir ini semut rangrang yang merajalela
keterlaluan, karena burung semakin bertransmigrasi ke
sangkar-sangkar orang kota yang berada. Jadi pemburu telur
semut ngangrang kita ini benar-benar berjasa, dan pantas
mendapat bintang Mahaakseptor kelas I dari Sudala Menteri Emil
Salim. Apalagi kalau anda dengar gumamnya yang berkali-kali ia
ucapkan dengan alamat padaku: "Yang penting halal, yang penting
jujur. Hidup jujur, di mana-mana punya sahabat."
Satu kilo telur semut dapat ia jual Rp 2000 kepada para cinta
burung kicauan yang seumurnya belum pernah mendengar nama Emil
Salim.
Lama kami omong-omong, atau lebih tepat, aku yang tanya dan
gerilyawan ekologi ini berkuliah. Tentang: manusia yang merdeka,
berdaulat, penuh inisiatif, bertanggung jawab. Dan last not
least, tentang istrinya yang masih muda, merdeka, berdaulat,
penuh inisiatif, dan bertanggung jawab, dan tentang anaknya
satu-satunya di SMP kelas 3 yang (kesimpulan dari penggambaran
ayahnya sendiri) saya khawatirkan akan bisa jadi seorang
proletar kerah putih di kelak kemudian hari.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini