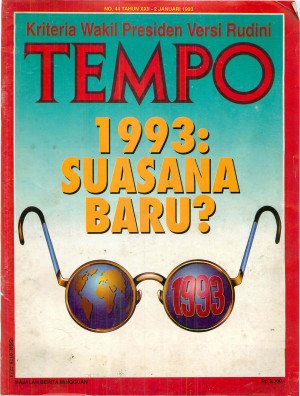KAUM muslimin dewasa ini hidup dalam tradisi kebudayaannya yang kompleks. Di kalangan cendekiawannya selalu terjadi pergulatan. Di satu pihak ada yang menginginkan terbentuknya budaya Islam yang ''ortodoks'' atau ''otentik'', sedangkan yang lain berusaha memperkembangkan dialog budaya Islam yang dinamis. Gampangnya, yang pertama cenderung melakukan konservasi budaya Islam dengan rujukan sejarah ke belakang, sementara yang kedua berupaya menciptakan bangunan budaya Islam yang berorientasi ke depan dalam kondisi sejarah yang berubah-ubah dan dalam horizon yang baru. Hal ini didasarkan atas keyakinan bahwa pemahaman Alquran dan perkembangan umat selalu memiliki dialektika, baik menurut situasi maupun pemikiran baru di luar dirinya. Karena itu harus ada ''liberalisasi'', yakni bagaimana merumuskan struktur kebudayaan modern yang memberikan ruang bagi dialektika, antara pemahaman wahyu dan pergulatan faktor-faktor kebudayaan kaum muslimin yang berbeda-beda itu. Sejarah telah mencatat bahwa Islam di Indonesia tidak luput dari dinamika pemikiran dan gerakan pembaruan. Dimulai sejak gerakan reformisme Abduh yang dianggap rasional-liberal, kemudian di Indonesia berpadu dengan paham Wahabiyah yang skriptural-formal. Inilah benih-benih kaum ''modernis'' Islam yang telah memberikan sumbangan politik tentang pentingnya merdeka dari penjajahan Barat. Sekaligus telah membuka kesadaran kaum muslimin untuk mengambil dinamika Barat yang dianggapnya telah lama hilang dari tangannya sendiri. Slogan tentang ''Islam yang dijumudkan kaum muslimin dan perlunya membuka kembali pintu ijtihad'' pada dasarnya merupakan cerminan dari kesadaran seperti itu. Hanya sayangnya di Indonesia semangat ijtihad itu lebih muncul sebagai gerakan pemurnian dalam tradisi kitab dan bukan dalam arti alam pemikiran. Karena itu, topiknya yang muncul lebih banyak soal fikih yang aneh-aneh ketimbang masalah moralitas yang filosofis. Dalam kaitan itu, mungkin bisa dicatat bahwa generasi Rasjidi, Mukti Ali, dan Harun Nasution, merupakan fenomena pertama tentang munculnya alam pemikiran yang cukup menonjol di kalangan umat Islam Indonesia yang diwarnai dengan dinamika Barat. Sebab, lepas dari soal pro dan kontra di antara mereka, dengan pulangnya dari Barat membawa filsafat dan alam pikiran, mereka telah mengenalkan tradisi pemikiran baru yang lebih didasarkan pada akal pikiran dan perkembangan pengetahuan modern di kalangan umat. Harun, misalnya, dengan kuliahnya tentang Mu'tazilah, telah memberikan sumbangan yang sangat besar bagi munculnya tradisi kebebasan berpikir yang telah menghasilkan intelektual muda yang berpikir bebas. Sementara itu, Mukti Ali tercatat yang memperkenalkan ilmu-ilmu sosial kepada intelektual muda Islam dengan kuliahnya tentang perbandingan agama dan isunya tentang metodologi penelitian agama. Tidak hanya itu, Mukti Ali adalah sponsor intelektual yang dengan limited group-nya telah menghasilkan orang seperti Dawam Rahardjo, Djohan Effendi, dan Ahmad Wahib. Pada gelombang berikutnya, dengan munculnya dua pendekar Islam dari Jombang, alam pemikiran Islam menjadi lebih semarak dalam publik dan tidak hanya terbatas di lingkungan umat Islam. Publik tidak pernah reda dari lontaran pikiran dan pemikiran dua pendekar ini, Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. Dengan sponsor media massa modern, keduanya tidak henti-hentinya menggebrak. Pada saat umat ada yang gundah tentang merosotnya partai Islam, Nurcholish berteriak: ''Islam yes, partai Islam no''. Di saat umat Islam ada yang ragu lagi tentang idiologi bangsa ini, Gus Dur dengan lantang berbicara tentang tidak adanya konsep negara Islam. Seolah-olah keduanya hendak membebaskan umat dari beban sejarah sosiologisnya selama ini, dan berupaya menegaskan bahwa umat Islam Indonesia harus bisa menjawab persoalan besarnya selama ini: kemajemukan, demokrasi, dan keadilan sosial. Saya kira, hampir semua isu yang muncul yang pernah dilontarkan kedua tokoh itu dapat dirangkum dalam tiga tema besar tersebut. Topik ''sekularisasi'', perlunya ''konvergensi nasional'', tidak ada ''absolutisme Islam''. Atau yang terakhir dari Cak Nur tentang beragama yang toleran, hampir bisa disimpulkan pesannya adalah ke arah menjawab persoalan kemajemukan bangsa. Begitu juga Gus Dur, dengan isu dan aksi politiknya selama ini tampak ingin mencari paradigma Islam yang baru yang lebih peduli dengan masalah perjumpaan Islam dengan budaya sendiri, dengan modernisasi dan pembangunan bangsa. Ruang dan diskusi Islam keduanya adalah sama: Indonesia. Bedanya mungkin ialah Cak Nur lebih mencari dasar-dasar otentitas teologisnya, sedangkan Gus Dur lebih mencari argumentasi dan aksi politiknya. Pergulatan Cak Nur ada dalam khazanah intelektualnya, sementara Gus Dur mungkin karena takdirnya sebagai ketua NU maka tidak bisa tidak ia masuk dalam realitas politik yang sesungguhnya, yakni kekuasaan. Saya khawatir, seperti yang kita lihat selama ini, Cak Nur akan menghadapi keawaman yang marah, yang bertanya: Islam kita hendak dibawa ke mana? Dan Gus Dur, sebagai konsekuensi dunianya, tentu harus lebih sabar. Bukan saja dimarahi umatnya tapi mungkin juga harus menanggung risiko jika dalam kalkulasi politiknya ada yang tidak tepat. Namun, jika boleh dibilang bahwa gerakan Cak Nur adalah gerakan ide, biarpun ide memang mempunyai kaki sendiri, juga diperlukan mekanisme yang bisa lebih efektif untuk menggerakkan kaki-kaki ide tersebut. Karena itu, selain memiliki teater sebagai forum penyampaian ide, barangkali juga harus ada padepokan dan jaringan kader. Semacam limited group yang bisa menghasilkan Ahmad-Ahmad Wahib baru. Adapun Gus Dur, yang gerakannya boleh dikatakan adalah gerakan transformasi umat, yang masih jadi masalah ialah belum ada mesin sosial yang paham dan dapat digunakan secara efektif mendukung gagasan-gagasannya selama ini. Apakah benar begitu, tentu kedua pendekar itu sendiri yang bisa menerangkan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini