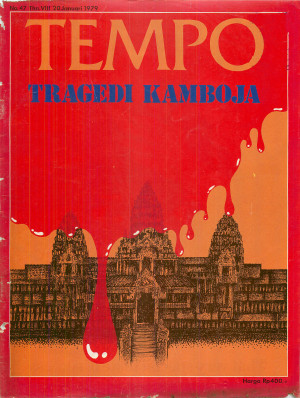DUA orang kulit putih berbicara tentang rakyat sebuah negeri di
wilayah Indo-Cina. Yang satu cemas negeri itu akan jatuh ke
dalam pemerintahan komunis. Yang lain nampaknya tidak cemas --
meskipun ia tahu bahwa itu memang akan terjadi.
"Tapi mereka tak menginginkan komunisme," kata yang cemas.
"Mereka menginginkan beras," sahut yang lain, "mereka tak ingin
ditembak. Mereka ingin suatu hari akan sama seperti hari yang
lain. Mereka tak ingin kita, orang putih, berseliweran di sini
mengajari mereka apa yang harus mereka inginkan."
"Jika Indo-Cina jatuh . . . "
"Saya sudah tahu rekaman itu. Siam jatuh. Malaya jatuh.
Indonesia jatuh. Apa artinya 'jatuh', sih?"
"Mereka akan dipaksa percaya apa yang diperintahkan kepada
mereka. Mereka tak akan diizinkan berfikir sendiri. "
"Fikiran itu barang mewah. Apa kau fikir para petani itu duduk
merenungkan Tuhan dan demokrasi ketika mereka masuk ke dalam
gubuk tanah liat mereka di waktu malam?"
"Kau bicara seakan-akan seluruh negeri terdiri dari petani.
Bagaimana halnya dengan mereka yang terdidik? Apakah mereka akan
berbahagia?"
"Ah, tidak. Kita sudah membesarkan mereka dalam ide-ide kita.
Kita telah ajari mereka permainan-permainan berbahaya, dan
itulah sebabnya kita menunggu di sini, berharap bahwa leher kita
tak akan dipotong. Sebenarnya kita layak dipotong .... "
***
HAMPIR selama seperempat abad setelah Graham Greene menuliskan
percakapan semacam itu dalam The Quiet American, banyak yang
terjadi di Indo-Cina.
Di Samlaut, misalnya, di tahun 1966. Samlaut adalah sebuah kota
kecil di timur Battambang, Kamboja. Ia terletak di sebuah
wilayah hutan yang tersisih. Di sana tinggal pors, anggota
sebuah suku yang agak terlupakan dalam sejarah modernisasi
Kamboja di bawah Pangeran Sihanouk.
Pada suatu hari para penguasa di Battambang memutuskan untuk
membangun sebuah pabrik gula di Kampong Kol di dekat Samlaut.
Mereka mengambil tanah dari para petani dan para petani tak
memperoleh imbalan cukup. Ketidak-puasan timbul. Mereka
berontak.
Memang, ada unsur "subversi" dalam pemberontakan itu. Di antara
penduduk ada kader-kader komunis Vietnam yang telah tinggal di
situ sejak perang Indocina pertama. Setelah perjanjian Geneva
1954, mereka rupanya diinstruksikan tinggal oleh partai. Konon
ada 200 bedil tersembunyi di hutan itu. Dan dengan hasutan
kader-kader Vietnam komunis itulah jacquerie di Samlaut terjadi.
Pemerintah pusat di Phnom Penh bertindak cepat -- tapi
berlebihan. Militer didatangkan. Satuan polisi juga dikirim.
Kedua pasukan bersenjata itu dengan tanpa banyak pertimbangan
menembaki para perusuh, merobohkan banyak korban dan membakar
rumah penduduk. Rakyat lari masuk hutan. Tapi mereka tak
melupakan ketidak-adilan dan kekejaman yang terjadi. Dan kaum
komunis mendapatkan lebih banyak penyokong.
Petani, seperti dalam bayangan orang putih Graham Greene, memang
tak biasa mempersoalkan komunisme atau Tuhan. Tapi benarkah
mereka hanya menginginkan beras? Benarkah bagi mereka "fikiran
itu barang mewah"? Orang putih Graham Greene, seperti banyak
intelektuil putih, kadang merasa jadi "pembela" petani Asia --
tapi dengan sikap merendahkan yang tak sepenuhnya disadari: Si
orang putih percaya petani tak akan memikirkan demokrasi di
gubuknya.
Tentu saja tidak. Tapi kemarahan petani di Samlaut, tanpa bicara
demokrasi, adalah kebutuhan akan pengakuan hak. Dan bila para
petani di Cina datang ke ibukota menyerukan hak-hak asasi,
sementara para petani Kamboja dan Vietnam lari menjadi
pengungsi, benarkah mereka hanya menginginkan beras?
Mereka bukan kerbau, mereka bukan sampi, kata Sihanouk tentang
rakyatnya yang tertindas. Agak telat, tapi lebih benar dari
orang putih Graham Greene, seperempat abad yang lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini