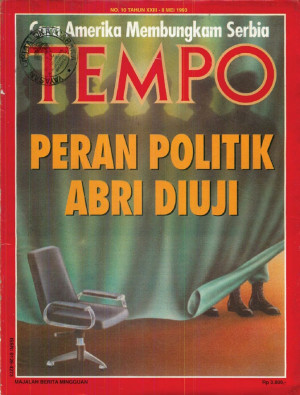FASISME bisa punya daya tariknya sendiri. ''Every woman loves a fascist,'' kata salah satu baris sajak penyair wanita Amerika terkenal, Sylvia Plath. Kaum feminis jangan marah: Sylvia Plath, seperti banyak penyair, sering menuliskan kalimat yang mengejutkan dengan gema yang bisa bermacam-macam. Toh kita tahu bahwa keterpesonaan orang kepada kaum fasis tak hanya menyangkut perempuan- perempuan. Fasisme melontarkan bayangan kegagahan, kekuatan yang megah dan juga muram. Kaum militeris di Jepang, kaum pengikut Mussolini di Italia yang berseragam hitam, kaum Nazi yang memakai baju cokelat dengan selempang kulit: semua mereka mengumandangkan keinginan yang sering merayap di hati kita keinginan untuk meraih sebuah gambaran ideal manusia: manusia sebagai tokoh yang perwira dan murni, makhluk yang tak jadi lembek oleh hidup empuk dalam keseharian dunia modern. Juga: makhluk yang bertindak, tak merenung. Mereka memimpikan kembali keteguhan para samurai, keperkasaan para prajurit Romawi, keunggulan jiwa raga para kesatria dalam dongeng Nibelungen. Ada sesuatu yang romantik di situ. Ada sesuatu yang ''indah'' tetapi juga sekaligus menakutkan. Kita bisa melihat tali samar-samar yang menghubungkan seorang seperti Hitler dengan musik Wagner sebagaimana kita pun melihat garis lurus yang seperti tak sengaja antara fasisme dan Yukio Mishima, sang novelis Jepang. Kita ingat bagaimana Mishima memaklumkan kekecewaannya kepada kehidupan Jepang yang baru, sebelum ia dengan pakaian seragam militer yang tampan merobek perutnya sendiri dengan pedang. Ia masygul bahwa Jepang berubah: orang lebih memilih semangat saudagar, bukan semangat prajurit kamikaze orang lebih menyukai hidup dalam angka dan prosa, bukan dalam epos. Keindahan memang bisa berlebihan, dan orang bisa terperosok ke dalam ''estetisme'': paham bahwa keindahan memimpin segala- galanya. Ada seorang yang mengatakan bahwa Naziisme pada dasarnya adalah ''estetisme nasional'': sebuah pemikiran yang mengaburkan batas antara dunia politik dan dunia seni sedemikian rupa sehingga masyarakat itu sendiri menjadi sejenis pertunjukan total, suatu Gesamtkunstwerk. Di situ, visi sang ''seniman'' atau kehendak sang Pemimpin tak bisa dibedakan dari pikiran dan hasrat rakyat, yang ditakdirkan bermain dalam drama yang megah dan dahsyat itu. Tampaknya, itulah sebabnya fasisme memikat, tak saja buat para perempuan (seperti dikatakan oleh Sylvia Plath), tapi juga buat Mishima. Tak cuma buat Mishima, tapi juga buat Heidegger, filosof Jerman yang termasyhur sebagai pelopor ''post- modernisme'' yang ternyata setidaknya menurut Philippe Lacoue- Labarth dalam Heidegger, Art and Politics mendukung semangat Nazi bukan cuma secara kebetulan. Namun, mungkin masalahnya bukan terletak pada hubungan fasisme dengan kegandrungan kepada segala hal yang estetis. Kini kita sudah tahu bahwa ada yang menjijikkan dalam fasisme. Kita muntah menyaksikan pemujaannya kepada keelokan dan keperwiraan, obsesinya terhadap ide tentang masyarakat sebagai sejenis pertunjukan total. Kita telah melihat bagaimana kaum militeris Jepang meletakkan kekerasan terhadap manusia sebagai bagian dari tugas suci, dan bagaimana kaum Nazi membunuhi orang Yahudi (juga orang ''non-Aria'' lain) agar dunia jadi lebih ''necis''. Kita telah menyaksikan bagaimana barisan masal, musik mars, pakaian seragam dan derap bersama pada akhirnya meskipun menampilkan sesuatu yang sedap dipandang mengancam kemerdekaan manusia. Rasanya memang ada yang salah dalam cara kaum fasis memandang keindahan dan menilai sejarah. Keindahan bagi mereka adalah sesuatu yang necis, rapi, terkendali dengan disiplin, seperti otot para pahlawan dalam dongeng-dongeng lama. Sejarah bagi mereka adalah sebuah jalan mundur: di masa kini yang kita alami adalah kemerosotan, kebangkrutan, sementara di masa silam yang ada adalah model kesempurnaan. Padahal, di dunia, ada hal-hal yang sangat berharga meskipun tak necis. Hidup bukanlah sebuah pentas balet Bolshoi, bukan parade para kadet di hari besar nasional. Tapi kita bisa menyukainya, meskipun di masa lampau kita tak punya surga dan tauladan suci. Setidaknya kita tak pernah bisa berjalan mundur. Kita toh bisa mensyukuri masa kini (dan berharap di masa depan). Ketika fasisme menampik semua itu, pada dasarnya ia menyiapkan kematian, dengan senjata atau bukan. Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini