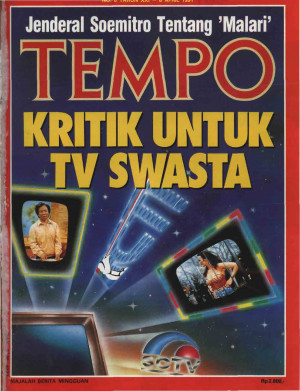BARU beberapa bulan tinggal di kota, Bakir sudah tidak betah. Bekerja pun tak tenteram. Sesudah usia dewasa, baru sekali ini ia merasakan lagi berpuasa di kota. Bukan tak dapat menahan lapar dan haus, tapi tak dapat menahan kantuk, kurang tidur selalu. Kembali ke desa, hanya beberapa kilometer dari kota, enggan rasanya, karena kurang bebas. Bakir sekeluarga pindah ke kota karena rumah warisan ayahnya kosong, setelah berkali-kali ditawarkan untuk dijual atau dikontrakkan tidak laku. Kakaknya, yang jadi pengusaha di kota, mencoba menawarkan kepada Bakir kalau-kalau mau pindah ke kota, sekalian membantu usahanya dan menempati rumah warisan orangtua mereka. Mendengar rencana ini, mata istri Bakir berbinar-binar kegirangan. Mereka memang turunan orang kota. Tetapi Bakir kemudian memilih tempat di luar kota setelah menikah dengan gadis setempat. Ternyata, betah, sambil berkebun buah. Sekali-sekali ia ke kota berbelanja bersama istri, sekalian menengok kakaknya. Di desa tempat tinggal Bakir ada kegiatan pengajian yang diselenggarakan Kiai Haji Manap, dua kali seminggu. Karena rumahnya berdekatan dengan rumah Kiai, dia dan istrinya termasuk yang rajin menghadiri pengajian. Kiai yang menganut aliran tasawuf dan memimpin tarekat ini memang pandai, ceramahnya mengenai agama atau masyarakat selalu menarik, di sela-sela dengan lelucon. Pengikut Kiai Manap bukan hanya dari daerah itu saja, tapi sampai ke desa-desa lain di sekitarnya. Pada hari-hari pengajian, rumahnya penuh sesak oleh jemaah. Bakir dan istrinya merasa senang dengan ajaran Kiai kendati mereka tidak ikut tarekatnya. Hanya satu hal yang kurang kena di hatinya: menurut penilaian Bakir, pandangan Kiai yang disegani penduduk ini masih kolot. Ia mengharamkan televisi sehingga di desanya tak ada orang yang berani memasang peti gambar itu, kecuali yang berjauhan dari rumah Kiai. Anehnya, pikir Bakir, Kiai tidak keberatan listrik masuk desa. Pasal keluarnya fatwa mengharamkan televisi itu bermula ketika Kiai ke kota, dan bermalam di rumah saudaranya yang punya televisi. Karena yang banyak ditayangkan adalah film Barat, setiap Kiai duduk di depan layar kaca itu, yang muncul kebetulan hanya paha-paha dan ketiak-ketiak perempuan bule, entah dalam acara balet, sirkus, rock and roll, olahraga, dan semacamnya. Menurut mata Kiai, keadaannya kok terbalik laki-laki berpakaian memenuhi ketentuan syariat, tetapi perempuan berpakaian maksiat, memamerkan aurat. Jadi, kesimpulannya, televisi haram. Pada suatu hari baik, Bakir berdiskusi dengan Kiai tentang betapa bermanfaatnya televisi. Pada malam Jumat, ada siaran agama, pembacaan Quran pada hari-hari besar Islam, perayaan Maulid, Isra, dan sebagainya disiarkan langsung dari Masjid Istiqlal. Belum lagi siaran pedesaan yang cocok buat warga desa. Tetapi Bakir kalah berdebat. Kata Kiai, dengan membawa dalil-dalil, semua itu bidah. Bakir tidak mengerti seluk-beluk agama. Ia diam, menerima kalah. Tidak itu saja, teringat dia, di masjidnya tak ada loudspeaker, karena juga bidah kata Kiai. Akibatnya, desa itu sunyi. Bila matahari mulai terbenam, yang terdengar hanya konser alam, suara-suara jangkrik, uir-uir, dan kodok. Satu dua rumah ada yang memasang radio atau kaset kalau kebetulan ada lagu-lagu kasidah, tapi tak berani keras-keras. Setelah mendapat ajakan kakaknya di kota, dia berpikir-pikir, siapa yang akan mengurus kebunnya nanti. Ah, serahkan saja kepada Haji Yatim, yang masih kerabatnya. Sekolah anak-anak bagaimana? "Sekolah anak-anak kan memang sudah di kota, setiap hari naik kendaraan umum," kata istrinya memperkuat desakannya. Selain akan mendapat tambahan penghasilan, di kota, mereka dapat menonton televisi, berjalan-jalan menikmati hiburan kota. Sekali seminggu pulang kampung menengok kebun dan rumah. Ketika melihat rumah yang akan ditempati, mereka puas. Cocok. Rumahnya sederhana, tapi terasa lingkungannya lebih bersemarak. Lebih beruntung karena rumah itu dekat masjid, sejuk rasanya, seperti di desanya. Bahkan ada beberapa musala di sekitar tempat itu. Pada hari-hari pertama saja, mereka sudah dapat menyesuaikan diri. Terasa memang agak bising sedikit. Tidak apa, kata istrinya, lama-lama terbiasa juga. Tindakan pertama yang mereka lakukan sebelum menempati rumah itu adalah membeli pesawat televisi. Hanya saja, setelah memasuki bulan Ramadan, makin lama suasananya makin ramai, makin bising, meski sebelum itu pun memang sudah mulai terasa. Bukan saja bunyi beduk, tapi suara-suara keras dari masjid dan musala, meraung-raung dari kanan, dari kiri, dari muka, dari belakang, hampir semalam penuh. Mulai dari menjelang magrib, disambung dengan salat tarawih dan ceramah. Lepas tengah malam, diselang-seling dengan pembacaan Quran, kadang sampai menjelang waktu sahur. "Kalau tanpa speker, tak apalah. Mereka menganggap dunia ini kepunyaan mereka sendiri saja," kata Bakir dalam hati. Ia tak berani bicara terus terang karena semua kegiatan itu mengatasnamakan agama. Apa daya, sudah beberapa malam ini keluarga Bakir tidur tak nyenyak. "Kalau begini terus-terusan, belum sampai berlebaran kita sudah jatuh sakit, Bang. Kasihan anak-anak," kata istrinya memelas. Ketika baru dua tiga hari bulan Puasa, suami-istri itu rajin ke masjid terdekat, ikut salat fardu dan salat tarawih. Lambat-laun, karena kesal, setop. "Kita salat di rumah saja, Bang," kata istrinya. "Tapi di rumah juga ibadah jadi terganggu," kata sang suami. "Lebih baik kita pulang kampung saja." Mereka menyampaikan keluhan itu kepada kakaknya. Sebenarnya, ada sesuatu yang dirahasiakan sang kakak kepada Bakir suami-istri. Ketika dulu mereka bersepakat, rumah waris dijual atau dikontrakkan saja, celakanya, semua calon pembeli dan pengontrak mundur setelah melihat lokasi. "Kalau memang sudah tak dapat ditahan," kata kakaknya kemudian, seperti putus asa, "sabarlah, Kir, sampai sesudah Lebaran yang hanya tinggal beberapa hari lagi." Tiba-tiba istrinya teringat pada fatwa Kiai Manap. "Lalu, televisi kita bagaimana, Bang?" tanyanya penasaran dengan suara garau.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini