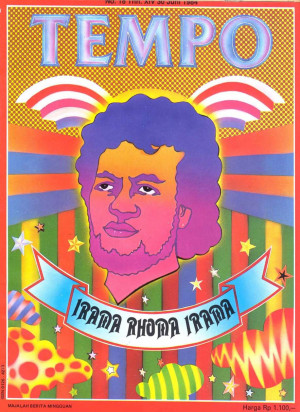PADA suatu hari di kampung saya dulu, seorang tetangga memperkenalkan sesuatu yang baru ke sekitar: orkes gambus. Ia, yang lebih berada dari yang lain-lain, punya hajat. Penyunatan anak sulungnya hendak ia rayakan secara istimewa. Orkes itu pun didatangkannya dari kota. Pukul 20.00 musik berbunyi. Pengeras suara (juga sesuatu yang baru) seakan memaklumkan kehadiran para pemain dan penyanyi yang 11 orang itu. lampu listrik dipasang terang di beranda yang empunya hajat. Dan orang desa pun - kebanyakan petani dan nelayan berbaju kasar cokelat gelap - datang berbondong. Orkes gambus itu memang suatu sensasi tersendiri. Selama ini orang kampung kami umumnya menggemari ketoprak, sandiwara Jawa dengan lakon dongeng atau kisah sejarah. Bahkan mereka sempat membentuk grup ketoprak amatir sendiri. Dengan itu mereka naik ke pentas kayu yang cara darurat didirikan di dekat sungai atau di lapangan rumput bekas pabrik gula abad ke- 19. Dan bila tak ada ketoprak dan tak ada wayang, mereka pun nonton rombongan doger yang datang - dengan segala follow-up-nya, termasuk membawa seorang doger kesemak-semak yang gelap untuk beberapa rupiah ciuman. Waktu itu saya masih di kelas VI sekolah dasar. Ketika saya menyelinap di antara jubelan penonton orkes gambus itu, saya terkesima oleh dua hal. Yang pertama adalah bahwa para penyanyinya menggerak-gerakkan seluruh tubuh mereka, seperti pohon-pohon didera angin. Yang kedua adalah bahwa di antara penyanyi itu ternyata ada teman saya sekelas, Rajak. Esok harinya di kelas saya tanyai Rajak. "Kenapa tubuhmu dan yang lain-lain bergoyang-goyang waktu nyanyi gambus?". Rajak, yang jauh lebih tua dari saya, dan anak perlente, tersenyum kecut. "Supaya jangan ketahuan kami gemetaran," jawabnya. Saya pikir, dia bohong. Tak berapa lama sesudah Rajak dkk. bergoyang-goyang, orkes gambus dan orkes Melayu dan film India dan lagu India secara cepat memulut ribuan orang. Di RRI Studio Jakarta, Abdul Harris menyanyi dengan suara bariton sebuah lagu yang tak ketahuan asal usulnya, Awarahum. Sebuah lagu lagi kemudian tetap populer 30 tahun kemudian, Larilah Hai Kudaku. Maka, satu tipe musik baru yang kemudian disebut "dangdut" pun lahirlah di Republik Indonesia. Di kota kecil kami sendiri, sementara itu, bioskop baru dibangun. Orang tak lagi menonton, berulang kali, Captain America yang bisu di bangunan yang dindingnya seng tua. Kini yang didatangi adalah sesuatu yang lebih gemerlapan dan sekaligus cocok dengan dongeng tentang raja dan pangeran: film India. Sejumlah orang Bombay tertentu pun disebut hangat di rumah-rumah: Shakila yang cantik, Mahipal yang berkumis, dan Raj Kapoor yang oleh tukang becak dan murid sekolah disebut sebagai "Rai Kapur". Bahasa Hindi pun masuk ke kosa kata kedai kopi: nehi berarti "tidak" dan sukriya berarti "matur nuwun". Agaknya ada sesuatu yang khas hingga itulah yang terjadi. Mungkin ada afinitas, ada persamaan ataupun kecocokan antara jutaan orang di Indonesia dan jutaan orang di Asia Selatan sana. Pada tahun 1966 saya berada di kampus sebuah universitas di Norwegia. Saya berkenalan dengan seorang insinyur listrik dari Pakistan, yang entah kenapa bernama Ali Khan. Suatu hari, sehabis mencoba bermain tenis secara ngawur dengan dua cewek Skandinavia, Ali Khan saya dengar bernyanyi-nyanyi kecil. Segera saya kenali: lagu dangdut. "Dari mana kau belajar lagu itu?" tanya saya. "Dari film India, waktu saya tinggal di Turki," jawabnya sembari menghapus keringat. Lalu Ali Khan pun meneruskan nyanyiannya: ... dunyia ... dunyia .... Pakistan, India, Turki, Indoncsia .... Kenapa justru dangdut? Saya tidak tahu. Tapi seorang teman punya teori. Ia konon sudah bikin studi atas pelbagai musik yang terutama menggunakan alat gesek, suling, dan gendang. Dalam musik-musik itu, katanya, yang dominan adalah elaborasi atas melodi, bukan kerapian harmoni. Dan bagi orang Indonesia, itu adalah semacam pembebasan: tatkala soal harmoni jadi soal yang kritis dalam kehidupan sosial, melodi yang berhanyut-hanyut bisa membuka gerbang jiwa yang lain. Lalu orang pun berjoget atau, seperti Rajak, teman saya dulu, bergoyang. Tentu saja, sebagaimana teori-teori lain, teori kawan itu sukar dipahami. Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini