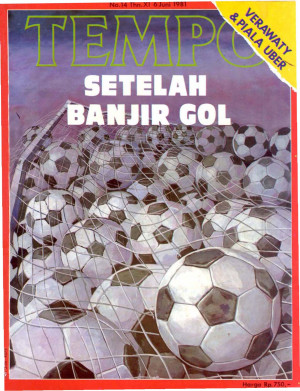MEREKA yang secara sukarela pergi ke medan perang jangan
mengeluh akan getirnya asap meriam." Itu suara hakim Musmanno di
tahun 1935 yang membacakan putusan suatu pengadilan diatrik AS
berkenaan gugatan penduduk untuk menutup pabrik semen yang
mengganggu lingkungan setempat.
Di Indonesia, 1981, seorang pengusaha industri belerang untuk
pembersih air minum menanyakan kepada Menteri PPLH Emil Salim,
apakah masih terjamin masa depan pabriknya. Sebab waktu ia
membangun kilang tersebut lebih dari 10 tahun silam, daerah itu
bagaikan tempat jin buang anak. Pemerintah lokal saat itu tentu
saja memuji usaha pionir itu -- selain memajukan industri, juga
mengembangkan wilayah kota. Kini penduduk telah banyak sekitar
pabrik, dan mulai rewel dengan urusan lingkungan.
Tentu saja persoalan yang diajukan sang industriawan tak dapat
langsung dipecahkan secara tuntas di forum pertemuan ramahtamah
itu. Tapi begitulah. Lingkungan hidup (LH) menjadi masalah dalam
suatu kondisi penuh ramuan berkait seperti ini: ledakan
penduduk, tataruang menjadi sempit, sumber daya terbatas,
sementara proses pembangunan makin meriah dan teknologi makin
berkembang.
Tak ada yang salah. Hanya soalnya, "komoditi" LH sebagai suatu
kebutuhan dalam beberapa aktivitas belum diperhitungkan secara
tuntas -- dan agak sial karena ada kesan, masalah LH
diterbangkan dari negeri maju juga.
Padahal ini tidak betul. Manakala corong halo-halo dari masjid
kampung seberang menyerukan para warga untuk berpatungan
membersihkan lingkungan kediaman, orang serempak toh sadar bahwa
sikap selama ini harus disempurnakan.
Masalah LH membimbing manusia untuk menata aktivitas mereka
sendiri, agar pencapaian maksud serasi dengan akibat yang
ditinggalkan.
Umumnya dikatakan bahwa dampak negatif dari pembangun haruslah
dijauhi, setidak-tidaknya diperkecil, sehingga manusia yang utuh
dapat tegak sejahtera. Prinsip ini dikandung hampir dalam semua
legislasi LH di mana-mana. Di AS, ada beleid pemerintah federal,
National Environmental Policy Act (NEPA), 1969. Di Jepang ada
Basic Act for Environmental Control, 1967. Di Jerman ada UU LH
Nasional, 1970.
Indonesia belum memiliki suatu UU LH yang terpadu, yang
mencerminkan suatu kebijaksanaan nasional. Namun sandaran untuk
bergerak ke arah itu telah disodorkan oleh UUD 1945 pasal 33 (3)
yang sering dibicarakan itu, yakni bahwa bumi dan kekayaan
alamnya "dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat."
Dalam cakrawala yang sesungguhnya, "kemakmuran" bukan hanya
kesejahteraan dalam kaitan ekonomis, tapi juga ekologis.
Kandungan pengertian yang luas ini dapat diteruskan pada
pengertian "rakyat" sebagai penghuni bumi pertiwi, bukan saja
pada masa sekarang, tapi juga generasi mendatang. Duduk pada
sandaran di atas, GBHN 1978 berwanti-wanti lebih jauh tentang
perlunya penjagaan keseimbangan antara pembangunan dan
perlindungan LH.
Namun tiada keseimbangan, keselarasan, keserasian atau harmoni
tanpa suatu harga. Menteri Perindustrian A.R. Soehoed belum lama
ini ada mengingatkan bahwa masyarakatlah yang menentukan tingkat
pencegahan pencemaran -- karena ini berkaitan dengan kemampuan
mereka untuk memikul biaya bagi tindakan tersebut. Atau dengan
alternatif sampai ke tingkat mana orang banyak dapat menerima
adanya pencemaran.
Cepat atau lambat, masyarakat memang akan menghadapi situasi
demikian. Secara individual, jika penduduk merasa tak pas lagi
tinggal di sekitar pabrik yang mecemari, biaya harus
dikeluarkan untuk pindah. Tapi kalau prinsip pencemar harus
membayar, atau terkenal dengan polluter pays principle hendak
diacukan, maka pabrik harus memasukkan biaya penanggulangan
pencemaran yang umumnya mahal itu, sebagai komponen biaya
produksi atau internalisasi biaya. Dan karena produsen tentu tak
mau menciutkan laba, biaya inipun disalurkan kepada konsumen
lewat kenaikan harga produksi.
Sebagian pengamat menilai, apa boleh buat, keadaan semacam ini
masih adil, karena hanya para pemakai barang itulah yang kena
beban -- tidak lagi masyarakat yang tak ada kaitannya dengan
produksi barang itu, dengan menanggungkan beban pencemaran
ataupun pindah. Tapi konsumen tertentu pun akan berkata, kenapa
mereka turut membayar biaya untuk LH yang jauh dari tempat
tinggal mereka.
Mengikuti hukum pasar, maka dalam hal demikian orang akan lari
ke merk yang lain, atau ke barang lain. Hanya dalam hal barang
tersebut amat diperlukan orang banyak substitusi tak seberapa
problem akan timbul. Biasanya di sini pemerintah, sebagai
pengelola LH, turun tangan mengulurkan bantuan, mungkin berupa
bantuan pengadaan alat pencegahan pencemaran atau keringanan
pajak dan sebagainya.
Ini penjabaran sederhana. Sebab masih bisa dipertanyakan, apakah
dengan adanya internalisasi biaya itu, produsen tidak terlebih
dahulu terpanggil untuk meninjau kembali proses usaha
industrinya, termasuk teknologi yang dipakai, sehingga dengan
berbagai modifikasi, pencemaran dapat diperkecil sampai ke
tingkat yang masih bisa ditenggang. Hanya produsen yang tahu
tentang hal itu. Di sini lagi rol pemerintah, yang dapat
menciptakan suatu suasana misalnya dengan memberikan perangsang
bagi pengusaha yang dalam proses produksinya dapat mengurangi
polusi dengan biaya yang rendah.
Trio masyarakat, produsen dan pemerintah dominan dalam mengatasi
harga pencapaian harmoni antara pembangunan dan pengurangan
dampak negatifnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini