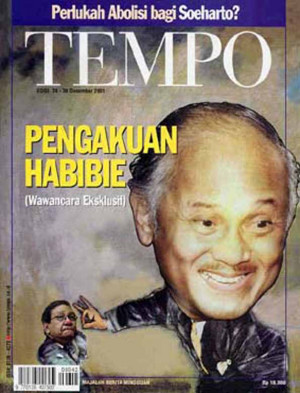Riswandha Imawan *)
*) Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada
PERISTIWA politik terpenting tahun 2001 adalah pergantian kekuasaan pemerintahan dari Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ke Presiden Megawati. Dengan pergantian ini, Indonesia kembali mencatat rekor: "dipimpin oleh tiga orang presiden dalam kurun waktu 50 bulan."
Mengapa Gus Dur jatuh? Bukankah khalayak dan banyak pengamat menyatakan bahwa terpilihnya Gus Dur merupakan keputusan taktis MPR untuk menghindari ancaman disintegrasi bangsa? Artinya, bila wakil merupakan representasi paling sempurna dari pihak yang diwakili, dukungan terhadap Gus Dur seharusnya kuat sekali.
Tapi titik awal kejatuhan Gus Dur bermula ketika dia tidak menyadari bahwa dia berkuasa di saat bangsa Indonesia mengalami anomali. Aturan dan pola berpolitik lama diberantas, sementara yang baru belum mapan, setidaknya mendapatkan persetujuan minimal dari kekuatan politik utama yang ada. Ranah politik satu tuan di era Soeharto berubah menjadi ranah banyak tuan. Pendulum politik bergeser dari executive heavy ke legislative heavy. Desentralisasi di sisi pemerintahan seolah-olah dikonter dengan makin mantapnya pola sentralisasi kerja partai politik.
Tentu saja dengan dukungan mayoritas pura-pura (pseudo majority) dari kelompok Poros Tengah yang menjadikannya presiden, Gus Dur kelabakan menghadapi situasi ini. Dukungan pseudo majority mengharuskannya bersikap super-akomodatif, yang pada gilirannya menyulitkan dia membentuk satu tim kerja yang solid. Tidak adanya kekuatan mayoritas yang sebenarnya (real majority) di parlemen membuat Gus Dur sangat rentan terhadap berbagai kepentingan politik di seputar istana dan parlemen. PKB sebagai diehard supporter bagi Gus Dur tidak memiliki kekuatan yang cukup berarti di parlemen. Tumpuan Gus Dur pada NU tidak bisa dimaksimalkan karena NU adalah organisasi sosial-keagamaan dan anggotanya tersebar di berbagai partai politik.
***
Gus Dur terjebak dalam satu permainan politik yang belum selesai (atau memang sengaja tidak diselesaikan) seiring dengan berakhirnya Pemilu 1999. Susahnya, dia menikmati permainan itu. Waktu persiapan dan pelaksanaan pemilu yang amat sempit tampaknya belum memuaskan para politisi untuk unjuk gigi. Para politisi kelihatannya sadar betul bahwa politik sebagai a matter of perception logis digunakan. Persepsi orang sangat ditentukan oleh informasi yang mereka terima. Maka mudah dipahami bila pemegang informasi mampu mengendalikan permainan politik yang sedang berlangsung. Padahal, dalam dunia politik, kemungkinan dilontarkannya informasi yang manipulatif sangat tinggi. Misalnya, benarkah saat Sidang Umum MPR 1999, bila Megawati tidak terpilih menjadi presiden, akan terjadi pertumpahan darah antara pendukung Habibie dan pendukung Megawati di Bundaran HI, Jakarta?
Pertanyaan ini penting direnungkan karena informasi yang manipulatif seperti inilah yang membuat element of surprise selalu muncul dan menentukan arah wacana politik di Indonesia. Simak saja realitas berikut ini. Warga masyarakat saling melempar batu saat kampanye hanya karena memakai warna kaus yang berbeda. Namun, beberapa jam kemudian, saat mencangkul sawah, mereka sangat rukun sekalipun tetap memakai warna kaus yang berbeda. Angkernya pendukung Gus Dur saat Memorandum I dijatuhkan DPR berubah menjadi senyum simpatik setelah hiruk-pikuk kasus Buloggate I berakhir. Gambaran akan terjadinya Jakarta massacre di pengujung kekuasaan Gus Dur ternyata menjadi titik awal penggalangan kembali rasa solidaritas sosial.
Mencermati kejadian-kejadian di atas, tampak bahwa kunci perjuangan politik di Indonesia masih terletak pada "penyelesaian dewa-dewi". Artinya, demokrasi di Indonesia masih sangat elitis. Berbagai krisis politik di negeri ini yang demikian sulit dipecahkan melalui mekanisme formal, semisal sidang DPR, bisa dipecahkan melalui acara sarapan pagi para dewa-dewi. Alotnya memutuskan amandemen terhadap UUD 1945 dalam Sidang Tahunan MPR 2001 lalu, contohnya, dapat dengan mudah diselesaikan lewat lobi para pemimpin partai politik. Namun, cara dewa-dewi ini hanya efektif bila masih ada rasa saling percaya di antara mereka. Justru faktor inilah yang luntur di era Gus Dur.
Sebagai pemimpin politik, seharusnya Gus Dur mengumpulkan sebanyak mungkin kawan. Namun, ia malah memproduksi terlalu banyak lawan. Gus Dur seakan berprinsip "satu kawan terlalu banyak, seribu lawan kurang banyak." Hampir semua pemimpin lembaga (tinggi) negara dimusuhi. Eksekutif dibawanya bermusuhan dengan DPR, DPA, BPK, BI, bahkan MA. Tidak cukup dengan itu, Gus Dur pun membuka arena konflik dengan para pembantunya sendiri. Fakta-fakta inilah yang menggiring penilaian masyarakat bahwa sebagai presiden, Gus Dur tidak memiliki kemampuan manajerial yang memadai.
Penilaian negatif pun menyeruak. Susahnya, itu ditanggapi dengan sikap super-cuek lewat ungkapan khas, "Kok, repot." Hobi jalan-jalannya pun tidak dikurangi. Celakanya, itu dilakukan pada saat keuangan negara sudah sangat parah serta konflik sosial merebak di mana-mana. Perjalanan ke luar negeri, katanya, untuk menarik investor. Realitasnya, sampai Gus Dur berhenti jadi presiden, para investor bukannya masuk (kembali) ke Indonesia, tapi malah memindahkan investasinya ke negara lain.
Perjalanan ke luar negeri yang dilakukan pada saat konflik sosial mewabah membuat jengkel banyak pihak. Di berbagai kesempatan, Gus Dur selalu mengasosiasikan dirinya dengan etnis tertentu. Namun, saat kelompok etnis ini mengalami kesulitan, mereka malah ditinggalkan begitu saja. Gus Dur seakan tidak menyadari bahwa salah satu pemicu bagi merebaknya societal terrorism adalah ucapannya sendiri: "Biarkan masyarakat menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri." Ungkapan ini sangat berbahaya, terutama bila dikaitkan dengan situasi anomali yang kita alami. Inilah yang menyebabkan khalayak menilai Gus Dur tidak memiliki sense of crises.
***
Bila melihat latar belakang aktivitas Gus Dur, sangat mengherankan bahwa hal-hal di atas terjadi pada dirinya. Bagaimana mungkin seorang aktivis demokrasi lebih suka menciptakan lawan daripada kawan? Tidak memiliki sense of crises sehingga tidak mampu bekerja dengan skala prioritas yang jelas? Bagaimana mungkin seorang Gus Dur yang sarat dengan pengalaman organisasi bisa dinilai tidak memiliki kemampuan manajerial yang memadai?
Jawaban besarnya dapat ditemukan pada kenyataan bahwa Gus Dur mengalami transformasi peran dan psikologis yang sangat cepat dan mendadak. Bayangkan, menjadi anggota MPR tahun 1999 dari utusan golongan saja sudah mengalami kesulitan, tiba-tiba malah dicalonkan (dan dipilih) menjadi presiden. Gus Dur tampaknya bukan sekadar tidak siap menjadi presiden. Dia juga tidak sepenuhnya sadar akan kondisi politik serta situasi lapangan yang penuh dengan intrik.
Oleh para "pendukungnya" (mereka yang mencalonkan Gus Dur sebagai presiden), Gus Dur ditempatkan pada posisi yang sangat sulit. Gus Dur ditumpuki segudang masalah, tapi kewenangan yang diberikan kepadanya dipangkas. Matematika politik menyatakan pemimpin yang sukses adalah yang memiliki kewenangan sesuai dengan besar tugas yang dibebankan. Bila kewenangan yang diberikan lebih besar dari tugasnya, dia akan menjadi seseorang yang otoriter. Sebaliknya, bila kewenangan lebih kecil dibandingkan dengan tugasnya, dia akan menjadi bulan-bulanan stakeholders politik yang ada di parlemen. Yang terakhir inilah yang menimpa Gus Dur. Bahkan lebih parah karena stakeholders politik yang dihadapi tidak sekadar ada di parlemen, tapi juga di jajaran pemerintahan. Mengapa hal ini terjadi?
Karena dasarnya UUD 1945, Gus Dur tetap merasa menjadi presiden dengan luas kewenangan yang sama dengan presiden-presiden sebelumnya. Padahal dia bekerja di atas ketentuan yang (sedang) direvisi (diamandemen), terutama pasal-pasal yang berhubungan dengan kekuasaan presiden. Gus Dur menjadi presiden dengan luas kewenangan yang makin dibatasi baik secara konstitusional maupun politik. Menunjuk Kepala Kepolisian RI, misalnya, bukan lagi kewenangan mutlak atau bagian dari hak prerogatif presiden. Demikian pula penentuan personalia kabinet. Basis dukungan yang sangat variatif (konsekuensi dari pseudo majority) menyulitkan Gus Dur untuk membagi posisi basah yang tersedia. Kekuatan politik yang besar merasa berhak karena kebesarannya. Yang kecil merasa berjasa melalui penggalangan pseudo majority.
Rebut-rebutan posisi basah inilah yang mengganggu keseimbangan jagat dewa-dewi. Namun, di sisi lain, situasi ini meyakinkan warga masyarakat bahwa orientasi para elite bukan pada penyelesaian krisis yang dihadapi bangsa ini, melainkan bagaimana mencari dan mengamankan sumber-sumber finansial untuk kepentingan Pemilu 2004 nanti. Artinya, para politisi memandang Pemilu 1999 lebih merupakan pemilu transisional. Otomatis periode 1999-2004 juga dipandang hanya sebagai periode transisi. Menempatkan Gus Dur dengan dukungan pseudo majority bermakna menciptakan celah yang bisa digunakan untuk mencari posisi strategis menghadapi pemilu "yang sebenarnya" tahun 2004.
Gus Dur diminta bersikap tegas, tapi tetap diiringi dengan dengung suara harus demokratis. Atas kritikan masyarakat dan nasihat berbagai pihak, Gus Dur melakukan reshuffle kabinet. Katanya, itu untuk meningkatkan kepercayaan dunia internasional. Ketika hal itu dilakukan, justru kredibilitas pemerintahannya berantakan. Kembali di sini Gus Dur termakan oleh kegamangannya dengan transformasi internal yang sedang dialaminya. Gus Dur yang terkenal karena memiliki rasa percaya diri (PD) yang sangat tinggi itu dibuat bingung dengan lontaran agenda yang datang dari berbagal arah. Ini sebuah paradoks. Orang yang PD-nya tinggi umumnya mengendalikan agenda. Gus Dur justru diombang-ambingkan oleh agenda yang dibuat dewa-dewi yang lain.
Gus Dur yang mengalami transformasi internal harus memimpin masyarakat yang juga sedang mengalami transformasi. Secara logika saja bisa ditebak, bila dua orang yang sedang bingung berjalan bersama, mereka tidak akan ke mana-mana.
Harus diakui, Gus Dur memiliki basis sosial dan politik yang berlapis-lapis. Dia cucu pendiri NU, anak mantan Menteri Agama. Istrinya juga datang dari kalangan darah biru di NU. Karena itu, sejak kecil Gus Dur terbiasa untuk tidak dibantah. Dia terkejut ketika berhadapan dengan para menteri yang berani bersikap argumentatif terhadap ide ataupun keputusannya. Tradisi dunia pesantren dilanjutkan saat mengelola negara ini. Semua orang yang dihadapi dianggapnya sebagai santrinya. Dalil santri tidak boleh menggugat otoritas kiai diyakininya akan efektif saat menghadapi politisi dan menteri. Dia tidak menyadari, sejalan dengan itu, personifikasi institusi yang merupakan penyakit kronis politik di Indonesia tumbuh subur di bawah gaya kepemimpinannya. Akibatnya, intrik dan bisik-bisik politik seputar istana dan dirinya berkembang tak terkendali, yang akhirnya menciptakan lubang besar bagi Gus Dur untuk terjerembap ke dalamnya.
Semoga kita bisa belajar dari pengalamannya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini