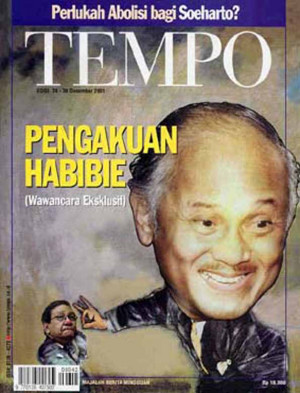Daniel S.Lev *)
*)Indonesianis, tinggal di Seattle, USA
SEJAK Presiden Soeharto meletakkan jabatan hampir empat tahun yang lalu, sudah muncul tiga presiden baru. Semua menjanjikan perbaikan atas proses hukum. Di luar pemerintah, dalam suasana yang makin penuh konflik, kekerasan, pembunuhan, dan kejengkelan, banyak warga negara ikut berpandangan bahwa negara hukum merupakan sine qua non.
Memang sine qua non karena, tanpa proses hukum yang efektif, tidak mungkin diharapkan perbaikan ekonomi, politik, kehidupan sosial—dan keadilan. Ternyata, cara pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru selama 40 tahun merupakan bencana untuk negara dan masyarakat Indonesia. Boleh dikatakan negara jadi babak-belur, penuh korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak-hak asasi manusia, tanpa lembaga-lembaga negara yang dapat dipercayai, termasuk pengadilan, kejaksaan, dan polisi.
Anehnya, walaupun hampir semua kalangan katanya bersepakat bahwa sistem hukum perlu diperhatikan betul, belum ada kemajuan yang banyak menuju negara hukum. Pada tahun 2001, seperti tahun-tahun sebelumnya, ada janji dan beberapa langkah di seputar soal hukum. Undang-undang baru diloloskan, RUU dipertimbangkan, lembaga-lembaga baru dibentuk, dua presiden mengimbau supaya hakim, jaksa, dan polisi bertindak semestinya, dan seterusnya. Tetapi belum terlihat perubahan fundamental. Selain pendobrakan sedikit pada Mahkamah Agung--penting tapi masih terlalu sedikit, dan tampaknya macet di situ--pengadilan, kejaksaan, dan polisi tidak jauh berbeda dengan empat tahun lalu. Di luar pemerintah ada sejumlah advokat yang mampu sekali, dan ada juga yang turut aktif sebagai reformis, tapi profesinya berantakan, dibagi antara beberapa asosiasi yang belum tentu tahu jumlah anggotanya dan tidak mampu mengawasi korupsinya. Menurut survei koran, amat sedikit orang yang percaya pada proses reformasi hukum, dan sinisme warga negara makin luas.
Soalnya apa? Apa sebabnya kehausan masyarakat atas negara hukum yang adil tidak dapat dipuaskan? Analisis kebudayaan tidak kena karena pernah ada negara hukum yang cukup bagus pada zaman parlementer sebelum tahun 1959. Pada zaman Demokrasi Terpimpin dan lebih lagi pada zaman Orba, negara hukum Indonesia dikesampingkan oleh negara kekerasan berdasarkan kekuatan militer, yang menghilangkan keseimbangan antara negara dan masyarakat dan memanfaatkan kalangan pimpinan. Jadi, bukan soal kebudayaan, melainkan soal politik. Dan masih saja soal politik.
Sejak pertengahan tahun 1998, tidak ada pembaharuan kelembagaan hukum karena elite politik tidak menginginkannya atau tidak mampu menjalankannya. Ketidakmauannya berakar pada kepentingan, kalau proses hukum makin kuat, pimpinan politik makin terbatas kekuasaannya. Selama 40 tahun sejak 1959, pimpinan politik menikmati keleluasaan bertindak menurut kemauan sendiri tanpa dikurungi tindakannya oleh pengadilan, kejaksaan, polisi, pers, atau organisasi dalam masyarakat. Semua lembaga hukum negara ditundukkan pada pimpinan politik dan dilindungi dari kritik, asal melayani keperluan atasan politik. Akibatnya, para hakim, jaksa, dan polisi kehilangan orientasinya pada hukum dan tidak lagi mengelak korupsi. Yang tidak ikut rakus terpaksa tutup mulut. Norma dan nilai lembaga hukum merosot. Suasana kesempatan itu, yang meluas pada semua kelembagaan negara, tidak mungkin hilang begitu saja, apalagi kalau cukup banyak pemimpin politik enggan melepaskannya. Dan di dalam lembaga-lembaga hukum, antara para hakim dan jaksa dan polisi, ditambah lagi banyak advokat, suasana itu masih terasa, sampai yang dari luar dianggap korupsi dan yang dari dalam dianggap hak yang biasa saja.
Penciptaan negara hukum di Indonesia, seperti di lain negara di dunia yang pernah mengalami transisi yang sulit itu, bergantung pada kesadaran pimpinan politik bahwa kedudukan (dan keselamatan) mereka sendiri, sebagai elite, dapat dijamin oleh stabilitas berdasarkan proses hukum yang dipercayai umum. Kesadaran itu menuntut kecanggihan sedikit dan imajinasi politik yang luas, seperti yang jadi pegangan generasi pimpinan zaman parlementer. Apakah mungkin bahwa justru pengertian dan imajinasi politik itu, dan rasa bertanggung jawab pada masyarakaat, yang hilang dari generasi Orba? Pertanyaan itu penting karena pemulihan negara hukum di Indonesia menuntut pemikiran strategi yang jelas, yang hanya bisa muncul dari pandangan ideologis dan imajinasi politik yang berorientasi pada masyarakat--yang jarang terlihat pada pemerintah selama empat tahun terakhir.
Ada dua macam strategi untuk menyehatkan lembaga-lembaga hukum: secara radikal dan berangsur-angsur. Dalam keadaan di Indonesia, karena lembaga-lembaga hukumnya tidak lagi berfungsi semestinya, yang paling efisien adalah pendekatan radikal. Umpamanya, pengadilan dan kejaksaan, yang memiliki persoalan yang terlalu parah untuk diperbaiki secara singkat, sebaiknya dihapuskan saja dan diganti dengan institusi-institusi yang baru, diisikan hakim dan jaksa yang baru, staf pembantu baru, dan struktur baru yang mengizinkan penanaman norma dan tradisi baru. Tentu saja kebijakan ini akan menyulitkan selama beberapa tahun, antara lain karena kekurangan personalia dan uang, tetapi keadaan peradilan sekarang lebih sulit lagi dan akan makan waktu lama sekali sebelum waras betul. Menciptakan lembaga-lembaga hukum baru membuka kesempatan untuk memikirkan kembali struktur dan prinsip negara pada umumnya, yang berimplikasi pada undang-undang dasar baru sebagai landasan institusi negara. Mulai dari nol tidak gampang, tapi kadang-kadang dalam sejarah langkah radikal itu merupakan solusi yang paling bijaksana.
Hanya, pendekatan itu menuntut pimpinan politik yang yakin atas tujuan reformasi, cukup bersatu, mampu, dipercayai rakyat, dan rela berisiko, seperti Prancis sesudah revolusi 1789, Jepang pada akhir abad ke-19, Jerman sesudah unifikasi tahun 1870, atau Turki sesudah Perang Dunia Pertama. Elite politik di Indonesia sekarang belum memenuhi syarat-syarat itu. Dalam keadaan ini, tiada pilihan lain terkecuali strategi reformasi hukum berangsur-angsur, yang lebih kompleks dan sukar karena menuntut perencanaan jangka panjang dan lebih gampang dielak oleh lembaga-lembaga yang menjadi sasarannya. Tapi jenis strategi itu juga tidak kelihatan pada pemerintah sejak pertengahan 1998. Yang agak mirip adalah kebijakan Abdurrahman Wahid dan Komisi Hukum Nasional, tapi kurang jelas, kurang teratur dan konsisten, dan gagal bermomentum.
Akibatnya, yang antireformasi kelembagaan hukum—termasuk hakim, jaksa, polisi, dan advokat yang sudah lama berkelompok dalam mafia peradilan—malah makin merasa aman dan berani, koruptor kurang merasa cemas, investor dalam dan luar negeri menunggu dulu, dan masyarakat makin jengkel, sinis, dan sering main hakim sendiri. Terkecuali muncul kesadaran baru antara kalangan elite politik, sukar diharapkan dari pemerintah langkah-langkah tegas terhadap lembaga-lembaga hukum, apakah radikal atau berangsur-angsur. Kesimpulan pesimistis itu berdasarkan terlalu banyak bukti.
Akan tetapi, kesimpulan itu hanya bersangkutan dengan peranan pemerintah. Ada pemain lain lagi di dalam masyarakat yang lebih unggul pekerjaannya. Komitmen pada reformasi hukum yang paling nyata terpusat dalam ornop-ornop seperti ICW (Indonesian Corruption Watch), PSHK, LeIP, Kontras, ICEL, Koalisi Ornop untuk Konstitusi Baru, LBH (yang paling lama memperjuangkan proses hukum yang sehat), Judicial Watch, dan lain lagi. Di situ terlihat kemauan, kemampuan, dan keseriusan generasi muda yang mangkir di badan-badan pemerintah. Ide-ide baru, riset yang rajin dan mengesankan, buku dan laporan dan analisis yang memperdalam pengertian tentang persoalan hukum yang ruwet, kritik yang tajam terhadap keadaan pengadilan, kejaksaan, polisi, dan profesi hukum, semuanya berasal dari LSM-LSM hukum itu. Kebanyakan mereka kurang dihiraukan oleh DPR, MPR, dan eksekutif. Dan mereka tidak cukup diperhatikan juga oleh kalangan-kalangan di luar pemerintah yang mengharapkan lembaga-lembaga hukum yang lurus. Ornop-ornop hukum itu bergantung pada sumber keuangan dari luar negeri, padahal firma advokat dan konsultan hukum, para profesional yang lain, dan pedagang-pedagang yang terlalu lama diperas oleh yang berkuasa juga akan bermanfaat kalau proses hukum mulai menentukan. Perlu dipertanyakan mengapa mereka belum turut berperan dalam pekerjaan reformasi.
Ornop-ornop hukum itu menarik juga dari sudut lain. Banyak unsur generasi muda yang aktif dalam lapangan reformasi hukum (dan reformasi politik pada umumnya) agak mirip pandangannya dengan generasi gerakan nasionalis dulu yang memimpin pemerintahan pertama Indonesia merdeka. Yang paling menonjol antara kedua generasi itu, dan yang membedakannya dengan generasi pimpinan zaman Orba, adalah orientasinya pada kemajuan masyarakat, keinginannya atas negara yang bertanggung jawab, dan kerelaannya mengorbankan diri menuju tujuan itu.
Mungkin saja negara hukum Indonesia akan mulai bangkit lagi segera setelah generasi muda itu mulai mengisikan elite politik yang baru.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini