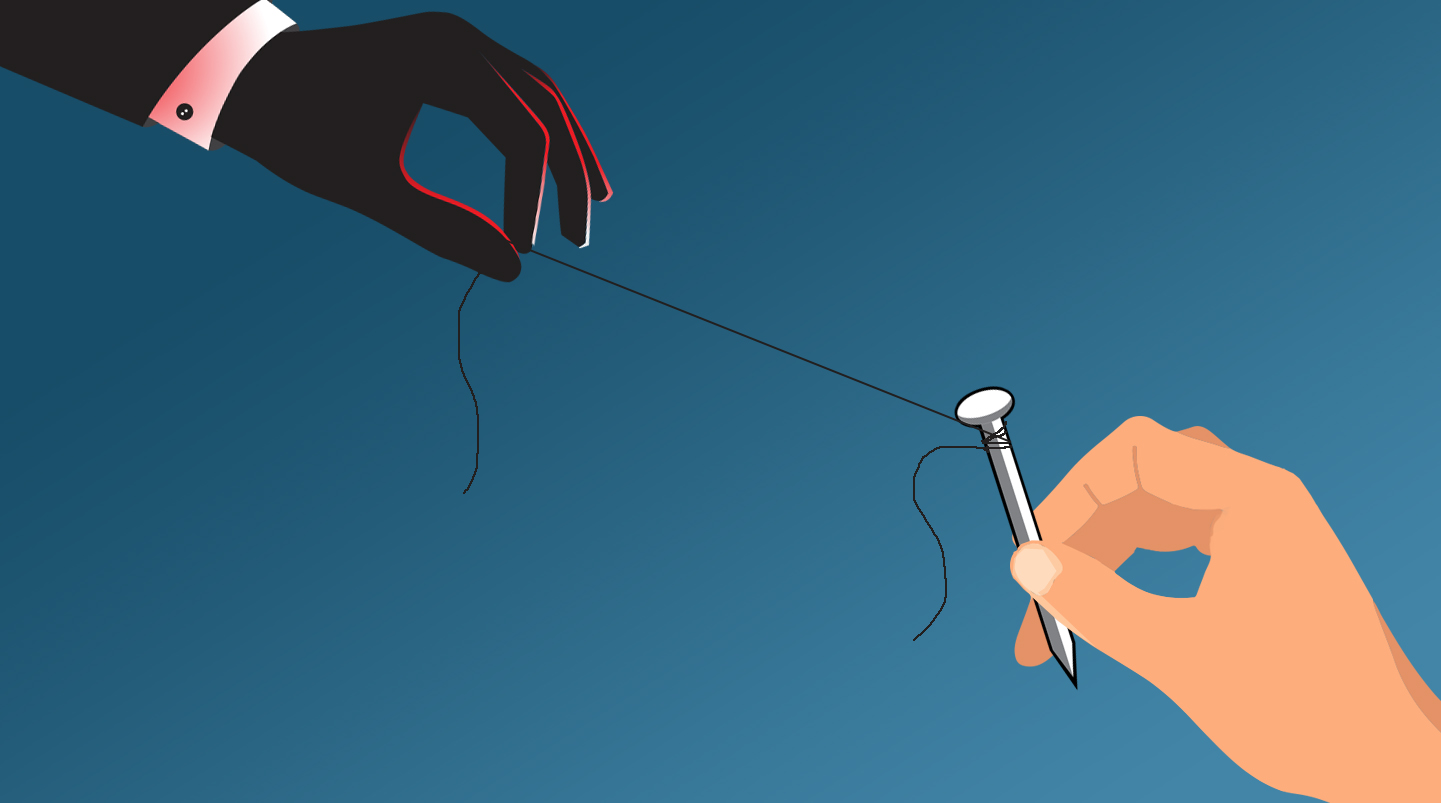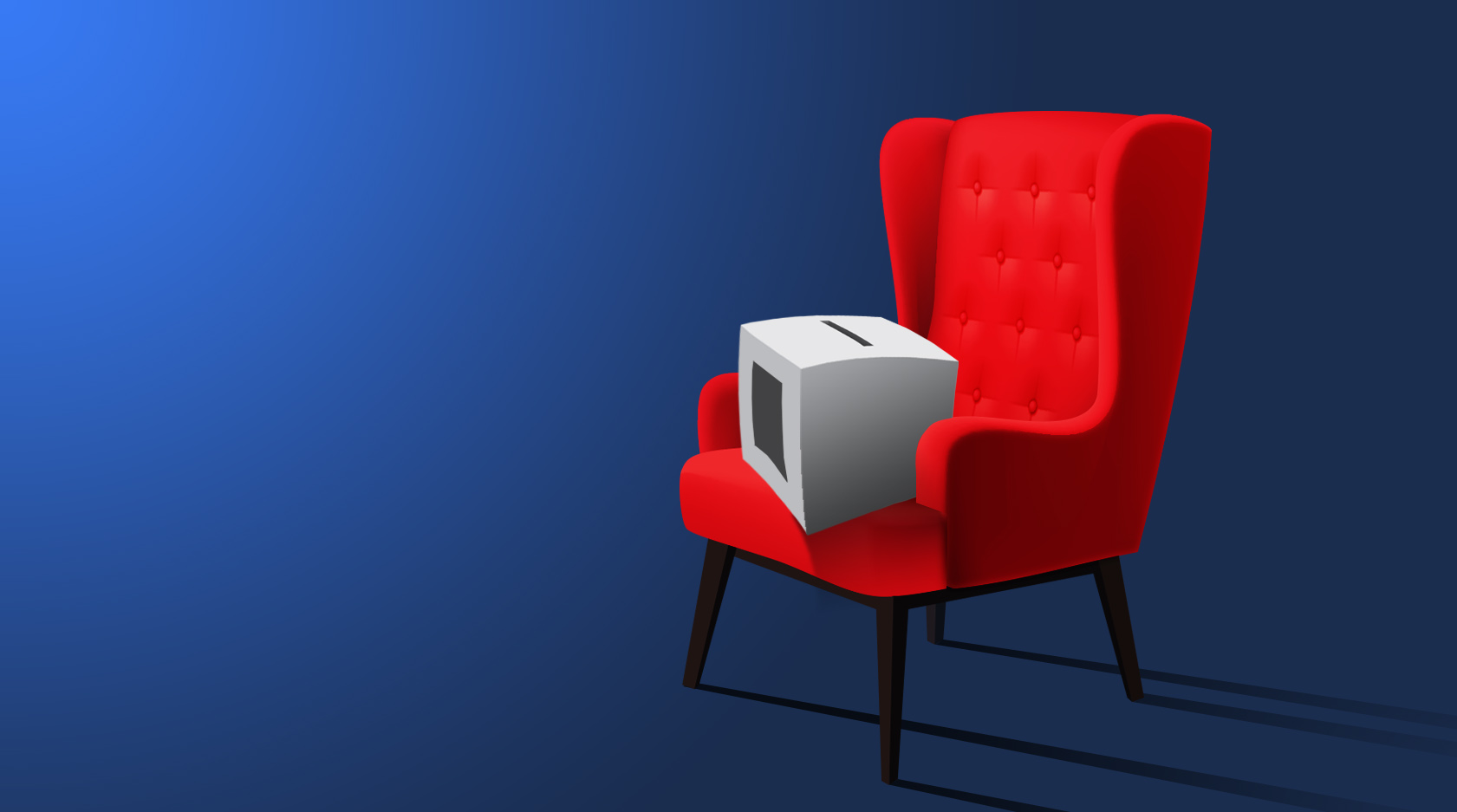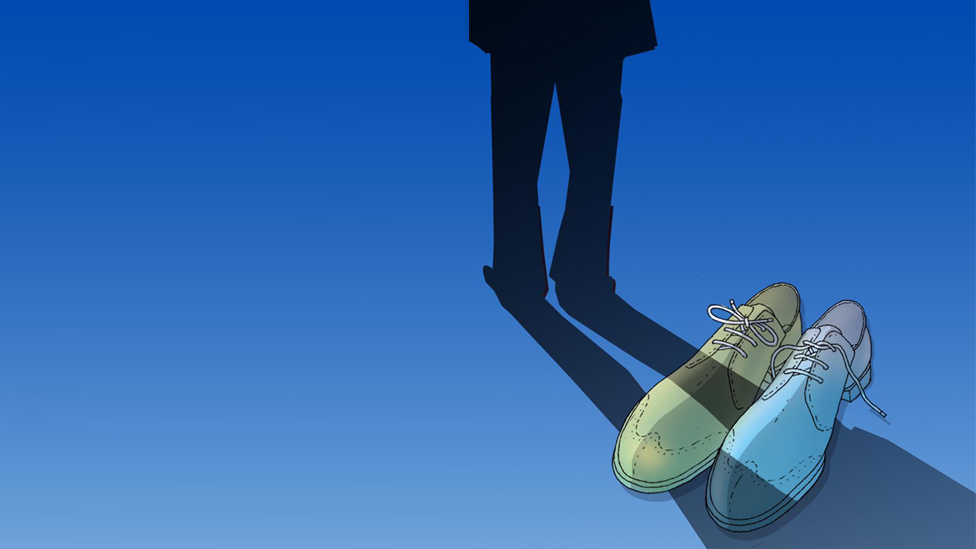Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia sering menggantikan kata yang menunjuk tempat keadilan ditentukan. Tapi tak jarang ia juga kata lain asal kesewenang-wenangan dan kesalahan. Atau sebaliknya: cikal-bakal kegemilangan.
Demikianlah “Jakarta”, sudah sekitar satu abad, bukan lagi nama wilayah tempat hidup manusia dan benda-benda. Dalam percakapan tertentu, ia justru tak kasatmata: bukan lagi deretan gedung kaku pemerintah, monumen yang bangga, boulevard yang lebar, masjid yang megah. Ia abstrak: “Jakarta” adalah sebuah konsep, seperti ketika orang mengatakan, “Jakarta menyetujui resolusi ASEAN.” Ia sebuah abstraksi dari jaringan dan proses yang kompleks, yang berlangsung di atas sebuah abstraksi lain: “pemerintah pusat”.
Sebagai konsep, Jakarta adalah “Indonesia”—sebagaimana “Gedung Putih” adalah Amerika Serikat, karena di sanalah posisi, bukan letak geografis, Presiden Amerika Serikat.
“Posisi”: juga sebuah konsep.
Kata “ibu” dalam “ibu kota” adalah metafor untuk menggambarkan konsep itu: posisi yang tunggal dalam sebuah peta politik—sebanding dengan “ibu” dalam sebuah keluarga. Dari sini diasumsikan pengaruh menyebar. Di sini dianggap letak asal energi, kekuatan dan kekuasaan, yang ikut memberi bentuk kehidupan di luar dirinya.
Tapi tak pernah ada asal yang tunggal dalam biografi sebuah negeri. Percakapan memang perlu penyederhanaan. Tapi ekonomi komunikasi itu, jika kita telaah, mengandung asumsi yang umumnya meleset.
Ketika kita menyebut “ibu kota”—juga “pemerintah”, juga “Indonesia”, juga “bangsa”, juga “masyarakat Indonesia”—kita memproyeksikan sesuatu yang tanpa detail dan tanpa kontradiksi. “Jakarta” disamakan dengan “pusat”, dan “pusat” disamakan dengan “pemerintah X”, dan “X” disamakan dengan, misalnya, “Jawa”. Jakarta = Pusat = Pemerintah = Jawa. Tak ada selisih.
Beberapa tahun yang lalu saya pergi ke Wamena, Papua, bersama Margaret Scott, penulis untuk The New York Review of Books, dan Akiko Tsuru, seorang teman aktivis dari Jepang. Kami bagian dari orang-orang yang cemas akan luasnya represi rezim Soeharto terhadap ketidakpuasan politik di Papua (dan di mana saja di Indonesia waktu itu). Hari itu kami mencoba menghubungi para tahanan politik yang disekap.
Pengacara mereka, seorang anak muda Papua, menganjurkan kami menyamar agar bisa lancar masuk ke penjara. Maka Margaret Scott mengaku sebagai wakil Gereja Methodis dan saya pastor Katholik. Akiko memilih berada di luar.
Di halaman kamar tahanan, seorang tokoh OPM mengemukakan alasan perlawanannya. Saya memahami kemarahannya, tapi pada satu bagian, kalimat yang dipilihnya seperti belum selesai. “Kami,” katanya, “marah besar karena banyak orang Papua dibunuh dan ditindas orang Jawa.”
Saya dengarkan sampai statemennya selesai, lalu saya—yang biasa cerewet dalam hal bahasa—mencoba mengoreksi: “Bukan orang Jawa, Pak, tapi Orde Baru.” Di tahun 1965, kata saya pula, juga banyak “orang Jawa” dibunuh Orde Baru dan pendukungnya.
Ia terdiam. Mungkin menyadari kekeliruannya, mungkin ia tak menyetujui kata-kata saya. Yang pasti, kami tak berbantah; kami tak sempat. Saya dan kawan-kawan harus pergi karena polisi penjaga sudah menegur....
Sambil berjalan keluar, saya sadar ada yang rancu yang belum diluruskan. Apa arti “Jawa”? “Jakarta”? Dan apa arti “Jakarta”? Tempat rezim Soeharto? Tempat orang “Jawa” sebagai “suku”? Apa arti sebuah “suku?” ....
Kerancuan terjadi karena kita bertolak dari salah lihat: sebenarnya tak ada himpunan sosial-politik yang, meskipun bernama satu, secara hakiki sama, tetap, tak berubah. Dalam perjalanan sejarahnya akan tampak ia justru sebuah kekurangan: tak punya struktur yang kekal, tak punya fondasi yang menyatupadukan, hukum yang niscaya siap. Bukan cuma Jawa, Papua, Indonesia. Juga Amerika Serikat, Jepang, bahkan Vatikan.
Masing-masing sebuah kekurangan; maka dalam tubuh itu faksi atau elemen yang berbeda-beda—kadang-kadang tak kentara—berjuang untuk memberi bentuk pada keseluruhan himpunan. Mereka mementaskan diri sebagai pembawa kepentingan bersama. Bersama itu, kekuasaan muncul di arena. Pada suatu tahap, hegemoni (untuk memakai pengertian Laclau) akan tercapai oleh faksi A di atas faksi-faksi lain. Maka A pun bisa menganggap diri mewakili himpunan sosial-politik itu, baik itu sebuah imperium maupun sebuah kecamatan.
Posisi “mewakili” itu penting untuk menciptakan identitas kolektif ketika sebuah himpunan sosial-politik majemuk dan retak-retak. Tapi “wakil” mengandung arti yang sering dilupakan: ia mewakili justru karena ada yang tak dapat dihadirkan. Ia sebenarnya rentan.
Sebab yang diwakilinya adalah wujud nyata yang rumit. Di kerumitan itu, tiap wakil selalu mengabaikan unsur-unsur dalam tubuh yang-diwakili yang tak menonjol, mungkin lemah, setidaknya dalam satu masa. Di sini kita diingatkan lagi akan ketaklengkapan dan kekurangan yang endemik itu—yang disebut “ketidakadilan”, yang selalu menuntut, yang memicu perjuangan politik dan demokrasi dalam tiap res publica.
Dalam proses itu, “ibu kota” tak lagi berperan konstruktif dari dalam mithologi politik. Tapi sejak semula ia memang bukan ibu yang di telapak kakinya ada surga.
GOENAWAN MOHAMAD
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo