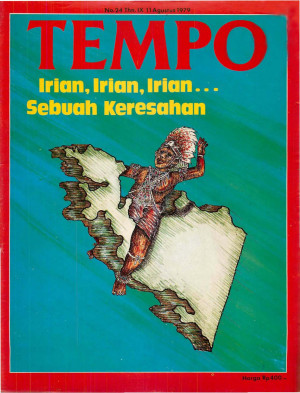KALAU tidak salah hitung dalam hampir dua dasawarsa terakhir
sudah 13 kali aku mengikuti penataran sebagai pegawai negeri.
Andaikan tiap penataran itu menempelkan sepotong sayap pada
pinggangku, tidak bisa tidak aku sudah sanggup terbang mengapung
ke langit yang ke tujuh. Dan andaikan tiap penataran itu
menancapkan sepotong tanduk di atas batok kepala, tak bisa tidak
aku tak ubahnya seperti rusa gurun yang gagah perkasa.
Penataran yang kuperoleh itu, sesuai dengan jamannya
masing-masing, mempunyai sebutannya sendiri-sendiri -- seperti
halnya nama gang dalam kota besar -- yang satu lebih bagus dari
yang lain. Dan seperti halnya kerang di laut, isi mutiara yang
terkandung pun berbeda-beda pula. Ada mutiara putih, ada pula
mutiara hitam, dan ada pula berwarna kelabu sehingga tidak mudah
mengenalnya dalam waktu cepat. Bagiku seorang pegawai negeri,
apa pun warnanya tidaklah menjadi persoalan benar, karena yang
penting penataran adalah penataran, harus kuikuti hingga ke
ujungnya benar scbagah1lana layaknya aturan dunia.
Ada penataran bernama coaching, indoktrinasi Manipol, kader
Revolusi, kader Nasakom, Trikora dan Dwikora, Berminggu bahkan
berbulan kuikuti dengan tekun lengkap dengan latihan baris
berbaris sambil melempar granat, merayap di atas gundukan tanah
bagai kepiting batu. Semua ajaran, pidato serta ceramah, kuikuti
semua dengan tekun hingga bola mata berair, kutelan dengan
semangat hingga untuk kencing pun rasanya tidak ada waktu.
Jangan dikira malam harinya aku terbaring semau-maunya, karena
sebelum tergolek tidur kukaji kembali bunyi ajaran lembar demi
lembar tak terlewat koma dan titiknya.
CIPAYUNG
Misalnya waktu aku peroleh coaching indoktrinasi Manipol dari
Dr. H. Ruslan Abdulgani di Cipayung awal tahun 1960-an. Ada
barangkali setengah jam aku terlongo-longo sehingga nyaris titik
air liur, tak habis pikir bagaimana mungkin ada makhluk sepandai
beliau. Seluruh masalah dunia baik kebajikan maupun
kejahatannya, kemelut negeri Afrika yang hampir tak tertandai di
peta, diteliti sampai sekecil-kecilnya.
Kuhirup habis amanat Bung Karno di depan Majelis Umum PBB
"Membangun Dunia Baru" berikut pembagian jagad menjadi dua
bagian menurut ukuran dosa dan kebajikannya tak ubahnya seperti
membelah sebuah kue tarcis dengan sekali penggal. Bagai lidah
api datang menyambar, hangat revolusi membakar sekujur tubuh
hingga ujung kuku, sehingga sehabis indoktrinasi ingin rasanya
aku menjungkirbalikkan isi dunia berikut perabot dan piring
mangkuk yang ada di atasnya, kemudian menatanya kembali menurut
keinginanku seraya memenggal batang leher semua bajingan sambil
membagi rata sesuap nasi pada tiap orang tanpa kecuali.
Oleh perjalanan misteri sang waktu yang sukar diperhitungkan,
sementara aku masih tetap sebagai pegawai negeri raya terus naik
derajat menurut jenjang peraturan, segala rupa coaching dan
indoktrinasi dan upgrading Manipol angsur berangsur kujauhi
seperti sumber penyakit kusta. Apa yang pernah kuperoleh tempo
hari kurahasiakan jauh-jauh di dalam kalbu sebisa mungkin tak
diketahui orang termasuk isteri sendiri.
Pernahkah aku menjadi Manipolis? Oh samasekali tidak. Mendengar
namanya pun rasanya tak pernah. Aku bersih dan suci bagai
seorang bayi terjulur dari rahim, pegawai negeri tulen ciptaan
langit, terjauh dari ajaran revolusi, tak pernah beranjak dari
meja kantor kecuali membuang hajat besar.
Terus-terang, sikap yang kuambil ini bukanlah datang mendadak
melainkan lewat renungan bulan berbulan, dengan tujuan satu
keselamatan diri dan tetap terpakai sebagai pegawai negeri
hingga badan rapuh dan datang pensiun. Apa yang lebih penting
buat seorang pegawai negeri ketimbang pensiun? Jika harimau mati
meninggalkan belang, pegawai negeri mati meninggalkan pensiun.
Belakangan ini, tanpa kuduga sebelumnya, datang lagi keharusan
mengikuti penataran. Lamanya dua minggu dan tanpa pandang bulu.
Kepala kantor, kepala bagian, kepala gudang, bagian umum maupun
bagian khusus, tak ada kecualinya musti mengikuti penataran.
Bagiku yang sudah terbiasa oleh urusan macam ini, tugas
kenegaraan itu kuterima tanpa kikuk sedikit pun. Empat belas
hari lamanya mulai pagi hingga matahari terbenam aku peroleh
pelajaran dan pidato dan ceramah dan diskusi dan bahan-bahan
penataran yang kupanggul pulang dengan riang gembira.
BON PALSU
Oleh ketekunan yang sukar dilukiskan, kukenal lebih baik
bagaimana mustinya mempraktekkan hidup berkonstitusi. bagaimana
mengamalkan Pancasila dalam hubungan kantor dan hidup
sehari-hari, bagaimana tidak berkorupsi, bagaimana menjauhi bon
bon palsu dan bagaimana tidak menerima peserta tender lewat
pintu belakang.
Pancasila, yang telah kukenal belasan tahun, menjadi dekat di
hatiku begitu rupa, lebih dekat dari kedua daun telingaku
sendiri. Akan halnya pidato lahirnya Pancasila oleh Bung Karno
bulan Juni 1945 tidak jadi mata acara di penataran, tidaklah
menjadi pikiranku benar, karena mengurusi perkara macam itu
tidak akan ada ujung pangkalnya.
Kesulitan sesungguhnya bukan timbul di saat penataran, melainkan
justru sesudahnya. Membuat "paper" kuselesaikan sambil bersiul,
apalagi judul yang kupilih teramatlah mudahnya: perataan
pendapatan hingga ke ujung gunung. Pidato di muka peserta
kulakukan seraya mengerenyutkan dahi sejadi-jadinya, sehingga
tanpa mendengarkan isi sekalipun, sudah menunjukkan berat
bobotnya. Dengan demikian siapa pun mudah menerka bahwa aku
menjadi juara pertama penataran, dan siap menatar eselon lebih
bawah di manapun mereka berada.
Yang kumaksud kesulitan hanyalah menyangkut perkara hidup
sederhana. Sebab hanya setan yang bisa membantu bagaimana kubisa
menghalau 10 mobil dari garasi, menenggelamkan ke bumi 5 rumah
gaya Spanyol, membungkus ratusan hektar tanah sehingga petani
tidak meleleh air liurnya. Sebagaimana kalian maklum, tabiat
mereka itu suka heran.
Selebihnya tidak ada persoalan. Kumasuk kantor dengan baju
safari pelbagai warna, dada busung dan senyum kebapakan sehingga
bawahan memandangku seperti juragan teladan, mulus bagai sebuah
lukisan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini