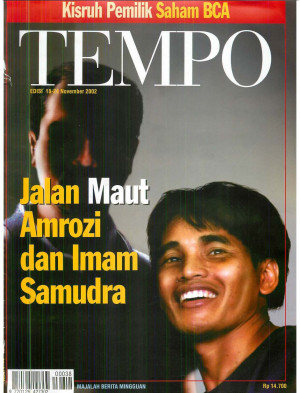Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PARA reformis akan frustrasi melihat jalannya proses reformasi di Indonesia. Lambannya proses ini mengakibatkan biaya neto reformasi meningkat secara signifikan. Biaya ini bisa dihitung secara kasar dengan realisasi pertumbuhan ekonomi yang relatif kurang cepat dibanding negara-negara Asia lainnya yang terkena krisis serupa, dan munculnya kebutuhan atas re-profiling utang domestik. Harus diakui, kegagalan proses reformasi ini bukan hanya di Indonesia. Penundaan reformasi ekonomi di Jepang, misalnya, telah menimbulkan biaya yang luar biasa terhadap perekonomian mereka. Sementara sejak tahun 1945 perekonomian Jepang tumbuh minimum 4 persen per tahun, sejak 1990 sudah tergolong luar biasa jika tumbuh 1-2 persen saja. Anecdotal evidences menunjukkan potensi biaya kredit macet perbankan Jepang bisa melebihi US$ 100 miliar.
Dalam kasus Indonesia, tidak berjalannya reformasi ekonomi ini bisa dilihat dalam banyak contoh. Kasus restrukturisasi perbankan--baik di bawah BPPN, Kantor Menteri Negara BUMN, maupun Departemen Keuangan--salah satunya. Setelah negara membuat "bail-out" kegagalan perbankan, dari Bank BUMN--yang memberikan kontribusi 60-65 persen dari biaya krisis perbankan--dan bank swasta, BPPN diharapkan meneruskan proses tersebut. Mereka harus mampu berfungsi dalam dua hal, yaitu menyehatkan kembali bank-bank yang ditransfer ke institusi tersebut dan memaksimalkan rate of recovery aset yang dikelola akibat proses pengambilalihan bank-bank tersebut. Untuk menjalankan fungsinya, BPPN dilengkapi dua perangkat hukum, yaitu PP No. 17 dan Undang-Undang Kebangkrutan. Mereka juga memiliki KKSK sebagai institusi penting untuk memproteksi BPPN dari tekanan politis dan membantu pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Untuk mencegah pegawai BPPN mengambil manfaat dari kekuasaan yang dimilikinya, tersedia oversight committee dan Komisi Ombudsman. Bagaimana bila staf BPPN tergoda melakukan praktek korupsi? Tenang, disediakan gaji khusus yang sangat memadai bagi mereka.
Nyatanya, kelengkapan institusi ini tidak menjamin apa yang dilakukan BPPN berjalan seperti yang diharapkan. Kalau dilihat sepintas, kelihatannya bank-bank di bawah BPPN telah menghasilkan keuntungan, tetapi analisis yang mendalam menunjukkan sebagian besar keuntungan ini diperoleh dari penerimaan bunga obligasi dari SBI, bukan dari ekspansi kredit seperti halnya bank normal. Presentasi kredit macet memang menurun, tetapi tidak secepat yang diharapkan. Bahkan salah satu bank pasien BPPN, yaitu BII, memerlukan tambahan rekap kedua kali.
Dalam kasus restrukturisasi aset pun, kontroversi kegiatan BPPN tidak henti-hentinya dibicarakan. Salah satunya perjanjian dengan konglomerat lewat MSAA ataupun MRNIA serta APU, yang memerlukan peninjauan ulang oleh tim bantuan hukum dan sampai kini tidak jelas ujungnya. Kegagalan menerapkan mekanisme stick and carrot, BPPN kemudian mengajukan reformulasi perhitungan kewajiban bunga konglomerat. Bukan berdasarkan bunga aktual, melainkan tingkat bunga tertentu yang tidak jelas dasar perhitungan.
Bahkan, berdasarkan--lagi-lagi--anecdotal evidences, aset-aset ini telah berpindah ke pemilik lama yang membeli secara murah dengan biaya yang ditanggung oleh pembayar pajak. Rate of recovery aset tidak seperti yang diharapkan, mencapai 30-40 persen. Bau busuk dalam proses penjualan pun tidak terhindari. Kasus yang terakhir menyangkut penjualan BCA, tempat Bank Indonesia dan BPPN secara mudah dikelabui dengan ketidakjelasan pemilikan konsorsium Farallon, yang sekarang memiliki Bank Central Asia.
***
Cerita kegagalan reformasi ini bukan monopoli BPPN saja. Penyelundupan adalah contoh lain lagi. Pemerintahan Soeharto sempat kehilangan akal mengatasi masalah penyelundupan ini dan akhirnya menyelesaikan langkah ad hock dengan menyerahkan hak pemeriksaan barang kepada perusahaan Swiss, SGS, yang memberikan beban tambahan bagi APBN. Kebijakan ini semula diharapkan dapat membuat aparat Bea Cukai berbenah memperbaiki diri saat diberikan kembali hak pemeriksaan pada pertengahan tahun 1990-an.
Kenyataannya, setelah hak mereka dikembalikan, kinerja Bea Cukai masih jauh di bawah harapan. Studi LPEM menunjukkan praktek-praktek penyelundupan telah merugikan negara sekitar US$ 700 juta-2 miliar dari bea masuk dan PPN yang tidak dibayar. Yang dirugikan adalah importir yang taat aturan, sementara aparat Bea Cukai dan importir yang nakal diuntungkan. Praktek penyelundupan memberikan dampak sekunder yang luar biasa, yaitu hilangnya keunggulan komparatif industri dalam negeri di pasar dalam negeri akibat perbedaan perlakuan pajak. Industri dalam negeri harus membayar PPN--dan dalam kasus tertentu, PPN barang mewah--sementara barang impor melenggang masuk tanpa harus membayar pajak. Respons yang diberikan Departemen Perdagangan dan Industri dengan memperkenalkan Nomor Pengenal Importir Khusus bukannya menyelesaikan persoalan, malah menambah biaya transaksi karena membuka peluang baru bagi praktek-praktek penyimpangan di lapangan.
***
Cerita serupa juga terjadi dalam kasus penyelundupan kayu log. Hasil perhitungan di atas kertas menunjukkan pemerintah dirugikan jutaan dolar akibat sistem pelarangan ekspor log, sementara Malaysia--yang menerapkan pajak log--mengambil keuntungan akibat kenaikan harga log dan sekaligus menikmati tambahan penerimaan pajak. Letter of Intent II, yang ditandatangani Desember 1998, menangkap peluang ini dengan mengubah pola pembatasan impor dari larangan menjadi sistem pajak dengan harapan akan terjadi tambahan penerimaan pajak log sekaligus bisa jadi instrumen untuk mengendalikan kerusakan hutan secara lebih efektif. Analisis di atas kertas dilakukan dengan asumsi bahwa institusi penegak hukum berjalan secara efektif. Namun, dalam kenyataannya, perubahan ini membuka peluang kolusi antara penyelundup dan aparat untuk melakukan penyelundupan besar-besaran yang merugikan negara dalam banyak hal: hilangnya penerimaan pajak log, terpukulnya industri dalam negeri akibat kesukaran memperoleh stok bahan baku kayu log dan perbedaan perlakuan pajak dan, lebih penting, makin cepatnya proses perusakan hutan.
***
Satu contoh lagi terjadi dalam kasus transportasi gas domestik. Kegiatan ini tergolong monopoli alamiah, karena merupakan hak bagi negara untuk melakukan intervensi, baik dalam bentuk regulasi maupun pemilikan langsung (BUMN). Rakyat tentu berharap biaya tol yang dikenakan adalah biaya rata-rata jangka panjang, bukan harga untuk memaksimalkan keuntungan. Ada dua perusahaan BUMN yang mendapat hak khusus ini: Pertamina dan PT PGN. Nyatanya, berdasarkan laporan audit Kantor Akuntan Arthur Andersen terhadap PT PLN, biaya tol penyaluran gas mencapai satu setengah sampai dua kali biaya yang dikenakan oleh perusahaan lain di negara lain dengan karakteristik risiko yang sama dengan Indonesia. Akibatnya, konsumen gas seperti PT PLN dan pabrik pupuk harus membayar harga gas lebih mahal dari yang seharusnya. Kasus ini disebabkan oleh ketiadaan kerangka regulasi yang jelas. Undang-undang migas yang baru diharapkan akan memberikan ruangan bagi reformasi ini.
***
Empat contoh di atas merupakan bukti adanya kegagalan institusi (institutional failures) yang menyebabkan proses reformasi tidak berjalan seperti yang diharapkan. Mengapa reformasi institusi diperlukan dalam menjamin terlaksananya transaksi ekonomi? Bukankah the invisible hand seperti yang diargumentasikan oleh Adam Smith dianggap telah memenuhi syarat cukup dan perlu (necessary and sufficient conditions)? Ekonom dari kelompok new institutional economics, yang juga memakai kerangka dasar ilmu ekonomi klasik, menganggap bahwa pelaku ekonomi tidak sepenuhnya rasional dalam mengambil keputusan. Potensi kegagalan pasar pun cukup besar sebagai akibat dari eksistensi barang publik, eksternalitas, monopoli alamiah, dan ketidaksempurnaan informasi. Jawaban atas hal ini adalah memperkenalkan pembangunan institusi. Bentuknya berupa munculnya aturan main--formal dan informal--dan mekanisme yang memaksa aturan main dijalankan, termasuk sistem insentif dan hukuman serta organisasi yang membuat, menjalankan, serta memaksa aturan tersebut dijalankan.
Dalam tiga kasus di atas, terlihat bahwa dari sisi kelengkapan aturan main tidak ada pertanyaan lagi. Tetapi "gap" yang paling besar terjadi dalam mekanisme penegakan aturan yang tidak berjalan dengan semestinya. Insentif untuk melakukan wrong doing sedemikian besarnya akibat sistem hukuman yang tidak berjalan. Akibatnya, sistem regulasi yang diperlukan untuk mendapat hasil yang terbaik tidak bisa diaplikasikan karena khawatir lebih besar biaya regulasi daripada manfaatnya.
Satu pelajaran penting bisa dipetik dari sini: reformasi ekonomi tidak akan sukses jika tidak diikuti dengan reformasi institusi secara komprehensif. Artinya, kebijakan-kebijakan yang dilakukan tanpa memperhatikan kapasitas institusi akan meningkatkan kegagalan reformasi. Dengan sistem hukum yang amburadul, jangan pernah berharap proses restrukturisasi perbankan bisa berjalan seperti yang diharapkan. Lihat berapa banyak kasus yang dimenangi BPPN di pengadilan. Selain itu, proses reformasi ekonomi juga harus dilengkapi dengan kerangka regulasi yang memadai. Kasus gas tidak akan terjadi jika kerangka regulasinya komplet. Ketiga, ekonom tidak bisa lagi sekadar melakukan reformasi dalam bidangnya, tetapi juga harus memperhatikan proses reformasi dalam bidang civil service, politik, dan terutama hukum. Berbagai studi dan pengalaman di negara yang memiliki sistem hukum (dan jaminan hukum) lebih baik akan menelurkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan di negara yang punya sistem hukum jelek. Yang terakhir, sekuens reformasi juga penting. Artinya, jangan pernah berharap hasil yang sesuai (dengan harapan) jika sistem insentif dan hukumannya tidak seimbang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo