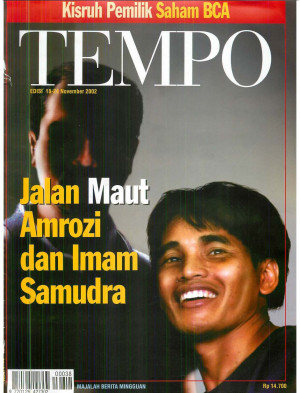Leo Batubara*)
*) Anggota tim pembuat draf UU Pers 40/1999 dan RUU Penyiaran 1999 & 2000
AKANKAH kita menolak atau mendukung Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang akan disahkan oleh DPR pada 25 November 2002? Penilaian dapat dilakukan paling tidak dengan dua parameter. Pertama: apakah produk politik tersebut berkiblat ke konstitusi? Kedua: apakah undang-undang itu berkiblat ke arah kekuasaan?
Seperti diketahui, DPR dan pemerintah di era Orde Baru membuat UU Pokok Pers No. 11/1966 yunto No. 4/1967 dan yunto No. 21/1982, serta UU Penyiaran No. 24/1997. Semuanya, langsung atau tidak langsung, didesain untuk membelenggu kebebasan pers dan jelas bertentangan dengan konstitusi yang menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan berekspresi.
Ketika Majalah TEMPO terlibat konflik dengan pemerintah, Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) TEMPO dibatalkan. Departemen Penerangan menilai liputan media ini—mengenai dugaan korupsi dalam pembelian kapal perang eks Jerman Timur—telah menyimpang dari prinsip pers yang bebas, dan bertanggung jawab.
Goenawan Mohamad, Pemimpin Redaksi TEMPO waktu itu, menang dalam gugatannya atas Menteri Penerangan RI di dua pengadilan: Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tinggi TUN. Surat keputusan Menteri Penerangan tersebut dinyatakan batal. Tapi, kasasi Mahkamah Agung (MA) RI 13 Juni 1996 malah mengesahkan pembatalan SIUPP TEMPO dan membatalkan putusan dua pengadilan sebelumnya.
Dalam kasus ini, pengadilan tingkat pertama dan kedua mengacu pada konstitusi dan UU. Sedangkan putusan MA mengacu pada Peraturan Menteri Penerangan No. 01/1984. Dengan itu, sadar atau tidak, peraturan menteri itu telah dipakai melanggengkan kekuasaan suatu rezim. Inilah Indonesia. Pejabat rendah berkiblat ke konstitusi. Pejabat tinggi MA berkiblat ke peraturan menteri.
Pada tahun 1999, sejalan dengan reformasi, DPR dan pemerintah berhasil membuat UU Pers No. 40/1999, yang didesain sebagai turunan dari konstitusi dan dinilai telah memerdekakan pers. Pelanggaran hukum oleh pers diproses secara hukum. Undang-undang ini mengakomodasi perubahan paradigma, dari pemerintah mengontrol pers menjadi pers mengontrol pemerintah agar tidak menyalahgunakan kekuasaan.
Kalangan pro-demokrasi menyambut positif undang-undang ini. Tapi sejumlah anggota DPR, juga Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Syamsul Mu'arif, menilai UU Pers 40/1999 telah menjadi penyebab lima penyakit pers: pornografi, character assassination, bohong dan provokasi, iklan yang tidak sesuai prosedur, dan munculnya wartawan "bodreks". Pers dituduh telah kebablasan. Karena itu, UU Pers tersebut perlu direvisi. Untuk itu pemerintah harus diberi legal authority agar dapat mengontrol pers.
Aktivis demokratisasi pers meng-counter gagasan itu. Revisi akhirnya ditunda. Bukankah bila rumah kemerdekaan pers dimasuki tikus, solusinya adalah menangkap tikus tanpa membakar rumahnya? Revisi akhirnya ditunda.Tapi semangat mengontrol pers rupanya belum padam, bahkan terakomodasi dengan sempurna dalam RUU Penyiaran hasil draf 20 November 2002.
Produk itu benar-benar sebuah ironi. Aktivis Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) terpanggil menyusun sendiri RUU Penyiaran pada Januari 1999. Pada Juni 2000, 26 anggota Komisi I DPR mengajukan RUU itu untuk diputuskan menjadi RUU Penyiaran usul inisiatif DPR. Pokok isinya masih mengandung prinsip-prinsip demokratisasi penyiaran. Pertama, kebebasan pers bersumber dari kedaulatan rakyat dan adalah hak warga negara dan, karena itu, penyiaran adalah urusan masyarakat. Kedua, badan pengatur penyiaran adalah badan negara yang independen dan bertanggung jawab kepada DPR sebagai representasi rakyat yang berdaulat. Badan itulah yang disebut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI berwenang memberi izin penyiaran. Ketiga, penyiaran diselenggarakan in the public interest dan diversity in ownership and content. Keempat, penyelenggaraan penyiaran bebas dari kontrol pemerintah, sensor, dan ancaman penjara, kecuali denda.
Namun, setelah dua setengah tahun dibahas oleh DPR dan pemerintah, RUU Penyiaran yang menunggu pengesahan itu telah berubah nyaris total. Sekitar 90 persen dari 50 anggota Panitia Khusus RUU Penyiaran rela melimpahkan kedaulatannya dan memberikan legal authority pada pemerintah untuk kembali menjadi penentu kebijakan dan pengendali penyiaran. Tidak berbeda dengan UU Penyiaran 24/1997, RUU ini sarat dengan pasal-pasal "cek kosong" (peraturan pelaksanaan oleh pemerintah), sensor, pengoperasian mata-mata penyiaran, dan ancaman pidana. Pemerintah kembali diberi otoritas pemberi izin frekuensi. KPI "direkayasa" hanya sebagai alat kendali pemerintah.
Agaknya jelas, semangat dalam pembuatan RUU Penyiaran ini bukanlah untuk memajukan industri penyiaran menjadi efisien dan kompetitif, melainkan agar terkontrol supaya melanggengkan kekuasaan.
MPPI telah berjuang habis-habisan, tapi kalah dalam pertempuran. MPPI berencana mengadu ke MA. Akankah MA memenangkan konsep aktivis demokratisasi penyiaran bahwa UU Penyiaran harus berkiblat ke konstitusi? Ataukah MA masih seperti di zaman Orde Baru dengan kembali berpihak pada pemerintah dan DPR—pembuat UU Penyiaran yang berkiblat untuk melanggengkan kekuasaan?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini