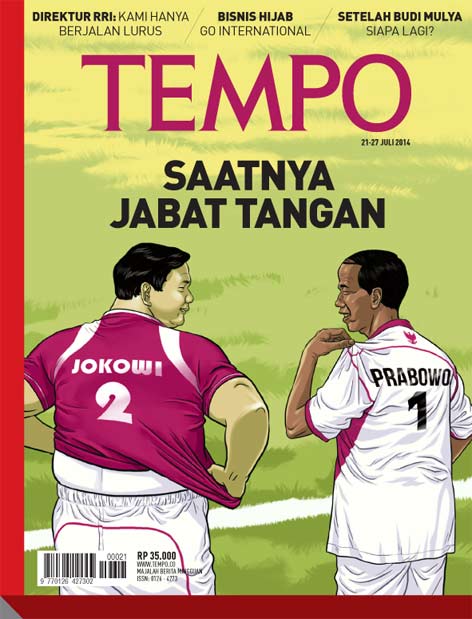Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Do I contradict myself? Very well, then I contradict myself.
I am large. I contain multitudes.
—Walt Whitman
Puluhan ribu orang berhimpun di sebuah sore yang tak terduga-duga: berlapis-lapis antusiasme, bertimbun-timbun harapan, juga cemas, berbaris-baris wajah yang tak cuma menatap kaku dan pasif.
Saat itu, dalam ruang itu berlangsung sebuah transformasi: kemeriahan itu seketika jadi sebuah "kami". Sebuah Kami yang siap. Sebuah Aku yang yakin. Sebuah subyek yang, dari saat ke saat, mengutuhkan dirinya.
Di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, 5 Juli 2014, konser dua jam untuk Jokowi itu sudah tentu bukan cuma sebuah perhelatan musik; tapi juga bukan hanya satu elemen kampanye politik. Saya kira saya menyaksikan sebuah "kejadian".
Dalam hal ini kata "kejadian" (dengan akar kata "jadi") lebih pas ketimbang (jika kita ikut-ikut membaca Badiou) "l'événement". Sebab yang semula tak berbentuk seketika hadir—tanpa digerakkan sebuah sistem, tanpa bisa dirumuskan dan dinamai.
Di sini saya tak berbicara tentang sebuah keajaiban. Yang ter-"jadi" adalah semata-mata sesuatu yang sangat langka, sesuatu yang tak bisa diuraikan dengan satu sebab dan satu akibat. Itu barangkali cirinya: tiap kejadian adalah terobosan dari tatanan sebab-akibat dan kelaziman yang biasanya berlaku. Ketika dalam politik hari ini pelbagai hal—dukungan di parlemen, demonstrasi di jalanan, pendapat di media massa—biasa diperdagangkan, di Gelora Bung Karno sebaliknya: puluhan ribu orang, ratusan musikus dan penyanyi, datang ke sana dan aktif di sana tanpa mendapatkan bayaran atau janji apa pun. Ketika lazimnya ribuan orang berhimpun dengan tujuan memprotes sesuatu, sore itu, dari tribun dan lapangan rumput stadion di Senayan itu, tak ada suara marah.
Fenomen penting dalam Pemilihan Presiden 2014 adalah berduyun-duyunnya ribuan relawan. Dengan segera "relawan" (dengan tekanan kembali kata "rela") jadi bagian kosakata politik Indonesia—sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah, dan mungkin sesuatu yang kelak akan mengubah hubungan-hubungan kekuasaan.
Tapi tak hanya itu. Fenomen lain yang penting: kreativitas dan humor, yang muncul dengan cepat dan tangkas, dari pelbagai sudut. Nyanyian "Salam Dua Jari" yang sederhana dan pas diciptakan Slank dan menyebar dari sudut ke sudut. Para perupa menghasilkan kartun (yang terkenal, Jokowi ditampilkan sebagai Tintin), stiker, poster, desain untuk kaus, dalam variasi yang hampir tak habis-habis. Para sineas dan pembuat karya audiovisual memproduksi film pendek dalam YouTube yang cerdas dan kocak.
Semacam anarki yang memikat berkecamuk. Tak ada pusat. Tak ada komando. Tapi ada sesuatu yang terasa hadir di mana-mana: harapan.
Sampai sekarang saya belum bisa sepenuhnya mengerti benar, mengapa Joko Widodo, tokoh kurus yang tak pandai berpidato itu—ia bukan Ali Sadikin yang karismatis atau Soeharto yang serius dan angker—bisa jadi fokus harapan orang banyak. Mungkin karena ia tampil sebagai seorang pemimpin yang bekerja, tanpa banyak lagak, bersahaja, bersih. Ia wajah baru ketika politik Indonesia mengecewakan. Tapi mungkin juga ia, sikapnya, kerjanya, telah mengisi sebuah lambang yang selama ini kosong: tanpa menjadi seorang suci, ia jadi lambang pemimpin yang "baik", yang justru tampak sebagai manusia yang tak istimewa.
Apa itu "baik"? Tak bisa dirumuskan. Tapi "yang-baik" itu sebenarnya hadir tiap hari dalam pergaulan manusia—kita mengenalnya dalam pertolongan dan pemberian yang ikhlas—dan sebab itu bukan keajaiban. Hanya, ketika pada suatu masa "yang-baik" itu terasa hilang, ia berubah jadi harapan yang intens. Juga sesuatu yang universal.
Sore itu, di Gelora Bung Karno, dalam gairah ribuan orang itu, yang universal sejenak singgah. Bukan dari langit, melainkan dari debu jalanan yang melekat di keringat orang yang berharap. Sebuah "Kami" pun lahir. Tapi pada saat itu, sebenarnya bukan hanya "Kami", melainkan juga "Kita".
Saya menyaksikan kejadian itu. Saya tak bisa merumuskannya dan saya kira ia bukan sesuatu yang bisa dirumuskan secara tetap. Tapi bagaimanapun, sore itu saya melihat bahwa politik, dengan akar kata polis ("kota" atau "negeri"), tak hanya satu wajah. Politik bukan hanya sebuah ketegangan dengan "Mereka". Ia juga sebuah proyek "Kami-Kita".
Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo