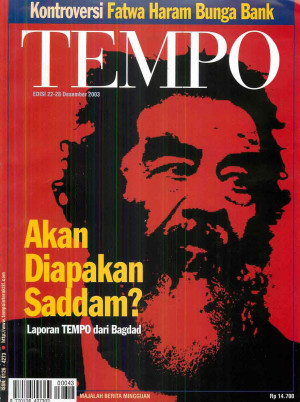Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TANPA disengaja, hasil verifikasi Komisi Pemilihan Umum menciptakan situasi kondusif bagi bangsa Indonesia untuk segera mencapai bentuk sistem kepartaian yang ideal, sistem multipartai sederhana. Jumlah partai politik menurun drastis. Dari 237 partai yang mendaftar ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 50 dinyatakan lolos verifikasi administratif dan langsung mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Akhirnya, oleh KPU ditetapkan 24 partai yang berhak ikut Pemilu 2004.
Dua hal perlu dicatat. Pertama, turunnya jumlah partai peserta pemilu dari 48 (tahun 1999) menjadi 24 (tahun 2004) bisa mengurangi kengerian masyarakat terhadap ingar-bingar dan dampak negatif dari proses pemilu. Dengan sistem proporsional terbuka dan ketentuan satu partai boleh mengajukan calon legislatif sebanyak 120 persen dari kuota yang tersedia, ngeri juga membayangkan kartu suara yang bisa menampung daftar nama dari 237 partai.
Saat ini saja, dengan 24 partai, tercatat 15.840 calon legislatif sementara. Menurut hasil sebuah simulasi memilih di Surabaya, dibutuhkan waktu empat menit bagi seorang "calon" pemilih menemukan nama yang diinginkannya. Bayangkan, berapa menit dibutuhkan oleh "calon pemilih" di Wamena, Kapuas Hulu, atau Mentawai? Namun, bagaimanapun, 24 partai jauh lebih manageable daripada 48 partai.
Kedua, tercipta polarisasi ideologi partai yang sangat jelas sehingga lebih mudah memetakan persaingan partai, sekaligus lebih menjamin terpilihnya presiden dan wakil presiden maksimal dalam dua putaran. Hasil verifikasi KPU seakan-akan membuktikan bahwa banyaknya partai yang muncul tidak sejalan dengan basis ideologi yang hidup di tataran masyarakat.
Hasil verifikasi itu (kembali) membuktikan bahwa basis ideologi orang Indonesia terpusat pada tiga titik: nasionalis, religius, dan sosialis. Tiga titik ini membangun garis: nasionalis-sosialis, nasionalis-religius, dan religius-sosialis. Variasi partai bermunculan dengan berbagai kombinasi di antara tiga garis ini.
Ada tiga variabel yang bisa kita gunakan untuk memahami pemetaan ke-24 partai peserta pemilu, yakni basis ideologi, basis massa, serta pengurus atau pendiri partai-partai baru. Ketiga variabel ini juga berfungsi memprediksi kecenderungan koalisi di antara partai-partai tersebut.
Data menunjukkan bahwa 70,83 persen partai peserta pemilu ada di garis nasionalis-sosialis; 25 persen ada di garis nasionalis-religius; dan 4,17 persen di garis sosialis-religius. Maknanya, ada kesadaran bersama dari partai baru untuk menggarap lahan suara di garis nasionalis-sosialis, yang selama ini "dikuasai" oleh PDIP dan Golkar. Tampaknya, cairnya identifikasi terhadap partai di garis ini (dibandingkan dengan identifikasi di garis nasionalis-religius) menarik perhatian para partai baru.
Berbagai simulasi statistik terhadap perolehan suara dalam pemilu di Indonesia, khususnya Pemilu 1955 dan 1999, telah dilakukan oleh para ahli. Hasilnya menunjukkan adanya konsistensi identifikasi di kalangan pemilih di garis nasionalis-religius dibandingkan dengan mereka yang di garis nasionalis-sosialis. Jelasnya, kapling suara di garis nasionalis-religius sudah terbentuk dan lebih permanen daripada kluster suara di garis nasionalis-sosialis.
Sukarnois Vs. Soehartois
Tampaknya, garis nasionalis-sosialis menjadi lahan suara yang menarik. Tapi ada dua catatan penting yang harus kita waspadai.
Pertama, berdasar data Pemilu 1999, "suara lepas" (lose votes) di garis ini hanya 5,279 persen. Itu akan direbut oleh 13 partai baru. Bandingkan dengan "suara lepas" di garis nasionalis-religius sebesar 8,248 persen, dan itu diperebutkan oleh tiga partai baru. Dari data ini bisa diprediksi bahwa perjuangan politik di garis nasionalis-sosialis akan lebih keras dibandingkan dengan mereka yang ada di garis nasionalis-religius.
Prediksi ini bisa meleset, bahkan menghasilkan fenomena sebaliknya. Boleh jadi justru koalisi antarpartai di garis nasionalis-sosialis mengental dan mendominasi peta politik Indonesia lima tahun ke depan. Sebuah simbol dibutuhkan. Gejalanya sudah mulai tampak dengan munculnya para anak "separuh dewa" atau kesayangan para separuh dewa dalam politik kita, seperti Megawati, Rachmawati, Tutut, ataupun para tokoh yang lahir dan besar di bawah karisma Sukarno maupun Soeharto.
Kedua, ke-24 partai itu dapat dibagi menjadi partai turunan atau anakan dari partai-partai besar, khususnya PDIP dan Golkar. Berdasarkan tiga variabel di atas, terlacak ada 8 partai anakan Golkar dan 4 partai anakan PDIP. Padahal, kita maklumi dominasi dinasti Sukarno di PDIP dan dominasi dinasti Soeharto di Golkar.
Bila dikaitkan dengan paparan pemetaan di atas, tidak salah bila disebutkan bahwa Pemilu 2004 akan diwarnai oleh persaingan Sukarnois melawan Soehartois. In menarik. Bukan sekadar karena ada aroma "dendam politik," atau Orde Lama versus Orde Baru, tapi pada tataran pemikiran menyangkut nasib bangsa Indonesia. Ajaran Sukarno yang populis berhadapan dengan ajaran Soeharto yang elitis.
Kalau saja ke-24 partai mampu mengelola dialektika antara pemikiran Sukarno dan Soeharto, bukan mustahil melalui Pemilu 2004 akan lahir pemikiran baru yang merupakan sinergi antar-keduanya, yang kita butuhkan. Artinya, polarisasi yang terbentuk tidak mutlak harus dibaca secara negatif. Kita harus membacanya secara positif. Untuk itu, rasionalitas harus dikedepankan. Lebih utama lagi kedewasaan berpolitik secara demokratis dari kalangan elite benar-benar diharapkan oleh rakyat Indonesia.
Upaya mensinergikan pemikiran dua bapak bangsa ini harus dipelopori oleh partai lama (besar) dan "dipaksa" oleh partai baru. Kesempatan bagi partai baru masih terbuka untuk memainkan peran bersejarah ini.
Memang, melihat "suara lepas" yang tersedia, basis finansial yang dimiliki, serta masih lemahnya efektivitas jaringan yang dibangun, tampaknya lahan terlalu sempit bagi partai baru untuk berbicara dalam Pemilu 2004. Tetapi fakta lain memberi harapan baru. Berdasarkan simulasi yang saya lakukan, diketahui bahwa derajat fragmentasi partai lama (dan besar) jauh lebih besar daripada partai baru. Konkretnya, partai lama (sekalipun besar) lebih mudah mreteli (terpecah) daripada partai baru. Misalnya, Partai Bintang Reformasi (PBR) datang dari PPP, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) datang dari PDIP, Partai Persatuan Nahdlatul Ummat Indonesia (PNUI) datang dari PKB, atau Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) datang dari Golkar. Tidak terdeteksi adanya partai anakan PAN atau PBB.
Demikian pula, cross cutting cleavages di partai lama (dan besar) sangat tinggi. Maknanya, derajat identifikasi di antara suporter atau simpatisan partai lama (dan besar) tidak sesolid di partai baru. Nah, bila partai baru berhasil mengumpulkan pecahan-pecahan itu, mereka berada pada posisi yang bisa menekan partai lama (dan besar) untuk mereka-reka sinergi pemikiran Sukarno dan Soeharto.
Di Simpang Jalan.
Kalau saja seluruh peserta Pemilu 2004 benar-benar berpikir tentang masa depan dan nasib bangsa dan negara Indonesia, koalisi yang akan segera mereka bangun akan mampu mengarahkan kita semua untuk lebih terfokus pada nation and character building. Masalahnya, muncul paradoks dalam politik Indonesia. Kekuatan reformasi 1998 terfragmentasi, sementara kekuatan politik lama (baca: Orde Baru) justru terkonsolidasi. Akibatnya, mereka kesulitan untuk membangun koalisi.
Koalisi politik umumnya dibangun di atas tiga landasan besar, yakni jumlah kursi di parlemen (terbanyak atau paling sedikit), kesamaan perspektif, dan kesamaan musuh. Partai reformis, yang umumnya tergolong sebagai partai baru, tidak memiliki basis untuk membangun koalisi berdasarkan jumlah kursi. Mereka belum pernah ikut pemilu, bahkan mereka perlu menunjukkan eksistensi dalam Pemilu 2004. Kebutuhan untuk menampakkan eksistensi inilah (antara lain mendapat suara memenuhi syarat electoral threshold) dapat membuat mereka saling menjegal. Sejauh ini, tampaknya hasrat untuk berkoalisi dari partai baru ditunda sampai hasil pemilu legislatif diumumkan.
Kesamaan perspektif merupakan basis yang masih bisa digunakan bagi partai baru untuk berkoalisi. Tapi, lagi-lagi kebutuhan menampakkan eksistensi diri tampaknya lebih mengedepan. Misalnya, partai PNI Marhaenisme dan PNBK sama-sama menyatakan berasas Marhaenisme Ajaran Bung Karno. PBR yang persis sebangun dengan PPP. Atau PKPB yang seasas dengan Partai Kongres Pekerja Indonesia (PKPI).
Harapan terakhir tampaknya ada pada kesamaan musuh. Munculnya Tutut, misalnya, bisa dibaca ke dalam dua arah. Pertama, sebagai upaya memacu konsolidasi dari kekuatan lama yang?karena asyik dengan rebut-rebutan kursi presiden?nyaris lupa bahwa situasi sosial-politik menguntungkan mereka. Peta calon presiden dalam konvensi Golkar, dengan nama-nama bermasalah pada peringkat teratas, jelas tidak menguntungkan kesempatan Golkar di Pemilu 2004. Tutut, sebagai anak separuh dewa, hadir untuk mengingatkan mereka akan semangat kebersamaan yang dulu pernah digalang dan sukses menjaga struktur kekuasaan Soeharto selama 32 tahun.
Seriuskah Tutut maju ke pencalonan sebagai presiden? Tergantung situasi yang berkembang dalam konvensi Golkar. Kalau yang muncul adalah tokoh yang tidak bisa diterima masyarakat dan itu merunyamkan nasib Golkar, tampaknya pencalonan Tutut bisa menjadi serius. Walaupun hanya dicalonkan oleh PKPB, sangat mungkin di ujung pertarungan akan ada mobilisasi seluruh partai anakan Golkar mendukung Tutut. Dengan cara ini, Golkar masih bisa mendominasi arena legislatif sekaligus "memenangi" kursi kepresidenan. Bukankah dengan sistem yang baru dimungkinkan presiden terpilih tidak memiliki dukungan mayoritas di parlemen?
Kedua, lemahnya basis-basis yang diperlukan bagi partai reformis (yang diasumsikan sangat ideologis) untuk bertahan dalam Pemilu 2004 membuat mereka lebih bersikap pragmatis. Basis finansial yang jauh dari memadai, basis ideologi yang tercabik-cabik, basis massa yang saling berebut, serta networking yang belum solid dapat menggoyahkan keyakinan partai baru akan ideologi yang diperjuangkan. Cara pandang yang pragmatis agaknya menjadi pilihan utama partai baru.
Sah saja. Apalagi, di era reformasi kita harus memiliki toleransi tinggi, bersikap fleksibel, dan berpikir pragmatis. Masalahnya, isi (content) dari pragmatisme yang berkembang sarat dengan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan permainan politik uang (money politics). Sejarah politik membuktikan bahwa musuh keduanya adalah ideologi.
Tampaknya, memasuki tahun 2004, kita akan disodori permainan lobi politik tingkat tinggi yang berupaya mencari titik keseimbangan Sukarnois versus Soehartois; reformis versus status quo, dan ideolog versus pragmatis. Sangat mungkin koalisi pelangi tergambar di cakrawala Pemilu 2004.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo