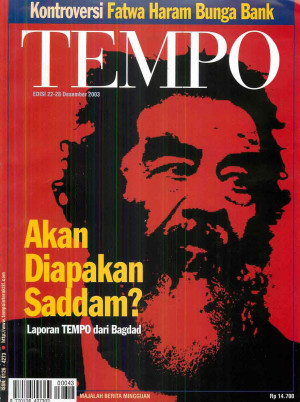Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
DI tengah ingar-bingar persiapan Pemilihan Umum 2004, terkadang muncul pertanyaan mengapa pemilu kali ini dianggap amat penting dan mungkin lebih penting daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Salah satu jawaban, inilah pertama kalinya diadakan pemilihan umum secara langsung pada berbagai tingkat pemilihan. Memang ada keterbatasan dalam tingkat "kelangsungan" ini, yang disebabkan oleh persyaratan calon-calon legislatif serta calon presiden dan calon wakil presiden. Misalnya, tidak semua partai politik berhak mengajukan calon presiden dan calon wakil presidennya (sebagai suatu paket) untuk dipilih, karena masih bergantung pada besarnya konstituensi yang dipersyaratkan. Menurut Undang-Undang No. 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, calon pasangan presiden dan wakil presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik atau koalisi yang sanggup memperoleh 15 persen dari jumlah kursi di DPR atau 20 persen suara dalam pemilihan umum untuk anggota DPR (pasal 5 ayat 4). Dengan lain perkataan, sudah ada semacam "seleksi alamiah" sebelumnya tentang siapa yang layak dijadikan calon kepala pemerintahan dan kepala negara. Kemudian calon presiden dan calon wakil presiden inilah yang akan dipilih secara langsung oleh para pemilih.
Berarti, keterlibatan rakyat dalam rekrutmen elite politiknya bersifat langsung. Tentu saja ini langkah maju yang penting, kalau saja diingat bahwa pemimpin redaksi sebuah majalah berita paling hanya bisa merekrut editor atau reporter baru buat majalahnya, sementara rakyat dapat merekrut presiden, wakil presiden, dan para legislatornya di DPR serta para wakil daerah di dalam DPD. Sekalipun demikian, mutu pemilihan masih bergantung pada sekurang-kurangnya dua pihak, yaitu adanya calon yang baik dan layak dipilih, dan adanya pengertian dan kesanggupan pada pemilih untuk memilih secara politically correct dan technically correct. Munculnya banyak partai politik sekarang ini (semenjak dari 112 partai yang mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia hingga ke 24 partai yang lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum) menunjukkan kesadaran tentang pentingnya menjadikan partai politik tempat pembinaan dan pematangan para calon yang akan ditawarkan ke hadapan publik pemilih. Pertanyaan yang menarik tentulah mengapa rakyat memilih dan mengapa mereka memilih si A dan bukan si B, atau partai A dan bukan partai B.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan bahwa dalam pemilu nanti para pemilih diharuskan menusuk tanda gambar partai dan tanda gambar calon (dengan variasi dalam keabsahannya). Hal ini secara implisit menunjukkan pengandaian tentang alasan atau motif yang diduga menggerakkan orang untuk memilih. Seorang yang memilih partai A, sebagai misal, diandaikan melakukan pilihan tersebut karena adanya identifikasi antara dirinya dan partai yang dipilihnya. Seterusnya orang lain yang menusuk tanda gambar calon B diandaikan melakukan pilihan karena ada identifikasi dengan tokoh atau seorang pemimpin politik. Pertanyaan sosiologis yang menarik ialah apakah pemilih di Indonesia lebih cenderung kepada party identification (identifikasi partai) atau figure identification (identifikasi sosok).
Dilihat sepintas, lalu dapat dikemukakan kecenderungan berikut ini. Partai yang bernapaskan keagamaan atau memakai atribut keagamaan lebih mudah menarik orang karena dorongan identifikasi dengan partainya.
Para warga NU dengan cepat mengidentifikasi dirinya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); kelompok-kelompok Islam yang lebih muda dan berbasiskan kampus mengidentifikasi dirinya dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS); sedangkan komunitas Islam lainnya mengidentifikasi dirinya dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Identifikasi semacam ini terjadi juga antara komunitas-komunitas Kristen dan Partai Demokrat Kasih Bang-sa (PDKB) atau antara komunitas-komunitas Katolik dan Partai Katolik Demokrat Indonesia (PKDI), meskipun dua partai terakhir ini tidak lolos verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. Sebaliknya partai nonkeagamaan rupanya lebih menarik orang karena identifikasi dengan seorang tokoh atau pemimpin dalam partai tersebut. Daya tarik untuk PDIP sebahagian besar disebabkan para anggota partai ini masih mengidentifikasi dirinya dengan Megawati Soekarnoputri, seperti juga PKPB (Partai Karya Peduli Bangsa) mencoba menarik simpati pendukungnya melalui identifikasi dengan tokoh seperti Siti Hardijanti Rukmana. Hal ini berlaku juga untuk partai nonkeagamaan yang lebih kecil.
Dua alasan tersebut sebetulnya dapat saling menunjang. Sebab, kelemahan seorang tokoh politik dapat diimbangi oleh visi, organisasi, dan disiplin partai, dan sebaliknya kelemahan dalam visi dan organisasi partai dapat diimbangi oleh inspirasi, kepemimpinan, dan karisma seorang pemimpin politik. Kalau dua jenis identifikasi ini menghadapi terlalu banyak kesulitan (partainya centang-perenang dan pemimpinnya tanpa integritas), besar kemungkinan orang tidak bergairah memilih, dan mulai berpikir untuk bergabung dengan golput (golongan putih). Pada titik ini sebaiknya dipertimbangkan kembali apakah sikap ini sesuai atau tidak dengan aspirasi untuk perubahan dan pembaharuan politik. Seseorang memilih menjadi golput karena dua kemungkinan. Pertama, opsi negatif, ketika dia merasa tidak mempunyai alasan cukup untuk turut memilih.
Kedua, opsi positif, ketika seseorang merasa mempunyai alasan cukup untuk tidak turut memilih. Opsi mana pun yang menjadi dasar pertimbangan, pilihan untuk tidak memilih tidaklah menguntungkan dilihat dari perlunya perubahan politik. Dengan tidak turut memilih dalam pemilu, seseorang sudah mengabaikan kesempatan (melalui pemberian suaranya) untuk menciptakan perubahan politik, khususnya menciptakan sirkulasi elite, melalui rekrutmen elite politik baru dalam pemilu. Tentu saja masih ada keraguan apakah suara yang diberikan dalam pemilu sanggup menciptakan perubahan politik, mengingat bahwa partai yang ada atau calon yang ada barangkali tidak cukup memenuhi harapan. Peluang untuk perubahan dan pembaharuan politik bisa besar atau kecil, tetapi kesempatan untuk melakukannya adalah sesuatu yang layak untuk dicoba dimanfaatkan. Sebab, dalam akibatnya (meskipun bukan dalam niatnya), tidak memilih berarti memilih untuk tidak mengadakan perubahan apa pun dalam politik Indonesia.
Dari segi itu terlihat dengan gamblang pentingnya partisipasi politik dalam pemilu, yang merupakan salah satu perwujudan dari partisipasi politik dalam demokrasi. Partisipasi itu memang merupakan suatu syarat mutlak tetapi?dan inilah keanehan demokrasi?belum merupakan syarat yang mencukupi. Beberapa teoretisi membedakan dua hal dalam kaitan ini. Pertama demokrasi mempersyaratkan luasnya atau besarnya partisipasi (the quantity of participation), yaitu aspek empiris dan kuantitatif dari demokrasi, sementara di pihak lain dia mempersyaratkan adanya alasan-alasan yang mendukung dan membenarkan partisipasi itu, yang membentuk kualitas wacana. Adapun kualitas wacana (the quality of discourse) adalah aspek kualitatif dan normatif dari demokrasi, yang ditentukan oleh dua kriteria lainnya, yaitu persyaratan argumentasi yang lebih baik (the criterion of better argument) dan persyaratan kepentingan lebih luas yang dipertaruhkan (the criterion of more general interests). Argumentasi yang lebih baik ini penting untuk demokratisasi, karena yang menjadi pokok pertimbangan adalah isi dan kuat-lemahnya alasan dan pertimbangan yang diajukan dan bukannya siapa yang mengucapkannya. Kepentingan yang lebih luas berarti bahwa seseorang yang hanya mengajukan alasan yang membela partainya saja harus dianggap kalah kalau berhadapan dengan orang lain yang mengajukan alasan yang membela kelompok miskin atau menyelamatkan lingkungan hidup.
Kedua komponen itu harus diambil bersama-sama, karena konsentrasi hanya pada kualitas wacana dapat membawa kita kepada oligarki orang-orang pintar dan kaum terpelajar dan menyingkirkan partisipasi masyarakat luas, yang barangkali kalah dalam berargumentasi tentang suatu soal. Sebaliknya, penekanan secara sepihak hanya pada besar dan luasnya partisipasi saja dapat membawa kita kepada menurunnya rasionalitas politik, karena pertimbangan didasarkan semata-mata pada "jumlah kepala" yang memilih dan mengabaikan "isi kepala" dalam memilih. Politik uang adalah sesuatu yang harus ditolak (dan dikutuk) karena dia menyingkirkan kualitas wacana demi mengejar kuantitas partisipasi. Masalah yang menjadi uji-coba untuk dua komponen demokrasi ini sekarang adalah kembalinya unsur Orde Baru ke dalam politik Indonesia. Apakah masalah ini akan diputuskan hanya berdasarkan besar-kecilnya partisipasi pendukung politik Orde Baru, atau juga berdasarkan argumentasi yang lebih baik, dan kepentingan lebih luas yang dipertaruhkan di sana.
Ujian lainnya adalah apakah kepemimpinan politik Indonesia bisa menerobos kecenderungan yang semakin kuat kepada kepemimpinan dengan legitimasi tradisional. Pemimpin jenis ini adalah mereka yang biasanya didukung oleh suatu tradisi yang berhubung dengan paham tertentu atau tokoh tertentu. Munculnya tiga partai peserta pemilu yang mengusung nama Bung Karno jelas menunjukkan kecenderungan ini, di samping jalur keagamaan yang juga mengandalkan pengikut yang setia pada tradisi suatu agama.
Maka kepemimpinan Indonesia, khususnya dalam pemilu yang akan datang, bukan saja mengalami diferensiasi dalam kepemimpinan yang didasarkan pada paham keagamaan dan kepemimpinan sekuler, tetapi juga melibatkan kompetisi di antara pemimpin dengan legitimasi tradisional dan legitimasi yang lebih rasional. Belum kelihatan tanda-tanda bahwa akan muncul seorang pemimpin dengan karisma yang besar dalam politik Indonesia. Maka para calon presiden dan calon wakil presiden mempunyai pilihan yang lebih sempit: mengandalkan legitimasi tradisional atau mencoba mencapai suatu legitimasi baru yang lebih rasional sifatnya. Legitimasi seperti ini pada hemat saya akan didukung oleh kompetensi seorang calon, berupa kesanggupannya bekerja dan keberaniannya mengambil keputusan politik, konstituensi yaitu luasnya dukungan yang dapat direbutnya melalui persuasi politik dan agregasi kepentingan politik, dan integritas yaitu adanya prinsip-prinsip politik yang menjadi pegangannya dalam menghadapi keberuntungan ataupun risiko-risiko politik.
Kalau hal ini tercapai dalam pemilu, partai politik benar-benar menjadi benchmark demokrasi, karena menyumbang sesuatu yang lebih besar dan lebih penting daripada sekadar politik partai.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo