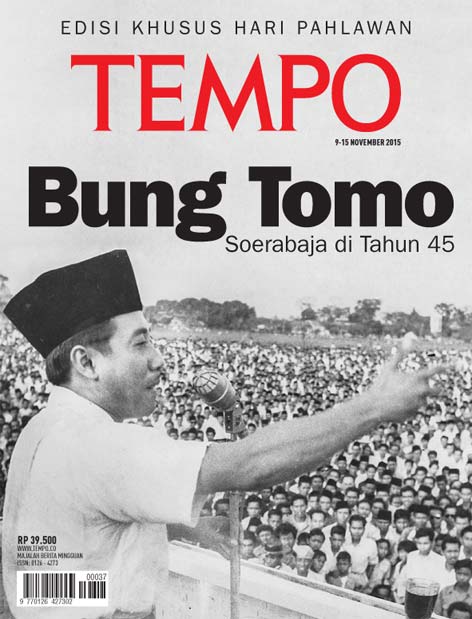Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
A, B, C. Map-map berisi kertas dengan daftar puluhan nama itu terletak di tengah meja kantor sebuah rumah tahanan di Jakarta, dengan klasifikasi yang akan menentukan nasib orang-orang yang disekap. A: dihabisi. B: dibuang ke Nusakambangan. C: dikurung di kota terdekat. Atau tak jelas nanti bagaimana.
"Tak jelas" adalah manifestasi kedaulatan dalam bentuknya yang paling ekstrem: kekuasaan bertindak dengan asumsi tak akan dituntut memberi alasan. Juga ketika menentukan hidup mati ribuan orang. Juga ketika salah.
Dengan kata lain, kedaulatan menampakkan diri dengan sebuah keputusan untuk mengecualikan diri dari hidup bersama yang dibentuk hukum dan bahasa. Ketika hidup ditinggalkan hukum dan percakapan, orang pun bisa dengan semena-mena digolongkan ke dalam oknum yang tak diakui: A, B, C, D....
Seakan-akan Giorgio Agamben sedang mengukuhkan thesisnya di Indonesia di hari-hari itu: kekuasaan tampil berdaulat ketika memproduksi manusia sebagai vita nuda, kehidupan bugil yang bisa dijadikan "korban" tanpa bisa digugat. Ia bukan "korban" sebagai putra Ibrahim yang disucikan, tapi semata-mata sebagai tumbal buat menegakkan sebuah Orde, seperti kerbau yang kepalanya ditanam sebelum sebuah gedung dibangun.
Tapi kekuasaan yang tak hendak berada dalam hukum dan percakapan makin tampak sebagai kekuasaan yang tegang dan penuh kecurigaan. Indonesia, hari-hari itu, adalah sebuah republik yang tak menentu.
Di ibu kota, tak jelas siapa yang mengendalikan aparat dan memberi arah. Bung Karno masih disebut Presiden dan Pemimpin Besar Revolusi; sistem politiknya "Demokrasi Terpimpin". Tapi bisakah ia mengontrol Angkatan Darat? Masih dipatuhikah ia oleh organisasi-organisasi politik yang selama ini jadi penyangga kekuasaannya?
Juga di ibu kota, Soeharto, yang belum seorang jenderal penuh, duduk sebagai panglima keamanan dan ketertiban; ia mengendalikan kekuatan militer, yang di masa itu juga mengendalikan pos-pos pemerintahan sipil. Sanggupkah ia terang-terangan melawan Bung Karno andai kepala negara yang sangat berwibawa itu berkeras memerintahkan pembantaian dihentikan?
Mungkin di hari-hari itu, di wilayah Indonesia tak ada Negara seperti dipikirkan para pakar hukum konstitusi. Yang mungkin ada hanya bayang-bayangnya: seperti hantu. Hantu yang menakutkan, tapi tak konsisten. Yang mungkin konsisten dan punya efek hanya ruang penyiksaan di pelbagai tempat, dengan map A, B, C atau tidak. Pembunuhan besar-besaran terjadi di Kediri, sebagaimana cerita seorang saksi mata, dilakukan para pemuda NU, PNI, dan lain-lain—bukan oleh alat Negara. Pembunuhan sejenis terjadi di Jawa Tengah dan Bali, dengan bantuan RPKAD, resimen khusus Angkatan Darat, alat Negara. Sebaliknya di Jawa Barat tak tercatat pembantaian orang PKI dalam skala besar—dan kalaupun terjadi, itu dilakukan jauh sebelum 1965 oleh pasukan Darul Islam di dusun-dusun. Pernah disebut, panglima militer di sini, Mayjen Ibrahim Adjie, mencegah pembantaian di wilayahnya; ia mengambil sikap yang berbeda dengan Soeharto. Ada pula yang menulis bahwa di Jawa Barat beberapa perwira teritorial (ya, alat Negara) pro-PKI; mereka tak membiarkan pembunuhan seperti di tempat lain terjadi.
Hari-hari yang bengis dan tak menentu itu menunjukkan betapa sulitnya menunjuk "Negara", menuntutnya agar minta maaf. "Negara" bukan satu struktur yang tak berubah sejak 1965. Jika "Negara" ibarat sebuah ruang, ia ruang yang diisi dan dibentuk sejarah—dan sejarah dibangun bukan saja oleh saat-saat seia-sekata, tapi juga saat-saat konflik. Jika "Negara" ibarat sebuah tata yang mirip bangunan, ia didirikan setelah menanam kepala yang lepas dari leher yang dipenggal, secara harfiah atau kiasan.
Dengan kata lain, Negara adalah kisah kekerasan dan waktu. Marx menunjukkan "Negara" selalu bersifat represif terhadap kelas yang lain, dan hanya kelak, ketika perbedaan kelas hilang, "Negara" akan lapuk dan layu. Para pemikir sesudahnya juga menunjukkan terpautnya "Negara" dengan sejarah. Bagi Badiou, misalnya, "Negara" selalu genting. L'État, menurut Badiou, sebenarnya efek "menghitung-jadi-satu", compte-pour-un, atas sebuah situasi—dan yang disebut "situasi" itu pun efek dari penyatuan yang ditampilkan dari multiplisitas yang mirip anarki. L'État tak stabil karena dalam tubuhnya selalu ada unsur yang tak diperhitungkan yang suatu saat bisa meletus sebagai pembangkangan.
Singkat kata, "Negara" adalah tata yang terbentuk secara acak dari saat ke saat, sebuah proses yang belum juga berakhir—dan selamanya mengandung instabilitas dan kekerasan. Hukum, yang menjaganya dari khaos, setali tiga uang.
Dalam perspektif ini, menghakiminya adalah sebuah ikhtiar yang rumit, mungkin heboh; tapi saya tak yakin keadilan akan tercapai setelah itu—baik ketika "Negara" dinyatakan bersalah maupun tidak.
Lagi pula, siapa yang patut mewakili "Negara" untuk dituntut atas kekejaman dan kejahatan setengah abad yang lalu—setidaknya karena telah membiarkannya? Dan jika "Negara" berdiri selalu dengan menciptakan orang-orang yang harus disisihkan, yang hidup dalam vita nuda, adilkah jika ia hanya digugat karena pembantaian di satu waktu, bukan di waktu lain?
Tentu, kita mesti mengungkap kekejaman 1965 (atau sebelumnya, atau sesudahnya). Kita perlu mengutuk keras-keras, menghukum para algojo, mengurung para penggerak mereka. Tapi ada satu kalimat tua yang arif: "...di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan."
Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo