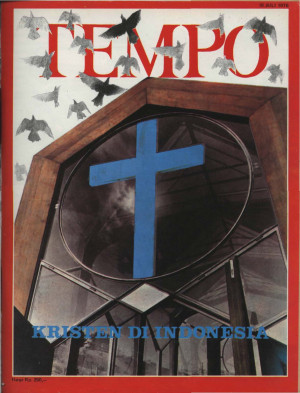KITA tahu, diskusi yang bersate kambing itu bisa sama menarik
dengan yang pakai mikropon. Seperti yang kejadian tiga tahun
yang lalu, itu di gedung DKI-Jaya, tepatnya 3 April. Kami sudah
cukup pusing membincangkan perkara-perkara muskil eperti
industrial design dan nasib kerajinan rakyat di pasaran dunia
dan sebagainya di muka mikropon. Pada acara menyikat sop buntut
dan sate kambing tahu-tahu saja mengelompok tiga orang: ibu
Suwarmilah (Kepala Lembaga Pengembangan Ekspor Nasional), ibu
Lasmidjah Hardi, dan saya. Ingat-ingat ada yang mulai bertanya
apakah sop yang kami cucup itu bukan sop buntut kuda, tapi
kalaupun begitu kami juga tidak tahu apa salahnya, biarpun tentu
sedikit aneh. Tapi kalau susu bubuk palsu dan sari jeruk palsu
itu terang tidak kami sukai. Bicara tentang pemberantasannya
maka langsung saja ibu Hardi bertekad untuk membikin semacam
lembaga pelindung konsumen Gegas seperti itu kontan saya
tanggapi dengan bersemangat. Kita semua ini kan konsumen, dan
setiap hari kita ini kan jadi permainan pedagang dan produsen?
Baiklah,ceritanya kemudian sudah kita tahu semua, meskipun bukan
cerita hot. Berdirilah Yayasan Lembaga Konsumen (YLK). Kita
tunggu saja. Satu ketika YLK ini bisa jadi berita paling hot di
negeri kita. Sekarang mereka sedang mencoba membereskan soal
praktek menentukan harga di tempat kita belanja.
Setiap barang itu mestinya punya harga tertentu tapi berapa,
itu tidak ada orang yang tahu pasti. Ekonomi kita ini menjadi
begitu kocak sampai pedagang sendiri tidak tahu harga barang
jualannya. Di setiap toko kita lihat pelayan yang linglung dan
gelagepan kalau ditanya harga suatu barang. Dan jangan kira
majikan toko juga selalu tahu. Cuma karena dia harus menyebut
harga, maka dia ngomong tapi siapa bisa jamin bahwa dia tidak
ngomong asal ngomong? Sudah begitu dia masih bisa dibisiki
konconya, lantas berubah pikiran, dan tentu saja menyebut harga
yang lebih tinggi. Maaf oom, barang ini ada anunya di dalam,
jadi mahalan.
Ada toko toko di mana pelayannya yang menentukan harga. Konsumen
menghampiri sang majikan di kassa untuk membayar, tapi ini
majikan kok malah tanya dulu kepada itu pelayan: "Jual berapa?"
Kadang-kadang saya pikir itu pelayan saya suap saja dulu dengan
sehelai sudirman.
Beberapa tahun yang lalu sobat saya yang baik budi membuka
restoran istimewa. Para pengunjung diperlihatkannya daftar
makanan berikut harganya. Setahun kemudian dia mulai "main". Dia
pasang daftar makanan, tapi lupa pasang daftar harga. Dia mulai
"pintar" menaksir tetamunya dengan sekejap saja: gengsinya,
duitnya, lagaknya dan sebagainya dengan maksud menyesuaikan
harga makanan dengan keadaan sang tamu. Kalau daftar harga sih
sebetulnya ada, itu yang disembunyikannya dalam laci uang. Jadi
sembari menghitung dia mengintip-ngintip ke dalamnya. Katanya
dia menyesuaikan diri dengan restoran-restoran lain. Kata saya
dia menyesuaikan diri dengan bangsa penipu. Cuma untungnya
penipu bangsa dia tidak pernah masuk koran atau masuk bui, sebab
liberalisme gaya pedagang ini sah di negeri kita. Ini sobat yang
baik budi kok begini jadinya.
Supaya tidak perlu mengintip-ngintip dan jadi linglung, banyak
pedagang lantas punya akal bulus. Namanya siasat "liberalisme
terpimpin". Barang-barang kelontong mereka tempeli label berisi
rerumusan rahasia Albert Einstone atau Ein-tsetung entah mana
yang betul. Maka setiap hari sang kelontong bisa menghibur diri
dengan pemandangan konsumen yang begitu gairah, mendekati barang
tapi mendadak kecele kalau membaca labelnya. Lihatlah dia lantas
menoleh ke yang empunya barang, mohon diberi tahu berapa
harganya. Sedaap. Ini bagus buat adegan film. Komedi boleh,
tragedi boleh.
Kata kawan, orang hidup di Indonesia ini musti tahu seni menawar
harga. Ini ekonomi liar sebetulnya disesuaikan dengan
kepribadian bangsa kita katanya. Kawan ini jelas tukang lawak.
Dia sebetulnya tahu bahwa kebudayaan nawar ini kebudayaan kelas
berduit yang dipaksakan kepada kelas miskin supaya yang miskin
tetap miskin. Mana pernah dia menawar di loket bioskop atau di
toko buku atau di salon kecantikan. Kalau dia coba nawar arloji
atau kopor echolac dia merengek seperti peminta-minta. Tapi
lihat kalau dia nawar tempe dan daun sledri. Si bakul sayuran
dikocoknya mati-matian dan kasar-kasaran sampai bertekuk lutut.
Ini namanya kebudayaan sakit dan kepribadian brengsek. Sidang
UNCTAD bisa jadi kocak kalau mendengar semua ini.
Kata saya dulu kepada ibu Hardi, suatu YLK itu bakal banyak
musuhnya, dan itu wajarlah. Mereka kuat-kuat dan akan
kusak-kusuk sampai tingkatan yang tertinggi. Mereka akan
membujuk dan menyuap dan menjegal dan menina-bobokkan YLK.
Mereka bisa bikin YLK tandingan berisi "staf ahli"nya sendiri
dengan maksud memberi informasi lain kepada konsumen. Senjata
mereka yang hebat tentulah iklan dengan segala rupa dongengnya
dan sayembaranya dan hadiahnya.
Syarat YLK yang kuat dan berwibawa memang cukup berat.
Semangatnya mesti kerakyatan, jiwanya mesti bersih, penilaiannya
mesti ilmiah, perjuangannya mesti tekun. Syarat lain ialah
masyarakat konsumen yang lebih dewasa, lebih arif dan tidak
mudah termakan dongeng dongeng yang kurang masuk akal. Kalau YLK
begini dan rakyat begini bisa bahu membahu, bisalah kita nanti
mengharapkan mekarnya ekonomi yang tambah sehat dan kepribadian
bangsa yang tambah terhormat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini