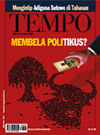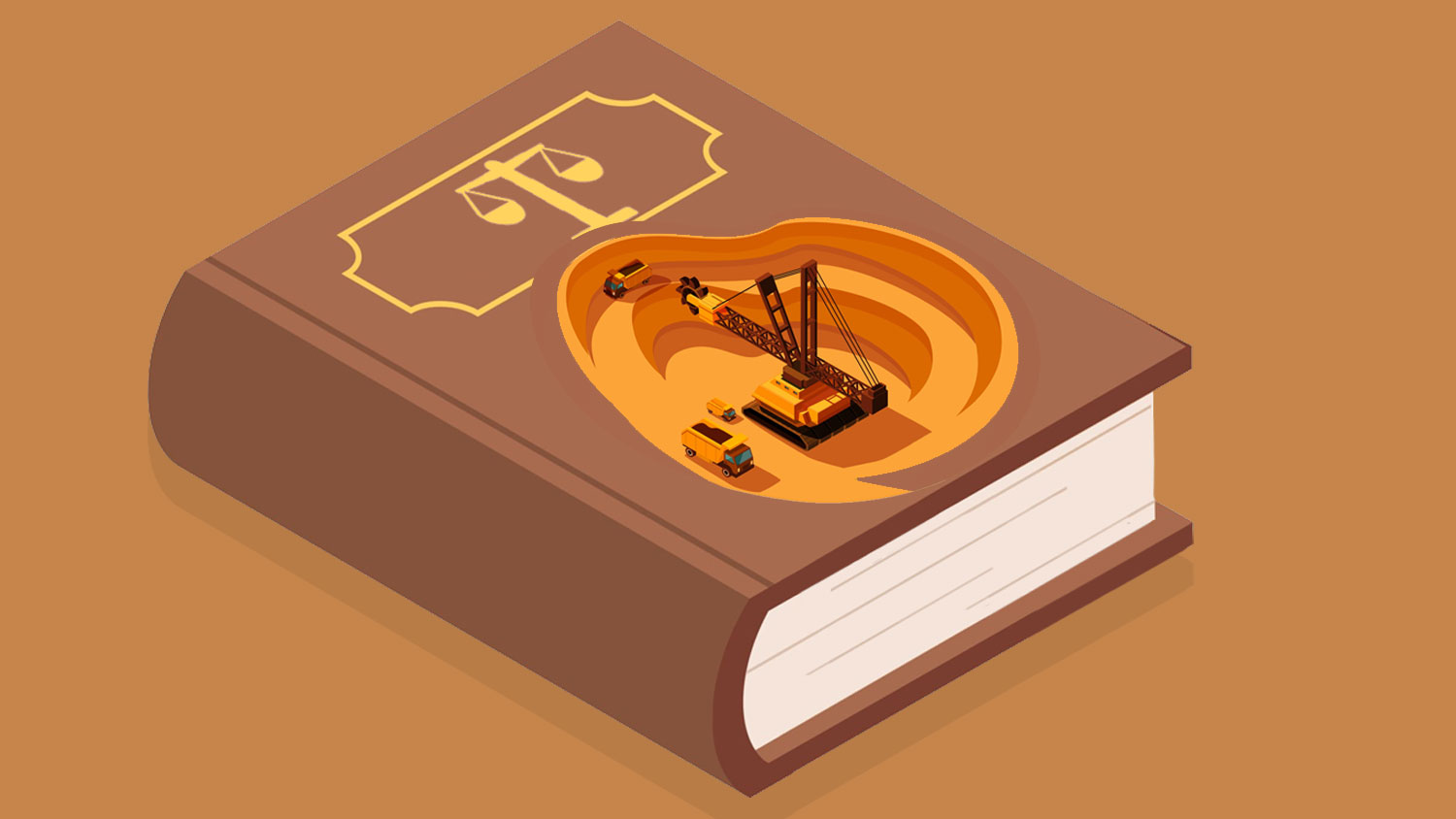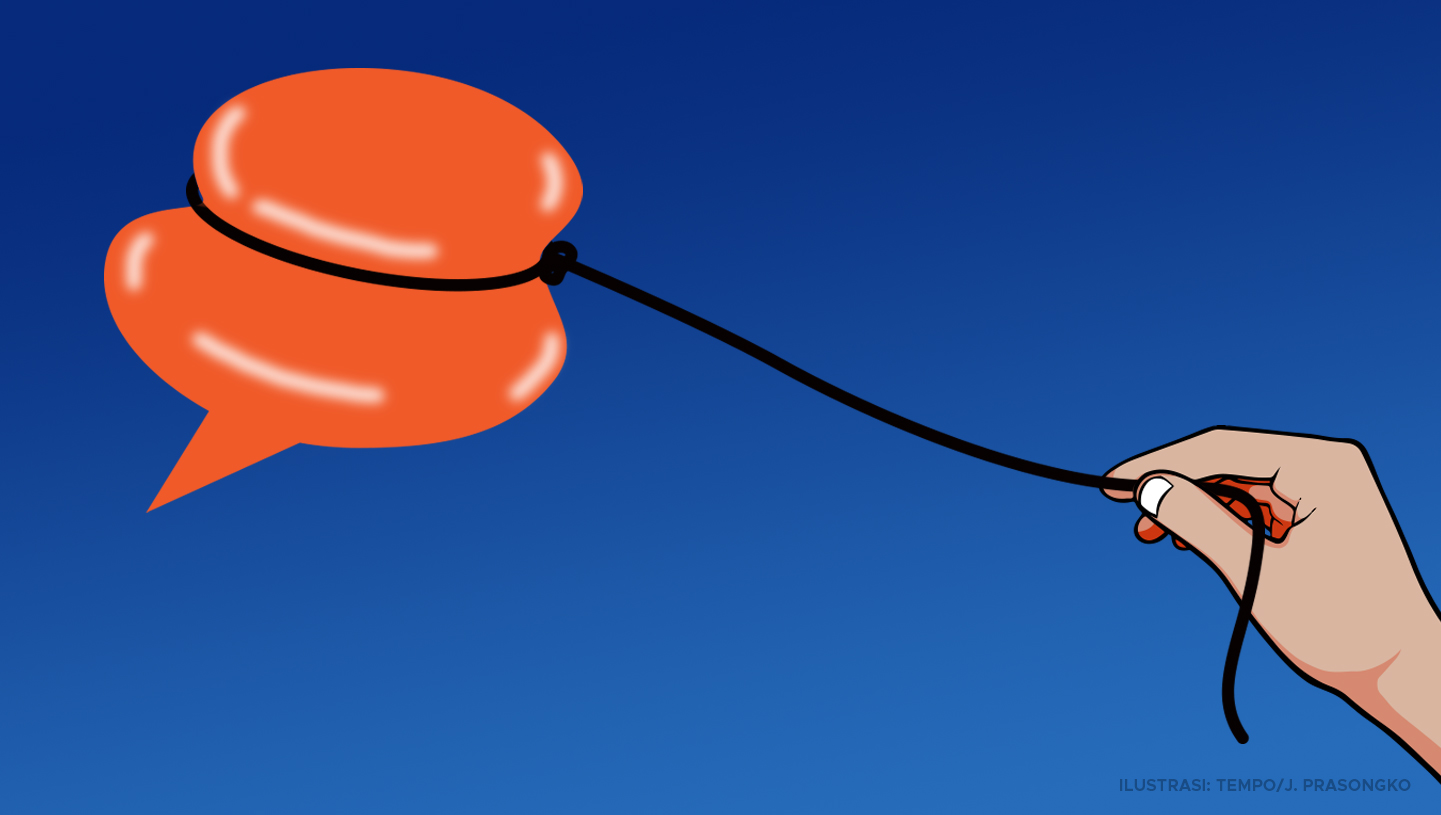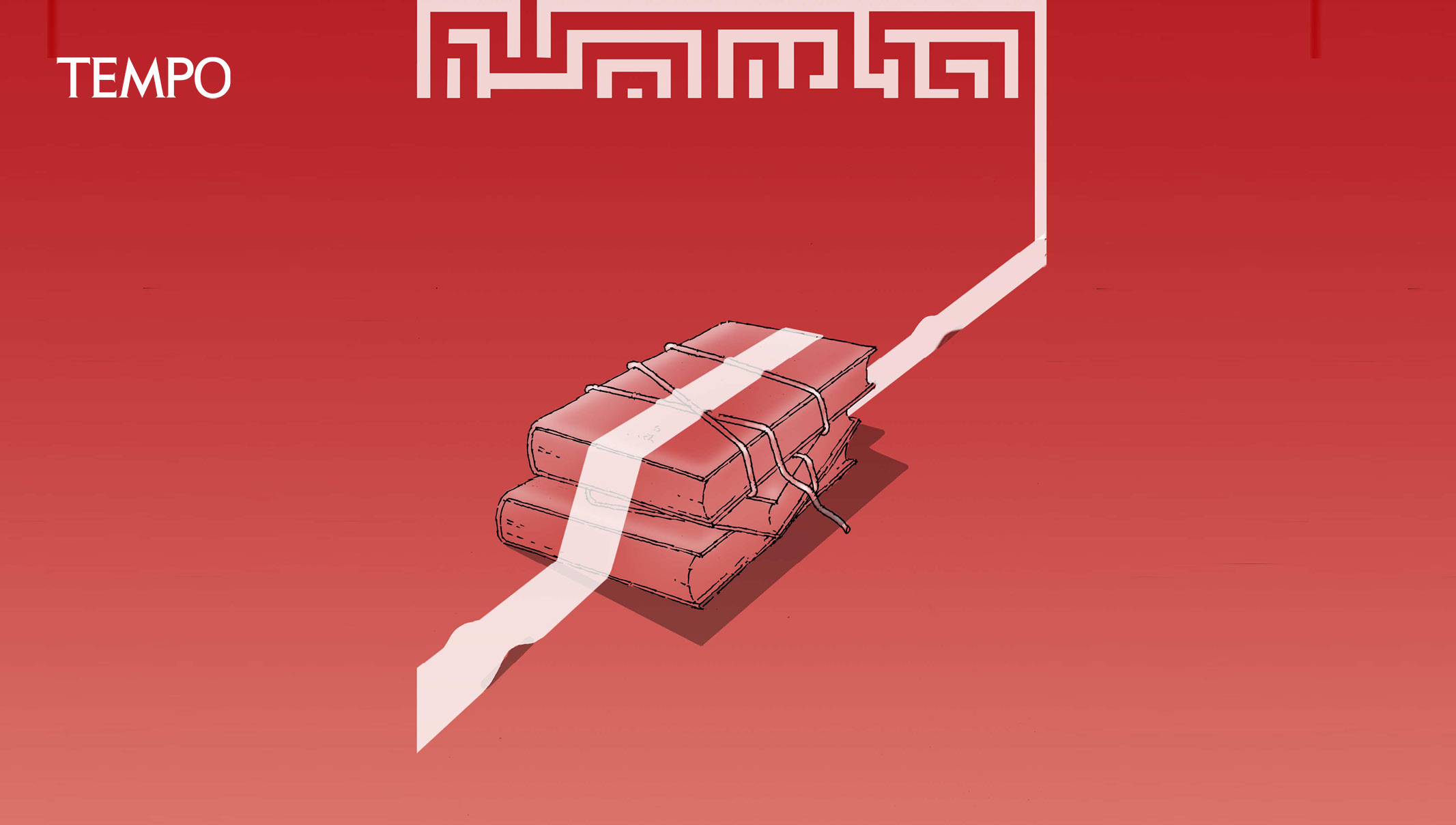Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SETELAH gelombang kepedulian yang besar terhadap akibat bencana gempa dan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara, masuklah kita kepada fase yang sangat menentukan. Fase menentukan itu adalah kaitan antara tawaran-tawaran bantuan mancanegara dan masalah-masalah geopolitik serta hitungan-hitungan untung rugi. Para pemerhati kerja sama internasional mulai teringat pada berbagai persyaratan yang biasanya mengiringi setiap komitmen bantuan.
Uluran tangan untuk rekonstruksi Aceh akhirnya tidak semata-mata berwajah kemanusiaan, namun bergeser ke masalah hubungan ekonomi, sosial, maupun politik.
Pemerintah Indonesia, yang sedang menjadi fokus internasional, memang bertanggung jawab, tapi peran masyarakat tidak dapat diabaikan. Keinginan sektor nonpemerintah di luar negeri untuk menyalurkan bantuan sedemikian besar, mungkin melebihi komitmen negara-negara donor. Mayoritas penggalang bantuan juga menghendaki akses langsung ke pihak yang memerlukan.
Jika kita ingin mengambil manfaat optimum dari kecenderungan ini, perlu falsafah dan pendekatan pengelolaan yang setimpal. Pemerintah sebagai otoritas perlu mengambil pendekatan kemitraan, serta bersikap transparan dan komunikatif dalam kebijakan rekonstruksi.
Peran masyarakat untuk saling berhubungan, baik sebagai sesama warga dunia yang saling membantu maupun dalam menjalin hubungan internasional antarmasyarakat, perlu diberi keleluasaan. Sungguh ini bukan hal mudah, karena para pejabat kita berada dalam masa kagok. Pendekatan etatisme sudah mulai tidak efektif, sedangkan demokratisasi dalam tahapan awal belum mampu menciptakan semangat egaliter yang produktif. Kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat pun belum terbiasa menangani pekerjaan dalam skala sebesar ini.
Kemampuan kita untuk memanfaatkan kepedulian global, sekaligus menegakkan harga diri serta menyelamatkan diri dari permainan geopolitik, antara lain tergantung pada isu yang selama ini terluput dari perhatian: sistem logistik terpadu.
Manajemen logistik dan keuangan merupakan standar nyata untuk mengukur transparansi dan akuntabilitas. Kita sering mendengar tentang salah satu ukuran terpenting manajemen keuangan, yaitu akuntabilitas menurut penilaian akuntan publik internasional. Tentang akuntabilitas manajemen logistik, kita tidak pernah mendengar standar yang digunakan. Padahal, tepercaya atau tidaknya pertanggungjawaban rekonstruksi tergantung pada manajemen logistik dari barang-barang yang dikelola.
Mereka tidak akan hanya mengerahkan barang-barang bekas, tapi juga produk-produk mutakhir yang diharapkan mempunyai efek positif bagi daya saing industri negara donor. Mereka pun mengharapkan barang-barang itu bisa dioperasikan dengan semestinya kelak, dan diurus oleh organisasi sipil yang jelas dan tertentu.
Kita tidak berurusan lagi dengan suplai barang-barang yang cepat habis seperti makanan dan obat-obatan, melainkan barang-barang modal yang mahal seperti peralatan medis, alat-alat berat, atau perangkat telekomunikasi.
Seluruh riwayat barang-barang ini harus bisa dijejaki sejak datang, digudangkan, diangkut, dipasang, dioperasikan, dirawat, dan berakhir usia teknisnya. Bisa dibayangkan betapa besar pekerjaan yang dihadapi untuk menyiapkan perangkat lunak, kelembagaan, maupun keterampilan berkualitas yang diperlukan untuk pekerjaan sebesar ini. Perlu juga diingat bahwa manusia yang perlu disiapkan dan dipekerjakan tentunya putra-putri setempat. Apakah kita mampu mengelola ini semua dengan semestinya?
Masalahnya bukan soal mampu atau tidak, tapi kemauan untuk bersikap terbuka dan bersedia belajar sambil bekerja serta melakukannya dengan kepala tegak. Semua orang tahu Indonesia adalah negara muda dengan segala kelemahannya. Yang dijengkelkan orang adalah kebiasaan komunikasi yang tidak pernah langsung menyentuh masalah, dan berkutat pada soal sosiopolitik yang abstrak dan kualitatif.
Mulusnya citra diri bangsa dalam penanganan rekonstruksi tergantung pada penanganan konkret kerja-kerja lapangan, demikian juga peniadaan potensi konflik. Mengenai masalah-masalah sosiopolitik yang kualitatif, kunci penyelesaiannya terdapat pada penanganan teknis yang terpadu dan terukur, bukan pada retorika.
Terlepas dari soal benar atau salah, Kapten Syuib dan Farid Faqih merupakan korban dari ketiadaan atensi pada keterpaduan sistem logistik. Mereka menjadi korban dari persepsi logistik yang tidak satu. Sang kapten mewakili pihak pemerintah dan Farid Faqih mewakili unsur masyarakat. Mereka terlibat konflik karena bekerja dalam keadaan yang menafikan sikap saling percaya.
Konflik kedua orang itu merupakan ujung dari kelemahan sistem dan manajemen, bukan soal hubungan antaretnis, bukan juga hubungan sipil-militer. Benturan antara keduanya merupakan peringatan tentang kemungkinan konflik yang lebih besar dalam fase rekonstruksi. Karena itu, kelemahan manajemen logistik bisa merupakan sumber benturan yang tidak hanya individual, tapi bisa menciptakan efek berantai yang menyangkut soal-soal makro politik.
Bencana besar sering membawa perkara besar yang tidak terduga. Harus juga diingat juga bahwa fase welas asih kemanusiaan yang penuh ketulusan sudah lewat. Boleh dikata kemampuan kita membalas kepercayaan di dalam maupun di luar negeri amat tergantung antara lain pada kemampuan kita menerapkan keterpaduan penanganan logistik, setidaknya kemauan untuk belajar menerapkannya.
Aneh, untuk urusan sepenting ini belum ada rumus yang keluar ke ranah publik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo