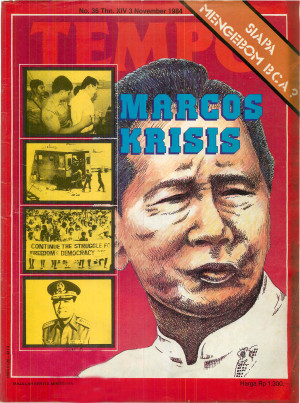ISLAM adalah agama yang penuh elan, tapi dengan umat yang hatinya luka. Seorang teman menyebutnya dengan nada sayu: a wounded civilization. Kiasan itu tentu saja berasal dari V.S. Naipaul, ketika ia menulis tentang tanah para Ieluhurnya yang jauh, India: A Wounded Civilization. Dalam sejarah tampaknya selalu saja suatu peradaban pernah menjulang kemudian terpukul, dan sindrom "peradaban yang terluka" hadir. Pada Islam, luka itu relatif baru setidaknya sisanya masih sangat terasa di akhir abad ke-20 ini. Dengan kata lain, ia belum lagi sembuh. Dulu, pada awal munculnya ke permukaan sejarah, kaum Muslimin menerima hidup dengan hati riang dan yakin. Mereka tak gentar mencari ilmu ke Negeri Cina, menyalin karya Yunani, menyadap puisi dari Persia dan teater di Timur Tauh. Dari semua itu. mereka menciptakan banyak hal, menemukan banyak segi. Mereka seakan tengah menjalankan mandat yang diberikan Tuhan untuk jadi khalifah di atas bumi, dan memperteguh sebuah surat kepercayaan. Tapi kemudian negeri-negeri Islam terdesak. Di abad ini sebagian besar Muslimin bahkan hidup dalam suatu wilayah luas yang disebut "Dunia Ketiga". Mereka berada paling akhir menurut ukuran prestasi yang kini tengah berlaku. Dan bila orang masih ingat akan Ibnu Khaldun atau Ibnu Sina, itu justru dengan merasa ada luka di hatinya. Yang kemudian terjadi adalah suatu proses, dengan akibat kadang kala muram kadang kala cemerlang. Yang muram ialah rasa putus asa. Habisnya harapan inilah yang mungkin menyebabkan seseorang meninggalkan agama. Atau ia justru tidak meninggalkan apa yang diyakini malah seseorang barangkali memutuskan untuk melakukan takfir - yakni mengafirkan seluruh dunia kontemporer di iuar dirh1ya. Dunia di luar itu memang dunia yang tak selamanya dapat dipahami dan dlterlma. Ia penuh dengan hal-hal yang asal usulnya "bukan Islam", melainkan, terutama, "Barat". Ada mesin-mesin, ada bisnis besar, ada penghargaan pokok pada hak-hak individu dan demokrasi, ada pula film porno atau filsafat Karl Marx. Hal-hal itu sangat kuat hadir, dan dengan satu dan lain cara seakan-akan mencemooh kita yang tak ikut menyertainya. Wajar bila kita cenderung menolaknya. Tapi menolak tak berarti mengalahkan dan itulah soalnya. Mungkin dari sinilah lahirnya "takfirisme", suatu isrilah yang saya rasa lebih sesuai dengan riwayat Islam sendiri dibanding dengan misalnya istilah "fundamentalisme". Dalam posisi belum bisa mengalahkan dunia yang serba salah itu, sejumlah Muslimin pun mematahkan kontak dengan tiap bersit pengaruh dari luar alam acuannya. Usaha memurnikan peri laku pun mulai. Kian terasa "kafir" dunia di scberang itu, kian hebat pula kehendak "memurnikan" itu. Bahwa "takfirisme" mengandung sikap menolak dan melawan, kiranya, tak dapat dihindarkan. Penolakan itu bisa sangat jauh: sampai-sampai karena demokrasi yang konstitusional dan pluralis datang dari "Barat", misalnya, maka ia pun dianggap bertentangan dengan Islam. Di sml memang bekerja kuat sikap waspada, bahkan curiga. Eksperimen ilmiah, eksperimen kesenian, warna-warni kebudayaan, yang umumnya bersifat lokal dan pribumi, pada gilirannya pun cenderung dijauhi. Kaum "takfiris" memang lebih sukar menerima kompromi. Kemurnian justru menghendaki hidup tanpa kompromi. Tapi, seperti tampak dalam sejarah, ajaran atau buah pikiran, sikap mental atau nilai-nilai - semua itu ternyata bukan faktor yang dengan sendirinya membentuk dunia obyektif di luar kita. Demikianlah, bila umat Islam terdesak, sebenarnya kita tak dapat menyalahkan cara berpikirnya yang salah ataupun ajarana larangannya yang sesat. Islam. apapun manifestasinya, tak dapat disebur sebagai biang keterbelakangan ekonomi, sebagaimana kebudayaan Hindu juga tak dapat sepenuhnya menerangkan kemiskinan. Betapapun termasyhurnya Max Weber dan Sombart, ada banyak bolong dalam teori bahwa agama Protcstan di Eropa Utara itu yang menyebabkan kapitalisme maju. Karena itu, dengan hanya mengandalkan diri pada kemurnian ajaran, kaum "takfiris" akan kecewa lagi bila melihat dunia modern tetap saja kian menyisihkan umat. Sebab, sejarah rak selamanya ditentukan oleh murni atau kotornya doktrin begitu banyak faktor kebetulan yang mengakibatkan kita berada di dalam status "Dunia Ketiga" dewasa ini, dengan sebuah peradaban yang luka. Syukur, sebuah peradaban yang luka kadang menerbitkan hal-hal yang cemerlang. Seperti umat Islam di mana-mana, di Indonesia pun mereka merasa terdesak. Tapi berbareng dengan kian banyaknya kalangan terpelajar yang lahir dari para santri itu, dalam kancah orang-orang Muslim Indonesia pula suatu pelangi dan kembang api pemikiran tampak - lebih hidup ketimbang yang terdapat dl kancah lain. Tak semuanya saling setuju. Tapi tak semuanya menunjukkan putus harapan bahwa keadaan tak lagi tak tertolong dan warna di luar hanya hitam. Barangkali karena itulah pelangi dan kembang api itu disebut rahmat. Sebab, peradaban yang luka ini justru suatu peradaban yang belum mati - bahkan sedang menyembuhkan diri. Ia tak mudah dihabisi. Goenawan Mobamad.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini