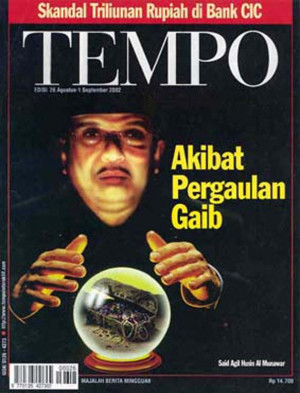INDONESIA adalah bangsa yang senang retorika dan metafora. Ketika ada tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dihukum pancung di Arab Saudi, pembantu wanita yang disiksa di Singapura, dan belakangan ini TKI ilegal yang didera hukum cambuk di Malaysia, seluruh bangsa ini marah dan merasa terhina. Kita melontarkan sumpah-serapah ke alamat musuh-musuh TKI di mancanegara, lalu memberikan penghormatan kepada TKI yang menyabung nyawa itu dengan gelar pahlawan devisa dan penyelamat keluarga.
Kita agaknya tidak menyadari bahwa melalui metafora, masalah TKI dianggap selesai dengan sendirinya. Dengan gelar pahlawan devisa, lalu tidak diusahakan mencari solusi jangka panjang bagi mereka. Tidak pula ditelisik bagaimana segala bentuk kezaliman bisa menimpa pahlawan devisa yang kita banggakan itu. Pokoknya, masalah TKI tak digali sampai ke akar-akarnya, sehingga solusi konkret pun tidak pernah ada.
Hal yang sama terulang ketika terjadi pengusiran TKI ilegal dari Malaysia sejak akhir Juli lalu. Departemen Tenaga Kerja bukan tidak mengetahui Akta No. 115/2002 yang mengancam TKI dengan hukum cambuk. Namun tidak ada antisipasi dengan misalnya khusus melobi Malaysia, semata-mata agar pemulangan TKI dapat terselenggara sebaik-baiknya. Memang ada perundingan antara Presiden Megawati dan Perdana Menteri Mahathir Mohamad, tapi tidak secara komprehensif membahas masalah TKI. Sebelum itu, Departemen Tenaga Kerja menyusun konsepnya sendiri dan Departemen Luar Negeri membentuk timnya sendiri pula. Tidak ada koordinasi dan tentu tidak ada program penyelamatan yang terencana rapi.
Setelah ribuan TKI berduyun-duyun pulang ke Indonesia—dan sudah ada yang dihukum cambuk—tidak juga dikirim bala bantuan bagi mereka; tidak ke Malaysia, tidak juga ke pintu-pintu masuk arus TKI di negeri ini. Tak kalah dengan babak I yang bertemakan lakon pengusiran dengan setting Malaysia, babak II dengan setting Indonesia pun berlumur duka dan air mata. Hingga pekan ini, menurut LSM Kopbumi, sudah 50 orang yang meninggal—termasuk beberapa bayi. Sangat memilukan dan sangat berbeda dengan apa yang dilakukan Filipina. Kita tersentuh mendengar bahwa Presiden Gloria Arroyo sendirilah yang berangkat menyambut buruh Filipina di perbatasan. Dan ia juga mengutus mantan presiden Fidel Ramos untuk berunding langsung dengan Mahathir Mohamad.
Sampai tahap ini kita bukannya mengoreksi diri, tapi dalam perkembangan yang bisa disebut sebagai babak III, Amien Rais mengecam hukuman cambuk, aparat di Sumatera Utara mengintimidasi warga Malaysia—kedua hal ini memancing reaksi keras dari negara jiran itu—lalu di Jakarta ada aksi unjuk rasa dan pekik "ganyang Malaysia!" Mungkin kita ini bukan bangsa tempe yang hanya mengandalkan metafora dan retorika. Tapi babak I, II, dan III dari "drama pengusiran TKI" telah dengan telak memperlihatkan betapa "tempe"-nya kita. Lihatlah, orang kaya Indonesia banyak sekali, tapi belum ada yang menyumbang dana penyelamatan TKI hingga mencapai Rp 50 miliar, misalnya. Ahli hukum Indonesia jempolan semua, tapi belum ada yang sukarela mendampingi TKI di pengadilan Malaysia. Cerdik cendekia juga banyak, tapi tak satu pun yang dipercaya memperkuat tim gabungan Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Luar Negeri, misalnya.
Masalah pengusiran TKI seharusnya dilihat sebagai masalah bersama sebagai bangsa dan diatasi bersama pula. Pemerintah semestinya melibatkan orang nonpemerintah yang punya integritas, mampu, dan diterima secara luas agar boleh berpartisipasi menyukseskan penanganan urusan TKI ini. Pemerintah juga harus memainkan bola panas TKI dengan rasional, seraya mengajak masyarakat mendinginkan hati yang membara dan bukan sebaliknya. Yang juga penting adalah melihat kelemahan kita dengan jujur, arif, dan berani, tanpa embel-embel retorika dan metafora, yang dalam hal ini bukan saja tidak relevan, tapi juga bisa menyesatkan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini