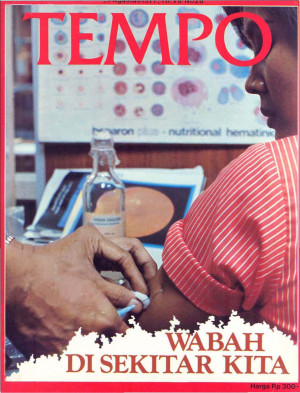BANGSA kita ini memang tergolong suka berfalsafah. Tidak ada
tindakan atau perbuatan yang tidak ada referensi
petatah-petitihnya. Perhatikan kekayaan isi pantun-pantun
Minang. Bukalah primbon Jawa atau Bali. Semuanya merupakan
perbendaharaan butiran kata penuh makna.
Kalau isinya sudah tidak mengena lagi di zaman sekarang, dicoba
diotak-atik supaya matuk (cocok). Kalau tidak,
sekurang-kurangnya toh tetap enak didengar. Karena itu tidak
perlu heran bila dari minum arak sampai mengatur Negara, kita
berfalsafah.
Pancagatra
Nah, kalau Negara kita dibangun atas dasar Pancasila. kota-kota
kita mesti dibangun atas dasar panca apalagi, sebagai turunan
Pancasila? Pikir punya pikir, baca punya baca dan dengar punya
dengar, ketemu pula pancagatra kota itu. Dengan dipelopori oleh
para sesepuh perencana kota Indonesia dicanangkanlah lima fungsi
kota: Wisma, Karya, Marga, Suka dan Penyempurna.
Tampaknya kerangka pikir ini masih mencekam banyak kalangan
perencana kota Indonesia masa kini. Padahal istilah-istilah yang
berbau kejawen itu sesungguhnya toh bukan asli digali dari
Primbon Betaljemur, misalnya. Melainkan berasal usul dari Piagam
Athena (1933).
Konon yang mula-mula punya akal membagi-bagi fungsi kota
sementara itu adalah orang Perancis. Le Corbusier namanya.
Karena itu sebutan aslinya pun memakai bahasa dan gaya Voltaire.
Habiter, Travailer, Cultiver le corps et l'esprit,
Transportation, artinya sama saja dengan Pancagatra tadi.
Benarkah penggolongan fungsi kota menurut Piagam Athena itu
mencerminkan gambaran gambaran yang tepat bagi kota-kota di
Indonesia?
Pada tahun 1938. Belanda bilang tidak seluruhny cocok. Buat
orang Indonesia seringkali rumahnya juga tempat kerja.
Rekreasinya bisa di pasar sekalipun. Karena itu waktu disusun
Stadvorming Ordonantie Stadsgemeenten Java (SVO), biarpun
tetap dipakai angka lima, tapi isi pembagiannya ternyata
berbeda. Menurut SVO bagi kota-kota di Jawa, pembagian ke dalam
lingkar-linkar utama itu lebih cocok terdiri dari lingkar utama
bangunan ruang terbuka. Ialu-lintas, air dan salurah induk,
daerah agraris dan alam. Katatanya pula, kerangka ini lebih
mengambarkan kepribadian dan keadaan nyata kota-kota di Jawa
saat itu.
Po Limo
Bung Karno, yang "jelek-jelek juga Insinyur" punya pandangan
tersendiri soal membangun kota ini. Sebab dia fikir kota toh
bukan hanya kumpulan gumpalan semen, betom aspal, mesin atau
mobil. Tetapi kota terutama dibangun untuk manusia. Karena itu
kenapa pancagatra itu tidak ada unsur "spirituil"nya?
Pada tahun 1959 Bung Karno keluar dengan polimonya (lima P):
Perut, Pakaian, Perumahan. Pergaulan dan Pengetahuan.
Dalam pergaulan dan pengetahuan ini termasuklah pula
pembudayaan, katanya. Waktu ia menerangkan soal perumahan,
ditambahnya pula dengan "inl een omgeving van schoonheid".
Dus, taman-taman yang indah, arsitektur kota yang cantik dan
perkampungan yang menyengsamkan jiwa. Bukan main. Jalan
fikirannya tentang permukiman pun, tetap romantis.
Karena yang bilang Bung Karno, dicari dalam texts-book mana pun
barangkali nyontek - juga tak ketemu, kita boleh percaya
membangun kota dengan po limo itu memang mencerminkan tujuan
perjuangan nasional saat itu.
Lalu bagaimana halnya dengan yang cocok dengan tujuan
pembangunan nasional saat ini? Karena menyangkut falsafah,
biasanya kita suka pertama-tama menggali pada kepribadian
sendiri.
Dasagatra
Menurut nenek moyang kita dahulu -- kalau percaya ki dalang -
suatu kota, tempat kedudukan pemerintahan suatu Negara, haruslah
panjang, punjung, pasir wukir, loh jinawi, gemah, ripah,
tata dan raharja.
Karena ada sepuluh kata bermakna, saya menyebutnya dasagatra
atau dasa apa sajalah. Kenapa mesti dasa, bila yang lain-lain
cukup lima?
Maka saya terpaksa meringkas kedalam lima unsur pembangunan
kota. Unsur idiil: panjang, punjung, unsur fisik: pasir wukir,
unsur ekonomi: loh, jinawi, unsur sosial: gemah, ripah, dan
unsur pemerintahan: tata, raharja.
Secara ideal, kota itu kata ki dalang, mesti mempunyai sejarah
dan reputasi yang "panjang ceritanya dan luhur wibawanya".
Apakah itu pusat pemerintahan Anarta yang bekas kerajaan jim
tetapi berhasil dijinakkan. Atau Jakarta yang sejak Faletehan,
Sultan Agung sampai Proklamasi punya sejarah perjoangah yang
gemilang dan berhasil mengangkat kewibawaan bangsa.
Secara fisik, kota mesti mempunyai hiterland alam pegunungan
yang indah (ngungkuraken hing pareden) dilengkapi dengan
sarana dan sistim lalu-lintas, air dan saluran induk yang baik
(nganaken hing benawi) memelihara kawasan produksi pangan yang
dekat dan terpadu dengan sistim kota itu (ngeringaken hing
pasabinan) dan punya fasilitas pelabuhan yang besar (ngajengaken
bandaran gede). Gambaran potensi ekonomi kota dilukiskan sebagai
kawasan yang punya produktivitas tinggi dan alam yang murah
(loh, jinawi). Lalu corak sosialnya ditandai pula dengan
pemukiman yang terpaksa padat (jejel apipit aben taritis) namun
pergaulan sosial tetap akrab. Banyak pendatang dari berbagai
penjuru daerah yang bermukim, berdagang atau bekerja di Kota.
Pemerintahnya stabil, wibawa kekuasaan memancar, rakyat hidup
dengan tenteram penuh rasa aman, tertib dan sejahtera.
Namun kalau kita jujur, tidak semua kepribadian kota
peninggalan nenek moyang itu menyejukkan malah ada yang sungguh
memuakkan.
Misalnya waktu bercerita tentang pemerintahan yang stabil dan
wibawa kekuasaan yang memancar itu penjelasan sebagai buktinya
adalah berkembangnya kebudayaan asok glondong
pengareng-ngareng, alias kebudayaan upeti. Diceritakan dengan
hangga oleh ki dalang, bahwa para penguasa daerah (taklukan)
selalu mempersembahkan emas, uang kekayaan dan barang mewah
(emas picis raja brana) sebagai tanda setia dan bakti kepada
sang maha penguasa ....
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini