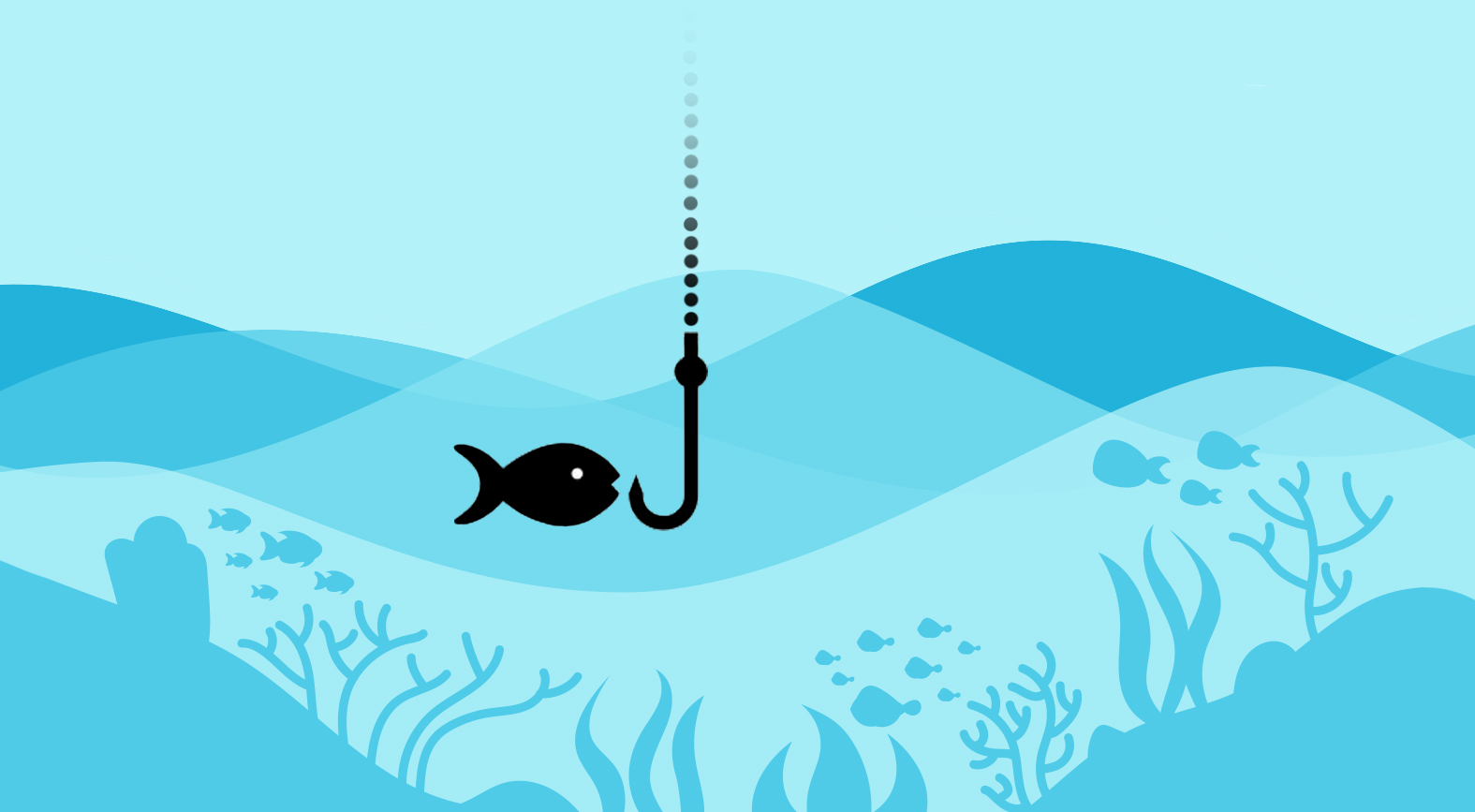Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Pemerintah tampak ingin melembagakan paradigma ekonomi biru.
Gejalanya terlihat pada kebijakan privatisasi perikanan serta perampasan laut dan sumber dayanya.
Paradigma ini dikritik karena berbagai dampak negatifnya.
Muhamad Karim
Dosen Universitas Trilogi dan Peneliti Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pemerintah Indonesia sedang getol menggunakan pendekatan ekonomi biru. Bank Dunia menyebut ekonomi biru sebagai penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi serta peningkatan mata pencarian dan pekerjaan sambil menjaga kesehatan ekosistem laut. Adapun Komisi Eropa mendefinisikannya secara sederhana sebagai semua kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan samudra, laut, dan pantai.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pemerintah mengadopsi pendekatan ini dan hendak melembagakannya sebagai paradigma pembangunan sektor kelautan dan perikanan, padahal sejatinya ekonomi biru itu hanyalah metamorfosis dari kapitalisme. Gejalanya tampak dalam berbagai kebijakan privatisasi sumber daya perikanan serta perampasan laut dan sumber dayanya (ocean grabbing). Contohnya adalah kebijakan pemerintah mengenai penangkapan ikan terukur berbasis kuota di 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yang menggunakan instrumen izin khusus. Ada pula lumbung udang (shrimp estate) seluas 11 ribu hektare yang terdiri atas 5.000 hektare yang dibangun pemerintah dan 6.000 hektare oleh swasta (KKP, 2021). Contoh lain adalah kenaikan fantastis harga tiket masuk Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dari semula Rp 150 ribu menjadi Rp 3,75 juta. Kasus ini dapat dikategorikan sebagai perampasan laut dan sumber dayanya (Bennet dkk, 2015).
Paradigma ekonomi biru telah menghegemoni dunia saat ini (Schutter dkk, 2021). Nyaris semua negara di dunia mengadopsinya sebagai paradigma pembangunan. Ia dianggap sebagai obat mujarab untuk mengatasi paradoks pertumbuhan (growth) dan keberlanjutan (sustainability). Indonesia juga bakal mengusungnya dalam pertemuan G-20 di Bali nanti.
Dinamika Ekonomi Biru
Paradigma ekonomi biru kini justru memicu kontroversi akibat dampak negatif yang telah ditimbulkannya. Setidaknya ada tiga kelompok besar yang menyikapi paradigma ini. Pertama, kelompok pro status quo. Ini berisi para intelektual, pemimpin negara, dan masyarakat sipil yang meyakini bahwa ekonomi biru bakal menyelamatkan bumi dari masalah ekonomi, sosial, dan ekologi hingga perubahan iklim, termasuk kelautan.
Salah satu negara yang mengadopsinya bulat-bulat adalah Seychelles, negara kepulauan di Samudra Hindia. Negara ini memposisikan laut sebagai ruang pembangunan demi mengejar pertumbuhan ekonomi lewat eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautannya secara masif, terutama ikan tuna. Mereka pun mendepolitisasi perdebatan publik soal ekonomi biru sehingga hal ini hanya menjadi urusan elite politik dan kekuasaan. Praktiknya pun diintervensi penuh oleh Bank Dunia lewat marine debt-for-nature swaps, yakni pengurangan utang luar negeri dengan menukarnya dengan komitmen negara pengutang untuk kegiatan konservasi laut.
Pada kenyataannya, pengelolaan perikanan tuna Seychelles justru lebih berorientasi industri hingga dikuasai armada Uni Eropa ketimbang melindungi perikanan skala kecil dan masyarakat adat. Hal ini menimbulkan paradoks antara orientasi pertumbuhan ekonomi versus keberlanjutan sumber daya ikan di Seychelles (Schutter dkk, 2021). Bahkan, Asian Development Bank Institute menerbitkan laporan Blue Economy and Blue Finance Toward Sustainable Development and Ocean Governance untuk mengukuhkan hegemoninya (Morgan dkk, 2022).
Kedua, kelompok kritis-korektif. Kelompok ini mengkritik dan mengoreksi ekonomi biru. Pasalnya, praktiknya kurang mempertimbangkan aspek keadilan, kesetaraan, serta keberpihakan kepada kelompok miskin, rentan, dan terpinggirkan, seperti nelayan skala kecil dan masyarakat adat hingga perempuan nelayan. Kelompok ini menerima konsep ekonomi biru, tapi mesti direkonseptualkan dan direvisi supaya menghilangkan ketidakadilan, kesenjangan, kemiskinan baru, hingga krisis ekologi dan iklim di kelautan (Schutter dkk., 2021). Lalu, Martínez-Vázquez dkk. (2021) mendukung pertumbuhan biru dan ekonomi sirkular sebagai alternatif mendamaikan ketegangan antara pendukung pertumbuhan dan degrowth, yakni perlambatan kegiatan ekonomi untuk mencegah kerugian lebih besar bagi manusia dan alam.
Ketiga, kelompok yang menolak ekonomi biru dengan mengusung beragam paradigma baru, yaitu degrowth biru, yang menganggap ekonomi biru berorientasi pada pertumbuhan biru sebagai ilusi (Ertör & Hadjimichael (2020); komunitas biru yang mengedepankan “kesejahteraan” dan pemerataan ketimbang pertumbuhan (Campbell dkk, 2021); serta keadilan biru sebagai antitesis ekonomi biru, yaitu suatu “governability” melalui mekanisme pengembangan kelembagaan yang bersifat transdisipliner (terintegrasi), partisipatif, dan holistik (Jentoft, 2022).
Saya berpandangan bahwa pengambil kebijakan di negeri ini gampang sekali terhipnotis terminologi baru. Setidaknya ada dua hal yang melatarinya. Pertama, pemerintah tak menyadari bahwa di balik paradigma ekonomi biru itu bercokol lembaga keuangan internasional ala Bank Dunia, IMF, dan organisasi nonpemerintah internasional. Mereka mempengaruhi serta mengintervensi kebijakan dan regulasi kelautan suatu negara. Tujuannya untuk mentransformasikan ideologi neoliberalnya melalui program “penyesuaian struktural” yang dibiayai utang di berbagai negara.
Kedua, pemerintah memang hendak menerapkan kebijakan neoliberal untuk mengakomodasi kepentingan korporasi kelautan atau perikanan transnasional supaya mereka mengeruk kekayaan laut Indonesia. Indikasinya adalah privatisasi wilayah-wilayah pengelolaan perikanan yang berorientasi pada industri promosi ekspor, pengurangan hingga penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) perikanan, mengundang kembali kapal ikan asing beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan, dan proyek-proyek strategis nasional yang mengubah kawasan konservasi laut seperti lumbung udang.
Apakah ada pendekatan alternatif?
Pendekatan Indonesia
Di tengah hegemoni ekonomi biru, semestinya pemerintah melongok kembali pendekatan historis-struktural dalam ekonomi politik pembangunan Indonesia. Furnival telah mengingatkan bahwa sejarah pendekatan pembangunan ekonomi sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia bersifat plural. Ia tak menganut satu mazhab pemikiran, melainkan beragam. Namun, seiring dengan perkembangan sejarah, ekonomi politik global melahirkan ragam pendekatan pembangunan alternatif yang menyempal dari kapitalisme maupun strukturalisme/sosialisme. Kaum intelektual penyokongnya menyebutnya sebagai pendekatan heterodoks atau eklektik.
Saya memandang Indonesia semestinya punya pendekatan sendiri. Setidaknya ada dua jenis. Pertama, pendekatan rekonstruktif, yaitu lewat “perkawinan silang” antara model-model pendekatan kultural/lokalitas berbasis adat, budaya, dan agama dengan yang modern berbasis inovasi, dan efisiensi. Hal ini kerap dikenal sebagai hibrida heterodoks/eklektik. Contohnya adalah model-model tata kelola berbasis adat maupun pengetahuan lokal pada sumber daya kelautan dan perikanan, seperti kearifan lokal nelayan Bagan etnis Bugis dan sasi di Maluku. Semestinya filsafat dan praksisnya dikawinkan dengan prinsip efisiensi dan inovasi berbasis teknologi mutakhir untuk melahirkan tata kelola kelautan hibrida ala Indonesia.
Kedua, pendekatan dekonstruktif, yaitu tidak bias pendekatan modern (Barat) yang tidak kongruen dan adaptif terhadap nilai-nilai lokal/adat, budaya, maupun agama. Sebaliknya juga, ia tidak bias lokalitas, sehingga menegasikan pendekatan Barat. Masalahnya, keduanya acapkali bertentangan dalam ide, konsep, dan praktiknya sebagai model pembangunan negara dunia ketiga dan negara terbelakang. Artinya, pendekatan ini melahirkan model tata kelola kelautan baru Indonesia yang “berbeda” secara geneologis dengan pendekatan Barat maupun lokalitas.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tak bisa diabaikan. Keduanya berkelindan dalam perkembangan peradaban umat manusia. Kuncinya adalah bagaimana merumuskan konsepnya sebagai pijakan dalam penyusunan kebijakan hingga program aksinya. Hal itu memang tak semudah membalikkan telapak tangan, tapi sangat mungkin dijalankan asalkan kita mau berpikir serta tak dikooptasi dan dihegemoni model-model pembangunan ekonomi kelautan berhaluan neoliberal ala ekonomi biru.
PENGUMUMAN
Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan nomor kontak dan CV ringkas.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo