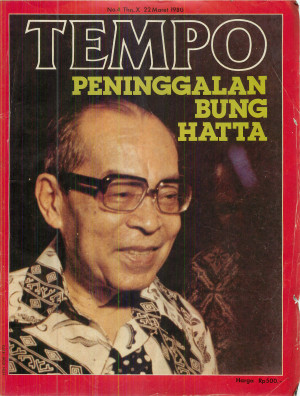BUNG Hatta wafat.
Waktu memang berjalan, membentuk zaman. Anak-anak lahir. Dan di
piramida penduduk, Indonesia dipenuhi bayi dan pemuda. Ketika
kita bertanya apa sebenarnya yang terjadi di masa lalu,
tiba-tiba kita tahu kenangan kian pendek di antara kita. Kian
sedikit orang tua yang masih menyimpan apa yang telah silam dan
bisa bercerita tentang semua itu.
Barangkali itulah sebabnya kita cenderung melihat sejarah kita
sebagai bangunan yang terdiri dari lingkaran-lingkaran tertutup.
Masing-masing lingkaran adalah sebuah masa. Masing-masing masa
seakan berdiri eksklusif, tak bersintuhan dengan, bahkan nyaris
asing bagi, yang lain. Yang kini tak bertaut dengan yang dulu.
Yang dulu berada di tingkat lain dari yang kini.
Barangkali itulah sebabnya kita cenderung membayangkan sejarah
sebagai sesuatu yang terdiri dari grup-grup "angkatan" -- seakan
kita tengah menyaksikan barisan-barisan yang berlainan bendera
dalam satu parade 17 Agustus. Hubungan mereka hanya dirumuskan
sebagai "pewarisan" (bila positif), atau "gap", "jurang pemisah"
(bila negatif).
Maka bukan hal yang aneh bila di sebuah ruang seminar yang sama,
ada "wakil Angkatan '45 ' yang mengritik atau memuji-muji
"Angkatan '66", atau sebaliknya. Seakan-akan mereka bukan lagi
sezaman. Seolah-olah mereka bertemu dengan susah payah sebuah
mesin waktu.
Dr. Abu Hanifah beberapa hari sebelum meninggal sering bicara
menyebut dirinya -- dan generasinya -- "mastodon". Anak-anak
muda setengah tertawa membayangkan seekor gajah purba yang besar
yang anehnya belum punah dan bisa jalan-jalan di lingkungan
yang tak lagi sepadan. Tak ada yang bertanya: benarkah "makhluk"
itu begitu kuno -- meskipun diketahui ia akan hilang? Benarkah
ia bukan lagi bagian dari kita, dan kita dari mereka?
*****
SEORANG pengarang di tahun 1978 pernah menulis, bahwa kini
sejarah telah direduksikan tak kepalang tanggung orang tiba-tiba
jadi "produk" dari sebuah dasawarsa masa hidup mereka bahkan
setengah dasawarsa. Dalam kata-kata Susan Sontag, itulah
"inhuman acceleration of historical change."
Tapi mungkin itu cuma ilusi. Setidaknya bagi kita. Sebab
sementara di kota-kota para intelektuil membagi-bagi diri dalam
"angkatan", di pedusunan anak-anak tak cukup waktu untuk jadi
"remaja" -- untuk bebas dari kewajiban ekonomi, sempat
memperoleh ilmu sendiri dan akhirnya membentuk gaya dan
pandangan sendiri.
Dengan kata lain, bagi mereka masa lalu justru terletak di
depan, masa depan justru yang tak kelihatan.
Tapi mungkin dari sinilah kita dapat merenungkan
kenyataan-kenyataan kita sebenarnya. Ketika Bung Hatta memimpin
PNI Baru di tahun 1930-an, ia menghadapi keresahan di desa-desa.
Contohnya di Indramayu, Jawa Barat. Rakyat, terdorong oleh
depresi ekonomi dan keogahan mentaati hukum pemerintah yang
asing bagi mereka, secara ilegal mengambil pohon jati dari
hutan. Maret 1932, misalnya, sekitar 700 orang desa bersenjata
menebang kayu di hadapan para petugas yang tak berdaya.
Pada masa itu, PNI Baru bergerak di antara penduduk. Dan rakyat
menyambut. Keanggotaan PNI Baru pun membesar di wilayah ini.
Tapi Residen Van der Plas awas: ia mencegah menyusupnya pengaruh
partai itu ke desa, dengan memperkuat lurah serta kaum menak.
Dan dia berhasil.
Setengah abad kemudian tentu saja tak ada lagi PNI Baru dan tak
ada Van der Plas. Bung Hatta juga telah wafat. Tapi benarkah
telah berubah desa-desa tempat para penebang liar itu?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini