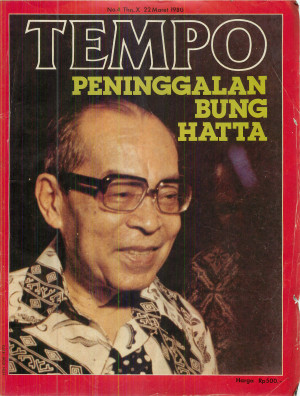TAK ada suasana sedih di rumah kediaman Hatta. Juga tak ada
keluarga yang berpura-pura sedih. Jum'at jam 18.58 pekan lalu
proklamator itu wafat di RSUP dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta,
(sekitar 1 kilometer saja dari rumahnya) dan nampaknya istri dan
ketiga putrinya sudah siap.
Tapi toh Republik Indonesia tiba-tiba seperti kehilangan seorang
ayah. Ketika iring-iringan jenasah sepanjang 4 km itu Sabtu
siang melewati Jalan Jenderal Sudirman, ratusan orang berbondong
menghormat dan sejumlah orang kampung mengibarkan spanduk putih
bercat hitam, "Selamat Jalan, Bapakku!" Dan ketika tubuh yang
berumur 77 tahun itu diturunkan ke liang lahat, di pemakaman
rakyat di Tanah Kusir, hujan turun rintik -- sampai upacara
selesai.
Buya Hamka, yang memimpin sembahyang di rumah almarhum dan
kemudian membacakan doa di makam, menangis di tengah
kata-katanya. Paginya penghormatan lain diberikan: seorang
lelaki agak tua datang ke Jalan Diponegoro, memasuki ruang
tempat jenasah. Ia minta izin untuk melagukan nyanyian rohani.
Ia seorang Kristen. Sementara itu di hari itu juga, dan begitu
pun Minggu esoknya, di sekolah dan gereja Katolik diujubkan
misa untuk arwah Bung Hatta.
Dukacita itu bisa hanya resmi ataupun tulus. Tapi nampaknya
banyak yang berdoa seperti Presiden Soeharto berdoa: "Tuhan Yang
Maha Kuasa, terimalah seorang putra besar bangsa kami."
Putra besar seluruh bangsa, tapi juga wakil utama sebual
generasi gemilang yang hampir punah.
Bung Hatta lahir di Aur Tajungkang Mandianin, Bukittinggi. 12
Agustus 1902, di sebuah rumah kayu bertingkat dua. Rumah itu
menghadap ke jalan raya Bukittinggi Payakumbuh, namun yang
istimewa adalah tebat ikan di tanah seluas 800 mÿFD itu.
Dalam memoarnya yang tak selesai, yang terbit tahun lalu,
ia sendiri melukiskan peran kolam ikan kaliuh itu bagi masa
depannya: "Ikan di tebat itu menimbulkan hubungan yang baik
antara kakekku, Ilyas gelar Baginda Marah, dengan orang
Belanda yang berkuasa di Bukittinggi. Sewaktu-waktu mereka
dikirimi ikan dari situ dan sebaliknya pada Hari Raya Idulfitri
mereka mengirimkan cerutu Belanda yang kesohor kepada beliau.
Perhubungan yang baik itu membukakan jalan bagiku untuk masuk
sekolah Belanda."
Hatta memang kemudian masuk sekolah Belanda -- dari rencana
kakak ayahnya, yang ia sebut "ayah gaekku", untuk membawa
kemanakannya yang yatim ini bersekolah agama di Mekah gagal.
Hatta nampaknya lebih mengagumi anak-anak Kota Gedang
yang banyak berpendidikan Belanda.
Hanya ia tak telanjur menjadi semacam tokoh Hanafi dalam novel
Sala Asuhan. Ketika Turki kalah perang di tahun 1912, negeri
Islam itu diolok-olok oleh anak-anak Belanda. Hatta ikut sakit
hati. Tapi kemudian ia tahu bahwa ia tak bisa bersimpati kepada
Sultan Turki. Dari "ayah gaek"-nya ia mendengar bagaimana
Sultan-Sultan Turki "melakukan kezaliman dan menjauhkan
perbuatan menurut keadilan Ilahi."
Pandangan semacam itu, yang di luar kelaziman waktu itu, agaknya
berbenih dalam kesadaran Hatta: dalam keteguhan beragamanya ia
tetap kritis -- seperti dalam sikap anti-kolonialnya ia tetap
tak anti-Barat.
Di MULO, sekolah menengah pertama, guru agamanya adalah Haji
Abdullah Ahmad, yang seperti hal-nya ayah Hamka, membawa
semangat "modernisme" Muhammad Abduh dari Mesir "Mereka setuju
sekali," tulis Hatta tentang kaum modernis yang dikaguminya itu,
"apabila orang Islam memiliki selekas-lekasnya ilmu dan
pengetahuan yang disebarkan orang Barat . . . "
Tapi jelas, Barat diketahui Hatta bukan cuma lewat buku dan
ajaran. Ia melanjutkan sekolah ke Rotterdam, Negeri Belanda,
sejak 1922 dan baru 11 tahun kemudian pulang.
Eropa merupakan tempat radikalisasi pandangan-pandangannya
tentang politik -- dan juga tempat ujian pertamanya dengan hukum
dan kekuasaan. Bahwa pengalamannya di sini sangat membekas,
dapat dimengerti. Hatta berada di sana dari umur yang paling
kreatif -- 20 tahun sampai dengan 31 tahun. Memoarnya bercerita
tentang masa ini sepanjang 140 halaman, penuh dengan perincian
yang nampaknya tak terlupakan.
Tak dapat diabaikan ialah bahwa puncak pertama perjuangan Hatta
untuk kemerdekaan bangsanya tercapai di sini, ketika ia memimpin
Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini hanya mencakup sebagian
kecil (sekitar 25%) saja dari mahasiswa Indonesia yang berada di
Negeri Belanda. Tapi para pemuda yang berada di tanah asing itu
bukan saja menemukan PI sebagai wadah untuk menyalurkan
kebutuhan merumuskan identitas diri, tapi juga sebagai
kegairahan untuk suatu kesempatan tampil.
Negeri Belanda, berbeda dari Hindia Belanda, bebas dari kekangan
masyarakat kolonial yang paternalistis dan membedakan warna
kulit. Ketika Hatta, beserta Ali Sastroamidjojo, Nazir
Pamuntjak, dan Abdulmadjid Djojoadiningrat ditangkap dan diadili
di Den Haag oleh pemerintah Belanda karena dituduh subversif,
suatu proses pengadilan yang fair diberikan kepada mereka. 22
Maret 1928 mereka dibebaskan dari segala tuduhan.
Hal-hal seperti itulah agaknya yang menyebabkan Hatta, walaupun
dengan asas "non-kooperasi"nya, pada dasarnya bukan seorang yang
"revolusioner" dalam pengertian sekarang. Ia tak secara
eksplisit menolak mutlak lembaga-lembaga masyarakat dalam
demokrasi Barat. "Non-kooperasi"nya mengandung pengertian, bahwa
kemerdekaan Indonesia tak akan dihadiahkan oleh Belanda, dan
karenanya harus direbut. Tapi tak ada petunjuk jelas adakah
jalan kekerasanlah yang akan ditempuh.
Nampaknya tidak. Kata "revolusioner" memang dipergunakan oleh
Hatta, tapi jalan kekerasan -- baik dengan mogok maupun dengan
perlawanan bersenjata --adalah perkara lain.
Hal yang sama terdapat dalam sikap Bung Karno. Dalam interogasi
di bulan Agustus 1933 ketika ia ditahan, Bung Karno memang
berbicara tentang perlunya "kekuatan" serta "tekanan", tapi itu
adalah "desakan moral" -- dan dijalankan dalam kerangka hukum.
Bung Karno kemudian menjalankan pembinaan "kekuatan" itu melalui
aksi massa, rapat umum dan pidato yang menggelcgar. Bung Hatta
-- yang mengecam cara-cara ini -- menjalankan sikap
"revolusioner"-nya dengan membentuk Pendidikan Nasional
Indonesia, menyusun serta mendidik kader. Dengan kata lain,
kedua pemimpin itu tak cukup perhatian untuk mendapatkan
alternatif misalnya dengan diam-diam menyiapkan angkatan
bersenjata.
Namun mengharapkan hal yang semacam itu tentulah mustahil di
Hindia Belanda yang dikontrol dengan ketat oleh Gubernur
Jenderal De Jonge. Tanpa gerak yang teramat membahayakan sekali
pun Hatta, Syahrir, Sukarno dan beberapa pemimpin pergerakan
lain ditahan di bulan Februari 1934 -- untuk dibuang. Baru
setelah Jepang datang, mereka bebas.
Tak dapat dikatakan, bahwa Hatta unya ilusi tentang imperialisme
Jepang. Tepat setahun setelah meletusnya "Perang Asia Timur
Raya", sebuah rapat umum diadakan di lapangan Ikada, Jakarta, 8
Desember 1942. Hatta diminta berpidato. Ucapannya, tanpa
melewati sensur Jepang lebih dulu, mengejutkan "Bagi pemuda
Indonesia, ia lebih suka melihat Indonesia tenggelam ke dasar
lautan dari pada mempunyainya sebagai jajahan orang kembali."
Tapi toh ketika Jepang kalah oleh Sekutu dan kemerdekaan di
ambang pintu, para pemuda kecewa kepadanya. 5 Agustus 1945,
pemuda Subadio Sastrosatomo dan Subianto Djojohadikusumo, yang
datang kepadanya untuk membujuk diserukannya pernyataan
kemerdekaan, tak memperoleh hasil dari Hatta. "Bung Hatta tidak
bisa diharapkan untuk revolusi," kata mereka, setelah
bertengkar.
Barangkali demikian. Tapi tak seorangpun dapat menuduh Bung
Hatta pengecut. Hatta dan Sukarno menolak desakan macam itu,
karena mereka terikat kepada janji, bahwa pernyataan kemerdekaan
adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan, bukan hak Sukarno dan
Hatta sendiri.
Betapapun, perselisihan penilaian semacam itu berlangsung
kembali tiga tahun setelah kemerdekaan sudah dicapai, dan
republik berdiri 19 Desember 1948, Yogya diserbu pasukan
Belanda. Lapangan Maguwo jam 6 pagi dibom. Pagi itu kemudian di
kepresidenan diadakan rapat Kabinet. Masalah yang dibicarakan
ialah: adakah Presiden dan Wakil Presiden akan ke luar kota dan
menjalankan perang gerilya.
Panglima Besar Sudirman sudah memutuskan, dia sendiri akan
bergerilya. Ia datang jam 7 pagi untuk pamitan dengan Presiden.
Sakit t.b.c.-nya nampak, dan Bung Karno membujuknya supaya
tinggal saja dalam kota. Presiden, tulis Bung Hatta dalam
memoarnya, "akan membicarakan dengan Panglima Belanda yang akan
masuk kota, supaya ia dirawat di rumah sakit." Sudirman menolak.
Dari pernyataan itu nampaklah, bahwa pagi-pagi benar Bung Karno
telah memutuskan untuk tak ikut ke luar kota -- meskipun ia tahu
musuh akan berhasil menyerbu. Maka ketika Kolonel T.B.
Simatupang mengatakan sebaiknya Presiden dan Wakil Presiden ikut
perang gerilya -- untuk "memperkuat perjuangan rakyat dan
tentara" -- saran itu tak berhasil.
Bung Hatta menyebut, bahwa pertimbangan lain telah mengharuskan
Presiden dan Wakil Presiden untuk tidak ke pedalaman. Tentara
telah tak ada. Semua telah menyingkir seakan-akan meninggalkan
Kepala Negara mereka. Tanpa pengawal, pimpinan negara memilih
tinggal di Yogya. Lagipula Presiden dan wakil, selama di dalam
kota, selalu dapat berhubungan dengan Komisi Tiga Negara
(Amerika, Australia dan Belgia) dari PBB yang bertugas mengawasi
gencatan senjata.
Tapi setelah Yogya jatuh Komisi Tiga Negara toh tak dapat
mencegah Belanda untuk menawan Sukarno dan Hatta. Rencana Bung
Karno untuk mengungsi ke New Delhi, India, lebih dulu telah
kandas. Para pengritik sekarang mungkin akan mengatakan bahwa
perhitungan-perhitungan itu hanya berdasarkan keinginan yang
kosong. Apa boleh buat mungkin itu kesalahan Bung Karno dan Bung
Hatta.
Tapi mungkin pula mereka berdua punya alasan -- dan punya
pengalaman -- bahwa jalan tanpa kekerasan akan lebih membawa
hasil. Betapa pun, mereka berasal dari suatu generasi, yang pada
dasarnya yakin bahwa aturan main dan janji pasti akan ditepati
-- tak peduli adakah itu dari Jepang atau pun Belanda.
Dalam hal Bung Hatta, setidaknya, hal itu nampak jelas. Jauh di
lubuk hatinya tersimpan kepercayaan yang besar kepada potensi
baik manusia. Ia memang lebih seorang etikus daripada seorang
politikus ataupun ekonom. Dasar teorinya tentang kooperasi
menunjukkan hal itu. "Kooperasi", begitulah tulisnya, "mendidik
manusia bersifat sosial dan jujur serta pandai menjaga diri dari
bujukan ekonomi."
Hidup Bung Hatta sendiri membuktikan bahwa etika itu bisa
berjalan. Ia wafat tanpa meninggalkan kekayaan yang besar. Hanya
ada rumahnya di Jalan Diponegoro dan villa kecilnya di Mega
Mendung.
Tapi sebagaimana ditunjukkan para pemimpin Indonesia dari
generasinya, kedudukan tak boleh melahirkan kekayaan. Di
Batuhampar tinggal dua kakak Bung Hatta dari ibu yang lain. Usia
mereka telah di atas 90 dan 80 tahun. Pekan lalu mereka
mendengar meninggalnya Hatta dari anak cucu. Tapi mereka tak
dapat mengikuti acara pemakaman lewat TVRI. Mereka tak punya
pesawat televisi.
Tak aneh bila Bung Hatta berwasiat agar tak dimakamkan di Taman
Pahlawan, "supaya dekat dengan rakyat."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini