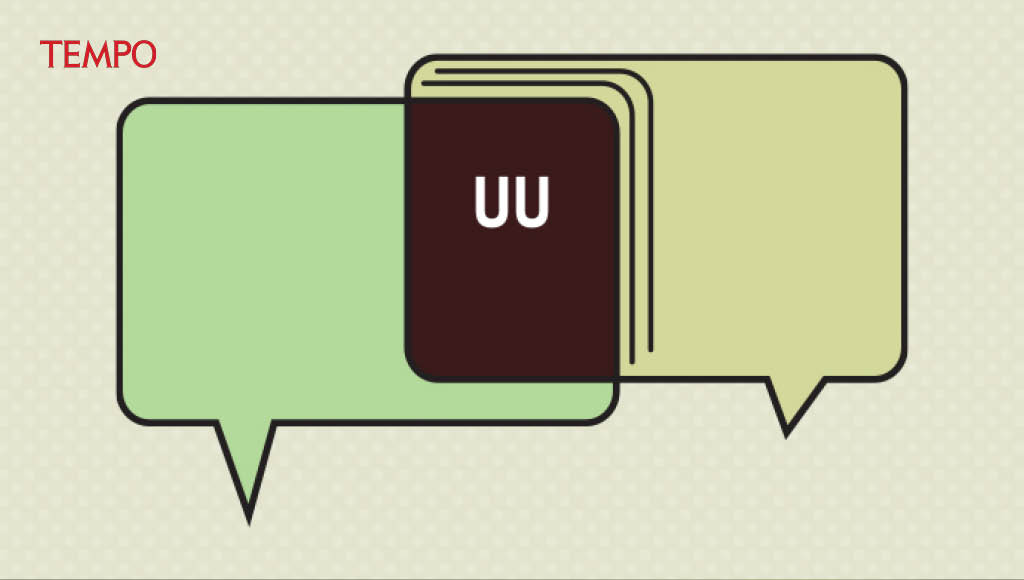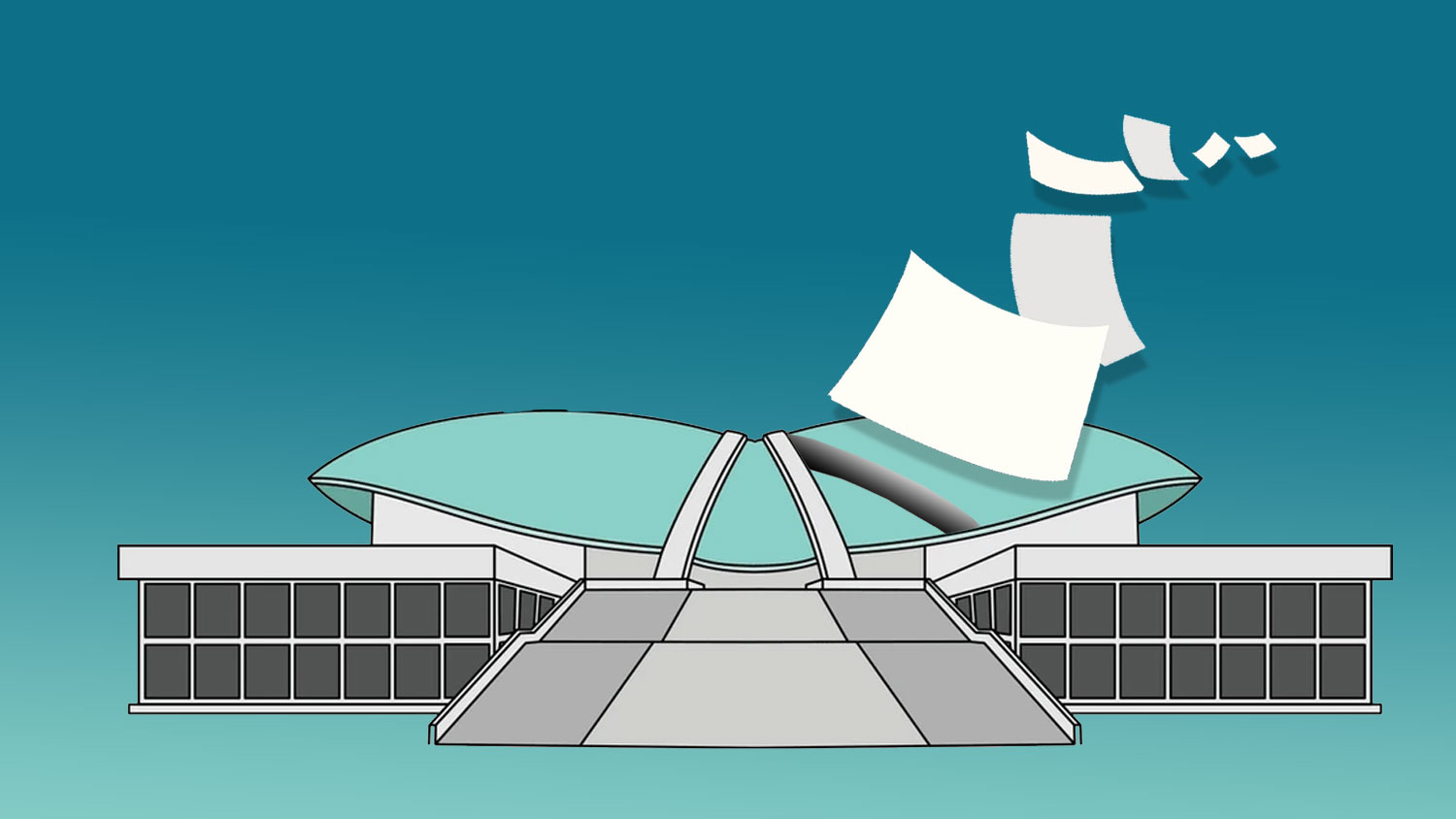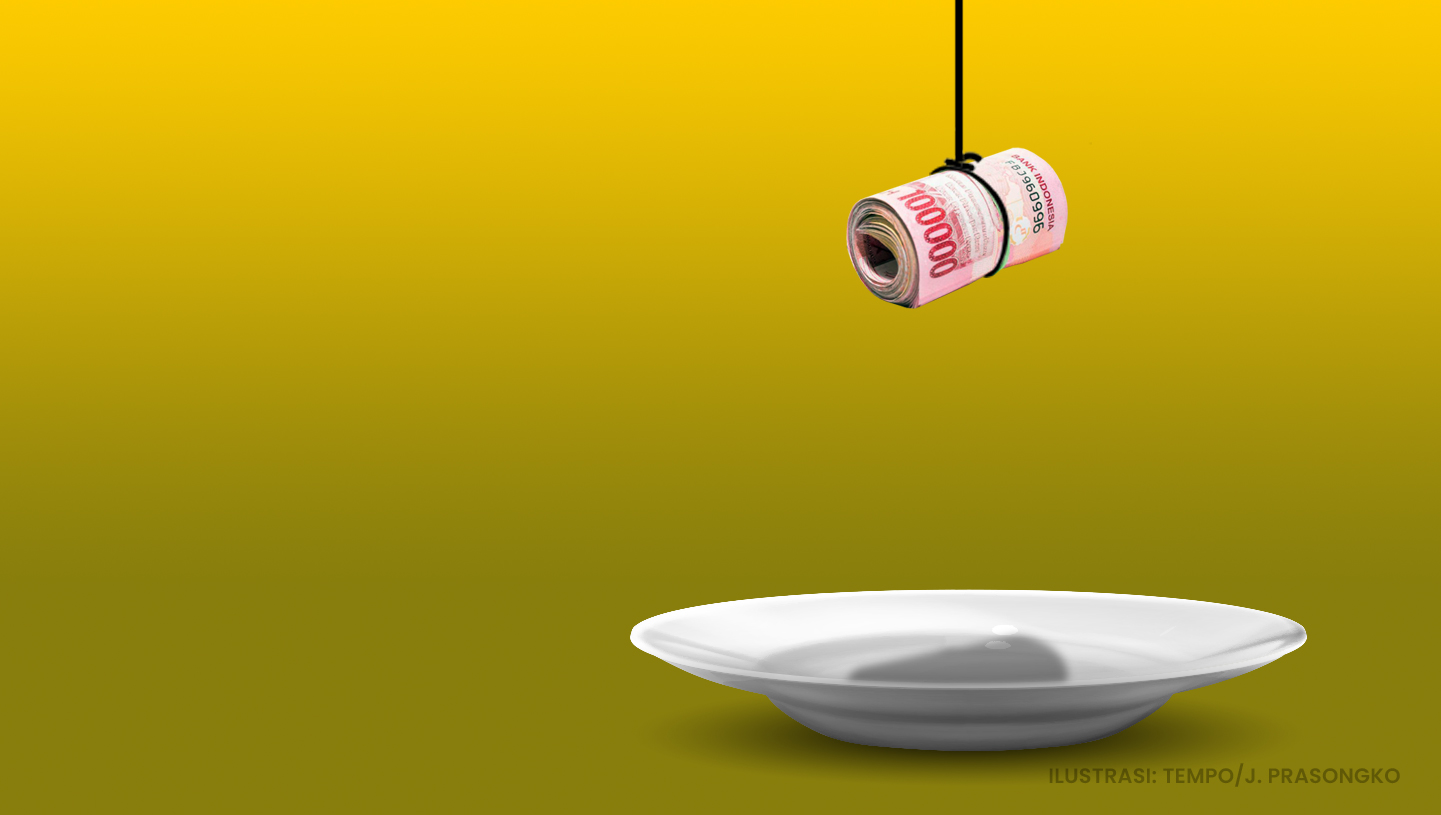INILAH saat-saat yang terindah, inilah saat-saat yang terburuk."
Seorang novelis pernah menuliskan kata-kata itu tentang
Revolusi Perancis 1789, ketika rakyat yang marah jadi
beringas, bui besar digempur, dan raja bersama ratusan bekas
penguasa dipenggal.
Saat-saat terindah, saat-saat terburuk -- benar. Juga untuk soal
yang lain. Kemeriahan kemenangan revolusi melahirkan semacam
karnaval ideologi-ideologi. Dari yang ekstim konservatif sampai
dengan yang ekstrim revolusioner bersemburan, berseru-seru. Dan
bila hal yang mirip terjadi di Indonesia 1945, (atau sebentar di
Iran 1979), apa sebenarnya yang terjadi?
Bukan hanya karena hari-hari revolusi adalah hari-hari pesta
kemerdekaan berfikir. Tapi terutama karena dasar budaya yang
tadinya mengatur kehidupan politik baru saja runtuh mendadak dan
orang banyak kehilangan sumber pembenaran yang sebelumnya mereka
kenal. Pegangan pun kacau dan arah pun rancu.
Maka ideologi-ideologi muncul. Mereka berusaha menawarkan
penjelasan tentang pengalaman yang gemuruh itu. Mereka
menawarkan program ke masa depan. Dan tak ketinggalan, mereka
menjanjikan solidaritas.
Jika kita tengok kembali sejarah (alangkah menyedihkannya orang
yang mengetahui tapi tak merenungkan sejarah!, hal seperti itu
wajar saja sebenarnya. Justru hiruk-pikuk yang berlangsung
sampai beberapa puluh tahun setelah kemerdekaan itu menyebabkan
kita kian sadar: kalau kita mau survive sebagai bangsa, kita
butuh lambang milik bersama. Semacam pelabuhan, semacam rumah
asal, ke mana kita bisa pulang bersama -- setelah saling
bertengkar.
Kita beruntung, bahwa di tahun 1945 itu ada sebuah dokumen
penting pidato yang kemudian dianggap menandai lahirnya
Pancasila. Dengan kata lain, sejak awal kemerdekaan itu kita
punya simbol tempat kita menambatkan diri sebagai satu kaum,
karena para perumus dasar negara 35 tahun yang silam itu sadar:
yang merintis kemerdekaan bukan cuma satu golongan, juga yang
harus mempertahankannya.
MEMANG ada yang menganggap ideologl sebagal topeng dan sebagai
senjata. Dalam "teori senjata" ini, ideologi adalah wajah lain
dan alat dari perjuangan manusia ke arah kemenangan
kepentingannya. Marxisme jelas menganut teoriini - juga untuk
dirinya sendiri.
Tapi Marxisme tak selamanya memadai untuk menjelaskan hal ihwal.
Ada satu penjelasan lain tentang peranan ideologi di masyarakat
sebagai pengobatan. "Teori penyembuhan" ini melihat ideologi
dalam fungsinya untuk mengoreksi terus-menerus rusaknya harmoni
sosio-psikologis. Ideologi menyediakan saluran simbolis bagi
guncangan-guncangan emosional masyarakat, di tengah terganggunya
keseimbangan sosial setiap kali.
Kiranya banyak yang akan melihat Pancasila sebagai contoh yang
baik ideologi sebagai penyembuhan: ia selalu dikaitkan dengan
kepekaan kita akan aneka ragamnya manusia, kelompok dan lapisan
sosial di negeri ini -- dan ia selalu dilekatkan ke hasrat
menemukan harmoni.
Dengan kata lain -- apa pun yang dihatakan para penganut
Marxisme (termasuk yang tak sadar dan diam-diam) -- Pancasila
bukanlah senjata. Bayangan tentang masyarakat dalam ideologi ini
bukanlah sebuah medan perang kepentingan, tapi lebih damai dari
itu. Meskipun, tak berarti Pancasila membayang kan masyarakat
sebagai taman Firdaus.
Justru karena ia selalu dilekatkan ke hasrat menemukan harmoni,
justru karena ia juga religius, masyarakat bagi pandangan
Pancasila adalah masyarakat manusia yang tak sempurna. Konflik,
misalnya, bukanlah sesuatu yang mustahil. Masalahnya ialah
bagaimana menyelesaikan serta mengelolanya.
**
KARENA itu agaknya menarik untuk merenungkan, bagaimana
pandangan Pancasila dalam mengelola konflik. Haruskah pihak yang
berkonflik -- "kita" vs "mereka" -- saling mengucilkan bahkan
menghabisi? Ataukah perlu selalu disediakan jembatan - antara
"kita" dan "mereka", sebagai kemungkinan, biar kecil, ke arah
berbaik kembali?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini