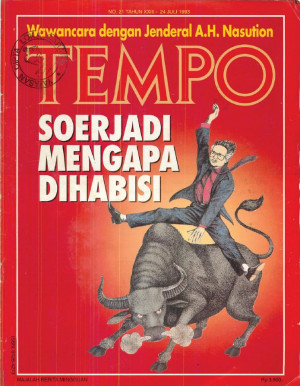WALAU unsur ''nasionalis'' masih kuat, PDI bukanlah lagi penjelmaan PNI, melihat Pemilu 1992 yang lalu. Dalam beberapa hal, partai ini justru lebih mirip PSI, ''seteru'' PNI di masa lalu. Seperti halnya partai-partai pra-Orde Baru lainnya, PNI adalah sebuah partai aliran yang tegak pada basis budaya ''priayi''. Karena itu, PNI di mata masyarakat banyak di Jawa tidaklah dihayati sebagai partai modern, melainkan personifikasi seorang ''bapak''. Lalu pada pertengahan 1950-an, pada posisi itulah ''sang anak'' (para kawula, rakyat) secara tiba-tiba dihadapkan pada pergumulan politik dan ideologi periode Demokrasi Liberal. Di mata mereka, ingar-bingar kebangkitan militansi Islam di mana-mana dan usaha PKI yang dengan teguh mempertanyakan keabsahan hierarki sosial-budaya yang telah mapan adalah proses kekacauan jagat simbolis mereka. Bagi mereka, dinamik politik nasional kala itu adalah sesuatu yang melahirkan pertanyaan-pertanyaan besar tentang ''pegangan hidup'' ketika kemapanan, yang diharapkan muncul dengan kemerdekaan yang baru diraih, justru menggelarkan disorganisasi sosial-budaya dan politik. Dalam konteks menemukan ''pegangan''inilah mereka mendambakan kontinuitas kultural yang menghubungkan mereka dengan masa lampau dan dengan periode pasca-kemerdekaan yang tak berpreseden itu. Inilah yang menye- babkan PNI, di mata massa, muncul sebagai ''bapak''. Melalui PNI, yang dengan sosok dirinya menyimbolkan keajekan budaya, mereka berharap mendapatkan bimbingan dalam meniti lingkungan kehidupan yang semakin asing dan aneh itu. Dus, dengan sedikit pengecualian, sebagian besar pendukung PNI dalam Pemilu 1955 adalah massa yang mendambakan ''Indonesia merdeka'' dengan tetap mempertahankan kontinuitas budaya adiluhung masa silam. PNI, dengan demikian, tegak pada lapisan massa tradisional dan hampir-hampir tak pernah beranjak dari dunia itu. Tentu saja, sisa-sisa semangat semacam ini masih terlihat di kalangan pendukung PDI dalam tiga pemilu Orde Baru belakangan ini. Tapi kondisi struktural tak lagi mengizinkan. Golkar, yang muncul sebagai partai penguasa, hampir secara keseluruhan mengambil alih fungsi simbolis dan kultural kepriayian PNI. Akibatnya, seperti kata beberapa kepala dukuh di desa-desa perbukitan Kulonprogo, sewaktu saya meneliti Kelompencapir beberapa tahun lalu, beralihlah orientasi politik desa. ''Sebab,'' kata mereka, ''kami sebagai pamong hanya akan mengikuti partai yang memerintah. Jika dulu PNI, maka kini Golkar.'' Namun, dalam usaha Golkar mengonsolidasikan seluruh elemen simbolis dan kultural PNI masa lalu, proses detradisionalisasi politik massa menjadi dipercepat. Untuk sebagian, proses ini terjadi karena, sebagai partai baru, Golkar tak pernah atau belum berhasil melembagakan segi emosional elemen simbolis itu menjadi sebuah ideologi yang bersifatpenetratif yang mengikat ''Beringin'' dengan massa. Sebagai akibatnya, pertautan massa dengan Golkar, seperti yang kita saksikan, lebih direkrut oleh basis material daripada semangat gagasan pembaruan dan modernisasi. Dan sejalan dengan semakin menyebarnya pengaruh material Golkar ke seluruh pedesaan, semakin meluas pula basis material tingkah-laku politik massa. Maka, bukan saja struktur politik aliran semakin menipis, tapi juga semakin membiaknya detradisionalisasi politik massa. Untuk sebagian, proses itu terjadi karena keberhasilan pembangunan ekonomi yang dicanangkan dan dilancarkan Golkar selama lebih dari dua dekade ini. Dalam satu setengah dekade pertama, keberhasilan pembangunan ekonomi itu memang telah menelurkan kaum menengah dan lapisan atas yang ''berterimakasih'', yang karena jumlahnya yang masih terbatas, loyalitas mereka relatif masih bisa terkontrol. Tapi, semakin bergerak ke masa kini, hasil-hasil pembangunan ekonomi itu telah melahirkan lapisan-lapisan masyarakat baru yang semakin luas dan dengan sendirinya melimpah ke luar arena pengontrolan pusat. Dengan kata lain, ketika pembangunan ekonomi telah mulai bersifat self-regulation, secara perlahan-lahan partisipannya semakin meluas dan semakin menghantarkan mereka ke periode ''pasca-nasi''. Basis ''pasca-nasi'' inilah yang secara struktural mendorong mereka, secara politik, semakin otonom. Maka, perlahan-lahan, terutama di kota-kota besar, muncul lapisan masyarakat''bebas'', baik dari struktur politik aliran maupun dari ''penjara loyalitas politik ekonomi''. Semakin mapan terlembaganya masa ''pasca-nasi'', akan semakin ''tinggi'' pula harapan-harapan politik mereka. Dalam konteks ini, tuntutan-tuntutan mereka telah mencapai taraf beyond pembangunan, ketika mereka mulai mempersoalkan kebebasan, keharusan terjadinya perubahan, dan sistem politik yang lebih demokratis. Jika perkembangan ini mengikuti garis linier, tidaklah mustahil, lapisan-lapisan masyarakat ini akan merekrut anggota dalam skala yang lebih luas. Dalam konteks inilah kita melihat PDI secara struktural bukan lagi penjelmaan PNI, melainkan mendekati sosok PSI. Sebab secara spekulatif saya percaya, kalangan yang mengalami detradisionalisasi politik dan semakin otonom di atas tidak punya alasan kuat berpaling, baik kepada PPP maupun Golkar. Berpaling pada PPP sama dengan kembali pada politik aliran. Dan melanjutkan dukungan kepada Golkar berarti mempertahankan kemapanan. Satu-satunya yang tersisa pada mereka adalah PDI, partai yang relatif bebas dari politik aliran maupun ''perangkap'' kemapanan. Munculnya lapisan masyarakat ''bebas'' inilah yang dulu diidamkan ''partai elitis-intelektual'' PSI untuk menjadi pendukungnya. Tapi, masalahnya, siapkah elite PDI secara konseptual menangkap tanda-tanda zaman ini, seperti dilakukan oleh Sjahrir? Siapkah mereka menjadi pemimpin yang tak ragu-ragu seperti yang selalu dikesankan mereka dewasa ini?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini