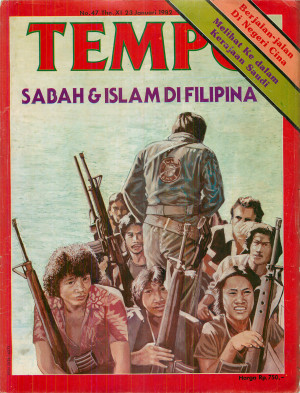VS. Naipaul memang bukan hendak menyenangkan orang Islam.
Dia berjalan jauh ke Iran, ke Pakistan, ke Malaysia dan
Indonesia, tempat tinggal lebih dari 250 juta orang muslim, lalu
menulis Among Tbe Believers dengan satu kesimpulan yang muram:
"Islam mensucikan amarah -- amarah mengenai iman, amarah politik
. . . "
"Lebih dari sekali dalam perjalanan ini," begitu kalimatnya
kemudian, "saya bersua dengan orang-orang perasa, yang siap
untuk merenungkan pergolakan-pergolakan besar." Pergolakan untuk
mengganti isi dunia yang dianggap kotor dan mengecewakan.
Pergolakan yang-hanya dengan amarah dan iman itu dan akan
memberi jawab yang memadai.
Jawab apakah yang memadai? Naipaul mengingatkan kita akan S.
Takdir Alisjahbana di tahun 1930-an, dalam suatu tukar pikiran
yang termasyhur di majalah Poedjangga Baroe dan kemudian
dibukukan dengan judul Polemik Kebudayaan. Seperti Takdir,
Naipaul menyebut pilihannya: "peradaban Barat".
Dan seperti Takdir, Naipaul memberi catatan tertentu kepada kata
"Barat" yang sering ditanggapi dengan purbasangka itu. Dalam
wawancaranya dengan Newsweek 18 Agustus 1980, ia berkata
tentang "suatu peradaban besar yang universal dewasa ini," yang
oleh banyak orang akan disebut " Barat " . Meski sebenarnya,
kata Naipaul, "peradaban ini telah diberi makan oleh sumber yang
tak terhitung banyaknya."
Dengan kata lain, "Barat" bukanlah sekedar seperti Eropa
sekarang. Peradaban besar itu tak ada kaitannya dengan watak
bangsa atau ras. "Kesalahan dari sikap pongah Barat ialah," kata
Naipaul, "karena mereka mengira, bahwa peradaban universal yang
ada sekarang lebih bersifat sesuatu yang rasial."
Karena itu, Naipaul juga berbicara tentang kesalahan di Dunia
Ketiga. "Apa yang memasygulkan saya ialah bahwa ada sebagian
kebudayaan di mana orang mengatakan, 'Putuskan kontakmu dengan
dunia luar. Kembalilah kepada dirimu yang dulu'. Tak ada yang
akan menggantikan peradaban universal yang mereka tolak itu."
MEMBACA Naipaul kita seakan membaca kembali percakapan kita yang
lama. Ya, Polemik Kebudaaan. Tapi juga hampir tiap debat,
selisih pendapat bahkan fitnah-memfitnah yang terjadi hampir di
tiap dasawarsa sejak 1930 sampai dengan 1980.
Maka tak heran bila Naipaul masih bisa membuat kita meradang.
Dia, yang tak bertanah air, tak beragama, yang lahir dari
keturunan India di Trinidad dan hidup di Inggris, orang yang
jauh dari semak-belukar dan begitu gampang memasuki balairung
kecerdasan Barat, tak mengalami apa yang kita alami.
Mungkin itulah kekurangan Naipaul: ia tak cukup punya simpati
pada pedihnya perasaan orang Dunia Ketiga yang harus
mematut-matut diri, kadang secara menggelikan, di depan
"negaranegara maju". Di samping itu, dia seakan mengelakkan
kenyataan, bahwa dalam soal "peradaban universal" itu ada
tersangkut banyak soal jual-beli.
Dalam cerita yang romantis, sikap kreatif dan berpikir kritis
memang bisa tumbuh di antara daunan padi. Dalam prakteknya,inti
suatu peradaban tak bisa cuma diproses di dekat pematang. Ia
memerlukan empu, sekolah, pengajar, perpustakaan, laboratoria,
dan lalulintas hasil penelitian serta teknologi.
Dan di zaman yang tak gampang bermurah hati ini, Dunia Ketiga
seakan senantiasa tersikut. Ia tersisa di luar garis. Di luar
garis itulah, amarah memang terasa jadi hak. Juga pengingkaran.
Pertanyaan kembali tak bisa dihindari: Jika kita tak akan bisa
menang, kenapa kita toh harus ikut berlomba di arena itu?
Tidakkah "peradaban universal" Naipaul pada akhirnya akan tetap
hanya milik eksklusif sejumput bangsa?
Lalu kita pun ingin berpaling. Yang jadi soal ialah bisakah kita
membedakan antara berpaling dan menutup pintu. Naipaul memang
punya petunjuk bahwa di Dunia Ketiga, banyak orang hanya mau
menyatukan diri kembali dengan belukar. Tapi mungkin dia tak
sabar: kebingungan memang bisa meledakkan kemarahan. Namun
kebingungan juga bisa jadi tanda bahwa sejumlah orang sedang
mengandung janin ide yang besar--meski selama ini keguguran.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini