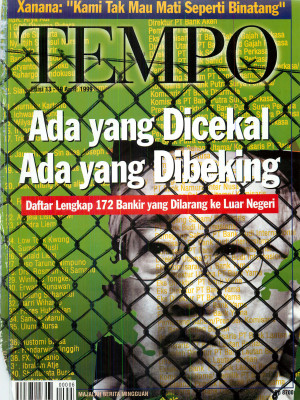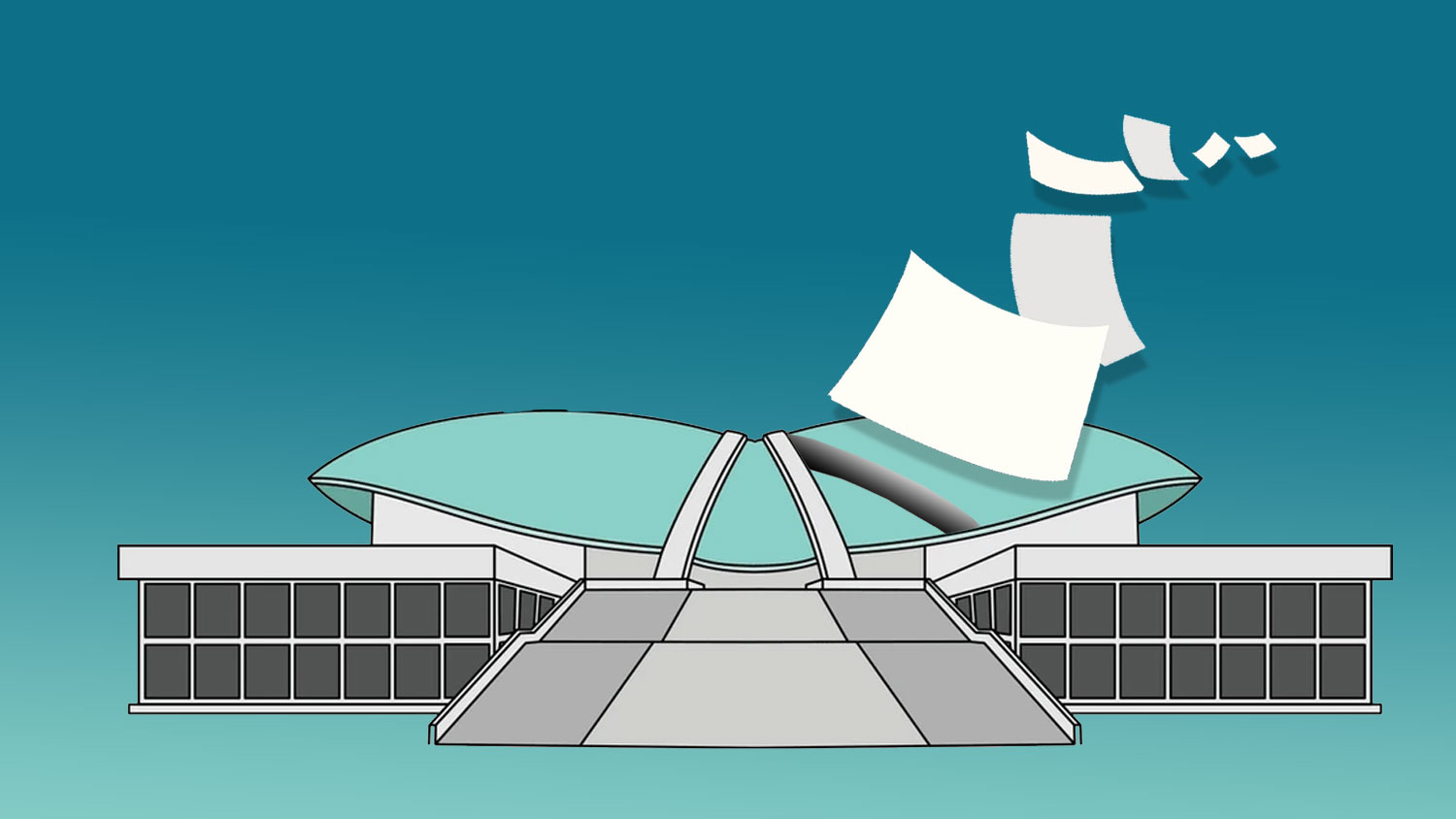H. Sujiwo Tejo
Budayawan dan mantan wartawan
KARTINI tak sempat mendengar apa boleh Megawati jadi presiden. Sama ketika Jaksa Agung Andi Ghalib dikirimi ayam betina karena dianggap nggak serius "mengurus" Soeharto. Pendekar wanita itu tak sempat melihat kaumnya protes lantaran kepengecutan masih disamakan dengan perempuan. Siapa berani menjamin segala yang jantan sejak ayam, kerbau, sampai presiden, tak pernah culas dan pengecut dalam sejarah?
Sekarang musim PHK. Jika ada korban PHK karena dianggap terlalu banyak cekikikan, tanpa menyimak nama, kita langsung main tebak pastilah dia perempuan. Seolah laki-laki, termasuk yang sering bersafari di televisi, tak banyak yang cekikikan baik manifes di wajah maupun cuma laten dalam hati. Mungkin karena sejak Abu Nawas, pengarang Anton Chekov, sampai kita dan lagu dangdut atau lagu apa pun, termasuk keroncongnya Mus Mulyadi perkara janda, begitu mendengar istilah janda, yang segera terbayang hanya kekembangannya. Perihal "ah uh ah uh"-nya. Bukan pergumulannya di luar ranjang.
Sajak Perempuan Perempuan Perkasa Hartojo Andangdjaja hampir terasa cuma intermeso. Segera terbayang, betapa berbunga-bunganya mengunjungi kampung ribuan janda di Aceh karena lakinya dibunuhi tentara. Bukan bayangan andai kata yang dibunuhi tentara para istri, ribuan duda akan cepat berkurang setiap hari karena sakit-sakitan lalu mati. Telah cukup bukti lelaki tak lebih tangguh. Kalau tidak serial, bayangan yang terakhir mendahului yang pertama, minimal bayangan kita tidak paralel.
Tahun lalu, di Gedung Pameran Seni Rupa Gambir, ada pertanyaan untuk mengantar karya-karya religius perupa perempuan. Betapa cukup lama, kata mereka, religiositas kita dikuasai imajinasi bahwa Tuhan itu He, bukannya She. Alih-alih membayangkan tidak He dan tidak She karena tak boleh ada suatu pun yang menyerupai-Nya. Betul juga. Cobalah menonton wayang outdoor pada tembang magis Ayak-Ayak Manyuro dan mendengar dalang menyebut Hyang Murbeng Dumadi. Yang segera terbayang, sambil menerawang bulan sabit di langit maupun empat bintang membentuk tanda salib atau apa pun, bukanlah sewujud Kanjeng Ratu Kidul, Cleopatra, Monalisa, maupun perempuan dalam lukisan Matisse.
Mari diturunkan Hyang Murbeng Dumadi ke gusti pengelola warga negara: Presiden. Bayangan kita kalau tidak Habibie, ya, Wiranto, Amien Rais, HB X, atau Pak Jan, penjual kopi tubruk sampai subuh di sebuah gang di Situbondo. Pokoknya bukan Marsinah maupun Pariyem. Lantas di manakah pada gorong-gorong imajinasi kita tentang kepemimpinan, tempat untuk Megawati, Nursjahbani Katjasungkana, Ratna Sarumpaet, Karlina Leksono, Wardah Hafidz, Niniek L. Karim, Evie Tamala, Ayu Utami, dan sebagainya, pokoknya yang perempuan?
Ketika ngamen di beberapa dusun, di sela-sela menyanyi saya bilang, sudah waktunya tembang-tembang tradisi tak cuma menyediakan syair bagi laki-laki untuk foreplay. Perempuan juga boleh merayu. Respons ibu-ibu cuma cekikikan.
Di luar dugaan, ketika saya bilang bahwa para istri juga boleh kalau perlu gantian melempar piring serta menempeleng suami, mereka keras bertepuk tangan. Itu pula yang kemudian saya laporkan pada pementasan untuk acara para feminis perkotaan di Galeri Cemara Jakarta akhir tahun lalu.
Tanpa mengaku feminis bahkan kenal istilah saja, dorongan dari desa-desa juga kuat agar perempuan mulai dianggap. Tapi bisa jadi keragu-raguan untuk Megawati dan perempuan mana pun menjadi presiden lantaran ini: Selalu tidak mustahil timbul subyektivitas untuk menafsirkan ajaran atau apa pun, meski untuk penafsiran tersebut telah ada metodologinya dengan disiplin yang amat ketat. Nah, pada sejumput rongga subyektivitas itu di antaranya ada hal-hal minor atas dasar kecurigaan yang memang empiris tentang perempuan.
Hal lain lagi, masih dalam sejumput rongga subyektivitas penafsiran, jangan-jangan kaum lelaki berpikir biarlah yang menjadi presiden itu pria. Toh ujung-ujungnya, lewat berbagai siasat, termasuk siasat menekuk lutut pria melalui sudut kerling mata pada lagu Sabda Alam, yang berkuasa tetap perempuan juga. Misalnya, usai memimpin deklarasi sebuah partai cukup besar, laki-laki gagah itu sudah lenyap ketika teman-teman wartawan mencarinya. Bawahannya bilang, "Beliau disuruh cepat pulang sama istrinya." Sudahlah. Tak usah Anda mengasihani pensiunan yang masih berpengaruh itu. Hal yang sama terdapat pada hampir semua cerita rakyat. Pak Sakerah dari legenda Madura itu kurang gagah dan berani bagaimana. Toh pada banyak pertunjukan ludruk sering ditampilkan betapa takut dan gemetar dia pada sang istri. Setiap kali Pak Sakerah akan main celurit terhadap orang, Mbok Sakerah naik ke atas kursi dan meja sambil mencincing kain panjangnya. Dan penonton bertepuk tangan.
Jika nanti HB X, atau lelaki mana pun, terpilih menjadi presiden, biarlah kosmologi Kanjeng Ratu Kidul semakin memahamkan bahwa sebenarnyalah kaum perempuan tetap tidak sepele. Saya termasuk yang mendukung tafsiran bahwa Mega tidak boleh jadi presiden, jika yakin bahwa subyektivitas tentang plus-minus perempuan seimbang, jika yakin tak ada motif politik lain kecuali membuat hari esok lebih baik bagi semua pihak.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini