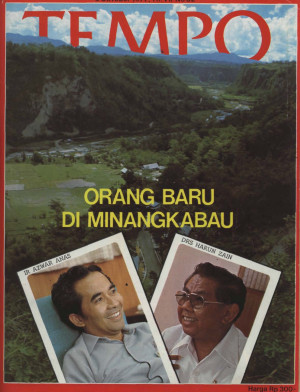"Tidak, Stella, rakyat tidak lagi dengan sengaja dirampok oleh
para penguasa mereka."
PADA tanggal 20 Januari 1900, Kartini menuliskan kata-kata itu
kepada sahabatnya, Stella Zeenhandelaar. Si gadis Belanda
bertanya adakah rakyat kecil masih menyedihkan keadaannya
seperti yang dilukiskan Multatuli dalam Max, Havelar. Si gadis
Jawa, puteri Regent yang bergelar Raden Adjeng, menjawab
dengan penuh harapan, keadaan tak terlalu jelek lagi.
Sementara itu di pendopo kabupaten Jepara di pesisir utara Jawa
Tengah gametan berbunyi ke udara malam Para niyogo memainkan
Ginohjing. Lagu itu telah berlusin kali didengar oleh Kartini,
tapi ia tak pernah tak jadi terharu. "Itu adalah suara jiwa
manusia yang berbicara padaku," kata Kartini, "kadang mengeluh,
kadang melenguh, kadang tertawa gembira. Dan sukmaku pun
melayang bersama getaran nada perak murni itu ke atas, ke
angkasa, ke pulau-pulau cahaya yang membiru, ke awan, ke
bintang-bintang bersinar .... " Kartini, waktu itu umurnya 21
tahun, terdengar seperti seorang penyair.
Namun bagian yang menarik dari suratnya 20 Januari 1900 itu
adalah mengenai pungli. Memungut suap bagi Kartini sama salah
dan sama memalukannya dengan merebut dengan pakisa miik rakyat
kecil seperti yang dilukiskan dalam Max Havelaar. "Namun
mungkin aku tak akan menghakimi ini dengan keras, bila kuingat
keadaannya. Mula-mula orang pribumi mengira bahwa menyajikan
pemberian kepada atasan mereka adalah tanda respek -- suatu
pernyataan rasa hormat. Menerima hadiah memang dilarang oleh
pemerintah bagi Para pegawai, tapi banyak gagal bangsa pribumi
begitu kecil gajinya! hingga ajaib juga bagaimana mereka rapat
hidup terus dengan penghasilan mereka yang begitu sedikit.....
Jangan hakimi mereka dengan keras . . . Jika seorang jurutulis
distrik ditawari sesuatu, munykin setandan pisang, ia pertama
kali mungkin akan menolaknya, begitu juga untuk kedua kali ia
akan menolaknya, tapi pada ketiga kalinya ia akan menerimaitu
dengan segan-segan, lalu untuk kali yang keempat ia akan
menerimanya tanpa ragu. Apa yang saya lakukan tak merugikan
siapa-siapa, begitu fikirnya, saya tak pernah memintanya tapi
toh diberikan kepadaku. Bodoh sekali bila saya ragu-ragu selama
itu adalah adat. Pemberian hadiah bukan saja merupakan petunjuk
menghormati, tapi juga suatu cara berjaga wntuk menghadapi nasib
malang yang mungkin tiba, bila "si orang kecil" butuh
perlindungan dari seseorang yang berwewenang."
Kartini pun bercerita tentang nasib para asisten wedana. Seorang
asisten wedana kelas dua bergaji cuma 85 florin. Dari
penghasilannya ini si asisten harus membayar gaji seorang
sekretaris. Ia harus merawat sebuah kereta kecil dengan kudanya,
dan bahkan seekor kuda khusus untuk dikendarainya dalam
perjalanan ke pelosok-pelosok. Sang asisten juga harus membeli
rumah dan perabot -- dan juga harus menjamu. Para tamunya
mungkin controleLlr wedana atau bahkan tuan asisten residen
yang lagi tune. Dalam kesempatan seperti itu para tamu yang
terhormat biasanya tidur di pesanggrahan, dan tugas sang
asisten-lah untuk menghidangkan makanan bagi mereka. "Sering
terjadi bahwa para petinggi pribumi itu menggaraikan perhiasan
isteri dan anak mereka untuk mendapatkan uang yang diperlukan,"
tulis Kartini. "Maka bila orang datang kepada mereka dengan
pemberian ketika mereka melihat isteri serta anak-anak mereka ke
sana ke mari dalam pakaian buruk - jangan hakimi mereka dengan
keras, Stella."
Kartini sendiri tak pernah menghakimi dengan keras.
Ayahnya sendiri, sang Regent Jepara, tak kita ketahui sampai
sejauh mana kekayaannya. Barangkali ia tidak sekaya para bupati
sekarang. Namun menurut puterinya yang cerdas dan bemandangan
luas itu, sang ayah tak pernah memanfaatkan hadiah dari
bawahannya dalam perjalanan turne. Ia selalu membawa sendiri
perlengkapannya. "Ayah sangat bangga akan asal-usul
kebangsawanannya, tapi yang benar adalah benar, dan keadilan
adalah keadilan."
Adakah di masa itu ia juga suatu perkecualian?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini