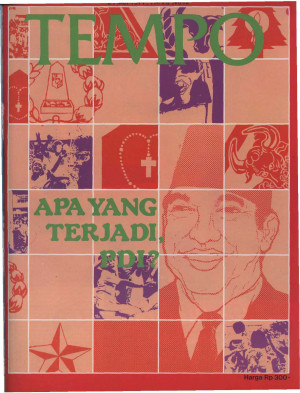MODAL klasik dari suatu masyarakat Jawa yang tradisionil terdiri
dari dua lapisan. Di satu pihak adalah Raja dengan keratonnya.
Di lain pihak terdapat massa petani.
Di antara keraton dan rakyat petani tidak ada pimpinan-pimpinan
lain seperti golongan tuan tanah atau golongan menengah di
kota-kota. Dalam masyarakat ini keraton (negara) mengontrol
seluruh perekonomian agraria. Kontrol politik dilakukan oleh
golongan priyayi, yang merupakan suatu golongan aristokrasi
pejahat, yang diangkat oleh negara. Dalam hal ini pun kepala
desa merupakan kaki-tangan negara dan otonomi desa adalah
khayalan belaka. Pola politik tradisionil ini kebanyakan
terdapat di pedalaman Masyarakat tradisionil tidak berarti bahwa
masyarakat itu tidak berubah. Justru kegoncangan-kegoncangan
dinastik di Jawa pada abad-abad yang lampau menunjukkan bahwa
struktur ini tidak dianggap sesuatu yang abadi dan diterima
demikian saja. Sayangnya kita belum banyak mengetahui mengenai
masyarakat kerajaan sebelum jatuhnya Majapahit (abad ke-XV)
untuk mengetahui dinamikanya.
Di samping pola politik yang klasik yang digambarkan di atas,
ada lagi suatu pola politik yang lain. Yakni kota pelabuhan.
Kota-kota pelabuhan di pasisiran Utara Jawa seperti Demak,
Tuban, Giri, Surabaya dll. punya penduduk yang kosmopolitan yang
terdiri dari pedagang, baik pribumi maupun asing dan tukang.
Golongan burjuis kota ini memiliki alat-alat ekonomi sendiri
dengan persediaan kekayaan, yang memungkinkan mereka mengimbangi
dan bila perlu menentang kekuasaan negara.
Menemukan Ideologi Menghadapi Majapahit
Pada kira-kira abad ke-XV (Masehi) agama Islam tersebar di
antara kota-kota pesisir Utara, dan dengan demikian masuk ke
Jawa. Apa yang terjadi adalah bahwa kekuatan politis dan
ekonomis kota-kota pelabuhan ini menemukan ideologi untuk
menentang pusat kerajaan Majapahit di pedalaman.
Penyebaran Islam sendiri ke pedalaman Jawa mungkin juga karena
adanya elemen-elemen oposisi lain terhadap susunan kerajaan
Majapahit, yang memang sedang mengalami proses keruntuhan karena
sebab-sebab intern. Pengislaman ini tidak selalu berjalan tanpa
kekerasan, dan mengalami oposisi di sana-sini. Pada akhirnya
menurut Babad, Majapahit jatuh (1400 Saka/1478 Masehi) karena
diserang oleh Raden Patah dari Demak. Kira-kira selama satu abad
pusat-pusat kerajaan Jawa berada di pantai Utara di sekitar
kota-kota pelabuhan. Tetapi dengan munculnya keraton Pajang, dan
terutama keraton Mataram yang kita jangan lupakan merupakan
dinasti-dinasti Islam, pusat politik berpindah sekali lagi ke
pedalaman.
Apa yang sebenarnya terjadi dalam pergolakan-pergolakan di atas?
Elemen-elemen oposisi terhadap konsep seorang Deva-Raja, yang
diwakili oleh Majapahit, menemukan dalam Islam suatu ideologi
yang lebih cocok untuk menentang kekuasaan negara yang mutlak.
Jadi penyebaran agama Islam bukan saja merupakan suatu revolusi
agama, namun juga memiliki unsur-unsur revolusi sosial.
Pertama-tama, menurut agama Islam, raja hanya merupakan orang
lslam lain, seorang anggota umat seperti anggota-anggota umat
yang lain. Jelas ini lebih menyamaratakan kedudukan raja dari
pada konsep Deva-Raja dari zaman Majapahit. Kedua, dan hal ini
adalah lebih penting lagi, Islam menciptakan suatu elite agama,
para ulama, yang dapat menegor raja atau paling sedikit
membatasi kesewenang-wenangan negara. Hal ini jadi lebih penting
lagi, bila kita ingat bahwa menurut ajaran Islam sebenarnya
tidak ada pemisahan antara kekuasaan duniawi dan rohani atau
antara politik dan agama.
Ulama dan Priyayi
Tetapi apa yang betul-betul menjadikan Islam ini suatu unsur
revolusioner dalam susunan kerajaan tradisionil adalah golongan
para ulama yang tinggal di desa dan jadi pemimpin-pemimpin
setempat. Para ulama tinggal di desa-desa di tengah rakyat
petani, sering bercocok tanam sendiri, dan mendiami rumah-rumah
biasa. Tidak seperti kaum priyayi yang tinggal di kediaman
resmi, dikelilingi oleh alun-alun dan tanda-tanda kebesaran yang
lain. Para ulama jadi pusat pendidikan di desa dan aktifitas
sosial lainnya.
Dengan adanya golongan ulama ini para petani di desa menemukan
pemimpin-pemimpin mereka. Secara ideologis para petani
dihubungkan oleh tokoh ulama dengan dunia yang lebih luas,
sehingga isolasi spirituil dari desa dahulu ditembus.
Golongan ulama ini merupakan elite yang tidak mudah dikontrol
oleh negara, dan sebenarnya berada di luar hierarki kerajaan.
Namun ini tidak berarti bahwa semua ulama adalah penentang raja
Mataram yang beragama Islam.
Raja-raja Mataram yang mendirikan keratonnya di pedalaman, yang
dikelilingi oleh puing monumen-monumen zaman pra-Islam yang
paling agung - Borobudur, Mendut dan Prambanan - memiliki dua
sikap terhadap Islam. Sebagai dinasti Islam, raja-raja Mataram
mendasarkan negaranya atas ajaran Islam yang populer pada waktu
itu yakni mistik Sufi. Ideologi negara Mataram disejajarkan
dengan agama: kesatuan yang mengikat raja dan rakyatnya adalah
sama seperti kesatuan antara umat dan Allah.
Dengan kata lain rakyat harus tunduk pada kehendak raja.
Manunggaling Kawula lan Gusti adalah dasar utama ideologi ini,
yaitu menjadi satunya Manusia dan Tuhan atau rakyat dan raja.
Menurut ideologi negara, raja sering disamakan dengan Nabi. Nabi
zaman dahulu diilhami oleh Allah, dan raja pada zaman sekarang
juga "langsung diilhami" oleh Allah. Gelar raja-raja Jawa
menjadi "Sunan", seperti gelar yang diberikan pada para Wali
yang pertama-tama menyebarkan agama Islam.
Konflik: Karena Soal Kepentingan
Jadi di suatu pihak raja-raja Mataram menerima agama Islam dan
tidak menentangnya. Tapi di lain pihak raja-raja Mataram tidak
mempunyai sikap terhadap zaman pra-Islam yang mungkin akan
diambil oleh tokoh Islam lain. Bagi orang-orang Islam, zaman
pra-Islam dilukiskan sebagai zaman jahiliah. Tapi raja-raja
Mataram dalam Babad Tanah Jawi melukiskan jatuhnya Majapahit ke
tangan kekuatan Islam dengan kata-kata: Hilang Sirna Kartaning
Bumi (Hilang zaman ke-emasan dari Dunia). Lebih-lebih dalam
genealogi raja-raja Mataram sering disebut Dewa-Dewa Hindu dan
tokoh-tokoh dari dunia pewayangan. Memang tidak mudah untuk
menghapus 3 dari sejarah gemilang suatu bangsa.
Pertentangan yang ada pada dasarnya tidak disebabkan karena
perbedaan-perbedaan pandangan seperti di atas ini. Pertentangan
kepentingan ekonomi dan politik yang ada dalam kerajaan Mataram
atau di Jawa telah mempertajam perbedaan-perbedaan ideologi.
Tapi konfliknya mengenai soal konkrit.
Jatuhnya kerajaan Majapahit di pedalaman oleh kekuatan oposisi
pasisir dan ulama-ulama, bagi Mataram adalah hantu. Mataram
berusaha supaya kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi.
Maka dilakukanlah kebijaksanaan untuk mengamankan Mataram dari
bahaya itu.
Untungnya raja-raja Mataram juga insyaf akan pentingnya golongan
ulama ini sebagai pemimpin. Dan memang tidak semua mereka
menentang raja-raja Mataram. Banyak di antara para ulama,
mungkin bagian terbesar, menyokong kerajaan. Di keraton bahkan
terdapat ulama-ulama agung yang berpengaruh besar di antara
masyarakat Jawa. Para ulama yang cukup dianggap berpengaruh
dicoba untuk diikat oleh kcrajaan Mataram dengan diberi tanah.
Sampai-sampai puteri-puteri keraton pun dinikahkan dengan para
ulama itu. Dan para raja sendiri sering kawin dengan wanita
keturunan wali.
Namun pada permulaan dinasti Mataram ada segolongan tokoh Islam
yang menentang kekuasaan Mataram ini. Mereka adalah keturunan
para wali di pantai Utara, seperti Sunan Giri, Sunan Ngampel dan
lain-lain. Atau mereka adalah ulama yang punya ikatan keluarga
dengan para wali atau pernah menjadi santri (murid) di pusat
agama di pasisir ini, dan sekarang tinggal di pedalaman.
Pembuuhaf Massal
Dengan singkat antara Mataram dan kekuatan oposisi ini terdapat
bentrokan. Kekuasaan politik ekonomi para keluarga wali di
pelabuhan-pelabuhan dihancurkan dengan bantuan VOC. Dengan VOC
ini diadakan persekutuan. Di pedalaman sendiri dua kali selama
pemerintahan Amangkurat I (1646-1677) dilakukan pembunuhan
massal yang serentak terhadap para ulama yang dianggap sebagai
oposisi. Setiap kalinya diperkirakan 4000 sampai 5000 ulama di
sekitar daerah keraton jadi korban bersama - dengan keluarga dan
anak-buah mereka. Pada akhirnya Mataram menang terhadap oposisi
itu. Tetapi harga yang dibayar sangat tinggi. VOC makin lama
makin mengikat raja-raja Mataram, dan yang sebenarnya jadi
korban dari politik itu adalah rakyat Jawa.
Oposisi ulama Islam tidak selalu bersangkut-paut dengan para
wali dan dengan kekuatan pclabuhan. Sebab ketik
kekuatan-kekuatan itu sudah hancur toh tetap ada suara yang
mencoba mengkoreksi raja. Suara ini datang dari para ulama.
Dalam abad ke-XVIII (1772) umpamanya terdapat surat dari seorang
haji kepada pangeran Mangkunegara I, yang menganjurkan beliau
untuk "berperang terhadap orang-orang kafir (Belanda), sebab
biarpun sedikit jumlahnya, mereka yang membela yang adil dapat
mengalahkan yang kuat, seperti diajarkan oleh Al-Qur'an".
Memang rupanya pada tahun-tahun tersebut ada kekesalan terhadap
pengaruh Belanda dan perkembangannya. Tapi sesuai dengan
pandangan tradisionil Jawa, bukan Belandayang lalu dimusuhi,
melainkan raja sendiri yang dianggap bertanggungjawab atas
kemunduran zaman. Pada tahun 1787 dipasang di pasar Surakarta
surat terbuka pada Sunan yang a.l memuat "... Macam raja apakah
kamu ini? Raja orang-orang Belanda? Kamu tidak lagi dikurniai
Tuhan. Telah habis riwayat kamu! Pergilah orang yang menyimpang
dari agama . . . Mana buktinya bahwa kamu Raja dari Tuhan...".
Pada abad ke-XIX, para pemimpin pembrontakan petani sering
dipegang oleh para ulama, yang dinamakan oleh Belanda sebagai
"sumber-sumber ketidak-tenteraman pulau Jawa". Dalam masyarakat
tradisionil baik negara maupun rakyat yang tidak puas memakai
bahasa agama. Tapi sebenarnya konflik ini adalah mengenai
isyu-isyu yang konkrit dan riil, dalam hubungan negara dan
rakyat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini