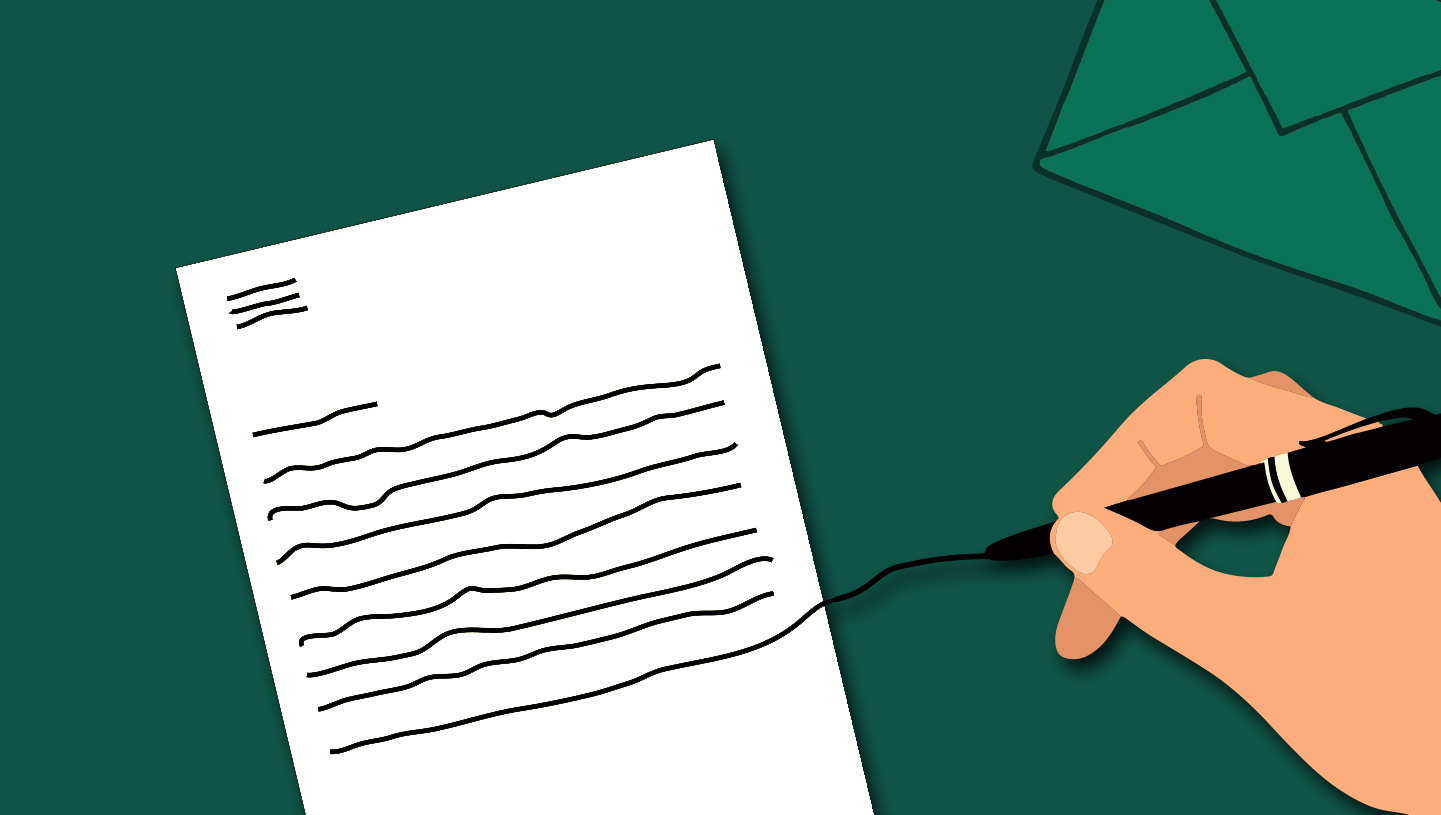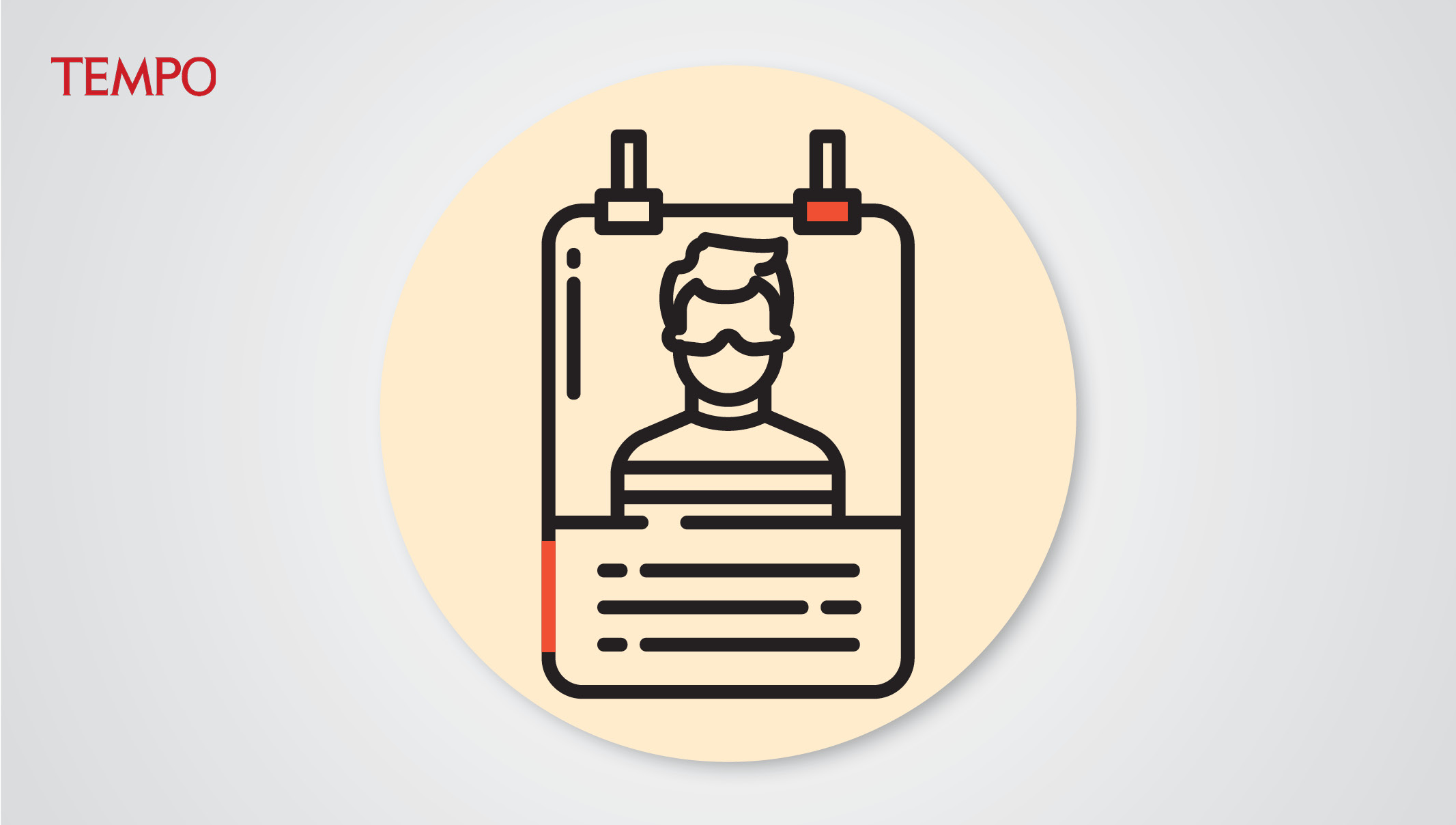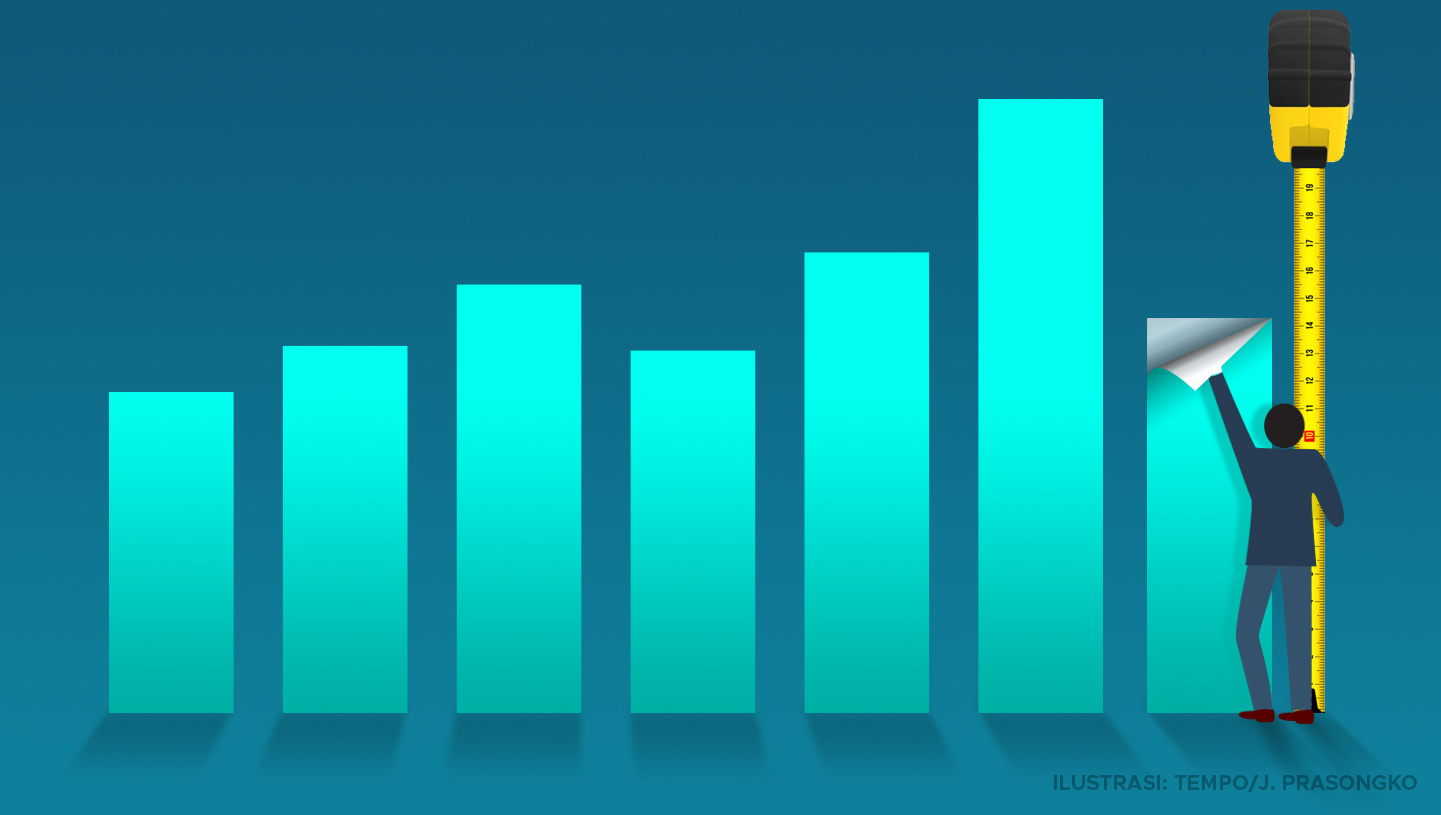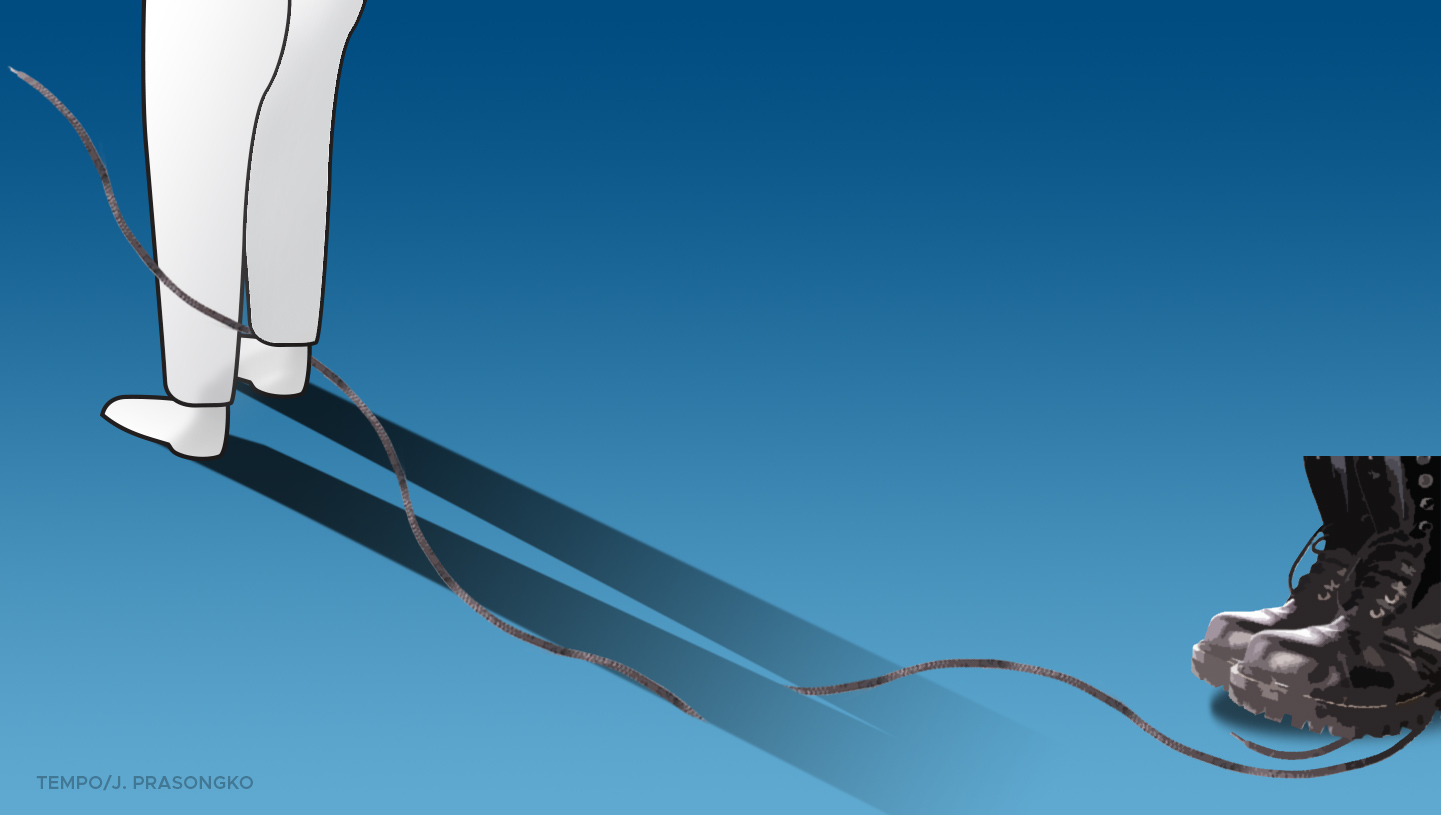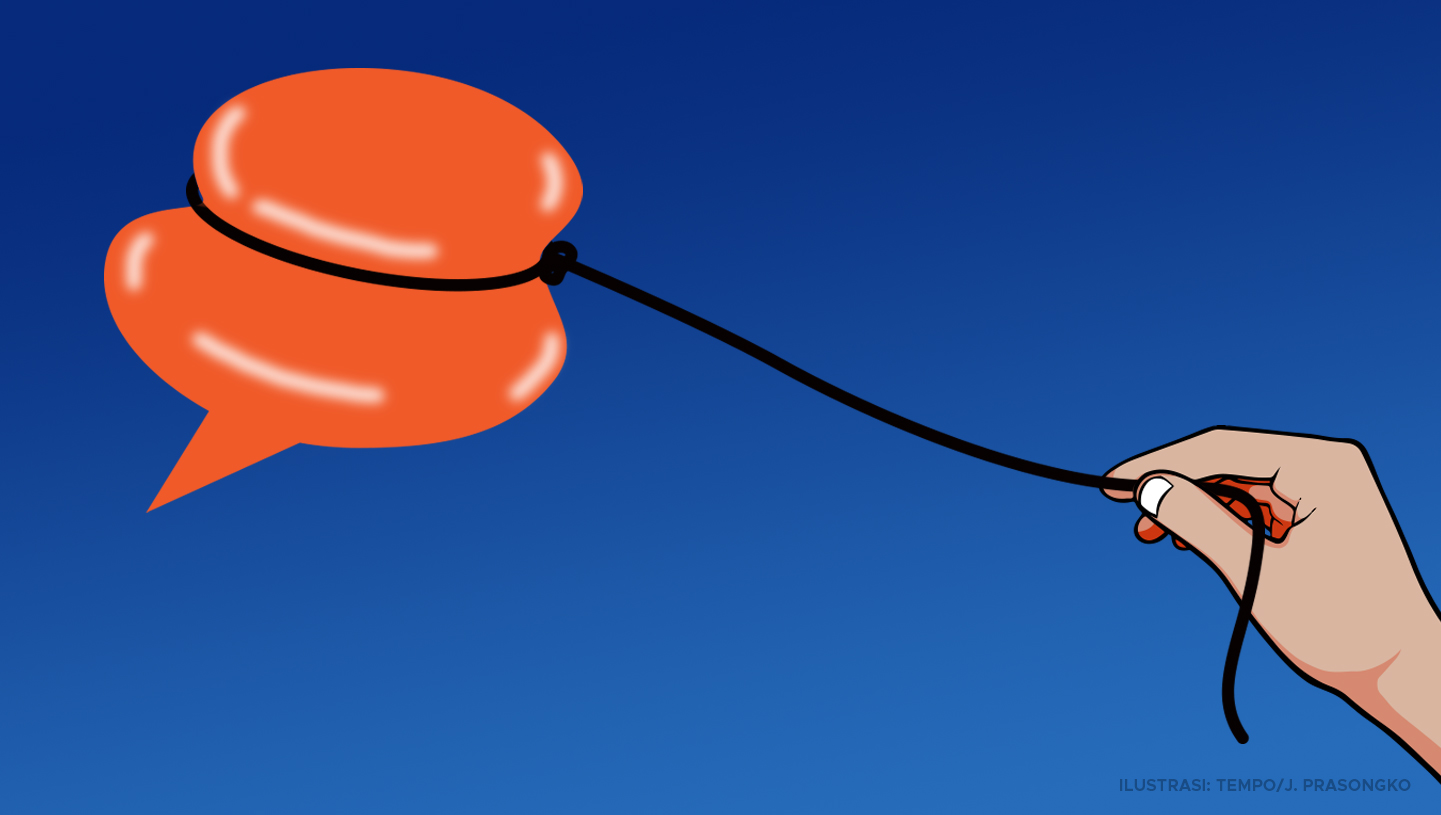Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pada suatu hari beberapa puluh tahun yang lalu, tiga orang Jawa ngobrol di sebuah kampus. Saya salah seorang di antaranya. Meskipun menetap di Jakarta, kami lebih sering menggunakan bahasa Jawa. Obrolan lancar-lancar saja sampai ketika saya mengucapkan kata randedhit. Salah seorang, yang berasal dari Solo, memahami arti kata itu, tapi orang Jawa yang lain, yang dibesarkan di Kediri, bertanya (dalam bahasa Jawa) apa arti kata itu. Rekan saya yang dari Solo menjelaskan, kata itu berarti "tidak punya uang", kependekan dari ora duwe dhuwit. Seandainya kami mencari kata itu di kamus bahasa Jawa, tentu sia-sia saja usaha itu. Tentu kita berhak bertanya, mengapa demikian. Letak masalahnya tidak pada perbedaan asal kami, atau pada beragamnya bahasa Jawa, tapi pada perbedaan antara bahasa lisan dan tulis.
Bahasa pada dasarnya lisan. Itu sebabnya perkembangan bahasa berasal dari yang lisan. Tulisan mengikuti yang lisan. Proses itu sederhana saja tampaknya: mengubah bunyi menjadi aksara. Bahasa lisan berkembang sangat-amat cepat. Setiap hari kita mendengar sejumlah kata "baru" yang sebenarnya kata lama yang diucapkan dengan keliru atau memang sengaja dikelirukan mengucapkannya sehingga sekilas terdengar sebagai baru. Di samping itu, memang ada sejumlah kata yang benar-benar baru bunyinya, meskipun yang dikandungnya sebenarnya sudah ada pada kata yang bunyinya sudah kita kenal. "Cius", misalnya, sudah kita kenal sebagai "serius" dan tentu sudah tercatat dalam banyak tulisan. Namun bisa saja kita tidak mengenal kata itu, sama halnya dengan teman dari Kediri yang tidak bisa menangkap makna bunyi randedhit, bunyi yang bagi orang Solo sama sekali tidak asing.
Demikianlah maka setiap hari kita bisa mendengar kata "baru" yang mungkin merupakan kependekan kata yang sudah ada, atau merupakan gabungan bunyi dua kata yang sudah ada, atau memang merupakan bunyi baru yang diciptakan untuk menampung makna yang tidak bisa ditampung oleh kata yang ada sebelumnya. Dalam bahasa Jawa, kata seperti ndladhuk, trompoling, sontoloyo, pengung, kenthir, dan pah-poh tidak bisa sepenuhnya dijelaskan maknanya, apalagi diterjemahkan agar maknanya tidak luntur. Sederet kata itu boleh saja diklasifikasikan sebagai umpatan, tapi "jenis" umpatan apa? Jenis yang menunjukkan kebencian atau justru jenis ungkapan keakraban? Dalam pada itu, kalau kita berniat melanjutkan (dan memang harus!) tradisi nenek moyang kita untuk mengubah bunyi menjadi aksara, pengetahuan dan pengalaman yang kita capai bisa diawetkan dalam aksara agar dapat disimpan demi pengembangan kehidupan dan ilmu pengetahuan. Sejak kita menciptakan aksara, perkembangan kemanusiaan berlangsung dengan sangat cepat. Sebelumnya, kehidupan dan pengetahuan kita terasa seperti jalan di tempat. Dalam kaitannya dengan pengaksaraan bunyi itu, kita pun menyusun kamus.
Ada, tentunya, kisi-kisi yang mengatur kata apa saja yang "berhak" masuk kamus, tapi semakin ketat kisi-kisi yang kita buat, akan semakin banyak ungkapan atau kata lisan yang tidak akan tercatat. Apakah yang berhak masuk kamus hanya kata yang pernah diaksarakan dalam berbagai bentuk tulisan, atau juga yang dilisankan? Kalau yang berhak masuk kamus semua kata yang kita ciptakan, lisan dan tulis, bisa dibayangkan kamus akan disusun dalam waktu yang sangat lama dan memuat begitu banyak kata sehingga sulit juga dibayangkan tebal bukunya. Di samping itu, tentu muncul masalah cara pencatatannya. Dalam bahasa lisan, kata-kata "baru" muncul dengan cepat dan tidak bisa dibendung, di samping pasti tidak mengikuti prinsip taat asas dalam pembentukannya.
Tentu tidak akan timbul masalah apa pun seandainya kata-kata "baru" yang muncul dalam bahasa lisan itu dibiarkan saja lewat dan tidak dicatat dalam tulisan. Tapi, karena niat kita sejak semula adalah merekam bahasa lisan ke dalam tulisan, semakin banyak yang kita lisankan semacam randedhit itu dituliskan, terutama dalam karya sastra. Tulisan tersebar lebih luas dan bertahan lebih lama—dan memang itulah maksud yang mendasari proses transkripsi. Kalau randedhit masuk ke sebuah karangan, yang penyebarannya tentu melampaui habitatnya semula, tapi kamus tidak mencatatnya, ke mana gerangan kita mencari tahu maknanya? Yang dilisankan cepat menguap dan terbatas penyebarannya, yang telah ditulis tidak dibatasi oleh waktu dan tempat penyebarannya.
Kedekatan dengan bahasa lisan adalah salah satu ciri kesusastraan. Pembaruannya antara lain, dan terutama, ditentukan oleh upaya sastrawan menciptakan "bahasa baru", yang tentu diawali dengan lisan. Itu salah satu sebab mengapa karya sastra memanfaatkan bahasa lisan. Dalam kesusastraan, salah satu ciri perkembangannya adalah diciptakannya "bahasa baru" yang menyangkut kiasan, penciptaan kata yang berupa gabungan kata atau peringkasan kata, dan pemanfaatan kata dari kekayaan bahasa lisan. Kata teori, kamus harus diperbarui setidaknya lima tahun sekali, tapi dalam waktu lima tahun bahasa lisan berkembang lebih pesat lagi, yang jelas tidak akan terkejar oleh penyusunan kamus. Kamus disusun untuk mencatat dan memberi definisi kata yang kita lisankan. Di dunia lisan, kata tidak mempedulikan kamus.
Namun dapatkah sekarang ini kita membayangkan komunikasi tanpa menyandarkan makna dan pengertian pada kamus? l
Sapardi Djoko Damono (Guru, sastrawan)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo