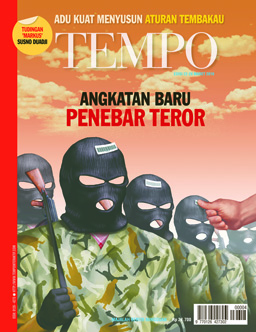Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
MELARANG merokok dengan fatwa sama musykilnya dengan menghalau korupsi lewat khotbah. Satu-dua orang mungkin jeri dan kemudian tobat, tapi tak ada perubahan berarti. Majelis Ulama Indonesia setahun lalu mengharamkan rokok bagi wanita hamil, anak-anak, dan perokok di tempat umum. Toh, dengan mudah kita jumpai orang merokok di mal, kafe, bus, bahkan di sebagian area rumah sakit.
Pembuat fatwa tentu tahu advis itu tidak mengikat pengikutnya, apalagi pengikut kelompok lain. Tapi soalnya bukan itu saja. Dalam urusan rokok ini terjadi ”tabrakan” fatwa yang membingungkan. Majelis Tarjih Muhammadiyah pekan lalu jelas menyatakan merokok itu haram. Sedangkan Nahdlatul Ulama, yang pengikutnya diyakini lebih banyak, berpendapat merokok itu makruh—tak berdosa kalau dilakukan, tapi berpahala bila ditinggalkan.
Meskipun belum final, ada dua fakta yang membuat fatwa Majelis Tarjih ini penting disorot. Pertama, pada 2005, Muhammadiyah memfatwakan merokok itu mubah—boleh dikerjakan, tapi ditinggalkan lebih baik—tapi kini ”naik pangkat” menjadi haram. Kedua, Muhammadiyah menerima dana dari lembaga luar negeri yang giat mengkampanyekan antirokok. Tentu saja perlu diterima suara pengurus Muhammadiyah yang membantah dua fakta tadi berkaitan. Tapi tetap perlu dikemukakan sebagai bahan bila ada kelompok masyarakat yang mempertimbangkan untuk mengikuti atau menolak fatwa itu.
Fatwa tak punya tempat di dalam hierarki ketentuan hukum kita. Kendati semangat fatwa Majelis Tarjih sejalan dengan program pemerintah melindungi masyarakat dari dampak buruk produk tembakau, fatwa tak bisa dijadikan acuan bertindak. Sayangnya, satu-satunya aturan hukum yang mengatur soal rokok, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ternyata belum lengkap. Bahkan undang-undang ini sempat ”bolong” setelah pasal 113 ayat 2 yang sudah disepakati pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat—tentang zat adiktif dalam rokok dan tembakau yang membuat pengguna ketagihan—sempat ”hilang” dalam proses akhir penyusunan. Banyak yang percaya kejadian ini menggambarkan betapa kuat keinginan pihak yang menolak peraturan ketat tentang rokok.
Apa boleh buat, terlihat jelas betapa ”mendua” sikap pemerintah dalam pembatasan tembakau dan rokok ini. Penerimaan cukai yang setahun mencapai sekitar Rp 60 triliun pasti menjadi alasan. Alotnya pembahasan rancangan peraturan pemerintah tentang pengendalian tembakau merupakan buktinya. Kementerian Kesehatan mengusulkan rokok tak boleh dijual eceran, tak boleh diiklankan di media apa pun, bahkan tak boleh dibagikan percuma meskipun sebatas promosi. Kementerian Perindustrian, Pertanian, dan Tenaga Kerja serta-merta menolak dengan merujuk pada tahap-tahap road map industri hasil tembakau yang pernah dibuat pemerintah. Pada tahap 2007-2010, menurut road map itu, pemerintah masih memberikan banyak kelonggaran pada ”industri asap” ini lantaran alasan penyerapan tenaga kerja.
Apa pun sikap pemerintah, penting sekali membuat aturan yang melindungi orang dari bahaya rokok. Bisa diterima pandangan bahwa merokok itu hak pribadi, tapi pemakaian hak itu tak boleh merugikan orang lain. Maka undang-undang pembatasan merokok di tempat umum merupakan kebutuhan mendesak. Peraturan daerah yang sudah berjalan di beberapa tempat, termasuk di Jakarta, terbukti tak ”bergigi” melindungi mereka yang tak merokok dari kepungan asap rokok.
Merokok—entah itu mubah, makruh, atau haram—tak boleh mencederai mereka yang tak melakukannya, terutama anak-anak kita.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo