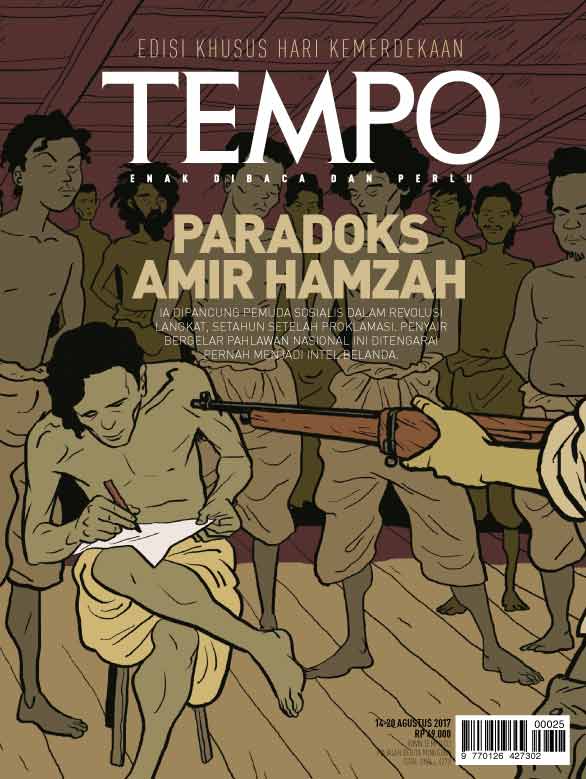Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PENGGUNAAN kata dalam berbahasa sering merupakan konsensus atau keumuman. Akibatnya, apa yang sudah menjadi umum menjadi "pelanggaran". Inilah yang disebut "salah kaprah", istilah dari bahasa Jawa yang bermakna kesalahan yang telanjur dipakai orang banyak dan dianggap tidak salah.
Salah satu salah kaprah mutakhir di zaman wabah media online adalah "meregang nyawa". Dua kata itu sering digunakan untuk menyebut orang yang mati karena kecelakaan atau tindak kejahatan. Makna asal "meregang nyawa" bukanlah mati. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikannya sebagai "hampir-hampir mati atau sekarat". Di laman yang sama ada juga istilah "meregang badan", yang diartikan dengan "bergerak-gerak badannya seperti orang yang akan meninggal".
Pengulangan pemakaian yang salah kaprah dan terus-menerus, setidaknya menurut makna logis awal, akan membentuk makna baru seperti dipakai oleh umum. Salah pun menjadi kaprah (meluas).
Pemakaian kata "pulang pergi" menjadi contoh salah kaprah yang sudah telanjur melekat. Secara logika seharusnya bukan kata "pulang" dulu, baru "pergi". Mungkin itu juga yang menyebabkan situs-situs online yang menawarkan fasilitas pembelian tiket pesawat, misalnya, tak menggunakan kata "pulang pergi" (atau yang tertib "pergi pulang"), tapi menulisnya dengan istilah round trip.
Salah kaprah yang sering terjadi ada di dalam dunia politik. Pada saat pemilihan Gubernur Jakarta, kata "sembako" digunakan untuk pemberitaan. Istilah ini dipakai seiring dengan pembagian paket-paket bahan makanan kepada calon pemilih, yang dipergoki pengawas ataupun pihak lawan. Orang yang menyebut kata "sembako" mungkin sudah melupakan kepanjangannya: sembilan bahan pokok.
Apakah paket-paket yang dibagi-bagikan itu berisi sembilan bahan pokok? Belum tentu. Paket itu bisa saja berisi beras, minyak goreng, gula, dan kopi atau teh. Banyak juga yang sudah lupa dan tak mau tahu arti sembilan bahan pokok. Apa pun yang dibagi-bagi menjelang pemilihan umum dimaknai sebagai "sembako" tanpa mempedulikan apakah isi paket tersebut memang terdiri atas sembilan bahan pokok. Bahkan, jika isinya sabun cuci atau sarung- yang tidak termasuk bahan pokok- tetap saja media online menyebutnya sebagai paket "sembako".
Istilah "sembako" sebetulnya menjadi penanda zaman. Di ujung kekuasaan rezim Soeharto, harga-harga bahan pokok melonjak karena krisis ekonomi. Untuk mengendalikan harga, pemerintah mengeluarkan keputusan buat menjaga kestabilan bahan-bahan pokok kebutuhan rakyat, yang berjumlah sembilan, yaitu (1) beras, sagu, jagung; (2) gula pasir, (3) sayur-sayuran dan buah-buahan, (4) daging sapi, ayam, atau ikan, (5) minyak goreng dan margarin, (6) susu, (7) telur, (8) minyak tanah atau elpiji, (9) garam beryodium dan bernatrium.
Apakah pemakaian salah kaprah "sembako" perlu diluruskan? Ada upaya pelurusan, seperti yang dilakukan Koran Tempo dengan menyebutnya pembagian "bahan pokok" untuk kasus menjelang pemilihan Gubernur Jakarta. Namun upaya ini jelas kalah deras dibanding "bagi-bagi sembako" yang sudah umum digunakan di media dan percakapan sehari-hari.
Di level negara, terjadi kesalahkaprahan dalam penamaan konsep trias politica, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif adalah serapan dari kata executive; legislatif dari legislative. Yudikatif memang diambil dari judicative. Tapi, dalam bahasa Inggris, judicative berarti having the power to judge (Merriam-Webster’s Dictionary). Maka, dalam bahasa Inggris, kata ini tidak digunakan dalam penamaan tiga pilar kekuasaan.
Bahasa Inggris menggunakan kata judicial, yang berarti cabang pemerintahan yang bertindak dalam urusan penegakan keadilan lewat hukum. Dalam kamus Merriam-Webster, lema judicial langsung diberi pranala compare executive, legislative. Jadi penamaan salah kaprah di negeri kita dengan yudikatif atau judikatif terjadi karena semacam penyamaan bunyi di akhir kata. Kalau mengacu ke asal bahasa serapannya, bahasa Inggris, semestinya eksekutif, legislatif, dan yudisial.
Negara sebenarnya juga menyerap istilah yudisial, yakni dalam penamaan Komisi Yudisial, lembaga tinggi negara pengawal etik peradilan. Sebenarnya ini menarik sebagai upaya pelurusan bahasa. Namun penyerapan kata yudisial di situ tak mengubah kebiasaan, bahkan dalam momen resmi, merangkaikan tiga pilar kekuasaan yang salah kaprah tapi lebih "bersajak", yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Berbahasa, seperti halnya dalam hidup sehari-hari, mungkin tak perlu radikal atau fundamentalis. "Fundamentalisme atau radikalisme bahasa" adalah kecenderungan yang mengacu pada logika yang lurus sesuai dengan kamus. Padahal tradisi penyerapan dan pemakaian kata dalam praktik sehari-hari bisa membias, menyimpang, lalu menjadi permanen meski berisiko salah kaprah. Maka lebih baik kita bersikap moderat, menganggap kesalahkaprahan itu hal yang wajar, asalkan jangan terlalu ngawur. WARTAWAN JAWA POS
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo