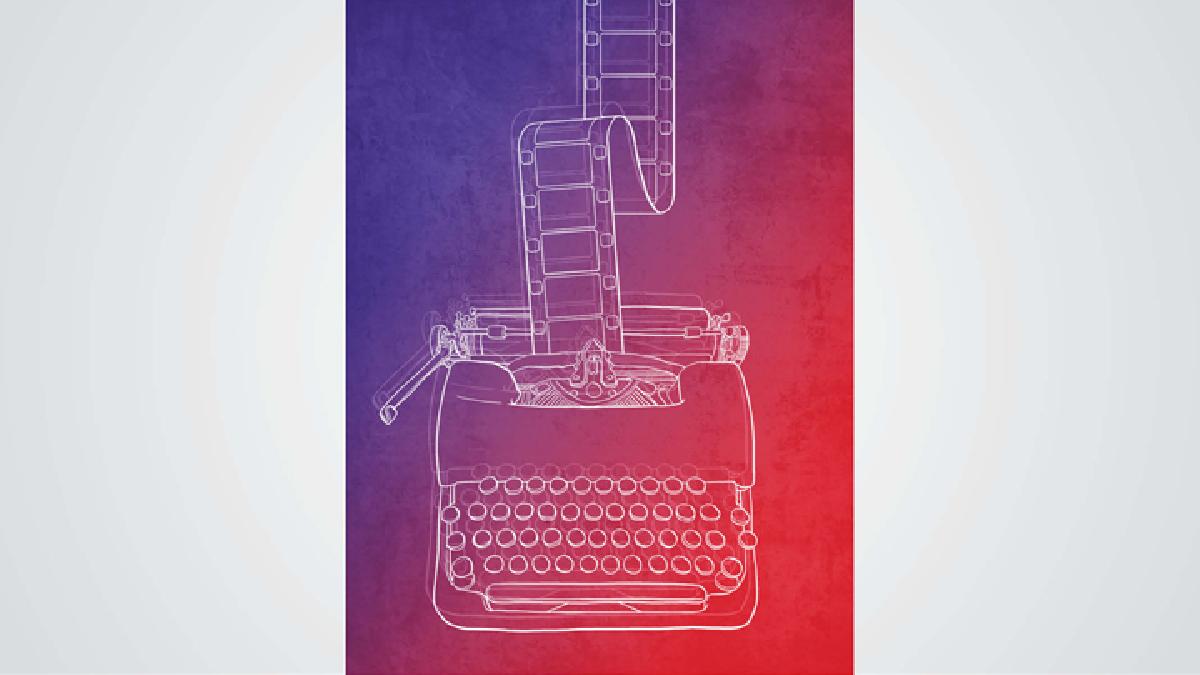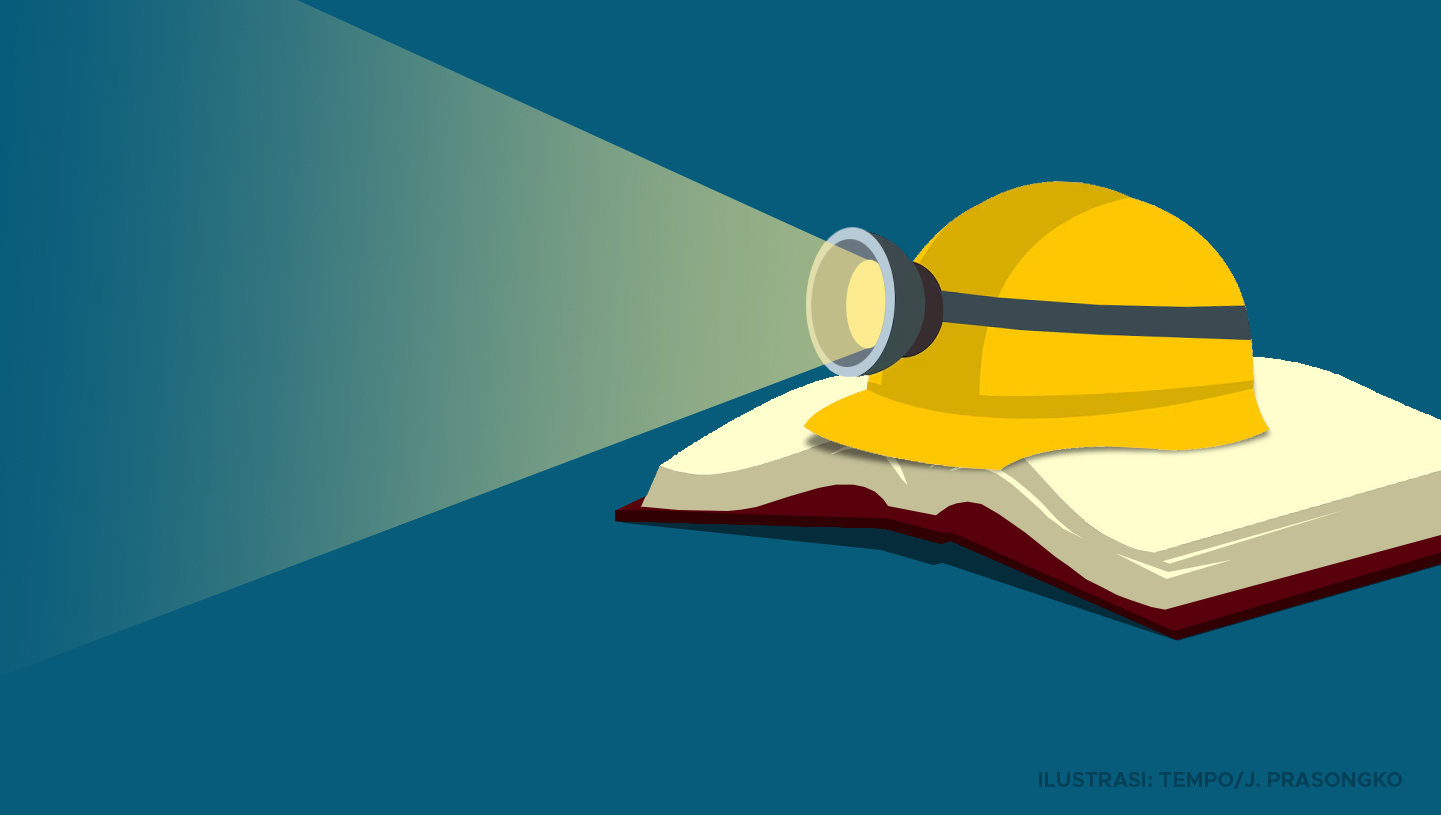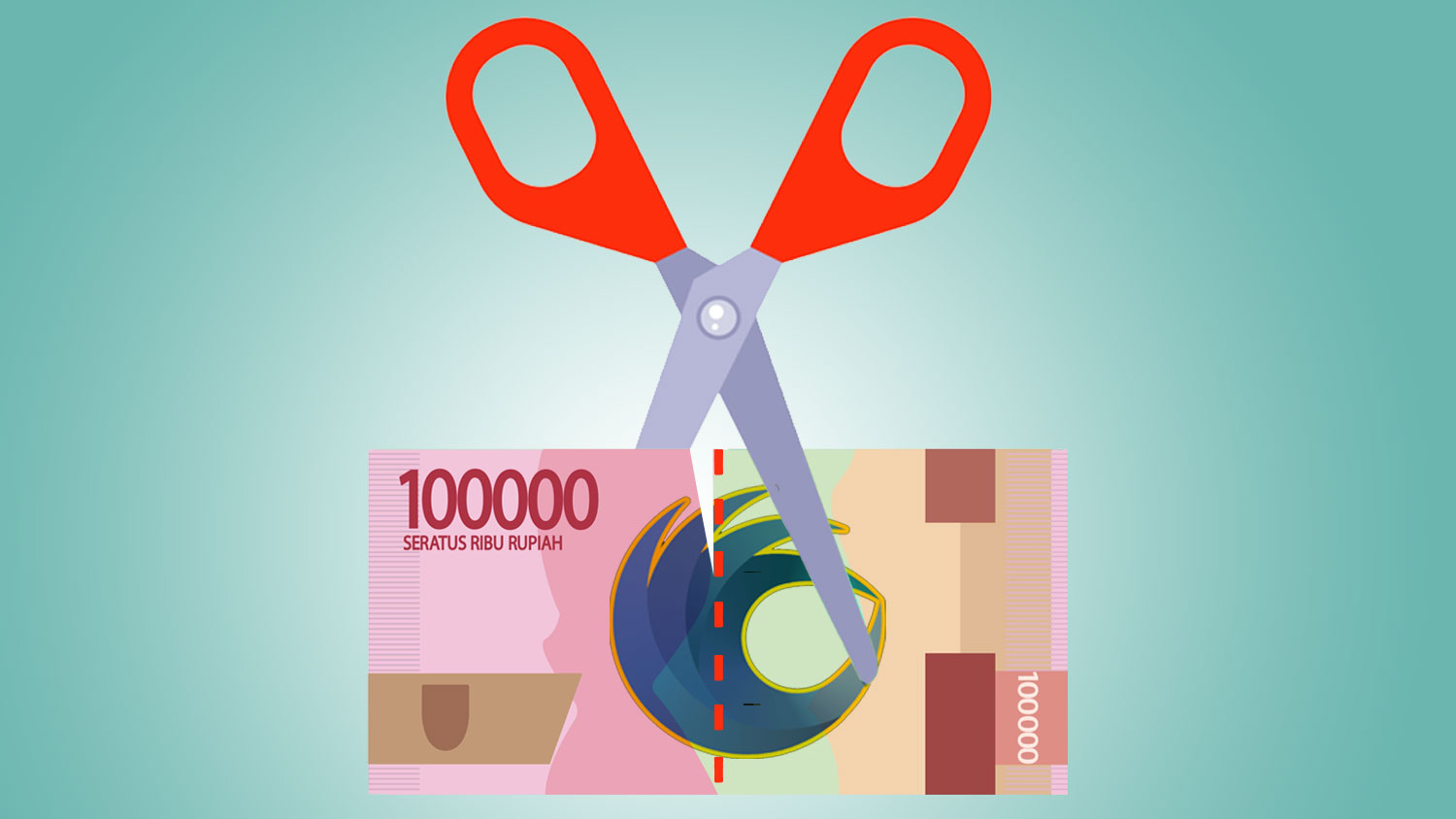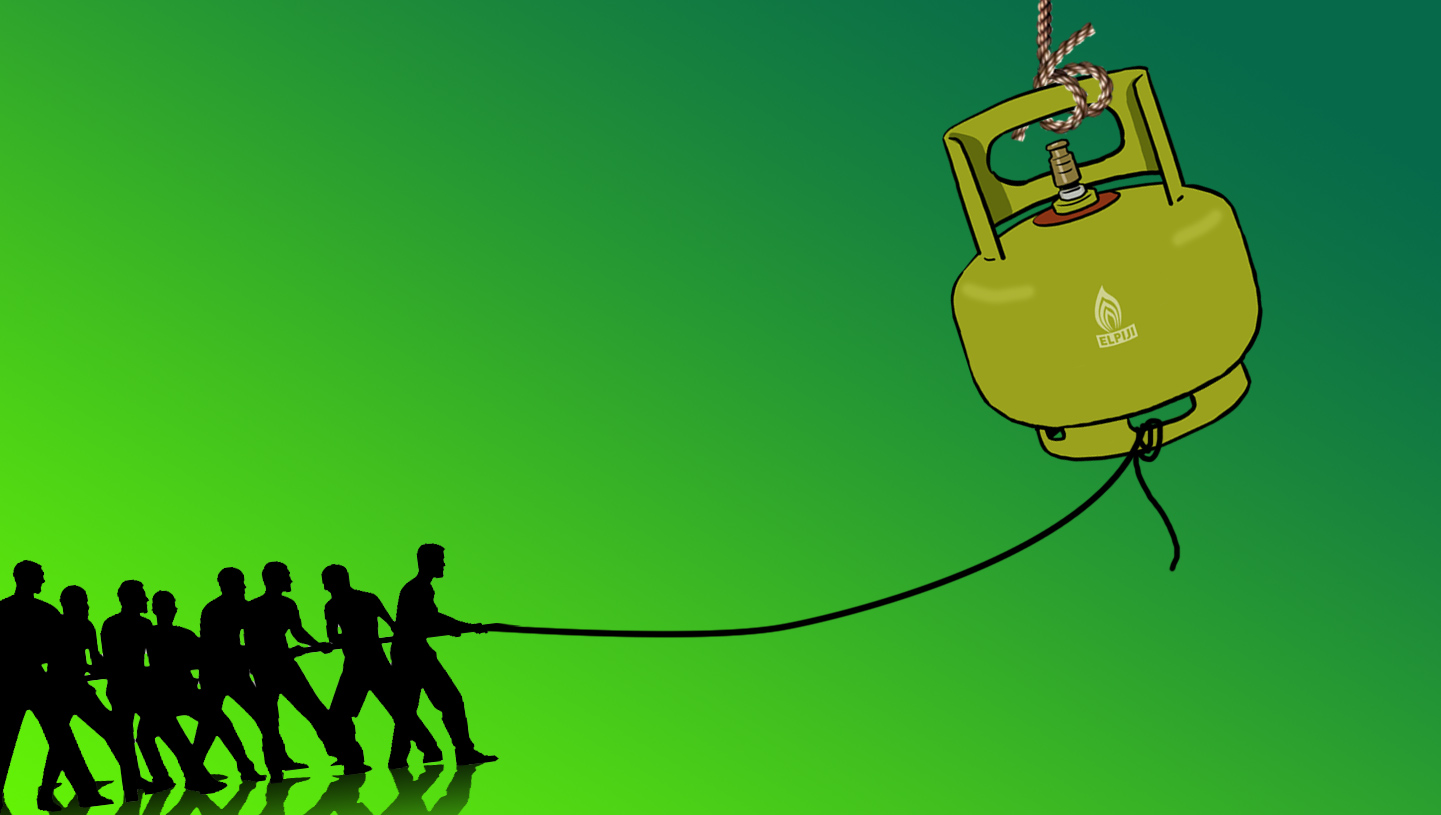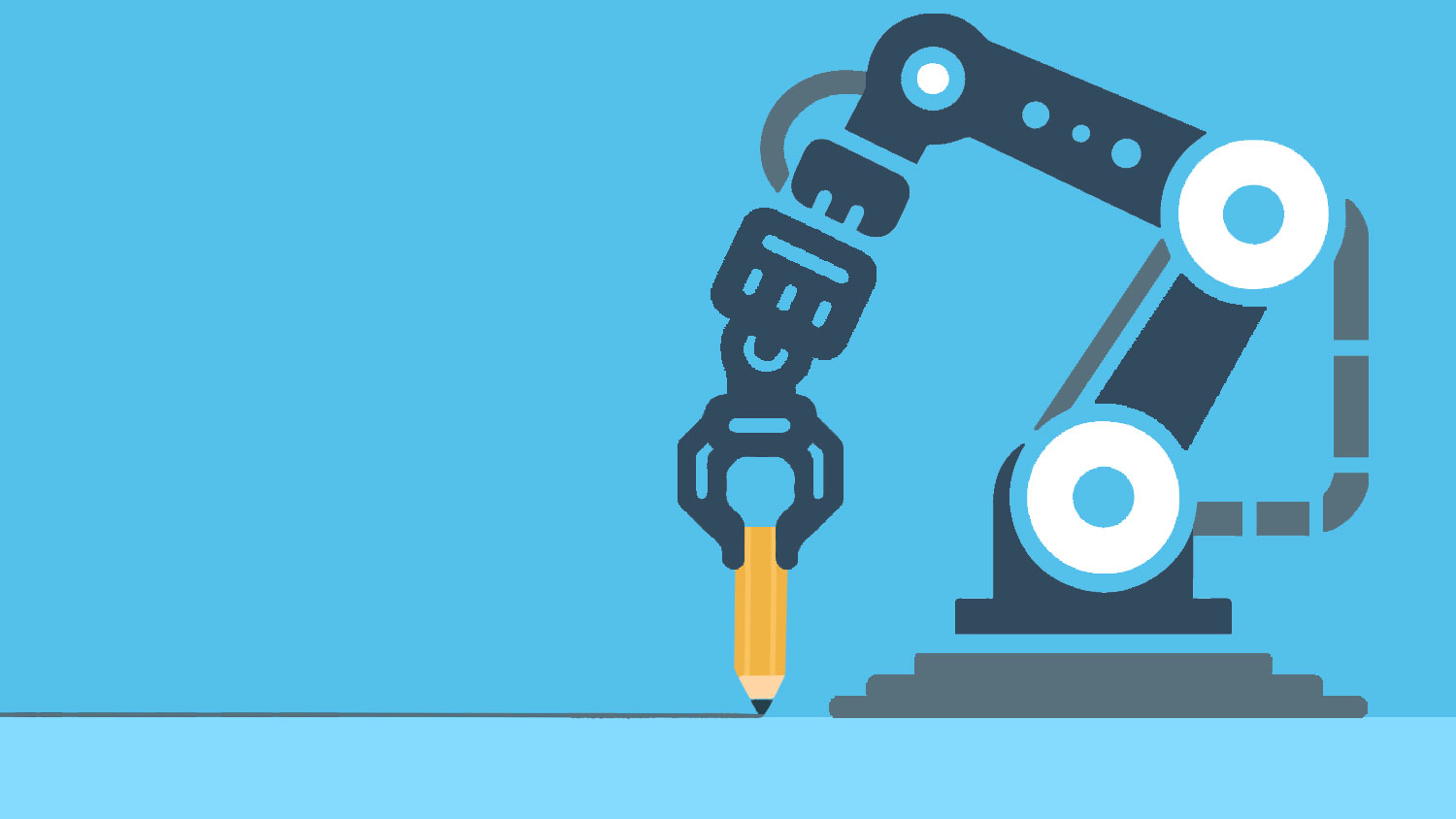Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Jagat sinema memang tidak bisa lepas dari politik, tapi setidaknya lewat film dunia bisa dilihat dari perspektif berbeda.
Syahdan, tersebutlah Juno, seorang penari lengger. Inilah seni tradisi asal Banyumas yang para penarinya adalah lelaki yang tampil seperti perempuan—campur aduk konsep maskulin dan feminin sekaligus. Lewat film Kucumbu Tubuh Indahku, sutradara Garin Nugroho mengangkat problem tubuh dan seksualitas transgender dengan berpusat pada tokoh Juno.
Dalam film itu, Juno dipertemukan dengan orang-orang yang membuat konsep seksualitas yang seharusnya alami menjadi begitu rumit. Garin memprotes sesuatu yang nifak di dalam masyarakat. Di tengah dikotomi identitas seksual yang cenderung hitam-putih, film ini membuka dialog tentang seksualitas dari sudut berbeda.
Dipersoalkan oleh kalangan yang ingin memurnikan agama, transgender sesungguhnya telah dikenal dalam budaya Indonesia sejak berabad silam. Di Bugis, Sulawesi Selatan, ada bissu, pendeta yang bukan laki-laki dan bukan perempuan. Mereka dipercaya sebagai separuh manusia dan separuh dewa serta bertindak sebagai penghubung di antara kedua dunia. Selain bissu, ada empat kategori gender lagi, yakni oroane (laki-laki), makunrai (perempuan), calalai (perempuan yang berpenampilan seperti laki-laki), dan calabai (laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan). Dalam masyarakat Bugis, semua gender itu diakui dan diperlakukan sederajat. Mereka yang menentang apalagi membatasi hak hidup kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dengan demikian dapat dikatakan berpikiran sempit dan ahistoris.
Festival Film Tempo (FFT) 2018 menetapkan Kucumbu sebagai film pilihan. Dimulai tahun lalu, FFT merupakan penghargaan tahunan yang cikal-bakalnya digagas sejak 2001. Kucumbu Tubuh Indahku—judul dalam bahasa Inggris terasa lebih puitis: Memories of My Body—pernah ditayangkan dalam Venice Biennale, Italia, dan mendapat Bisato d’Oro Award 2018 dari Venice Independent Film Critic.
Seperti Kucumbu, film lain yang dipilih dalam festival ini umumnya bersifat antihero. Para tokoh yang dikisahkan terluka dan tak sempurna: bukan mereka yang protagonis. Tokoh May dalam 27 Steps of May, misalnya, merupakan korban pemerkosaan yang mencari jalan untuk mengobati cedera batinnya. Diilhami peristiwa pemerkosaan 1998, film ini merupakan kisah personal tentang sang korban pasca-kejadian. Dalam FFT 2018, lewat 27 Steps of May, Rayya Makarim ditetapkan sebagai penulis skenario -pilihan.
Film lain, Love for Sale, menampilkan dunia sempit Richard Ahmad, bujangan 41 tahun. Kesibukannya hanya berjibaku di rumah dan usaha percetakan yang berada di lantai dasar rumahnya. Hidupnya monoton: ia malas bangun pagi, bekerja, lalu kembali ke rumah. Di rumahnya, tak ada keceriaan. Richard hanya berteman dengan Keloen, kura-kura peliharaannya.
Film ciamik, bintang berbakat bertabur, skenario yang kuat: semua tidak datang dengan sendirinya.
Pada 1990-an, ketika layar bioskop dipenuhi film roman picisan, Festival Film Indonesia dihentikan karena panitia tak mendapatkan nomine. Di tengah paceklik film, Garin Nugroho muncul sebagai pendobrak: ia membuat Cinta dalam Sepotong Roti, sebuah roman yang puitis. Pada dekade yang sama, Shanty Har-mayn mengambil peran dengan menggelar Jakarta International Film Festival (JiFFest)—ikhtiar untuk mengembalikan kegemaran publik menonton di bioskop.
Setelah itu adalah tumbuhnya pelbagai festival. Keriuhan ini harus dikembangkan. Seperti sepak bola yang makin bermutu jika banyak liga diseleng-garakan, film akan makin berkualitas jika festival disemarakkan—baik jumlah maupun mutu kurasinya. Dari kompetisi itu diharapkan lahir inovasi yang menggerakkan roda industri. Pemerintah bisa berperan dengan membuka jalan meluaskan produk-produk film dan karya seni lain. Badan Ekonomi Kreatif, yang sudah ber-ikhtiar menggerakkan industri film, harus mempertahankan upaya ini.
Di tengah terbatasnya sumber daya alam dan terseok-seoknya industri manufaktur, industri kreatif dapat menjadi alternatif. Korea dan India merupakan dua negara yang sukses menjadikan film sebagai komoditas ekonominya.
Tentu tak ada yang instan. Tapi setidaknya Indonesia tidak memulai dari nol. Pemerintah tidak pula sendiri: sejumlah inisiatif dalam mengembangkan industri sinema justru dimulai oleh orang ramai. Yang dibutuhkan kini upaya melapangkan jalan bagi sebanyak mungkin orang untuk masuk ke bidang ini. Juga memastikan terjaminnya kemerdekaan berpikir dan berkreasi—dua hal yang menjadi modal dasar kreativitas.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo