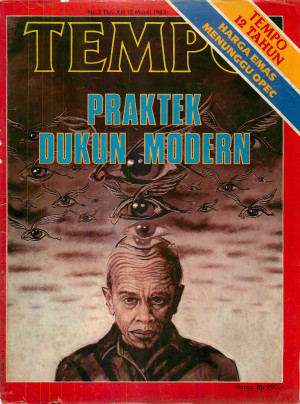(Di rumah seorang tokoh Islam puncak di Jakarta, di dinding
ruang tamu, tergantung ayat: 'Dan siapa yang berjuang di Jalan
Kami, Kami tunjukkan kepadanya berbagai jalan Kami'. Waktu itu
saya lalu teringat DI).
TIADA lagi Imam Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo. Di sebuah
gubuk tersembunyi, di hutan Gunung Rakutak yang gelap, "Presiden
Negara Islam Indonesia" ini terbaring sakit. Ia, demikian
dilaporkan, merasa amat lapar, sementara sang istri sudah
beberapa bulan terpisah, tak diketahui tempatnya sembunyi.
Waktu itulah, 3Junil962, ketika kegelapan magrib menutupi
hutan-hutan di seluruh Cicalengka, Letda Suhanda dari Bataliyon
328 Kujang memimpin penyergapan ke tempat itu. Tokoh berumur 57
tahun itu tertangkap - dengan luka bekas tembakan yang semakin
parah di kaki, dengan keris jimat Ki Dongkol terselip di
pinggangnya yang tua.
Tiada lagi Kartosuwirjo. Seberondong peluru, yang mengakhiri
hidupnya di Teluk Jakarta, September tahun itu juga, melenyapkan
bayangan terakhir "kegagahan Islam masa lampau". Tak ada lagi
prajurit yang mengacungkan bedil "atas nama Islam. Tanah air
tak akan lagi mengenal semacam tentara Paderi yang melawan
Belanda, membakar rumah adat dan "segala berltuk berhala". Tak
ada lagi bayangan para sahabat Nabi yang harus menghadapi
tantangan kafir dengan menghunjamkan tombak dari punggung kuda,
lalu bersujud di padang pasir. Tanah air yang lemah lembut ini,
dan Priangan yang indah, penuh tembang, manja, serta teledor,
menderita kehilangan yang tak disadari. Tak akan ada lagi
panji-panji di gunung-gunung. Yang ada akan hanya tinggal
Jaipongan.
'Dan siapa yang berjuang di Jalan Kami, Kami tunjukkan kepadanya
berbagai jalan Kami'.
Lihatlah keikhlasan imam ini. Keuntungan apa, yang diterima di
hutan, selain bayangan cita-cita? Berjalan dari pengejaran ke
pengejaran, dengan seluruh anak-bini dan bayi-bayi, sementara
rekan-rekan mereka hidup tenteram di rumah-rumah yang penuh
listrik, berlibur sambil menikmati hasil kemerdekaan?
Tapi tembakan pertama sudah meletus. Tembakan itu berdentuman
ketika pasukan Siliwangi, setelah pengungsian ke Yogya atas
perintah persetujuan Renville 1948, mengadakan perembesan
kembali ke Jawa Barat yang dahulu harus dikosongkan dan dikuasai
pasukan-pasukan Hibullah, Sabilillah dan balatentara lain
Kartosuwirjo yang menolak hijrah. Clash terjadi. Dan pada 7
Agustus 1949, diproklamasikannya 'Negara Islam Indonesia' di
Malangbong. Langkah tak boleh surut lagi.
Dan alangkah hebatnya langkah itu. Bataliyon 423 dan 426, kita
tahu, melakukan desersi. Bersama kelompok Islam garis keras di
Kebumen dan Tegal-Brebes di tahun 1952 mereka menggabung dengan
Kartosuwirjo. Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, yang oleh
faktor-faktor pribadi juga memberontak, tahun itu juga
menyatakan pula bergabung dengan sang imam. Juga Daud Beureueh
di Aceh di tahun 1953, yang kecewa kepada perlakuan Pusat
terhadap daerah ujung Sumatera yang dia pimpin.
Kartosuwirjo-lah imam itu. Dan 'NII'nya, seperti diumumkannya
sendiri, adalah kelanjutan RI yang "sudah tumbang dengan
Jatuhnya Yogya dan ditawannya Soekarno-Hatta" - meski Sjafruddin
Prawiranegara membentuk pemerintah darurat di Sumatera Barat.
Maka Jawa Barat bergolak. Tanah air bergolak. Tentara, yang
masih sanat muda, hanya dengan susah-payah bisa dipersatukan.
Pemberontakan PKI di Madiun, APRIS, RMS, para pejuang tercecer,
garonggarong (kemudian PRRI, permesta), mewarnai pertumbuhan
Republik yang muda. Bendera RI berkibar. Bendera komunis
sebentar berkibar. Bendera NII berkibar. Kiai-kiai disembelih di
Madiun. Musuh-musuh 'Tentara Islam Indonesia' disembelih di
tanah Sunda. Kabel telepon diputuskan. Kereta api digulingkan.
Gadis-gadis menanis. Anak-anak menjerit. (Dan Dedeh, oh Dedeh:
temanku di sekolah guru agama, pulang berlibur dari Yogya ke
Cicalengka, tanpa pernah sampai di rumah: mayat kaum laki-laki
bergeletakan di tengah jalan Priangan, sementara semua barang
dan perempuan diboyong hilang. Tak ada yang tahu oleh siapa, dan
ke mana). Hanya epi dan lengang. Dan demikianlah Priangan.
Seruling berkawan pantun
tangiskan derita orang priangan
selendang merah, merah darah
menurun di cikapundung
"Tengok dataran tanah priangan, gadisku manis"
Ayah dipaku di lima tempat
Bunda berlari dari tepi ke tepi
Tiada menemu teratak lengang
di bumi bayi turunnya
besar dibawa mengungsi
sepi bumi priangan sepi menghadapi mati )
Itulah, Imam, yang kemudian terjadi. Untuk apa? Bahkan Daud
Beureueh turun gunung, akhirnya. "Dahulu naik gunung karena
ijtihad, sekarang turun gunung karena ijtihad", pernah kudengar
sendiri dari mulutnya.
Tetapi ijtihad-mu rupanya tak sampai ke sana. Di tahun 1948
engkau bubarkan Masjumi, "partai betina" menurut pidatomu, di
Tasikmalaya. Bahkan sejak Agutus 1945 engkau kemukakan gagasan
negara Islam. Tapi tahukan engkau, Imam, mengapa Kiai Yusuf
Tadjiri dari Wanaraja menolak? Mengapa rakyat, kecuali mungkin
yang pernah punya kebanggaan pegang senjata, tidak bergeming?
Mengapa daerah para kiai seperti Jawa Timur, bahkan Sumatera
Barat, tidak menyambut?
Ketulusan tekad yang bagaimana yang ada dalam dirimu? Demam
kepemimpinan yang bagaimana? Kecintaan kepada anak buah yang
bagaimana? Megalomania yang bagaimana? Enkau, yang konon
sederhana dan bisa menarik simpati, dengan gerahammu yang kuat
dan sarafmu yang baja, yang hampir tak pernah mengenakan pakaian
seragam dengan bintang-bintang, meski di kalanganmu engkau
jenderal berbintang empat? Engkau, yang pernah bertapa 40 hari
di Gunung Kidul, yang meyakini diri sebagai keturunan Aria
Penangsang, dengan bayangan Ratu Adil alias Imam Mahdi dalam
matamu? Di bagian mana, Imam, Islam masuk dalam dirimu?
'Dan siapa yang berjuang di jalan Kami, Kami tunjukkan
kepada-Nya berbagai jalan Kami'.
Ini adalah sebuah diskusi yang terselip dalam catatan masa-masa
sekitar berdirinya Republik. Kartosuwirjo sendiri menceritakan,
keislaman dia antara lain didapat dari seorang kiai di Sidoarjo,
dekat Surabaya. Ia baru masuk PSII di tahun 1927, dan mendapat
tempat di hati Tjokro. Ia jelas berasal dari kalangan 'muslimin
pinggir', tokoh yang tumbuh sebagai muslim bukan lantaran asuhan
sejak bayi. Seperti juga Bung Karno dan banyak yang lain, mereka
bertemu Islam di jalan perjuangan. .
Ini adalah masa ketika nasionalisme, sosialisme, masalah imam,
negara Islam, pan-Islamisme, komunisme, Imam Mahdi, Ghulam
Ahmad, khalifah dunia Islam, diperbincangkan. Gelombang 'politik
Islam' Jamaluddin Afghani di akhir abad XIX, kejatuhan khilafat
Turki, Muktamar Mekah, seakan mencabut Islam dari kitab-kitab
tua di pondok-pondok pesantren, dan menyodorkannya sebagai pokok
perdebatan lapisan yang sama sekali baru.
Bahkan Tjokroaminoto pecah dari Muhammadiyah oleh soal 'sikap
politik Islam'. Bahkan Soekarno menulis 'Surat-surat dari Endeh'
kepada ulama A. Hassan di Ban dung. Bahkan Soekarno memesan De
Heilige Quran, sementara Tjokroaminoto menerjemahkannya dalam
perjalanan kapal menuju konperensi di Mekah. Dan Kartosuwirjo,
kemanakan Mas Marco Martodikromo yang wartawan 'kiri', pernah
empat tahun di Sekolah Dokter Jawa, dan adi pengurus Jong
Islamieten Bond, sekretaris Tjokroaminoto, dan salah satu dari -
menurut pengakuannya - 'Tiga Serangkai', bersama Soekarno dan
Scmaun, murid pemimpin pergerakan besar itu, berada di sana.
Betulkah Islam, yang jadi penggeraknya yang terutama?
Cara kiai di surau-surau dengan tenang tetap mengajar fiqh dan
memelihara akhlaq. Tapi ide 'negara Islam' justru lahir dari
generasi yang baru. Sebuah ilusi yang memunguti lambang-lambng
lama, praktis memilih hanya yang cocok, mengingkari
sangkut-pautnya yang kompleks dan mengundang debat, memberinya
bentuk dalam satu pengertian yang paling menggetarkan perasaan,
sebagai bekal 'berjuang'. Allahu Akbar! Dan peluru ditembakkan.
Tidak, bukan kerusuhan memang yang pertama dicanangkan dalam
pikiran. Sebuah lingkungan yang damai, perempuan berkudung dan
laki-laki sembahyang, mengedarkan zakat antar-sesama. Hanya saja
diberi baju terlalu gagah. Alangkah indahnya suara tembakan,
bagi para bekas pejuang - dan kemudian anak turunan. Alangkah
indahnya lambang, dan wadah formal, serta bendera, kekuasaan -
dan kepemimpinan.
Tidak, Imam. Anda hanya tak bisa tunduk kepada permainan
bersama. Anda hanya tak bisa mengalahkan diri sendiri dari segi
yang justru paling kecil - dan, menurut Nabi, yang paling berat.
Garis yang direntangkan toh akhirnya semu, bila yang di dalam
dan yang di luar praktis sama akhirnya. Istilah-istiah lama
toh akhirnya kehilangan makna, bila pengertian menalami
perjalanan wajar dan berubah perlahan-lahan.
Itulah, agaknya, mengapa Daud Beureueh turun gunung.
Tapi anda tidak.
Dan bekas-bekas anak buahmu pun sebagian, tampaknya, tidak.
Sebab alangkah indahnya hidup tualang. Sebuah gaya yang penuh
bahaya, "demi iman" - dan perampokan. Sebab degradasi memang
sangat pantas terjadi, Imam - dan pendangkalan, meskipun
bibitnya justru sudah kau tanam sejak permulaan. Barangkali kita
memang tak harus lagi punya prajurit Paderi: kita bukan lagi
Hindia Belanda, atau Afghanistan dan Palestina.
Kuda-kuda para sahabat Rasul makin menjauh juga, sementara dunia
yang dihasilkan seribu kuda terinjak-injak hanya lantaran samar
di dalam nama. Tapi anakanak ingusan itu? Imran, dan mereka yang
sangat mudah terangsang, yang jumlahnya dibesar-besarkan ?
Tidak, Imam. Ketika tembakan eksekusi memberondong tubuhmu di
Teluk Jakarta, September 1962, tak ada yang heran. Jiwa dari
Allah pulang kepada Allah, dan masing-masing amal dinilai
menurut niatnya. Sebuah babakan sudah harus berlalu. Dan bagai
bunga, tanah air menggeliat dan melemparkan kelopak kelahirannya
yang busuk. Yang sudah harus sirna.
'Dan siapa berjuang diJalan Kami, Kami
tunjukkan kepadanya jalan-jalan Kami.
sedang Allah bersama mereka yang baik
budi' (Q.29:69).
) Petihan sajak panjang Ramadhan KH, Priangn Si Jelita,
(1958), dengan urutan tidak setia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini