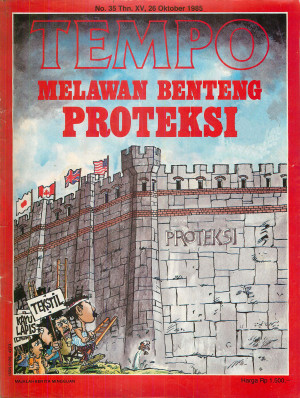SI miskin adalah tokoh sejarah dengan riwayat yang sangat panjang. Mungkin terlalu panjang. Ia ada sebelum para raja dinobatkan, dan ia tetap ada di zaman ini, sesudah para raja (kecuali di Arab Saudi dan di kartu bridge) berhenti berfungsi. Si miskin lahir, anehnya, bersamaan dengan lahirnya si kaya. Di masyarakat yang masih terbatas gerak naik-turunnya, di kalangan puak yang belum mengenal uang yang dimiliki sendiri dan barang yang diperjual-belikan, si miskin adalah tokoh cerita yang ganjil. Seorang antropolog pernah berbicara kepada seorang pribumi di Samoa tentang nasib orang miskin Kota London. Si Samoa takjub, "Bagaimana, ya? Tak punya makanan? Tak punya teman?" Ia tak bisa membayangkannya. Tapi justru karena si miskin bermula bersama dengan si kaya itulah kegelisahan timbul. Tiba-tiba tampak ada orang yang menderita, tertekan, dan bahkan tertindas di satu pihak, dan ada yang punya banyak previlese di lain pihak. Entah karena apa, simpati dan rasa belas kasih selalu dijuruskan kepada yang pertama, sejak dari zaman yang paling kuno. Seorang raja Sumeria, bernama Urukagina, yang berasal dari sebuah peradaban 3.000 tahun Sebelum Masehi, mungkin contoh tertua tentang compassion seorang manusia kepada si miskin. Dalam satu maklumatnya, ia tak memperbolehkan para pendeta agung "memasuki kebun seorang ibu yang papa dan mengambil kayu dari sana, atau meemetik buah dari sana". Sikap melindungi semacam itu biasanya datang dari yang berkuasa. Sikap lain, yang memihak kepada si miskin, adalah cercaan kepada pihak yang punya previlese. Sebelum Masehi, ada Nabi Amos di negeri Judea. Ia datang, dari dusun, ke pintu gerbang Kota Yerusalem. Suaranya menyeru. Kalimatnya penuh amarah kepada mereka, yang "hendak membeli orang lemah dengan sekian perak, orang miskin seharga sepasang kasut". Pidatonya penuh getar. Ia menyerang yang "menindas orang yang jujur", yang "menerima uang sogok", dan "mendesak orang miskin di pintu gerbang". Amos mungkin letupan protes sosial pertama yang tercatat dalam sejarah - lebih tua dari sajak-sajak Rendra dan lebih membakar dari film Matahari, Matahari Arifin C. Noer. Untungnya, Amos tak pernah disensor dan kata-katanya dapat dibaca di Perjanjian Lama, biarpun bagaikan api. Tapi, sejarah tak cuma mencatat api jika manusia berbicara tentang si miskin. Simpati kadang-kadang bisa turun lebih sejuk: ia berkembang jadi sikap menyatukan diri kepada pihak yang membangkitkan simpati. Di Jazirah Arab abad ke-7, ada Abu Dharr al-Ghifari. Salah satu sahabat Nabi ini - begitulah dikisahkan oleh Imam Bukhori - mencoba melaksanakan petuah Rasul yang luhur. Ia ingin memperlakukan para sahaya sebagai manusia sederajat, bahkan bersikap sama rata dengan mereka. Ia tak ragu untuk suatu ketika membagi kain kepada pembantunya sebanyak yang ia dapatkan sendiri. Abu Dharr, seperti halnya Santo Fransiskus dari Assisi di abad ke-13 dan Gandhi di abad ke-20, memang cenderung melihat si miskin sebagai pemegang kunci keselamatan. Bagi pandangan ini, kemiskinan bukan hal nista. Kemelaratan bahkan, sebagai pilihan yang sadar, suatu kebajikan. Dalam bentuk yang lebih lunak, gema semangat itu merupakan penolakan kepada "materialisme". Di tiap periode selalu saja ada orang yang tak hendak mempertaruhkan kebahagiaan dan harga dirinya pada hal yang aneh - misalnya pada merk mobil yang keren. Di depan benda-benda mentereng, ada yang merasa asing, ada saja yang merasa muak. Tapi menolak yang mentereng tentu saja tak selalu berarti menyucikan kemiskinan. Salah satu kritik terhadap Gandhi dan Abu Dharr dan Santo Fransiskus ialah: sikap hidup itu hanya cocok untuk orang suci - yang umumnya dipuja tapi sangat sulit diikuti. Kebanyakan orang, dan terutama si miskin sendiri, tak menyukai kemelaratan. Di tahun-tahun 60-an, mereka yang hidup bergelandang dan disebut hippies kebanyakan justru anak-anak Amerika yang berada, yang bosan, dan mencoba hidup di kaki lima, berpiknik dalam kemelaratan. Tentu saja dengan uang, nun jauh di sana, dalam bank. Tak heran bila para penganjur sosialisme, yang mengecam kelas borjuis yang kaya, pada dasarnya bukanlah guru-guru kehidupan asketik, yang menolak kemakmuran dan kemelimpahan. Dan pemerintah mana pun, di RRC atau di RI, di AS atau di US, bertahun-tahun sibuk memerangi kemiskinan - yang bagi mereka bukan suatu kemuliaan. Bahkan itulah riwayat kita. "Seluruh sejarah perekonomian," tulis seorang penyusun buku tentang perkembangan peradaban manusia, "adalah denyut jantung yang pelan dari tubuh organisme sosial". Ada systole dan diastole, berganti-ganti: sekali waktu kekayaan terpusat di satu kalangan, pada saat berikutnya kekayaan itu tersebar pecah lagi. Begitulah seterusnya. Terkadang, meletup suatu revolusi. Tentu, revolusi sering gagal atau sia-sia. Simiskin tak juga punah. Tapi adakah itu berarti simpati kepadanya hanya seuntai petai kosong - saya kira kita tahu apa jawabnya. Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini