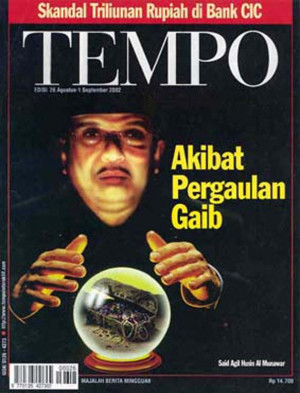JIKA filsafat hanya dimulai dengan kepala yang jernih, kenapa Sokrates menjadi penting di tahun-tahun kemerosotan Athena? Jawabnya karena orang berpikir bukan saja karena otak yang cemerlang, tapi karena tulang kering yang sakit. Ketika sebuah negeri yang demokratis kalah oleh sebuah Sparta yang militeristis, mau tak mau ratusan pertanyaan pun muncul. Apa artinya kebebasan, sebenarnya? Apa artinya kekuasaan? Apa artinya "kuat" dan "lemah"?
Pada tahun 404 sebelum Masehi itu, ketika Athena akhirnya menyerah, perang yang terjadi sebenarnya bukan perang yang mudah bagi Sparta. Selama sepuluh tahun, seraya dirundung krisis, Athena mampu bertahan—sebuah bukti ketangguhan demokrasi sebenarnya. Tapi Sparta menunjukkan bahwa demokrasi cuma sebuah hiruk-pikuk; yang menang adalah yang kuat, dan yang kuat adalah yang mampu membangun regimentasi masyarakat, dalam kesiagaan dan disiplin seperti sebuah barak tentara. Maka tak mengherankan bila setelah Athena kalah, demokrasi dihapuskan di negeri itu. Oligarki pun ditegakkan dengan dukungan sang penakluk.
Tapi krisis tak selesai. Para penguasa baru—leluasa dari keharusan memperbincangkan keputusan politik di sebuah majelis—punya kans untuk menyita harta para saudagar yang tak mereka sukai, merampok kuil-kuil, mengirim 5.000 kaum demokrat ke pembuangan, dan membunuh 1.500 yang lain. Kegilaan seperti itu tak berumur lama. Pada tahun 403 SM, perlawanan dari bawah berhasil, dan oligarki pun digantikan oleh demokrasi.
Yang menarik ialah bahwa para penguasa demokrasi yang menang inilah yang empat tahun kemudian menghukum mati Sokrates. Ada yang mengatakan bahwa hal ini dilakukan oleh karena Anytus, pemimpin kaum demokrat, menganggap Sokrates telah meracuni anak kandungnya, seorang pemuda yang kemudian hidup dengan sikap skeptis, tak menghormati lagi orang tua dan para dewa. Juga Anytus tahu Sokrates tak menyukai demokrasi. Demokrasi mengandalkan demos, orang ramai yang memang, sebagai massa, bukan sebuah kekuatan untuk berpikir, melainkan kekuatan untuk mendesak. Sokrates tentu saja melupakan bahwa di setiap pertanyaan filsafat sebenarnya membayang sebuah desakan—yang melahirkan dan dilahirkan oleh kerisauan orang banyak. Tapi Anytus juga melupakan bahwa sikap skeptis tak berhenti pada tahun 399 SM. Ia juga tak menyadari bahwa anaknya bukanlah satu-satunya yang jadi menyeleweng karena Sokrates dan rangkaian pertanyaannya.
Ketika Sokrates meninggal karena dihukum meminum racun, Plato berumur 30 tahun. Orang muda yang tampan dan agak tambun ini pandai dalam matematika serta puisi. Ia sebenarnya punya kesempatan untuk memilih karir dalam politik. Garis keturunan ayah dan ibunya, para aristokrat, membuka pintu ke sana, dan sebagai warga ia pernah membuktikan diri menjadi prajurit yang berani dalam tiga peperangan. Tapi pada umur 20 tahun, ia bertemu dengan seorang tua bertampang buruk yang bernama Sokrates, teman dari pamannya, Charmides. Sokrates tidak menawarkan apa-apa selain kemuskilan yang lazim disebut sebagai filsafat. Plato pun memutuskan untuk mengikuti orang yang tak suka bersandal atau bersepatu ini. Hampir dua setengah millennia kemudian kita tahu bahwa keputusan itulah yang menyebabkan dunia mempunyai seorang pendahulu filsafat yang tak ada bandingannya.
Plato juga yang merawat kenangan tentang Sokrates. Bagaimanapun, ada yang memikat pada diri laki-laki berbibir tebal dan berhidung lebar yang lahir sebagai anak pemahat ini. Ia arif dan baik budi, tapi yang penting ialah bahwa ia telah menyebabkan hidup anak-anak muda seperti Plato mempunyai makna. Baginya, begitulah kata-katanya yang termasyhur, "Sebuah kehidupan yang tak diamati dan direnungkan tidaklah berharga bagi seorang manusia." Maka setiap kali ia akan bersoal-jawab mengenai apa yang menyangkut hidup. Ia akan mempersoalkan apa yang alim, apa yang tak alim, apa yang adil, apa yang tak adil, apa yang sehat, dan apa yang gila, apa keberanian, apa pula kepengecutan, apa kodrat pemerintahan atas manusia, dan apa pula kualitas serta keterampilan memerintah. Ia akan bangun pagi-pagi dan berangkat ke pekan, ke gimnasium, ke palaestra, ke bengkel para tukang, dan entah apa lagi. "Bukankah jalan menuju ke Athena dibuat untuk tempat bercakap-cakap?" tanyanya.
Jalanan sebagai tempat mengamati dan merenungkan kehidupan—saya kira itu yang membuktikan bahwa Sokrates, yang tak menyukai demokrasi, menjalankan cara berfilsafat yang sebenarnya bertolak dari sejarah yang melahirkan demokrasi: tulang kering yang sakit terpacak di permukaan bumi. Sebab itulah saya teringat akan Sokrates ketika saya melihat sesuatu yang luar biasa: pekan lalu, di Jakarta, di ruang yang sederhana di Teater Utan Kayu, lebih dari seratus anak muda, berusia 25 sampai 35 tahun, berjejal dan bertahan duduk di lantai selama tiga jam untuk mendengarkan ulasan tentang Ibn Rush atau Habermas, filsafat, setiap malam, selama tiga hari berturut-turut.
Tentu Indonesia kini bukan sebuah Athena, juga bukan sebuah negeri yang kalah perang. Tapi ia, seperti Athena, sebuah negeri yang mencoba mengembalikan kemerdekaan bersuara dan berpikir, sementara krisis dan perasaan sedang-runtuh merundungnya. Maka ia pun menjadi sebuah negeri 220 juta pertanyaan. Apakah yang adil dan yang tak adil? Apa artinya kebebasan, sebenarnya? Apa artinya kekuasaan? Apa artinya "kuat" dan "lemah"? Benarkah Tuhan berperan dalam persoalan ini?
Tapi pertanyaan seperti itu adalah sesuatu yang mengandung kepedulian dan kecerdasan. Maka sebuah bangsa jangan-jangan menyembunyikan harapan sebenarnya ketika justru di tengah krisis, anak-anak muda masih berani bertanya dan mencari jawab. Sebab di perjalanan yang rumit itu, mereka umumnya, gagal ataupun berhasil, akan tumbuh dalam kearifan, dan maju dalam kematangan.
Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini