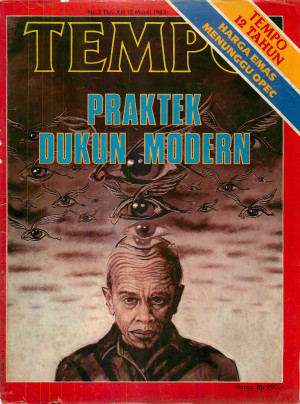"SOSIALISME telah mati!", seru lelaki tampan berambut hitam
panjang menggelombang itu.
Dalam umur 35 tahun, Bernard-Henri Levy memang jadi termayshur
karena dua hal: wajahnya yang fotogenik dan pikirannya yang
sarat polemik. Dia suka mengenakan celana karduroi dan berkemeja
dengan lengan digulung. Dia menulis buku filsafat yang laris dan
diserang atau dipuji selama enam tahun.
Para pengagumnya menobatkannya sebagai pangeran filsafat Prancis
sekarang, setelah Sang Raja, Jean-Paul Sartre, wafat. Para
pengkritiknya mencemoohkannya sebagai tukang putar piringan
hitam di tempat ajojing ide-ide.
Bagaimanapun juga, Levy tokoh yang menarik. Pemuda ini tak cuma
lulusan sekolah termasyhur I'Ecole Norrnale Superieure, tempat
dia belajar di bawah filosof Marxis terkemuka Louis Althussen.
Di tahun 1968 ia ikut aktif berdemonstrasi menyerukan revolusi.
Tapi pelan-pelan, tapi pasti, pandangannya berubah ....
Sebenarnya aneh juga dia demikian ramai dielu-elukan bagaikan
seorang penemu ide baru. Perpindahannya dari Marxisme menjadi
anti-Marxisme tidaklah sedahsyat perpindahan sejumlah
intelektuil Eropa lain dua serta tiga dasawarsa yang lalu. Dia
tak pernah mencium lantai penjara dan mendengar sejumlah kenalan
ditembak atas nama Sejarah dan Proletariat. Dia tidak seperti
Arthur Koestler yang pekan lalu meninggal: sastrawan yang pernah
bertempur untuk kaum kiri Spanyol tapi kemudian tahu sejumlah
orang dibersihkan dalam gelap Kota Kremlin.
Bernard-Henri Levy, dengan kata lain, hidup lebih dekat pada
mawar. Memang orang patut curiga bahwa satu-satunya alasan dia
dijulang-julang oleh pers Barat kini ialah karena dia sexy. Dulu
kiri adalah sexy. Kini si antikiri juga bisa sexy.
Namun mungkin juga ada sebab yang tak kalah serius di hari ini
untuk kecewa kepada radikalisme kaum Marxis. Vietnam menyebabkan
ribuan "orang perahu". Pol Pot membunuh lebih seram dari
Stalin. Di Cina Komunis darah memang tak banyak tumpah, namun
Nyonya Mao yang memekikan revolusi toh ternyata menylmpan
koleksi pribadi film Greta Garbo di salah satu rumah mewahnya
....
Revolusi meragukan, bukan karena ongkosnya, tapi karena
hasilnya. Negeri-negeri sosiais kini identik dengan negeri para
birokrat. Gagasan besar dan orisinil tak lahir dari dalamnya.
Marxisme melarang. "Marxisme," kata Levy kepada The Christian
Science Monitor 20 Januari 1983, "adalah seorang polisi di tiap
kepala orang yang tertindas."
Masalahnya kemudian, apakah dengan demikian sosialisme harus
masuk kotak. Artinya manusia yang menyerukan setiakawan adalah
palsu dan keserakahan halal karena lumrah?
Kita, di Indonesia, tidak mudah buat menjawab. Manusia memang
bukan semuanya pertapa yang mencari kemurnian. Hidup penuh
dengan kompromi juga dengan kebendaan. Tapi jika sosialisme
masuk kotak, kita mungkin tak punya lagi gambaran yang lebih
menggembirakan tentang manusia, tentang diri sendiri. Sosialisme
memang sering mengecewakan. Tapi ia tetap bisa memberi makna di
tengah garis yang kusut dan muram dari sejarah.
Kira-kira 40 tahun yang lalu Arthur Koestler menulis satu esei
tentang perlunya sintesis antara sang yogi yang suci dan sang
komisar yang memimpin perubahan: satu alternatif agar kaum
revolusioner tak jatuh dalam godaan kekuasaan baru. Dia tak tahu
apakah sintesis itu bisa tercapai. Mungkin dia mimpi. Tapi dia
berkata bahwa jika tidak, di mana lagi harapan?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini