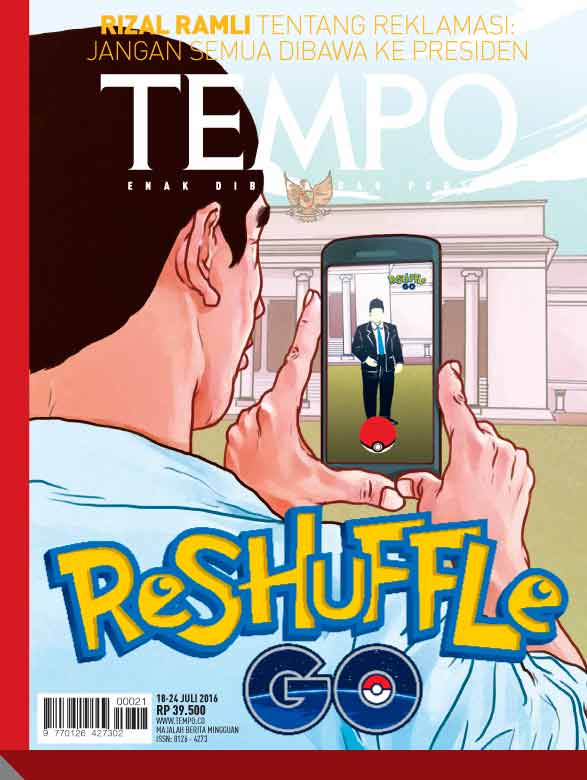Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Iblis, menurut Rumi, memberikan sebuah petuah—dan agaknya penting bagi percakapan manusia. "Orang yang berpikiran buruk tak akan dengarkan kebenaran meskipun dihadapkan pada seratus tanda-tanda."
Iblis, dalam pandangan seorang sufi seperti Rumi, bukan makhluk yang negatif, dan dalam hal ini kata-katanya meyakinkan: salah satu kegagalan yang berulang dalam sejarah adalah kegagalan mendengarkan. Tanda, kata, isyarat yang mengantar ke kebenaran ternyata tetap saja tak membuat orang berubah jadi mengerti. Dan itu berlaku sampai abad ini. Kini para psikolog berbicara tentang cognitive dissonance.
Gejala "sumbang" dalam pemahaman itu tak serta-merta karena "pikiran buruk". Seorang perokok berat berulang kali membaca ulasan tentang bahaya nikotin, berulang kali melihat gambar paru-paru manusia yang digerogoti kanker, tapi ia terus saja mengisap tembakau. Ia tahu bahaya itu. Ia sebenarnya terusik. Ia mengalami cognitive dissonance. Ada yang tak konsisten antara apa yang dimengertinya dan apa yang dilakukannya. Tapi alih-alih mengubah tindakannya, ia menciptakan konsistensi dalam dirinya dengan mengikuti informasi lain yang cocok dengan keinginannya terus merokok. Ia ingin harmoni terbentuk kembali. Informasi ("tanda-tanda") yang sebenarnya bisa mengubahnya terbentur tembok, sia-sia.
Dalam interaksi antarmanusia, kesia-siaan itu telah menambah bagian yang suram, bahkan menakutkan, dalam sejarah. Berabad-abad orang tak mau ada yang sumbang dalam dirinya, ada konflik antara pengetahuannya yang baru dan keyakinannya yang semula. Maka mereka pun berpegang teguh pada idée fixe mereka. Stereotipe tentang liyan, misalnya, terus bertahan: orang hitam tolol, orang putih bejat, orang kuning culas, orang cokelat malas, perempuan tak rasional, laki-laki misoginis. Bahkan sampai di abad ke-21, laki-laki pirang pucat yang kini jadi Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson, mengaitkan orang Papua Nugini dengan "kanibalisme" dan menyebut orang Afrika piccaninnies, ejekan buat anak-anak kulit hitam.
Beratus buku pernah ditulis, berpuluh film dibuat, berbentuk fiksi atau reportase, yang menunjukkan bahwa dunia amat kompleks dan manusia sering berbeda secara tak disangka-sangka. Hari ini seharusnya orang tahu bahwa tiap stereotipe adalah bentuk yang dimencongkan. Tapi seperti dikatakan Iblis dalam versi Rumi, "Ketika kepada orang yang berkhayal dikemukakan nalar, khayalnya justru bertambah." Dan ketika nalar gagal meluruskan khayal buruk tentang liyan, bukan hanya salah paham yang terjadi; kebencian dan penghancuran menyusul.
Mungkin aneh, mungkin tidak, tapi merisaukan: ada yang mengatakan, kini kita dibentuk tsunami informasi yang selalu baru dan berubah, tapi manusia mengatasi cognitive dissonance-nya dengan nalar yang lain, bukan nalar yang mencari dan memverifikasi. Agama, lengkap dengan kecenderungan dogmatisnya, tampak kian tegar bahkan di universitas-universitas di Indonesia, ruang yang dulu dibangun untuk melatih pengetahuan empiris dan penalaran. Sementara itu, di media sosial yang diciptakan teknologi mutakhir, "khayal" jenis lain berkecamuk: dugaan-dugaan yang ganjil, fitnah yang liar, dan teori konspirasi yang paling absurd.
Apa yang dicapai manusia, sebenarnya, sejak percakapan dimulai? Sejak orang mencoba bertukar-pikiran, sejak data dan fakta dicari, dihimpun dan disusun, sejak pengetahuan empiris menggantikan pengetahuan spekulatif, sejak takhayul diusir dari argumen?
Lebih dari satu dasawarsa yang lalu Bush di Amerika Serikat dan Blair di Inggris memutuskan untuk menyerbu Irak, untuk melucuti Saddam Hussein dari "senjata pemusnah massal". Lebih dari satu dasawarsa yang lalu pelbagai sumber meragukan adanya senjata itu—dan inspeksi resmi bahkan membantah informasi itu. Tapi Bush dan Blair tak hendak mendengarkan. Tentu ada sesuatu yang bukan sekadar alasan psikologis dalam penolakan itu; kepentingan-kepentingan imperialisme pasti jadi dasarnya. Tapi tampak pula bahwa ada nalar lain yang membuat "kebenaran" tak hendak bergerak dari posisi yang beku.
Kini dunia pemikiran tak yakin lagi ada jaminan dari sebuah pusat, dari sebuah fondasi, untuk menentukan "kebenaran". Kini agama jadi demikian sektarian dan egosentris, hingga tak punya wibawa untuk jadi dasar universal. Kini ilmu-ilmu makin jelas hanya menjawab sebagian pertanyaan kehidupan. Apa selanjutnya? Sebaiknyakah percakapan terhenti dan jawaban yang terbaik adalah, seperti pesan Iblis dalam Masnawi Rumi, "diam dan damai"?
Saya ingin jawab: jangan. Saya ingin jawab: selalu ada celah dan saat ketika kebenaran masuk. Tapi kita memang lebih dulu harus berangkat dari sebuah awal, dari "diam dan damai".
Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo