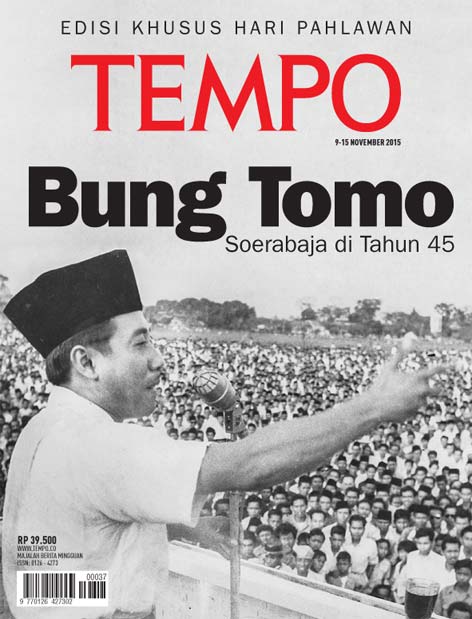Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
NEGARA tak boleh diberi ruang sekecil apa pun untuk mengatur arus opini dan ekspresi masyarakat. Kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat ini dijamin penuh konstitusi. Maka, kalaupun harus diterbitkan, Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang penanganan ujaran kebencian atau hate speech, yang diteken pada 8 Oktober lalu, semestinya mengacu pada prinsip utama demokrasi.
Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti menegaskan surat edaran itu justru untuk memperjelas perbedaan antara ujaran kebencian dan kebebasan berekspresi. Ujaran kebencian yang dimaksud adalah segala tindakan yang mengarah pada perusakan, penghasutan, dan kekerasan. Kalau benar demikian nawaitunya, gagasan ini patut diapresiasi. Garis batasnya jelas. Negara wajib menerapkan asas zero tolerance pada tindakan ujaran kebencian seperti di negara lain.
Namun isi surat ini malah mengaburkan garis pembeda kedua perbuatan tersebut. Definisi ujaran kebencian ternyata terlalu luas. Dicantumkannya pasal pencemaran nama baik (defamation law), perbuatan tidak menyenangkan, bahkan penistaan sebagaimana diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan perundangan lainnya justru bisa kontraproduktif. Hate speech law dan defamation law jelas dua perkara berbeda, tak boleh dicampur aduk. Dirujuknya pasal-pasal karet seperti defamation law tersebut sungguh berbahaya.
Surat ini merupakan petunjuk teknis kepolisian dan tak boleh dijadikan alat pemidanaan. Tapi bisa saja disalahgunakan untuk mengkriminalisasi individu dan kelompok masyarakat yang kritis, termasuk mencibir penguasa. Kalau edaran ini lantas dijadikan acuan polisi untuk membungkam dan menjerat mereka, niscaya kita akan kembali ke zaman kegelapan. Kebebasan berpendapat kembali dikebiri seperti di era Orde Lama dan Orde Baru. Banyak penindakan hukum memakai pasal karet ini.
Susah dimungkiri bahwa surat Kapolri ini merupakan reaksi terhadap maraknya fenomena media sosial seperti Twitter dan Facebook, yang bisa berwajah ganda. Selain dimanfaatkan untuk membangun jaringan pertemanan dan berbagi informasi, yang tentunya positif, juga bisa untuk ajang provokasi dan hate speech untuk memicu kekerasan terhadap individu maupun kelompok. Isunya tentunya berkaitan dengan aspek ras, etnis, agama, gender, difabilitas, dan orientasi seksual.
Namun sisi positifnya jauh lebih banyak. Media sosial mampu melakukan perubahan besar menuju keadaan yang lebih baik, seperti revolusi "Arab Spring" di Timur Tengah, dan revolusi payung di Hong Kong. Bisa juga dijadikan media kampanye politik ampuh sehingga Amerika Serikat memilih BarackObama, presiden berkulit hitam pertama. Bahkan diyakini sebagai media yang sukses mengantarJoko Widodo, "tukang mebel" dari Solo, menjadi presiden.
Surat edaran ini tak boleh dijadikan spirit menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap kepala negara yang sudah dikubur Mahkamah Konstitusi pada 2006. Kendati tak spesifik ditujukan untuk memproteksi presiden dan wakilnya, kelahirannya sulit untuk tidak dikaitkan dengan banyaknya ancaman penghinaan dan fitnah terhadap Presiden Jokowi, khususnya di media sosial. Apalagi pemerintah sejauh ini belum berhasil memasukkan pasal penghinaan presiden ke dalam Rancangan Undang-Undang KUHP.
Pemerintah harus menjamin hak-hak konstitusional warga negara, terutama hak berekspresi dan berpendapat. Ini penting ditekankan lantaran pemaknaan terhadap ujaran kebencian itu bisa sangat subyektif. Langkah menghidupkan kembali pasal pelarangan penghinaan itu hanya akan merusak reputasi pemerintahan Jokowi dan membahayakan keberlangsungan demokrasi di negeri ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo