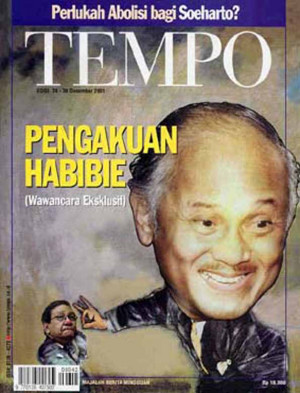Raden Pardede *)
*) Kepala Riset Danareksa
SECARA umum dapat digambarkan bahwa kondisi moneter tahun 2001 hampir tidak berubah banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Contohnya adalah pertumbuhan uang primer, yang menjadi sasaran operasional Bank Indonesia. Pada tahun 2001, pertumbuhan uang primer tidak auh berbeda dengan pertumbuhan pada tahun 2000. Operasi pasar terbuka terus-menerus dilakukan secara berkala dalam rangka mencoba menjaga agar sasaran operasional BI tersebut dapat dicapai, yang selanjutnya diharapkan dapat mencapai sasaran akhir BI, yaitu laju inflasi yang terjaga.
Kenyataannya, sasaran operasional hampir tidak pernah dicapai sepanjang tahun, demikian pula sasaran akhir. Operasi pasar terbuka lewat pelelangan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dalam rangka menjaga pertumbuhan uang primer ternyata bukan hanya tidak sanggup menyerap likuiditas, tapi juga menyebabkan kenaikan suku bunga SBI. Terbukti, sampai November 2001, pertumbuhan uang primer adalah 21 persen. Ini jauh di atas target BI, sebesar rata-rata 12 persen. Dan target inflasi pun telah dan akan jauh terlampaui karena hingga November 2001 saja angka inflasi sudah mencapai 10,8 persen, sedangkan target inflasi hanya 9 persen sepanjang tahun. Diperkirakan inflasi tahun 2001 akan melewati angka 12 persen. Yang lebih menyesakkan adalah suku bunga SBI yang terus-menerus naik hingga mencapai 17,63 persen pada 5 Desember 2001. Bandingkan dengan 14,41 persen di awal 2001.
Tren suku bunga yang cenderung menaik sebagai konsekuensi dari penyerapan likuiditas di pasar secara terus-menerus sangat bertolak belakang dengan tren suku bunga di hampir semua negara di dunia, yang cenderung menurun. Kenyataan ini lebih jelas sesudah perekonomian dunia mengalami perlambatan pertumbuhan yang sangat drastis, apalagi sesudah peristiwa World Trade Center pada September lalu. Hampir semua bank sentral menurunkan suku bunga—kecuali Bank Indonesia.
Hal itu pulalah yang menjadi bahan perdebatan hangat hampir sepanjang tahun 2001. Banyak pihak, terutama para pelaku bisnis dan para analis, mengkritik kebijakan yang mengakibatkan kenaikan suku bunga itu. Kritik tersebut sebagian besar ditujukan bukan hanya ke BI, tapi bahkan juga kepada Dana Moneter Internasional (IMF) sebagai institusi yang menganjurkan dan mendukung kebijakan uang ketat tersebut.
Ada beberapa alasan utama para pengkritik. Suku bunga yang tinggi akan menyebabkan kesulitan bagi dunia usaha dalam mengembalikan kredit dan bukan tidak mungkin menaikkan kembali kredit macet perbankan nasional. Kenaikan suku bunga SBI juga tidak dapat mencegah melemahnya rupiah karena memang kepercayaan terhadap perbankan dalam negeri dan terhadap negara secara umum masih sangat rapuh sebagaimana tecermin dalam risk premium yang sangat tinggi. Yang lebih ironis, kenaikan suku bunga menjadi penghalang bagi bank untuk menyalurkan kreditnya ke sektor riil karena bank yang kelebihan likuiditas dapat membeli SBI dengan return yang sangat menarik dan tanpa risiko daripada jika bank tersebut menyalurkan kredit ke sektor riil.
Sementara itu, BI pun punya alasan-alasan tersendiri dalam mempertahankan kebijakan tersebut—meskipun target operasional BI pun tidak tercapai. Apabila target operasional harus dicapai, penyerapan likuiditas harus lebih agresif dan sebagai akibatnya bukan tidak mungkin suku bunga SBI pun akan lebih tinggi lagi dari tingkat yang ada sekarang. Pendekatan monetaris yang dianut BI dan IMF ini sebetulnya bisa saja mencapai sasaran hasil penurunan inflasi apabila BI mau melakukannya dengan tidak ragu-ragu, yaitu dengan agresif menyerap likuiditas yang berlebih. Tapi BI harus mampu pula menjelaskan dampaknya—yaitu suku bunga SBI yang akan naik—ke masyarakat. Sampai saat ini, BI tampak ragu-ragu me-lakukannya secara total karena takut mendapat kritik yang lebih pedas dari para pelaku ekonomi.
Memang harus diakui, BI sudah mencoba melakukan usaha menjaga keseimbangan moneter. Tapi usaha itu tampaknya kurang berhasil. Permasalahannya memang tidaklah mudah. Dapat dipahami bahwa inflasi yang sangat tinggi pada tahun 2001 bukanlah disebabkan oleh tekanan dari sisi permintaan saja (demand pull), yang relatif lebih mudah diatasi lewat kebijakan moneter. Inflasi tinggi lebih disebabkan oleh faktor suplai (cost push) seperti kenaikan harga-harga yang di bawah pengaruh pemerintah: harga bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan sebagainya, yang semuanya di luar pengaruh BI. Di samping itu, tekanan terhadap inflasi diperkuat oleh harga bahan makanan yang cenderung berfluktuasi sangat tajam sebagai akibat dari sistem distribusi dan tata niaga yang tidak efisien. Melemahnya rupiah juga ikut menyebabkan kenaikan inflasi yang berasal dari kenaikan harga impor. Dapat pula dipahami bahwa kegagalan BI untuk mencapai sasaran operasional, uang primer, juga tidak lepas dari transfer pengeluaran pemerintah pusat ke daerah yang tidak terantisipasi dengan baik, seperti adanya kenaikan rapel gaji guru pada tahun 2001 ini.
Perdebatan semacam itu tampaknya masih akan berlangsung hingga tahun 2002 ini. Dan itu akan lebih menggema lagi pada saat pembahasan amandemen UU No. 23/1999 tentang BI, yang sangat kontroversial, yang akan dimulai awal tahun 2002. Pasal 7 dalam undang-undang tersebut menyebutkan, tujuan utama BI adalah menjaga stabilitas harga, dan pasal ini pun sudah mendapat restu dari pemerintah dan DPR. Jika memang begitu adanya, BI tidak perlu ragu-ragu lagi dalam melaksanakan tugasnya: tinggal menjaga stabilitas harga tanpa perlu memperhatikan pertumbuhan ataupun penyediaan lapangan kerja sebagaimana dikeluhkan oleh banyak kalangan. Bila perlu, BI dapat melakukan pengetatan lebih kencang meskipun akan berakibat suku bunga tinggi dan tanpa perlu khawatir terhadap kritik atas tindakan itu karena mereka terlindungi oleh undang-undang.
Menurut hemat kami, di sinilah letak kontroversi UU tentang BI tersebut. Perdebatan dan revisi terhadap pasal 7 seharusnya lebih penting daripada pasal 75 (tentang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Gubernur BI) jika memang kita masih ingin memperoleh stabilitas harga serta pertumbuhan sekaligus. Memang harus diakui, pasal 75 menjadi fokus yang paling menarik karena menyangkut jabatan, tapi substansi undang-undang tersebut sebetulnya ada pada pasal tentang tujuan (pasal 7) tersebut. Sedangkan pasal mengenai jabatan (pasal 75) hanyalah turunannya.
Sebagaimana diketahui, manakala ada kejutan dari sisi permintaan (demand shock), itu akan sangat mudah diatasi dengan kebijakan moneter. Sebab, demand shock akan mendorong output penyediaan lapangan kerja dan inflasi dalam arah yang sama. Jadi, kalau inflasi naik karena naiknya permintaan, pengetatan moneter akan dapat mengurangi pertumbuhan dan inflasi sekaligus. Kenyataannya, inflasi di Indonesia naik pada saat pertumbuhan melambat tahun 2001.
Persoalannya menjadi berbeda manakala sumber kejutan berasal dari sisi suplai (supply shock), baik disebabkan oleh kenaikan harga barang yang dikuasai pemerintah, seperti harga energi, maupun karena perubahan produktivitas. Sebagai contoh, kenaikan harga BBM akan menaikkan ongkos produksi perusahaan dan seterusnya akan mendorong perusahaan menaikkan harga. Supply shock semacam ini menyebabkan kenaikan inflasi meskipun permintaan tidak berubah. Gejala inilah yang lebih dominan kita lihat sekarang di Indonesia. Apabila kebijakan moneter dipakai untuk mengatasi gejala seperti ini, akan terjadi dilema: melakukan kebijakan uang ketat untuk menurunkan inflasi ataukah kebijakan uang longgar untuk mempercepat pertumbuhan?
Bila sumber kejutannya dari sisi suplai, jelas tidak akan mungkin dicapai sekaligus penurunan inflasi dan pertumbuhan ekonomi jika hanya mengandalkan kebijakan moneter. Diagnosis terhadap penyebab kenaikan harga seharusnya dilakukan secara akurat, baru kemudian diberikan obatnya yang mungkin tidak harus satu macam, yaitu mengandalkan kebijakan moneter saja, tapi merupakan obat campuran, kebijakan moneter, fiskal, distribusi, investasi, dan lain-lain, secara bersamaan. Persoalan inilah yang akan mengemuka dari waktu ke waktu dan memerlukan fleksibilitas dan kreativitas pembuat kebijakan, dan bukan hanya mengandalkan satu kebijakan dan rule of thumb saja—semua penyakit dikasih obat yang sama.
Lalu, bagaimana prospek moneter tahun 2002? Dengan melihat pengalaman tahun 2001, prediksi terhadap keadaan moneter tahun 2002 pun tidak akan jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Yang sudah jelas, tekanan terhadap inflasi akan datang dari kenaikan harga BBM, tarif listrik, serta tarif telepon. Semuanya lebih dari sisi suplai, bukan dari sisi permintaan. Apabila BI kembali menganut kebijakan moneter yang sama seperti tahun 2001 untuk menurunkan inflasi, tanpa ada perbaikan produktivitas dan efisiensi di sektor riil, kebijakan uang ketat akan mengakibatkan suku bunga tetap tinggi dan pemulihan ekonomi pun akan tetap lambat. Seharusnya BI cukup berkonsentrasi terhadap penyebab inflasi dari sisi permintaan (underlying/core inflation). Apabila target ini sudah dapat dicapai, BI tidak perlu melakukan pengetatan lagi. Biarlah kebijakan lainnya seperti kebijakan fiskal, kebijakan tarif, dan distribusi yang dapat mengatasi kejutan dari sisi suplai yang berperan. Jika tidak, pasien akan kembali diberi resep yang salah. Dan kalau terlampau sering salah obat/resep, akumulasinya akan sangat berdampak negatif. Penyakit lain yang lebih parah bisa muncul. Atau pasiennya bisa mati alias perekonomian Indonesia tidak responsif lagi terhadap perubahan kebijakan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini