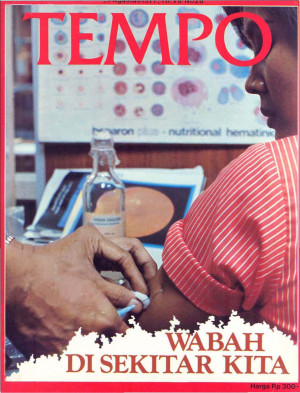BAGI bapak Sampurno, semua perbuatan orla itu buruk, tapi yang
terburuk adalah UU Pokok Agrarianya. Ini betul-betul perbuatan
setan yang dapat dilihat mata. Bagaimana mungkin ada
perundang-undangan yang membatasi hak milik atas tanah, padahal
Belanda yang kolonial sekalipun tidak berbuat segila itu?
Membela kaum Tani? Omong kosong. Dia sendiri merasa Tani juga,
biar pun tidak pernah turun ke sawah seumur hidupnya. Bukankah
Tani itu, seperti juga batu-batuan ada jamrud ada kerikil, ada
Tani penggarap ada Tani pemilik, yang hanya berhubungan dengan
padi apabila panen lewat laporan pabrik penggiling. Perbedaan
ini berdasar pembagian jalur rezeki yang tunduk pada ketentuan
gaib yang tidak bisa dicampuri manusia. Inilah yang disebut
nasib. Apabila ada perundang-undangan yang coba-coba
mengobrak-abrik pengotakannya, dia mesti ditolak.
Tapi, karena bapak Sampurno bukanlah orang bodoh, dia tahu bahwa
menolak peraturan perundangan itu suatu perbuatan seni. Caranya
macam-macam. Bukankah perawan zaman bahari menolak pinangan
bukan dengan kata-kata, atau surat lewat pos, melainkan cukup
pergi ke dapur, mengambil seutas tali, dan menggantung batang
lehernya di pinggir sumur?
Maka dari itu, cara menolak yang dipilih bapak Sampurno adalah
mengembangkan semaksimal mungkin bakat manipulatornya, yang
tampaknya terbawa lahir dari perut ibunya. Bakat itu, apabila
dijabarkan, sebetulnya sederhana saja: menggunakan sedikit akal,
meramunya dengan kerakusan individuil, seraya tak henti-hentinya
bermanis muka di depan Pemerintah kita mengentuti
peraturan-peraturannya. Pemerintah itu, menurut penelitian
seksama bapak Sampurno, bagaikan seorang separo umur yang mesti
dihormat, betapa pun orang membelot di belakang punggungnya.
Itulah akhlak berwarganegara.
Syahdan tatkala UU Pokok Agraria itu lahir tanggal 24 September
i960, tatkala orang menyambutnya sebagai langkah pembaharuan
hukum agraria, tatkala orang menganggapnya sebagai usaha
penghapusan hak-hak asing dan konsesi kolonial atas tanah,
tatkala penduduk melihatnya sebagai pengakhiran penghapusan
feodalisme secara berangsur-angsur, tatkala kaum Tani kecil
bersorak-sorak menyaksikan adanya perombakan mengenai pemilikan
dan penguasaan atas tanah serta hubungan-hubungan hukum yang
bersangkutan dengan penguasaan tanah, dan tatkala tanggal 24
September itu diresmikan sebagai "Hari Tani", bapak Sampurno
sedang repot dengan urusannya sendiri.
Jauh di Mata . . .
Betapa takkan repot! Di pulau Jawa yang begitu padat, nyaris
tiap pantat bersinggungan sesamanya, bapak Sampurno memiliki
tidak kurang dari 200 Ha tanah. Padahal, UU membatasinya cuma 5
Ha. Apa akal? Bapak Sampurno bekerja keras "menghibah"kan
tanahnya 4 Ha seorang kepada anak kemenakan, menantu serta
besan, lewat akte yang dibubuhi tanggal mundur, sebelum 24
September 1960.
Bagaimana mungkin? Bukankah akte itu diketahui pqabat? Tentu
saja. Akte yang tidak diketahui pejabat harganya lebih buruk
dari koran bekas. Dan tentu saja, bapak Sampurno sudah menguasai
adat-istiadat menyelesaikan kemelut seperti itu. Sedangkan
terhadap tanah-tanah yang tergolong absentee owner ship, dia pun
bisa mengatasinya tanpa hirukpikuk. Biar tanah-tanah itu jauh di
mata, tapi dekat di hati.
Sekarang, biarpun UU Pokok Agraria itu formil masih berlaku,
tapi boleh dibilang seperti tidak ada saja. Paling-paling dia
diperbincangkan orang di seminar atau lokakarya, seperti
Lokakarya "Masalah Pemukiman" yang diselenggarakan oleh Dirjen
Cipta Karya itu, kemudian hilang menguap. Bahkan, seringkali
terasa orang enggan menyebut-nyebutnya kembali, khawatir
disangka orla, atau kalau awak lagi apes, dianggap berindikasi.
Sedangkan DPR sebagai lembaga pembikin UU dan pengawasnya acuh
tak acuh, mengapa pula orang biasa repot-repot mempersoalkannya?
Toh kaum Tani sekarang sudah baik-baik, tidak banyak tingkah,
punya sepotong tanah syukur, tidak punya ya bertransmigrasi.
Akan halnya tokoh cerita kita bapak Sampurno, rasa tertekannya
sudah sirna sesirna-sirnanya. Sekarang dia tidak merasa perlu
munafik lagi, main hibah pura-pura atau main selingkuh terhadap
hak miliknya sendiri, melainkan segala sesuatu, entah beli atau
jual tanah, dilakukan berterang-terang. Semua akte, semua
keterangan pemilikan, tersusun dengan nama jelas, dan dalam
bahasa Indonesia yang bisa difaham tiap orang. Tidak peduli
berapa luas tanah kepunyaannya, tidak peduli di mana letak tanah
itu, segalanya tercantum sebaRaimana adanya. Landreform,
absentee ownership, itu sudah bukan persoalan. Yang penting
sekarang ini adalah apa yang disebut serikat. Barangsiapa sudah
pegang sertifikat tanah, kedudukannya kokoh seperti dewa. Dan
apabila dia masuk ke Bank, dia akan disambut seperti seorang
paman yang baik hati. Hambatan satu-satunya adalah kalau ada
sertifkat dobel. Ini baru celaka.
Ikhlas
Perlu ditegaskan di sini, supaya jangan salah sangka, bapak
Samprno itu tak ubahnya seperti manusia biasa, yaitu perasa. Dia
tidak bisa tidur, bahkan sesak nafas, bilamana orang
memanggilnya "tuantanah". Panggilan itu bernada sindiran. Dia
cinta Tanah air, khususnya tanah, tapi "tuantanah" adalah lain
samasekali. Berhubung nyatanya memang dia tuantanah, maka
orang-orang sekeliling mencari akal bagaimana caranya supaya ada
sebutan yang tidak menyinggungnya. Bagaimana kalau "tuantanah
Pancasilais"? Kedengarannya serasi dan persis sasarannya.
Bapak Sampurno pun menerima dengan hati ihlas. Sebab, meskipun
dia punya rumah yang pekarangannya 1 Ha, karena itu pagarnya
diberi strom listrik, dan tanahnya di tepi kota dan di pedalaman
beratus Ha, toh bapak Sampurno tidak merasa merugikan siapapun,
bahkan semut pun tidak. Kaum Tani yang tak bertanah, daripada
narik beca atau gelandangan, boleh menggarap tanahnya, asal
tunduk pada perjanjian bagi-hasil yang progresif, artinya bisa
berubah-ubah menurut keadaan. Mereka yang berhasrat naik haji
dan mau jual murah sawahnya, boleh lekas-lekas berhubungan
dengan bapak Sampurno, tanggung beres. Kesempatan serupa juga
terbuka buat orang-orang yang perlu uang mendadak, misalnya
untuk pesta kawin atau sunatan. Pahala dapat, untung apalagi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini