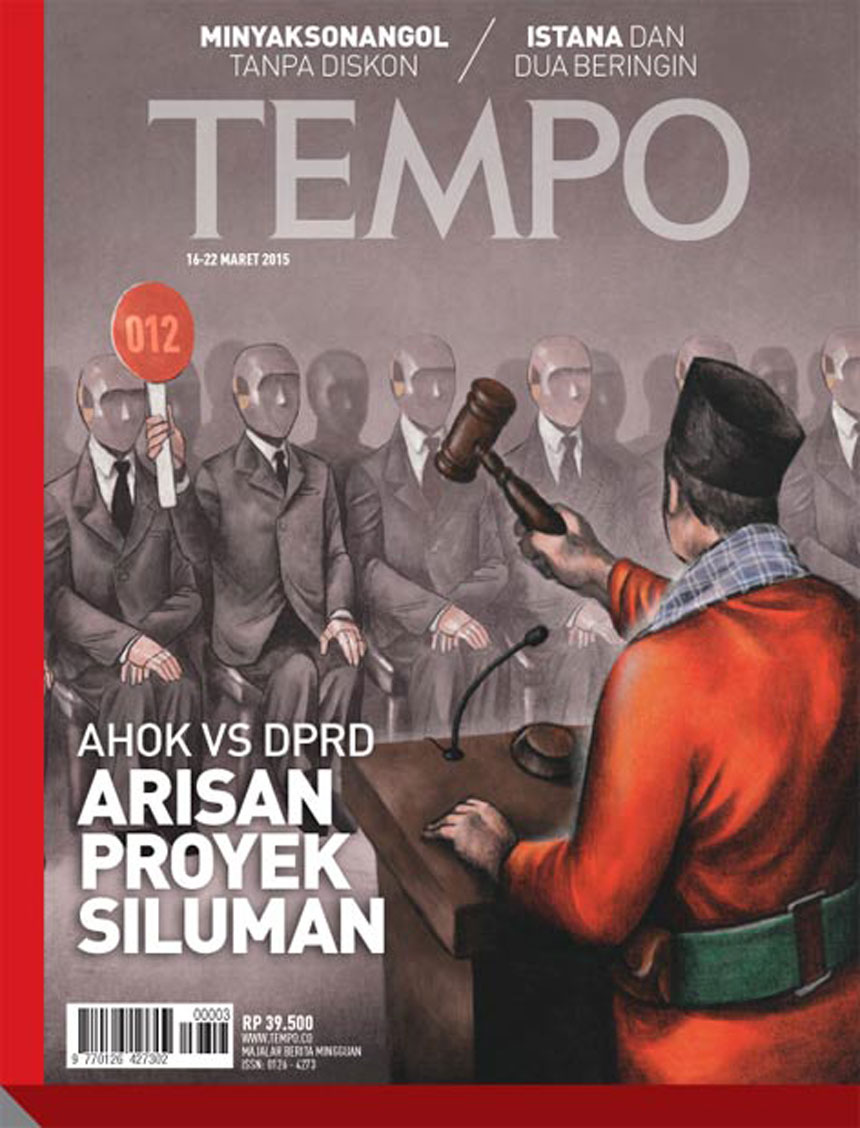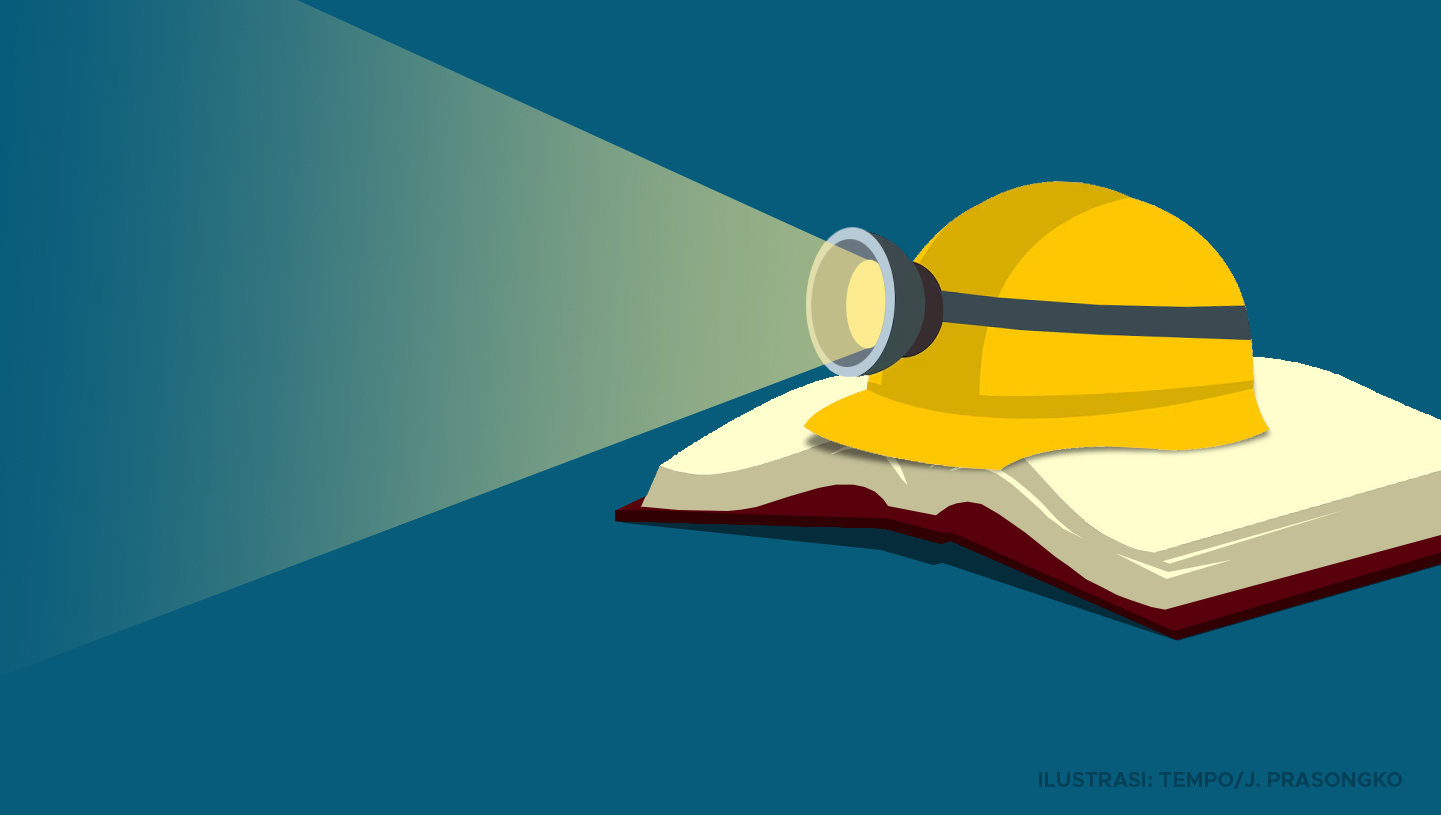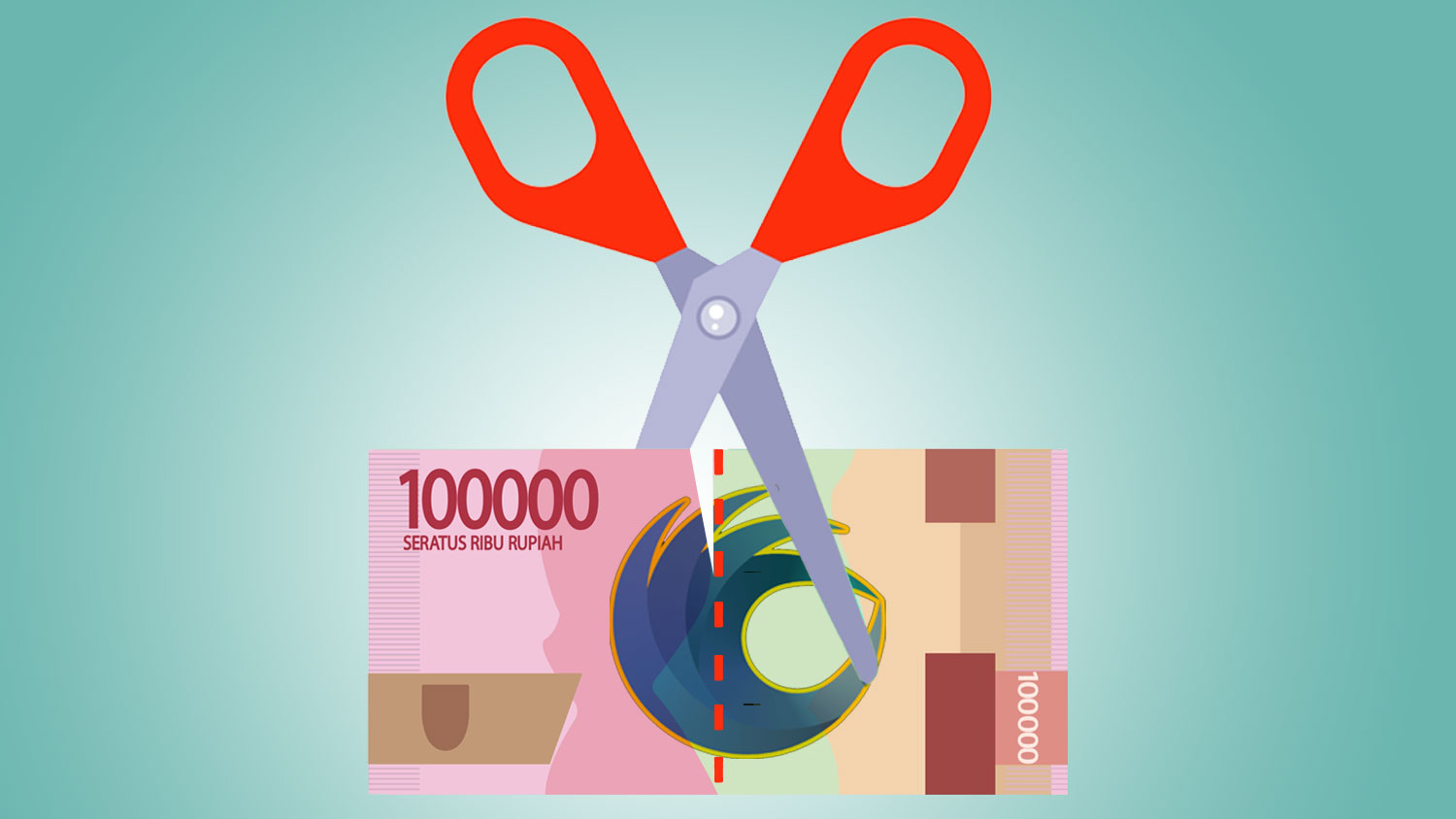Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Destry Damayanti*
Perekonomian Indonesia sedang memasuki masa ujian yang sulit. Dalam dua minggu terakhir ini, rupiah sudah terdepresiasi 6,3 persen terhadap dolar Amerika Serikat dibanding akhir tahun lalu. Hal ini memicu arus dana keluar di pasar modal kita hingga mencapai Rp 13,5 triliun pada 12 Maret lalu. Indeks harga saham pun terus melorot menjadi 5.427 dari tingkat tertinggi 5.514 pada awal Maret. Imbal hasil Surat Utang Negara jangka 10 tahun naik menjadi 7,9 persen dari level terendah di angka 7 persen pada awal Maret.
Sayangnya, dalam kondisi seperti ini, berbagai pernyataan dari para regulator cenderung normatif dan mengindikasikan kurangnya sense of crisis. Misalnya pengaruh depresiasi yang tidak terlalu signifikan terhadap inflasi, yaitu hanya 0,07 persen dari setiap depresiasi 1 persen. Ada juga depresiasi positif untuk penerimaan negara karena setiap Rp 100 depresiasi akan menambah penerimaan bersih negara Rp 2,5 triliun. Ada lagi pernyataan bahwa ekonomi Indonesia tetap kuat walaupun rupiah menembus angka 13.500 per dolar dan akan baik untuk ekspor kita.
Berbagai pernyataan seperti ini bukannya menenangkan pasar, justru memantik kekhawatiran dan pertanyaan dari pelaku pasar mengenai ke mana sebenarnya arah kebijakan pemerintah terhadap rupiah. Regulator seolah-olah menyerah pada keadaan ini dan akhirnya mencari "biang keladi", yakni adanya normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat, yang akan mendorong naiknya suku bunga bank sentral yang saat ini 0,25 persen.
Memang tidak dapat dimungkiri tekanan pada rupiah saat ini banyak dipengaruhi faktor global, yaitu adanya penguatan dolar terhadap mata uang kuat lain. Rupiah memang tidak sendirian mengalami pelemahan. Namun rupiah terdepresiasi paling dalam. Ringgit, dolar Singapura, dan won masing-masing melemah 5,3 persen; 4,3 persen; dan 3,2 persen. Peso dan baht malah menguat 1,3 persen dan 0,3 persen.
Pertanyaannya adalah mengapa rupiah sangat tertekan justru ketika ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif. Pemerintah berhasil menurunkan beban anggaran subsidi bahan bakar minyak secara signifikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 dan mengalokasikannya untuk infrastruktur. Inflasi turun drastis menjadi 6,3 persen pada Februari dari 8,4 persen pada Desember 2014. Neraca perdagangan Indonesia surplus US$ 710 juta pada Januari. Cadangan devisa mencapai US$ 115,5 miliar pada Februari. Arus dana masuk ke pasar modal mencapai tingkat tertinggi, yakni Rp 59,7 triliun, pada awal Maret lalu.
Kita tidak dapat begitu saja mengambinghitamkan perekonomian global. Sebaiknya kita duduk bersama dan melakukan introspeksi, melihat secara riil apa sebenarnya yang terjadi dengan pasar valuta asing kita ini. Upaya pemerintah mengeluarkan sepuluh kebijakan fiskal untuk mengatasi tekanan pada rupiah patut diapresiasi. Misalnya insentif pajak bagi perusahaan yang mereinvestasikan keuntungannya di Indonesia dan perusahaan yang mengekspor 30 persen dari hasil produksinya, pengenaan tarif antidumping untuk impor komoditas tertentu, penggunaan rupiah untuk transaksi di dalam negeri, serta penggunaan L/C bagi eksportir batu bara, kelapa sawit, hasil mineral, dan sektor minyak. Namun butuh waktu untuk melihat hasilnya.
Yang segera terjadi, depresiasi rupiah yang berkepanjangan akan memukul sektor riil dan pada akhirnya bakal menekan pertumbuhan ekonomi. Bayangkan seorang pengusaha yang pada akhir 2012 mempunyai utang luar negeri sebesar US$ 100 juta dengan rate Rp 9.600 (setara dengan Rp 960 miliar) kini menjadi Rp 1,32 triliun (kurs Rp 13.200) atau naik 37,5 persen. Bagaimana bisnis dapat bertahan jika kondisi seperti ini terus berulang? Karena itu, harus dicari langkah yang sistematis dan berkesinambungan untuk menghadapi gejolak rupiah ini.
Menarik untuk mencermati pergerakan rupiah terhadap dolar dari sisi fundamental. Secara teoretis, nilai tukar rupiah terhadap dolar ditentukan oleh penawaran dan permintaan dolar. Pasokan dolar dapat berasal dari ekspor dan arus dana masuk ke dalam negeri (pinjaman ataupun investasi), sementara permintaan dolar digunakan untuk impor, pembayaran utang luar negeri, repatriasi pendapatan, dan arus dana keluar untuk investasi. Jika penawaran dolar lebih tinggi dibanding permintaan, akan terjadi apresiasi rupiah, demikian sebaliknya.
Pada kenyataannya, kondisi teoretis tersebut tidak tecermin dalam rupiah kita. Pada 2013-2014, suplai dolar sangat tinggi, sehingga neraca pembayaran kita surplus US$ 15,2 miliar, cadangan devisa mencapai US$ 112 miliar, arus masuk portofolio dan investasi riil mencapai US$ 41 miliar, serta penambahan utang luar negeri US$ 26 miliar. Secara teoretis, semua itu semestinya mengangkat rupiah, tapi yang terjadi rupiah justru terdepresiasi 2,2 persen pada 2014 setelah tahun sebelumnya melemah 26 persen. Tingginya volatilitas ini menyulitkan siapa pun yang hendak memprediksi pergerakan rupiah serta menyulitkan pengusaha dan investor.
Penulis menganggap ada yang salah dengan pasar valuta asing kita. Data sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa rata-rata transaksi harian dolar relatif tidak berubah, yaitu di kisaran US$ 2-2,5 miliar. Sedangkan transaksi yang menggunakan dolar, baik untuk ekspor maupun impor, melompat tiga kali lipat, dari US$ 5 miliar per bulan pada awal tahun 2000 menjadi US$ 15 miliar saat ini. Repatriasi pendapatan juga melonjak dari sekitar US$ 10 miliar per tahun menjadi US$ 27 miliar pada 2014. Kebutuhan untuk membayar utang juga terus naik karena utang luar negeri meningkat signifikan dari US$ 134 miliar pada 2006 menjadi US$ 293 miliar pada akhir 2014--naik 119 persen hanya dalam delapan tahun.
Logikanya, masuknya dana asing tersebut akan menambah suplai dolar dalam perdagangan valuta asing. Kenyataannya, rata-rata transaksi harian relatif tidak berubah. Hal inilah yang bisa menerangkan betapa rentannya rupiah karena suplai dolar tidak bertambah, sementara kebutuhan terus meningkat. Lalu ke mana larinya dolar yang masuk tersebut? Ke mana penerimaan ekspor kita yang mencapai US$ 180 miliar per tahun dan capital inflow sebesar US$ 44 miliar tersebut?
Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak devisa hasil ekspor berada di luar negeri. Sedangkan pasar valuta asing kita masih dangkal dan konsekuensinya akan sangat volatile pada saat terjadi perubahan sentimen di pasar. Mengandalkan Bank Indonesia sebagai supplier utama dolar di pasar tentu sangat tidak bijak, karena fungsi BI sebagai regulator, bukan sebagai "pemain". Walaupun saat ini memiliki cadangan devisa US$ 115,5 miliar, BI tetap harus berhati-hati menggunakannya, apalagi ketidakpastian ekonomi global masih terus membayangi perekonomian kita.
Inilah saatnya bagi pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan membuat kebijakan yang lebih konkret berkaitan dengan sisi suplai dolar tersebut. Malaysia, Thailand, dan India mengharuskan eksportir mereka menempatkan dananya di perbankan domestik dan menjual ke mata uang lokal setelah periode tertentu. Thailand juga mengharuskan sekian persen utang luar negeri dan arus modal masuk ditempatkan di bank sentral dalam jangka waktu tertentu. Kita pun harus mempercepat penerbitan instrumen investasi jangka panjang, misalnya obligasi infrastruktur dengan insentif menarik yang dapat menarik dana asing jangka panjang.
Kita kadang terbentur Undang-Undang Devisa Bebas yang kita anut selama ini. Dalam saat sistem ekonomi global yang sudah sedemikian terbukanya dan keterkaitan antarnegara sangat tinggi, sementara tatanan fundamental kita belum siap, sistem devisa bebas pada akhirnya justru meningkatkan risiko yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian nasional. Sudah saatnya kita mengkaji kembali sistem tersebut dan menerapkannya secara selektif.
Di samping itu, kebijakan pendalaman pasar keuangan tidak dapat ditunda lagi agar sektor keuangan kita mempunyai daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi gejolak, global ataupun domestik. Penguatan investor domestik perlu diprioritaskan untuk mengurangi ketergantungan pada investor asing di pasar modal. Pemerintah perlu mengeluarkan terobosan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan di sektor keuangan dan sektor riil, bukan hanya kebijakan yang sifatnya ad hoc dan parsial.
Sesungguhnya kondisi global yang mempengaruhi gejolak di pasar keuangan kita saat ini barulah awal dari gejolak yang sebenarnya. Saat ini kondisi yang sebetulnya kita khawatirkan, yakni kenaikan tingkat bunga bank sentral Amerika serta pemburukan ekonomi Eropa dan Cina, belum menjadi kenyataan. Karena itu, kita masih harus bersiap menghadapi gejolak yang sesungguhnya.
*) Direktur Eksekutif Mandiri Institute
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo