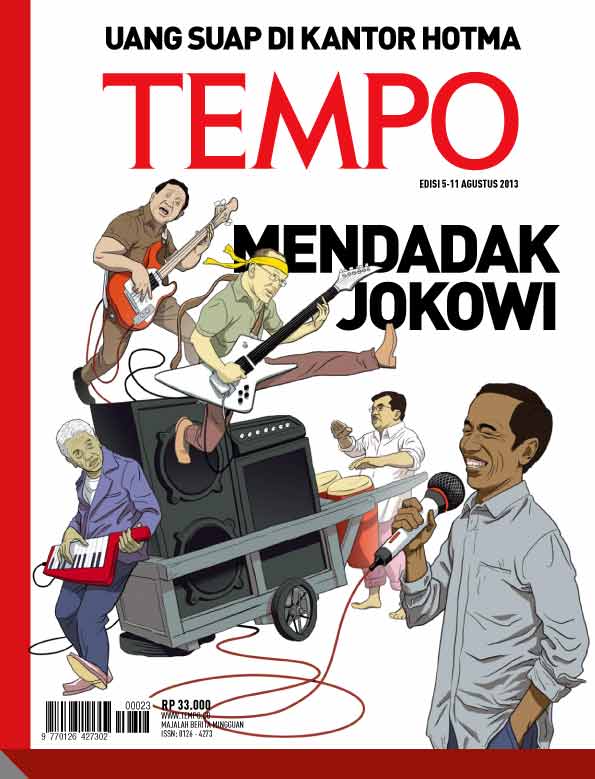Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Apa yang pertama kali akan dilakukan Konghucu jika ia mendapat kesempatan memerintah sebuah negeri? Jawabnya, "Membereskan nama-nama."
Membereskan nama-nama, atau Zhèngmíng, bagi sang Guru adalah langkah yang menentukan. Khususnya dalam kehidupan sosial-politik. "Jika nama-nama tak benar," katanya, "bahasa tak akan sesuai dengan kebenaran hal-ihwal. Jika bahasa tak sesuai dengan kebenaran hal-ihwal, perkara tak akan ada yang berhasil diatasi." Dengan kata lain, nama, sebagai penanda, harus punya arti yang tertib.
Saya tak kenal betul konteks pemikiran Konghucu di Cina abad ke-6 sebelum Masehi. Yang bisa saya tebak, ia tampak meyakini adanya kebenaran yang terakhir, dan menganggap bahasa bisa jadi representasi kebenaran itu. Ia tak melihat bahwa kebenaran terakhir (kalaupun ada) tak bisa sepenuhnya diwakili dunia kata-kata: begitu banyak perubahan yang bisa terjadi, begitu banyak yang terpendam dalam pengalaman.
Menurut sebagian pakar, dalam teks Cina lama "nama" (míng) memang tak identik dengan "kata". Tapi sama-sama sebagai penanda, kata (dan terutama nama) bukanlah wadah kebenaran yang transendental, yang melampaui ruang dan waktu. Nama bermula dari perbedaan yang timbul dalam pengalaman manusia sehari-hari.
Para pengikut Mo Tzu, yang hidup sekitar 100 tahun setelah Konghucu dan dianggap sebagai lawan filsafatnya, menegaskan hal itu: seseorang dianggap "tahu" bukan karena mengerti arti kata dengan tepat, melainkan karena mampu membedakan hal-ihwal dalam laku. Bagi para pengikut Mo Tzu—umumnya orang kebanyakan—bukan ketertiban bahasa yang menentukan kehidupan sosial-politik, melainkan kemampuan bertindak dalam memilih dari hal-hal yang berbeda.
Tapi dalam satu hal penting Konghucu benar. Bahasa, dan di dalamnya nama-nama, terkait dengan kekuasaan dan politik. Bukan hanya dalam efeknya, tapi juga dalam mekanismenya.
Terutama di Cina, negeri orang-orang yang telah mengenal aksara sejak ribuan tahun yang lalu. Tulisan, kata Walter Ong, penulis buku terkenal Orality and Literacy, "bergantung pada aturan yang secara sadar direncanakan". Dengan kata lain, para pengatur kata (dan aksara) memegang posisi yang nyaris tak tergantikan dalam bahasa Cina.
Dulu posisi itu di tangan para punggawa kemaharajaan, kemudian ia di bawah birokrasi Negara yang mengatur Republik Rakyat Cina dan Taiwan. Atau, sebagaimana halnya di Hong Kong, aturan itu dinegosiasikan di antara penguasa media.
Bahasa dan kekuasaan: kita tahu betapa efektifnya kombinasi kedua hal itu. Dalam salah satu esai dalam The Hall of Uselessness, Simon Leys, sang penulis, menunjukkan bahwa sejarah aksara Cina sejak mula "secara akrab terhubung dengan… otoritas politik". Sejarah aksara itu juga sejarah seluruh bahasa.
Zaman Mao Zedong adalah contohnya yang ekstrem. Simon Leys bukan pengagum komunisme Mao. Bagi pakar Sinologi yang dikenal sebagai Pierre Ryckmans ini, zaman Mao adalah "tiga dasawarsa pemerintahan orang buta huruf". Tentu saja kesimpulan ini berlebihan. Sebab di zaman itu—sebuah masa kekuasaan totaliter seperti dalam novel Orwell 1984—huruf & bahasa justru dipakai menghancurkan musuh politik dan memperkukuh sang Ketua. Kata "kontrarevolusioner", "kanan", atau "pengambil jalan kapitalistis" dipakai sebagai cap. Orang yang terkena cap itu akan dihabisi hidup atau kariernya. Tentu saja yang menentukan arti kata dan korbannya adalah Ketua Mao dan aparat propaganda Partai Komunis-nya.
Mao tahu benar daya yang tersimpan dalam bahasa. Ia menulis puisi dan membuat kaligrafi yang sampai setelah ia dikuburkan tetap dipuja, disebut khusus gaya Maoti, meskipun, dalam penilaian Leys, karya Mao hanya menunjukkan "egoisme yang flamboyan". Kata-katanya jadi hafalan wajib seperti fatwa suci di kalangan Pengawal Merah yang militan. Dalam arti tertentu, di bawah Mao, RRC adalah sebuah "lingokrasi": kekuasaan yang mengandalkan peran bahasa.
Dalam bentuknya yang lebih lunak, "lingokrasi" berkuasa di mana-mana di zaman ini. Deleuze menyebutnya "imperialisme bahasa" dan dalam telaahnya tentang karya-karya Samuel Beckett ia berbicara tentang "bahasa nama-nama" (langue des noms) yang terbentuk dari nama atau penanda yang terpisah-pisah atau dipasang dalam kombinasi. Saya bayangkan sebagai tiang-tiang pancang yang tak bergerak.
Tapi bukannya tak ada celah untuk pelbagai gerak. Leys dengan tepat melihatnya dalam puisi klasik Cina. Puisi ini bukan lukisan yang menirukan alam. Sajak-sajak itu tampil seakan-akan bukan ekspresi subyektif penyair, melainkan manifestasi alam itu sendiri. Karya seni bukan meniru alam, kata Picasso, melainkan bekerja seperti alam. Maka gunung, kembang, dan jalan di hutan disajakkan berulang-ulang, tapi dalam puisi ada proses dan "pertemuan yang tak terduga-duga", kata Leys, dan "satu kehidupan baru mungkin berpijar".
Dan bahasa pun bukan lagi dibangun dari nama-nama yang ditentukan tempatnya. Ia mengalir, tak tegar tak kaku, selalu mengandung yang tak terduga, yang hadir dan tak hadir, yang ganjil.
Bahasa yang seperti itu—dengan keindahannya—mau tak mau akan bertabrakan dengan program Konghucu untuk "membereskan nama-nama".
Berabad-abad kemudian tabrakan itu terjadi. Mao, menurut Leys, menghancurkan karya seni peninggalan lama, bukan karena mereka karya seni feodal, melainkan karena mereka indah.
Saya tak percaya itu sebabnya. Tapi keindahan memang tak cocok untuk kekuasaan dan doktrin yang ingin semuanya beres dan patuh. Keindahan membuat gunung, kembang, dan jalan di hutan hidup kembali, liar kembali, sebelum dijinakkan.
Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo