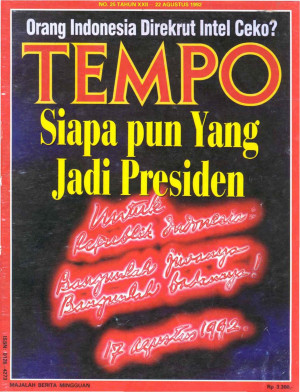SOAL harga pangan dan kebutuhan pokok memang hampir tak ada masalah. Tapi soal dana pembangunan, penerimaan negara untuk menyusun angaran pembangunan mungkin akan menghadapi kendala di masa datang. Sukses di masa lalu, nampaknya tak terlalu mulus terulang dalam tahap kedua pembangunan 25 tahun mendatang. "Dalam tahap itu kita bertekad mengejar semua ketinggalan sehingga bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju," kata Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraan Sabtu lalu. Berbicara di depan sidang pleno DPR, Presiden juga menunjukkan sukses di masa lalu. "Pada tahun 1992 ini ekonomi kita kembali menjurus ke jalur pertumbuhan yang lebih mantap," kata presiden. Pertumbuhan ekonomi sepanjang 1991 tercatat 6,6%. Dan cadangan devisa yang ada di tangan pemerintah saat ini tak kurang dari U$ 11 milyar dollar, jumlah yang cukup untuk menngamankan perdagangan luar negeri. Namun pekerjaan belum selesai. Apa yang telah diraih selama ini, pada kurun pembangunan 25 tahun pertama yang berakhir 1993 nanti, harus diteruskan dalam periode 25 tahun berikutnya. Pembangunan jangka panjang tahap ke-2 ini, 1993-2018, sebuah kerja besar. Pada periode ini, penduduk Indonesia bakal tumbuh hingga menjadi 250 juta pada 2018. Pertumbuhan ekonomi tak boleh tidak harus terus dipacu, untuk mengatrol mutu hidup manusia Indonesia yang kini pendapatan perkapitanya U$ 570. Bila pertumbuhan bisa bertahan 6-6,5% per tahun, pendapatan per kapita orang Indonesia pada 2018 nanti mencapai U$ 2000 - angka yang setara dengan pendapatan warga Malaysia dan Meksiko tahun 1992 itu. Untuk mencapai pertumbuhan sebesar itu, kiranya tak sedikit kendala yang dihadapi. Salah satu batu ganjalannya adalah utang luar negeri. Untuk tahun anggaran yang berjalan, besarnya cicilan utang sekitar Rp 15 trilyun, atau hampir separuh pengeluaran rutin untuk gaji pegwai, belanja barang dan subsidi daerah otonom. Besarnya cicilan utang itu cenderung naik. Diperkirakan sampai akhir abad ini rata-rata setiap tahun harus menyediakan dana Rp 21 trilyun untuk membayar utang. Walau berat, tidaklah berarti Indonesia harus menyetop pinjaman luar negeri itu. Tabungan pemerintah harus tebal untuk membiayai seluruh proyek pembangunan. Tahun ini, misalnya, dari Rp 22 trilyun pengeluaran pembangunan hampir 45% masih ditopang pinjaman luar negeri itu. Dana itulah yang didapat lewat CGI (Consultative Group for Indonesia) yang bersidang di Paris akhir Juli. Sidang CGI pertama yang menggantikan peran IGGI yang dibubarkan Maret lalu memberikan pinjaman US$ 4,93 milyar pada Indonesia. Namun seperti diakui oleh Menteri Radius Prawiro pinjaman itu akan kian susah dicari. "Ini masalah yang dihadapi Indonesia," ujarnya. Banyak pesaing yang muncul. Negara-negara persemakmuran bekas Uni Soviet, negara-negara Eropa Timur, India dan negara-negara Amerika Latin mulai mulai giat menggaet dana murah itu. Kawasan Amerika latin punya posisi tersendiri di mata Radius. "Mereka mulai menerapkan kebijaksanaan yang lebih sehat dari masa lalu," ujarnya. Namun banyak pengamat ekonomi yang mengingatkan agar Indonesia mem-perhitungkan pesaing dari Eropa Timur. Bagi donor di Eropa Barat, ban-tuan ke Timur membawa manfaat konkrit yakni untuk mengerem eksodus pendatang haram dari timur bila keadaan ekonominya tak segera pulih. Tapi tampaknya bantuan itu hanya bersifat darurat. Seorang pejabat tinggi tak terlalu khawatir karena pinjaman dari Eropa Barat untuk Indonesia cuma US$ 350 juta dari total pinjaman lewat CGI itu. Seandainya bantuan Eropa Barat dialihkan ke Eropa Timur, Indonesia masih punya peluang mendapat pinjaman dari negara di luar Eropa dan lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia atau ADB. Betapapun persaingan makin ketat, Menteri Radius percaya, bahwa ke-ran bantuan bagi Indonesia tak akan macet. Namun yang harus diperhitungkan adalah syarat-syarat non ekonomi dari negara donor seperti soal demokrasi, hak asasi, kebebasan pers atau lingkungan. Pemerintah Indonesia, menurut Radius, telah berbenah, antara lain lewat jurus-jurus deregulasi. Birokrasi disederhanakan dan perijinan usaha yang berbelit dipangkas. Hasilnya telah kelihatan. Nisbah antara nilai ekspor terhadap cici-lan utang dan bunganya, yang sering disebut debt service ratio, menurun, dari 35%, menjadi 27%, dan kini 25%. Angka itu indikasi kondisi ekonomi yang makin sehat. "Kalau kita mengikuti garis kebijaksanaan ekonomi makro yang sehat, pinjaman luar negeri lebih mudah didapat," ujarnya. Kalau toh kecenderungan pinjaman dikaitkan dengan masalah politik atau hak asasi, Indonesia memang mesti ancang-ancang. "Kita bukannya tak mau demokratisasi atau hak asasi. Tapi kita bisa terapkan sesuai dengan nilai-nilai kita," kata Menteri Negara Ketua Bappenas, Saleh Afif. Kalau toh syarat semacam itu dipaksakan, "mungkin kita harus siap-siap menghadapinya," tambahnya. Caranya, katanya, kalau tak bisa dengan pinjaman lunak (soft loan), bisa dicari pinjaman dengan kredit ekspor yang setengah lunak. Ini telah ditempuh Indonesia dalam membiayai proyek-proyek besar selama ini. "Kredit lunak seperti yang kita terima tiap tahun, tak berarti apa-apa untuk pembangunan proyek raksasa seperti pelabuhan, listrik, telkom dan lain-lain," kata Afif. Ia menunjuk contoh pembangunan listrik yang akan makan biaya sekitar US$ 10 milyar. Mau tak mau, Indonesia mesti mencari kredit ekspor untuk proyek itu. Jurus lain yang lebih berat, kalau terpaksa, bisa juga ditempuh dengan pinjaman komersial, yang jangka pengembaliannya lima tahun. Maka pinjaman luar negeri itu sulit diproyeksikan besarnya. Mood dunia internasional akan menentukan jatah bantuan. Dalam kondisi semacam ini, sumber dalam negeri harus makin bisa menggantikanya. Celakanya, di masa-masa sulit itu justru salah satu sumber andalan penerimaan pemerintah, minyak mulai surut perannya. "Kejayaan migas telah berlalu," ujar Hadi Susastro, ahli ekonomi energi dari CSIS. Dirjen Minyak dan Gas Bumi Sujitno Patmosukismo membenarkan sinyalemen Hadi Susastro. Saat ini produksi minyak Pertamina 1,5 juta barel per hari. Sumur baru, katanya, sulit ditemukan. Kalaupun ada, de-positnya tak seberapa - disedot 6-7 tahun sudah kering. Padahal sumur-sumur tua pun isi perutnya semakin menipis. "Kalau kita bisa bertahan di angka 1,5 juta barel itu sudah bagus," tambahnya. Sumbangan migas pernah mencatat prestasi yang spektakuler pada APBN 1974/1974, ketika harganya melonjak. Harga tertinggi yang pernah dinikmati adalah US$ 35 per barel. Kini harga konstan, sekitar US$ 20. Dengan harga yang tinggi itu, peran migas menonjol dalam menggaet devisa. Pada Pelita II misalnya, porsi ekspor migas antara 65-73% dari nilai ekspor keseluruhan. Pada Pelita III porsinya naik lagi menjadi 67-82%. Pada Pelita IV anjlok. Dan kini porsi minyak tinggal 31-35% saja. Sumbangan migas ke kocek pemerintah, lewat pos penerimaan dalam negeri mengikuti pola yang sama, menyumbang 54-56% dalam Pelita II, naik 64-71% pada Pelita III, dan akhir Pelita V ini turun lagi tinggal sekitar 25% saja. Tanpa ada sumur baru yang potensial, dan laju konsumsi dalam negeri tetap pesat seperti sekarang, Sujitno Patmosukismo memperkirakan 10 tahun lagi Indonesia menjadi pengimpor minyak. Konsumsi melebihi produksi. Usaha menekan konsumsi menjadi-jadi di sektor transportasi dan manufaktur. Namun Hadi Susastro punya skenario yang lebih optimistis. Indonesia akan jadi net importer minyak baru tahun 2010 nanti. Antara 1993-2000, menurut Hadi, Indonesia masih mungkin menggaet US$ 100 milyar dari minyak dan gas, dengan asumsi tingkat harga minyak US$ 20-25 per barel. Asal 50% dari uang migas itu harus dikembalikan ke sektor energi, membangun instalasi listrik baru dan kilang-kilang minyak. Pada saat yang sama, menurut perkiraan Hadi, ekspor non migas terus meningkat. Porsi migas paling banter hanya 25% dari keseluruhan ekspor. Migas bukan lagi sektor terpenting bagi roda perekonomian Indonesia, terutama dalam penerimaan APBN. "Dan APBN itu tetap akan menjadi faktor penting, untuk penyediaan infrastruktur," ujar doktor ekonomi lulusan Universitas Santa Monica, California, 1978 itu. Melihat gambaran itu, menurut Hadi Susastro, mau tak mau Pemerintah harus lebih giat menggali sumber penerimaan di luar migas, dari sektor pajak misalnya. Penerimaan pemerintah dari pajak, kata Hadi pula, masih sangat mungkin ditingkatkan. Pungutan pajak saat ini, masih sekitar 12%-15% dari produk domestik brutto (PDB). "Tinggal bagaimana kita bisa membuat inovasi baru dalam pemungutan pajak," kata Hadi (lihat box: Kejarlah Pajak Sampai Warisan). Yang tak kalah penting dari kedua penerimaan anggaran negara itu adalah perolehan devisa dari ekspor. Setelah serentetan deregulasi dilakukan, angka ekspor meningkat pesat. Pertumbuhan ekspor non migas selama 1986-1990 tercatat sekitar 20% pertahun. Sektor industri tumbuh meyakinkan, rata-rata 27%. Industri alas kaki, meubel, barang kaca, dan kertas masing-masing tumbuh 208%, 103%, 66%, dan 49% setahun. Sektor pariwisata agak keteter, pertumbuhannya cuma 4,4% setahun. Asia Timur, Asia Tenggara, Amerika Utara dan Eropa Barat adalah ka-wasan terpenting bagi pemasaran komoditi non mogas Indonesia. Pada periode 1986-1990, Asia Timur --terbesar Jepang sampai 21%-- menyerap 35% dari seluruh ekspor. Asia Tenggara mengkonsumsi 16,8%, sedangkan Amerika dan Eropa Barat masing- masing 16,3 dan 21,3%. Kendati mengalami lonjakan besar, namun angka abosut ekspor Indonesia tidaklah luar bila dibandingkan ekspor dari para tetangga di Asia Tenggara. Dalam memanfaatkan preferensi tarif di pasar Amerika, melalui program GSP misalnya, Indonesia masih lemah, hanya mampu menangguk US$ 87 juta. Itu cuma 2% dari jumlah yang diperoleh negara ASEAN lainnya. Peningkatan nilai ekspor sejak 1988 menjadi indikasi semakin kuatnya daya saing produk industri Indonesia. Namun, pada saat yang sama, seperti dikatakan Menteri Muda Perdagangan Sudradjat Djiwandono, pasar internasional yang terbuka makin susut. "Banyak negara yang semakin proteksinistis," ujarnya. Masyarakat industri internasional kini sedang dibikin kaget oleh NAFTA (North America Free Trade Area), pasar eksklusif yang beranggotakan Kanada, Amerika, Meksiko, dan Chli. NAFTA tentu mengutamakan kepentingan anggotanya dibanding "orang luar". Di Eropa sejak 1986 MEE berlaku Single European Act, pasar tunggal Eropa yang menghambat arus barang dan jasa dari luar. MEE itu, menurut Menteri Sudradjat, diperluas dengan adanya AFTAL, pasar eksklusif yang beranggotakan Swedia, Islandia, dan Swis. Negara-negara Asia Pasific tak mau ketinggalan, membentuk pasar bersama ASPAC (Asia Pasific Economic Corporation). ASEAN pun ikut-ikutan dengan membentuk Asean Free Trade Area, yang akan efektif bekerja mulai tahun depan. "Harapan kita kelompok- kelompok itu tak menjadi benteng," kata Sudradjat. Kalau kelompok itu cenderung menjadi benteng, Indonesia mudah terpukul. Rupanya, ancaman ekspor Indonesia juga datang dari gaya lain proteksi negara maju. Mereka menuduh negara produsen melakukan dumping dengan subsidi ekspor. Ironisnya, GATT yang menjadi "polisi" tarif perdagangan internasional, tak banyak bicara. Contohnya kemacetan Putaan Uruguay yang disponsori GATT. Menurut Duta Besar Indonesia di GATT, Husain Kartadjumena, itu sangat merugikan Indonesia. "Tanpa ada aturan permainan yang jelas, akan terjadi tindakan yang sewenang-wenang," ujarnya. Tindakan itu, yang biasanya mengacu pada proteksi, bakal menghambat barang dan jasa Indonesia ke negara yang dituju. Ancaman konkrit GATT bagi Indonesia, menurut Husein, belum muncul secara konkrit. Perkara industri yang dikaitkan dengan soal lingkungan, hal yang bisa memojokkan Indonesia, belum masuk dalam agenda GATT. Begitu pula dengan soal upah buruh. "Tapi memang, isu lingkungan dan upah buruh itu bisa dipakai secara sepihak untuk menghalangi masuknya barang buatan Indonesia," kata Husein. Perangai perdagangan internasional, yang sering berubah cepat dan sulit diduga itu, memang bisa mengakibatkan ekspor negara sedang berkembang semacam Indonesia bisa naik-turun secara tajam. Akibatnya, industri di dalam negeri juga mudah bergoyang. Maka, dalam kaitannya dengan anggaran pemerintah, menurut Hadi Susastro, perlu ada deversivikasi sumber penerimaaan. "Penerimaan dari pajak tak bisa dipaksa-kan terus meningkat. Pada saat tertentu bisa menyusut," katanya. Hadi Susastro mengusulkan sumber dana lain, yakni obligasi pemerintah. Sayangnya, obligasi ini belum populer di kalangan masyarakat. Hanya saja, ketergantungan pemerintah terhadap pajak dan obligasi itu, dikehendaki atau tidak, membuat posisi masyarakat makin kuat. Mereka tentu menuntut keterlibatan lebih banyak dalam pelbagai keputusan, termasuk keputusan politik. Putut Trihusodo, Iwan Qodar, dan Wahyu Muryadi
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini